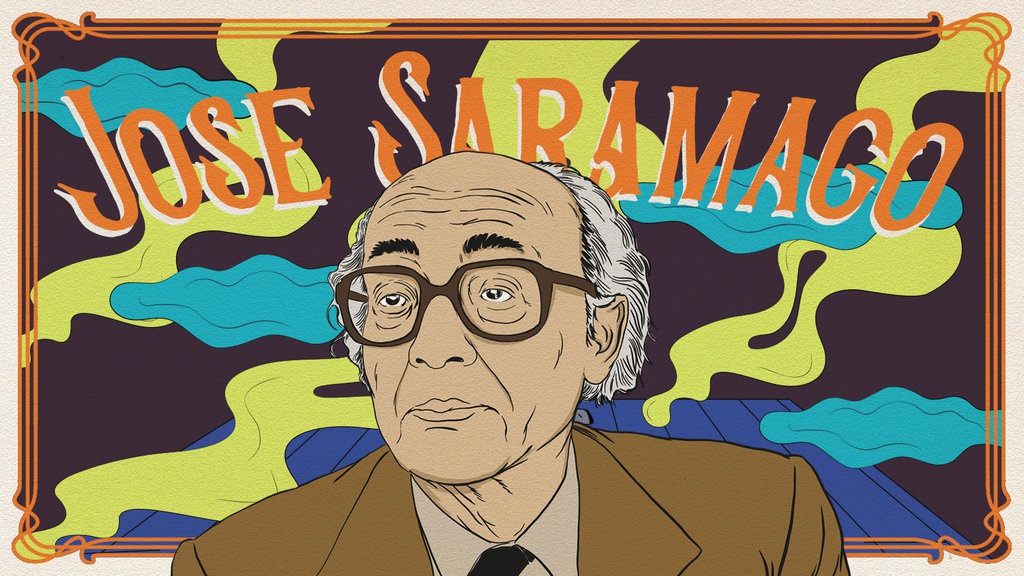tirto.id - José Saramago meninggal pada 18 Juni 2010, tepat hari ini 11 tahun lalu. Ia dibenci oleh kaum konservatif sebagaimana dikagumi oleh banyak pembacanya. Penulis berbahasa Portugis pertama yang meraih Hadiah Nobel Sastra pada 1998 ini adalah sosok yang tak gampang diletakkan dalam patok-patok konvensional.
Kiwari, saat semua orang dipacu untuk “berprestasi” di usia muda, akan janggal melihat penulis yang baru menemukan suara khasnya—dan selanjutnya pamor internasionalnya—pada usia hampir 60 tahun. Dan kedahsyatannya semakin bersinar seiring usia yang kian renta. Pada 2005, saat sastrawan besar Gabriel García Márquez sudah sakit-sakitan dan mengaku tak bisa menulis lagi sebaris kalimat pun, Saramago masih sanggup menelurkan As Intermitências da Morte yang cemerlang. Dilanjutkan buku-buku lain hingga meninggal di usia 87 tahun.
Membaca Saramago tak pernah mudah, tetapi selalu memuaskan. Ia tak menggunakan tanda baca sesuai konvensi lazim. Ia jarang menggunakan titik. Kalimat deskriptif maupun dialog dirangkainya hanya dengan koma. Anak kalimat sambung-menyambung dan terus sambung-menyambung, kadang satu alinea bisa sampai satu halaman lebih panjangnya. Tanda petik untuk dialog? Nihil. Huruf kapital sering ia pakai sesudah koma, hanya sebagai penanda pergantian pengucap atau narator. Suara naratif inilah yang memberi kekhasan pada karya-karyanya, setidaknya sejak Levantado do Chão (1980).
Buat saya, José Saramago adalah salah seorang penulis fantasi terbesar. Ia memperluas cakrawala pemahaman tentang genre sastra fantasi melampaui sekadar naga, sihir, dan supranatural—unsur-unsur pokok yang biasa ada dalam genre itu. Fantasi spekulatif Saramago adalah skenario “bagaimana jika” (what if) gila-gilaan yang dipijakkan di dunia kenyataan dan ditelusuri implikasi-implikasi sosiologis, psikologis, dan politisnya sampai kemungkinan terjauh.
A Jangada de Pedra (1986): bagaimana jika Semenanjung Iberia retak terlepas dari benua Eropa dan mengambang-ambang hingga ke Samudra Atlantik? História do Cerco de Lisboa (1989): bagaimana jika seorang pemeriksa aksara di sebuah penerbitan membubuhkan tambahan satu kata “tidak” dan dengan itu mengubah narasi sejarah? Ensaio sobre a Cegueira (1995): bagaimana jika wabah kebutaan melanda dan seisi kota tak dapat melihat? O Homem Duplicado (2002): bagaimana jika seseorang menemukan orang lain dengan kemiripan tak terbedakan dari dirinya dan mereka memutuskan bertukar hidup? Ensaio sobre a Lucidez (2004): bagaimana jika suara golput dalam suatu pemilu—mereka yang datang ke bilik suara tetapi tak memilih satu pun kandidat yang ada—mencapai lebih dari 80 persen? As Intermitências da Morte (2005): bagaimana jika maut urung datang dan orang-orang hanya terus menua tanpa meninggal?
Bagaimana jika… bagaimana jika… Di situlah imajinasi Saramago sebagai penulis tercurah. Namun perlu diingat, Saramago juga seorang komunis yang hingga wafat tak pernah menyangkal jalan politiknya. Fantasi spekulatif Saramago adalah caranya untuk berpijak ke kenyataan sosial, menyelami soal-soal kemasyarakatan dan membahas secara sastrawi (juga kerap filosofis) isu-isu besar kontemporer seperti proyek Uni Eropa, kritik terhadap konservatisme agama, kritik terhadap demokrasi elektoral neoliberal, alienasi individu dalam masyarakat kapitalis-birokratis, dll. Dengan ini pula, runtuhlah patokan lawas bahwa seorang penulis komunis seharusnya hanya menulis “realisme.” Menengok sekilas riwayat hidupnya mungkin bisa membikin jelas mengapa dua kecenderungan ini—komunis dan fantastis—hadir dalam dirinya.
Dari Montir sampai Redaktur Budaya
Saramago lahir dari keluarga petani tunakisma (petani yang tidak punya lahan) di desa kecil Azinhaga, sekitar 100 km ke arah timur laut Lisabon. Ia akan bernama José de Sousa andai pegawai catatan sipil tidak berinisiatif membubuhkan sendiri nama panggilan keluarga si ayah di desa itu, saramago:nama lokal bagi semacam spesies lobak liar.
Meski ayahnya memutuskan pindah sekeluarga ke Lisabon saat José berusia 2 tahun, ia selalu menghabiskan masa liburannya kembali ke perdesaan. Di sana, di bawah pohon ara, ia menyimak dongengan-dongengan kakeknya. Di perdesaan pula ia mendengar bagaimana para petani buta huruf bercerita: mengalir tak putus, susul-menyusul, kisah lampau dan kisah kini tumpang-tindih bersahutan. Maka jauh hari kemudian, saat menggarap Levantado do Chão (1980) yang berkisah tentang perjuangan kaum tani tertindas dalam mempertahankan tanahnya, ia mencoba memindahkan gaya bahasa lisan tersebut ke atas kertas, mengesampingkan aturan pemakaian tanda baca konvensional yang lantas menjadi gaya naratif khasnya.
Pindah ke ibukota dari desa terpencil tidak serta-merta melepaskan hidup keluarga itu dari kemiskinan akut. Saramago mengenang dalam memoarnya As Pequenas Memórias (2006): “Ibuku biasa menggadai selimut-selimut begitu musim dingin berakhir, hanya untuk menebusnya kembali begitu cuaca dingin mulai menggigit lagi dan dia sudah punya cukup tabungan untuk membayar bunga bulanannya dan pinjaman pokoknya.”
José kecil suka membaca, meski buku nyaris tidak ada di rumahnya, setidaknya koran-koran yang dibawa pulang ayahnya. Ia mengaku dalam memoarnya, “Aku membaca bahkan sebelum bisa mengeja dengan benar, meskipun aku tidak langsung mengerti apa yang aku baca. Mampu mengidentifikasi sebuah kata yang aku kenal rasanya seperti menemukan rambu di jalan yang memberitahu bahwa jalanku sudah benar.”
José kecil cemerlang di sekolah. Bahkan saat kelas tiga, kepala sekolah Senhor Vairinho memanggil ayahnya untuk memberitahu bahwa José bisa langsung menempuh pelajaran kelas empat sekaligus, yang ternyata juga dituntaskannya dengan predikat memuaskan. Bagaimanapun, kemiskinan membuat keluarganya tidak mampu untuk terus menyekolahkannya di sekolah umum. Maka pada usia 12 tahun José pindah ke sekolah teknik yang—untungnya buat dia—tetap mengajarkan sastra. Lulus dari sana ia menjadi montir di bengkel mobil selama dua tahun, sambil terus mengasah dan memperluas wawasan bacaannya di perpustakaan umum Lisabon sepulang jam kerja.
Pada 1947, saat berusia 24 tahun, ia berhasil menerbitkan novelnya yang pertama, Terra do Pecado, tanpa mendapat banyak sambutan. Saat menuliskan novel berikutnya, ia menyadari bahwa ia sesungguhnya tidak memiliki sesuatu yang benar-benar penting untuk disampaikan sebagai seorang penulis, karena itulah ia memutuskan berhenti menulis sama sekali. Hampir 20 tahun lamanya ia absen dari gelanggang sastra Portugal, dan baru muncul lagi pada 1966 saat menerbitkan kumpulan puisi Os Poemas Possíveis. Sepanjang waktu itu, menurutnya, ia “hanya menjalani hidup” dan tidak menyesalinya.
Portugal waktu itu berada di bawah kediktatoran sayap kanan Presiden António de Oliveira Salazar yang berkuasa sejak kudeta militer 1926. Saramago telah berganti-ganti pekerjaan dari montir ke juru tulis ke manajer perusahaan logam ke penerjemah di sebuah penerbitan. Pada 1969, ia bergabung dengan Partai Komunis dan setahun berikutnya Presiden Salazar meninggal dunia. Meski demikian, model pemerintahan otoritarian korporatis yang diwariskan Salazar—diistilahkan sebagai “Estado Novo”—tetap bertahan.
Menjelang akhir 1971, Saramago keluar dari kerjanya di penerbit untuk menjadi redaktur budaya di koran sore Diário de Lisboa. Kumpulan opininya selama kerja di koran ini terbit dengan judul As Opiniões que o DL teve pada 1974—tahun yang sama berlangsungnya Revolusi Anyelir yang menumbangkan sisa-sisa kediktatoran Estado Novo.
Terdepak dari Koran dan Mulai Menulis Lagi
Revolusi Anyelir bermula dari protes sekumpulan perwira militer anti kediktatoran yang berorganisasi dengan nama Movimento das Forças Armadas (MFA, Gerakan Angkatan Bersenjata), yang langsung diikuti oleh gerakan protes sipil yang lebih luas. Pasca Revolusi Anyelir, kekuasaan masih dipegang oleh junta militer, dan Portugal mengalami masa-masa penuh gejolak yang dikenal sebagai “Proses Revolusioner yang Sedang Berjalan”. Persaingan antara kubu kiri mentok—Saramago termasuk di dalamnya—dengan golongan sosialis yang lebih moderat membuat MFA bubar dan berujung pada kudeta serta kudeta-tandingan tanggal 25 November 1975. Ini membuat kubu komunis terpukul oleh kubu sosialis dan liberal dalam transisi demokratis selanjutnya di Portugal.
Kekalahan politik kubu komunis ini membuat Saramago terdepak dari koran tempatnya bekerja. Kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan, ia mengenang positif peristiwa ini sebagai titik balik saat ia harus memutuskan apakah ia benar-benar seorang penulis dan ingin membaktikan hidupnya kepada kesusastraan. Dari situlah berturut-turut lahir novel Manual de Pintura e Caligrafia (1977), kumpulan cerpen Objecto Quase (1978), travelog Viagem a Portugal (1981)… dan selebihnya adalah sejarah.
Bukan hanya komunis, Saramago juga ateis, yang membuatnya seperti ikut “terdepak” dari kekolotan masyarakat Katolik Portugal. Novelnya tahun 1991, yang buat saya merupakan karya terbaiknya, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, berawal dari premis bagaimana jika Yesus adalah sosok yang penuh kekurangan-kekurangan manusiawi sementara Tuhan adalah sosok gila kuasa? Dengan sensitif Saramago menggambarkan Yesus sebagai manusia berdarah dan berdaging, sesosok pion tak berdaya dalam pertarungan akbar Tuhan lawan Setan. Yesus mengenal sangsi, mengenal takut, dan mengenal seks.
Menjelang akhir novel, saat berada di kayu salib dan akhirnya menyadari apa yang dimaksud sebagai “rencana Tuhan”—yakni berabad-abad kekerasan, inkuisisi, pembunuhan, penindasan yang diperbuat atas nama agama Kristen dan ditulis beruntun berhalaman-halaman panjangnya—Yesus pun berbisik sebelum mengembuskan napas terakhirnya, “Ya manusia, ampunilah Dia, sebab Dia tidak tahu apa yang Dia perbuat” (memplesetkan apa yang tertulis di Alkitab “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.”)
Novel ini dikecam oleh Vatikan dan pemerintahan kanan tengah Portugal saat itu. Pemerintah bahkan ikut memveto nominasinya untuk penghargaan sastra Eropa. Saramago akhirnya hengkang dari Portugal pada 1992 lalu menetap bersama istrinya, wartawati Spanyol Pilar del Río di pulau kecil Lanzarote, Kepulauan Kanari, yang secara yuridis masuk wilayah Spanyol. Di Lanzarote Saramago menyepi meski bukan berarti menjauhkan diri dari kehidupan. Di sinilah ia menulis dan menetap hingga akhir hayatnya.

Hingga akhir hayatnya pula Saramago tetap memegang kartu anggota Partai Komunis dan tak pernah mengingkari ideal politiknya: “Saya tidak mencari-cari alasan untuk apa yang telah diperbuat rezim-rezim komunis, tetapi saya punya hak untuk mempertahankan gagasan-gagasan saya.”
Komunis macam apakah Saramago? Kumpulan cerpennya Objecto Quase dibuka dengan kutipan dari Marx dan Engels dalam bab 6 Die heilige Familie (1844): “Jika manusia dibentuk oleh lingkungannya, maka lingkungannya mesti dijadikan manusiawi.”
Manusia dan martabatnya dengan demikian menempati posisi sentral dalam kerja kepenulisan maupun aktivisme politik Saramago (ingat bagaimana ia menggambarkan pergulatan Yesus). Saat menerima Hadiah Nobel, pidato jamuan makannya ia manfaatkan untuk bicara tentang Deklarasi Universal HAM dan bagaimana hak-hak asasi manusia itu semakin terlecehkan di era globalisasi neoliberal. Yayasan José Saramago juga ia dirikan dengan salah satu misinya untuk mempertahankan dan menyebarkan Deklarasi Universal HAM. Saramago juga memanfaatkan teknologi media baru (internet dan blog) untuk menulis opini dan esai tentang peristiwa-peristiwa aktual, mulai dari krisis ekonomi global hingga penjajahan Israel atas Palestina.
Saramago pernah menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh yang ia tulis adalah esai dan novel-novelnya adalah bentuk gagal dari esai. Pada beberapa bagian, novel-novelnya memang seperti terbaca sebagai esai (dan memang sebagiannya dengan gamblang dijuduli sebagai “Esai” meski judul ini lantas dibuang atau diganti pada edisi-edisi terjemahan).
Narator dalam novel-novelnya sering dibuat untuk tampak berjarak secara objektif dan tak memiliki ikatan emosional dengan apa yang dijabarkannya. Sang narator bisa tampak sangat bijak karena bisa melihat segala hal, sekaligus sangat beloon karena mengulas detail-detail yang tampaknya tak bakal dihiraukan oleh orang pada umumnya. Gaya naratif ini juga dimanfaatkan Saramago untuk memasukkan renungan-renungan filosofis yang kerap terbaca seperti lanturan ngalor-ngidul.
Bahkan dalam salah satu karyanya yang paling terkenal Ensaio sobre a Lucidez (yang secara harfiah berarti Esai tentang Terang, tetapi diterjemahkan hanya menjadi Seeing dalam edisi Inggrisnya), kita seperti membaca metafiksi saat sang narator mengomentari narasinya sendiri yang melantur ke mana-mana:
“Yang jadi masalah dengan lanturan-lanturan naratif ini, yang menyita kita dengan kelokan-kelokan menyusahkan, adalah bahwa kita jadi mendapati, dengan sudah kelewat telat tentunya, nyaris tanpa menyadari, bahwa peristiwa-peristiwa telah berlalu, telah berjalan maju, dan alih-alih kita mengumumkan apa yang bakal terjadi, yang bagaimanapun juga memang sudah menjadi kewajiban mendasar pencerita mana saja yang mumpuni, yang bisa kita lakukan cuma mengakui dengan menyesal bahwa peristiwanya memang telah berlalu.”
Mengenang Saramago adalah mengenang zaman yang mungkin terasa lebih masuk akal bagi sebagian kita. Zaman ketika seorang sastrawan memilih jalan sunyi kepenulisan dengan mematangkan diri puluhan tahun daripada secara instan lewat ingar-bingar media sosial. Zaman ketika seorang aktivis terus bersetia dengan kemanusiaan dan martabat orang banyak. Ketika seorang komunis tak takut-takut menyatakan idealnya yang paling keras. Ketika seorang intelektual mematok standar erudisi tertinggi bagi kerja-kerja kebudayaan dan tak merasa perlu mengencerkannya demi rating dan jumlah like.
Namun mungkin juga dalam kenangan ini terkandung kerinduan: akan seorang penulis yang tak ragu berkhayal untuk membahas persoalan-persoalan paling nyata dan intim bagi manusia kontemporer.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id