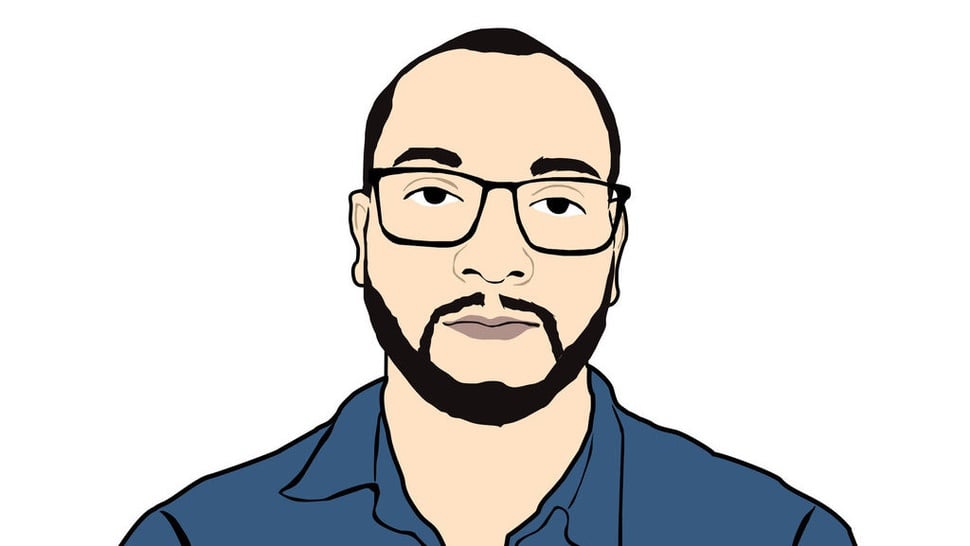tirto.id - Sebagaimana banyak organisasi kemasyarakatan lain di Indonesia, ormas-ormas Islam sangat diuntungkan oleh jatuhnya Orde Baru. Mereka lebih leluasa menjalankan kegiatan organisasi tanpa harus direpresi negara seperti di bawah rezim Soeharto. Baik organisasi lawas dan bersejarah seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, maupun organisasi baru seperti Front Pembela Islam, semua mendapat kebebasan yang kurang lebih sama.
Namun, kebebasan yang baru diperoleh itu mengandung konsekuensi internal: beberapa organisasi mengalami friksi internal yang serius. Organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU adalah contoh bagaimana friksi internal bisa membuat organisasi gagal menyatukan agenda mengenai isu-isu sensitif seperti hak penganut kepercayaan lokal, hak minoritas muslim seperti Syiah dan Ahmadiyah, serta hak minoritas etnik dan agama lain.
Perselisihan dalam sebuah organisasi wajar belaka. Namun, NU dan Muhammadiyah mencapai kedudukan politiknya hari ini karena memiliki kemampuan untuk mengonsolidasikan pengikutnya, serta memiliki narasi dan agenda publik yang terkoordinir. Friksi internal yang tidak terkontrol bisa memengaruhi konsolidasi organisasi dan membuat narasi publik tak seirama.
Tetapi, apa sebenarnya penyebab friksi internal di NU dan Muhammadiyah pasca-Orde Baru? Bagaimana friksi internal ini memengaruhi posisi politik dua organisasi Islam paling berpengaruh di Indonesia tersebut?
Pergeseran Tren Dakwah
Setelah kejatuhan Orde Baru, setidaknya ada dua perkara yang mewarnai perkembangan Islam di Indonesia.
Pertama, hubungan dengan dunia internasional yang semakin aktif, baik dengan Timur Tengah maupun dengan ide-ide dari Barat. Kedua, demokrasi elektoral yang telah menyeret ormas-ormas Islam ke dalam politik dan membuat mereka sulit menghindar dari aktivitas politik praktis.
Di kalangan muslim tradisional yang lazim diasosiasikan dengan NU, peran kiai sebagai pemimpin agama dan pesantren sebagai pusat pengajaran Islam tradisional tetap tak tergoyahkan. Kiai juga memainkan peran penting di luar pesantren, misalnya memimpin pengajian, tahlilan, selamatan, atau ziarah. Kiai juga mengajarkan ilmu fikih (hukum Islam) di luar pesantren, dengan topik ringan seperti salat, haji, zakat, waris, dan lainnya. Topik-topik keagamaan yang lebih serius (dan sensitif) seperti tauhid dan keimanan biasanya dibahas hanya di dalam lingkaran pesantren.
Ada dua perubahan penting dalam komunitas muslim tradisionalis selama beberapa tahun terakhir.
Pertama, kemunculan para ulama baru, termasuk di antaranya para ulama sufi dari komunitas sayid yang biasa disebut habib, para cendekiawan liberal, dan ulama tradisional yang tidak lahir dari tradisi pesantren. Generasi baru ulama ini membawa ajaran dan topik pembicaraan baru ke lingkaran Islam tradisional, yang terkadang tidak selalu sesuai tradisi pesantren. Di sisi lain, muncul pula pandangan sosial dan politik para cendekiawan liberal dari NU yang mendukung hak-hak individual, misalnya pernikahan antar-agama atau hak-hak LGBT, yang masih sulit diterima kiai tradisional.
Kedua, ada perubahan dalam jenis-jenis topik yang diminati kelompok-kelompok pengajian. Sebelumnya, pengajian dan majelis taklim di daerah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya atau Palembang hanya berfokus pada tema-tema ringan seputar fikih. Namun, beberapa tahun terakhir, perdebatan sekitar akidah marak di lingkaran pengajian di kota-kota besar. Kecenderungan ini sangat memprihatinkan bagi para kiai dan ulama yang percaya pembicaraan tentang akidah dan topik serius lain semestinya hanya dilakukan di lingkungan pesantren atau sesama ulama.
Sialnya lagi, fokus pada topik akidah sering menghasilkan pelabelan non-muslim sebagai kafir dan kemudian menyulut intoleransi dan radikalisme. Perkembangan ini terjadi baik di kelompok-kelompok pengajian NU maupun Muhammadiyah.
Muhammadiyah sendiri menghadapi tantangan berat dari gerakan Tarbiyah, sebuah gerakan pendidikan puritan yang menginspirasi lahirnya Ikhwanul Muslimin. Anggota gerakan Tarbiyah sering diasosiasikan dengan Partai Keadilan Sejahtera, juga Hizbut Tahrir Indonesia yang baru-baru ini dilarang.
Pada 2006, Haedar Nashir menulis sebuah buku berjudul Manifestasi Gerakan Tarbiyah; Bagaimana Sikap Muhammadiyah? Dalam buku itu, Nashir mengutarakan keprihatinannya bahwa gerakan Tabiyah bisa menggeser garis politik dan dakwah Muhammadiyah. Komunitas Tarbiyah secara berkala menyebarkan karya-karya pemikir Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir di kalangan mahasiswa dan orang-orang Muhammadiyah pada umumnya.
Nashir juga mengkhawatirkan infiltrasi PKS di Muhammadiyah. Tentu sebelumnya Muhammadiyah memiliki sejarah afiliasi dengan Partai Amanat Nasional. Tetapi PAN hanya memanfaatkan basis massa Muhammadiyah untuk keuntungan politik elektoral tanpa pernah berusaha memengaruhi urusan-urusan keagamaan Muhammadiyah.
Walaupun Muhammadiyah dan Tarbiyah memiliki garis teologis yang sama, tetapi mereka sangat berbeda dalam pandangan politik. Bagi para aktivis politik Tarbiyah, agama dan negara tak sepatutnya dipisahkan. Bagi mereka, prinsip-prinsip inti akidah tidak boleh tunduk oleh ideologi apa pun, termasuk ideologi negara Pancasila.
Selain membuat basis keanggotan Muhammadiyah menyusut, ada dua konsekuensi besar lain yang ditimbulkan gerakan Tarbiyah. Pertama, karakter anti-sekuler dan transnasional gerakan Tarbiyah menyusup ke Muhammadiyah dan membahayakan hubungan antara Muhammadiyah dan negara kesatuan. Untuk menandingi narasi politik Tarbiyah mengenai ideologi negara, selama kongres nasional ke-47 Muhammadiyah, Nashir mempromosikan negara Pancasila sebagai konsensus nasional yang harus didukung oleh semua anggota Muhammadiyah.
Kedua, pengikut Tarbiyah dalam Muhammadiyah punya tujuan memperbaharui komitmen pemurnian Islam dalam organisasi tersebut. Pengikut Tarbiyah ingin membangkitkan anti-“TBC” (Takhayul, Bid'ah, Churofat). Jauh sebelum ini, Muhammadiyah telah memoderasi narasi anti-“TBC” demi membangun hubungan baik dengan muslim tradisional. Mereka sudah tidak lagi menjadikan gerakan anti bid’ah sebagai agenda organisasi. Pada titik inilah infiltrasi Tarbiyah bisa membahayakan hubungan Muhammadiyah dan NU serta komunitas Muslim tradisional lain.
Berpengaruh ke Politik Nasional
Meskipun mengalami tantangan internal serupa, NU dan Muhammadiyah berada dalam situasi berbeda. Di internal NU, kendati ada jurang yang besar antara Nahdliyin moderat, garis keras, dan liberal, semua faksi bersatu di bawah panji ‘Ahlussunnah Wal Jamaah’, yang tetap berpijak pada kaidah-kaidah empat mazhab, terutama Syafi’i. Bahkan organisasi vigilante seperti FPI dengan bangga menyatakan mereka adalah bagian dari NU dan Ahlussunnah Wal Jamaah.
Sebenarnya FPI adalah kasus yang menarik: para kiai dan habib moderat NU memiliki akses ke anggota FPI, seperti halnya para pengkhotbah FPI konservatif punya akses ke pengikut NU. Irisan keagamaan ini menjelaskan mengapa gerakan 'NU Garis Lurus'—yang menempatkan Rizieq Shihab sebagai contoh Ahlussunnah Wal Jamaah sejati—bisa muncul.
Di sisi lain, keanggotaan Muhammadiyah terus menyusut dan pindah ke PKS, HTI, atau kelompok Tarbiyah non-politik. Terlepas dari kenyataan bahwa Muhammadiyah dan gerakan Tarbiyah memiliki akar teologis yang sama, kelompok Tarbiyah sangat disiplin dan anggotanya hanya mengakses informasi yang bersumber dari ulama kalangan sendiri. Bahkan pemimpin Muhammadiyah yang relatif konservatif seperti Din Syamsuddin pun tak memiliki akses ke gerakan Tarbiyah. Komunitas Tarbiyah yang saya temui di Jakarta sebelumnya punya latar belakang Muhammadiyah, tapi kini enggan mengaitkan diri ke Muhammadiyah.
Friksi di dalam NU dan Muhammadiyah kian pelik dalam konteks politik nasional. Para politikus menyadari friksi ini. Beberapa di antara mereka bahkan mulai mendekati faksi-faksi tertentu di NU dan Muhammadiyah. Sementara Presiden Joko Widodo yang menjalin hubungan baik dengan ketua masing-masing organisasi tersebut belum tentu mampu mengais dukungan dari faksi-faksi di dalamnya.
Namun demikian, perselisihan internal tak melulu menyebabkan perpecahan. Perselisihan adalah bagian dari dinamika sebuah organisasi besar. Organisasi bersejarah seperti Muhammadiyah dan NU sudah memiliki infrastruktur internal untuk mengelola perselisihan.
Perselisihan internal yang terjadi saat ini menjadi penting untuk diamati karena terkait erat dengan bagaimana NU dan Muhammadiyah menggalang aliansi-aliansi politik, terutama dengan aktor-aktor pemerintah dan ormas lain. Akhirnya, friksi ini pula yang memengaruhi posisi kedua ormas dalam isu-isu penting seperti toleransi, hak minoritas, dan politik elektoral.
======
Tulisan ini diterjemahkan oleh Windu Jusuf dari “Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah struggle with internal divisions in the post-Soeharto era” yang dimuat di Indonesia at Melbourne pada 28 Mei 2018. Penerjemahan dan penerbitan di Tirto atas seizin penulis dan penerbit. Edisi Indonesia sudah diperiksa oleh penulis.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.