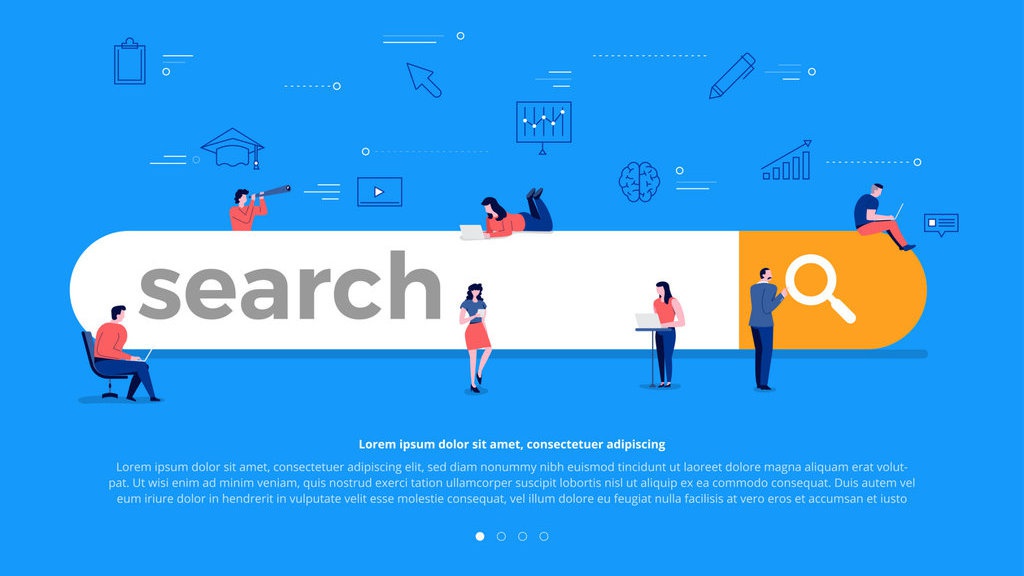tirto.id - Dulu, buku disebut sebagai jendela dunia karena mampu membawa pembacanya melanglang buana, mempelajari hal-hal baru, dan berimajinasi. Kini, peran tersebut sedikit banyak telah diambil alih oleh sebuah mesin pencari bernama Google. Setiap kali membutuhkan informasi tentang sesuatu, Google menjadi pintu pertama yang kita buka.
Dari sana, kita bisa menemukan banyak sekali hal, mulai dari berita, opini, cerita, gambar, video, atau hal-hal lain yang bisa membantu kita untuk memantik daya kreasi. Setidaknya, begitulah pola yang selama ini dipercaya berhasil.
Namun, sebuah studi dari psikolog kognitif Daniel Oppenheimer dan Mark Patterson dari Carnegie Mellon University justru memberi kabar mengejutkan tentang Google dan kreativitas. Mereka mendapati bahwa kelompok yang tidak menggunakan Google dalam proses kreatif ternyata menghasilkan ide yang lebih banyak, lebih beragam, dan lebih efektif.
Dalam eksperimen yang dipublikasikan di jurnal Memory & Cognition (2025), Oppenheimer dan Patterson membagi partisipan menjadi dua kelompok: satu dengan akses penuh ke internet, satu lagi tanpa akses. Hasilnya sangat kontras. Kelompok offline lebih unggul di semua aspek kreativitas.
Temuan ini memperkuat hipotesis tentang cognitive fixation. Yakni, ketika kita menggunakan Google untuk mencari ide, kita cenderung terpaku pada contoh-contoh yang sudah ada. “Fixation” di sini bukan hanya soal menjiplak bulat-bulat, tetapi menjiplak dengan lebih halus. Dalam proses ini, otak kita terjebak dalam pola yang familiar dan gagal menjelajah ke arah yang baru. Seperti yang dijelaskan dalam laporan PsyPost mengenai studi ini, akses ke informasi instan bisa mempersempit ruang ide dan mematikan potensi divergensi.
Temuan ini bukan kebetulan. Studi tersebut mereplikasi pola yang sebelumnya ditemukan oleh Oliva & Storm (2023), yang juga mencatat bahwa akses ke Google dalam tugas-tugas seperti alternative uses task membuat peserta menghasilkan lebih sedikit ide unik. Kemudahan akses memang mempercepat proses berpikir, tapi pada saat yang sama bisa menjadi "penjara tak terlihat" yang menahan otak di zona aman.
Dalam makalahnya, Oppenheimer dan Patterson menyimpulkan bahwa Google mungkin sangat berguna untuk tugas-tugas konvergen—misalnya, mencari fakta—tetapi bisa kontraproduktif untuk pekerjaan kreatif yang menuntut eksplorasi luas dan berpikir divergen. Mereka menekankan pentingnya menunda penggunaan alat bantu digital jika tujuannya adalah mencipta, bukan sekadar mencari.
Dari situ, muncul paradoks yang relevan dengan zaman kita: semakin mudah kita mencari ide, semakin jarang kita benar-benar menciptakan ide sendiri. Kita terbiasa mengetik alih-alih merenung. Proses kreatif justru sering kali lahir dari kekosongan; dari ruang kosong yang tak diisi oleh hasil pencarian siapa pun.
AI dan Ilusi Kreativitas
Setelah Google, datang gelombang baru: ChatGPT, Copilot, Gemini, dan AI generatif lainnya. Jika Google memudahkan pencarian, alat-alat AI generatif menawarkan hasil instan. Bukan cuma ringkasan, tetapi juga teks utuh, puisi, slogan iklan, bahkan lirik lagu. Di permukaan, semua ini tampak seperti revolusi kreativitas. Tapi, apakah benar begitu?
Sebuah studi baru yang dilaporkan oleh PsyPost pada Mei 2025 menunjukkan bahwa manusia masih unggul dalam satu aspek krusial dibanding AI: kreativitas divergen—kemampuan menghasilkan banyak ide unik dari satu stimulus.
Dalam eksperimen yang melibatkan ChatGPT, para peneliti meminta baik manusia maupun AI untuk memberikan sebanyak mungkin kegunaan alternatif untuk benda-benda sehari-hari, seperti pensil atau kardus telur. Hasilnya, manusia secara konsisten mengalahkan AI dalam jumlah, variasi, dan kebaruan ide.
AI memang hebat dalam mengenali pola. Tapi justru di situlah masalahnya. Ia mengulang pola yang sudah ada, bukan menciptakan lompatan ide yang benar-benar baru. Ini disebut sebagai “generative stagnation”, yaitu sebuah kondisi di mana AI tampak produktif tapi sebenarnya hanya mendaur ulang probabilitas dari miliaran contoh sebelumnya. Mesin seperti ChatGPT tidak “berpikir,” melainkan hanya menghitung kemungkinan kata berikutnya berdasarkan data besar yang digunakan untuk melatihnya.
Sebuah studi meta-analisis internasional menunjukkan bahwa AI generatif tidak lebih kreatif dibanding manusia (g = –0,05). Sementara itu, meskipun kolaborasi dengan AI memang meningkatkan output kreatif, keberagaman ide yang dihasilkan menurun secara signifikan (g = –0,86). Ini menegaskan bahwa AI lebih efektif sebagai asisten, bukan mesin pemicu kreativitas sejati.
Studi lain dari Zhang, dkk. (2025) menambahkan bahwa, meski AI unggul dalam beberapa tes kreativitas seperti pemikiran divergen, kemampuan berpikir kreatif secara otentik belum ditiru dengan baik oleh AI. Yang muncul dalam obrolan-obrolan kita dengan AI adalah hasil prediktif, bukan proses inovatif.
Terakhir, temuan empiris tambahan dari studi kolaborasi Wharton menyoroti problem serupa. AI memang bisa menyajikan banyak ide, tapi variasinya jauh lebih sempit dibanding jika manusia memulai tanpa bantuan apa pun, entah dari mesin pencari maupun AI generatif.
Dengan kata lain, AI dan Google kini membentuk satu rangkaian jebakan modern: satu mengarahkan kita ke ide-ide yang sudah dominan di web, dan satunya lagi mengemas ulang ide-ide itu agar terdengar baru (padahal tidak). Ketika dipakai tanpa kendali, keduanya bukan memicu kreativitas, tapi membunuh potensi orisinalitas sejak dari akar.
Mulai dari Kekosongan
Kehidupan lahir dari ketiadaan, begitu pula dengan karya yang hebat. Proses penciptaan yang hakiki lahir dari ruang kosong. Kekosongan inilah yang membuat otak manusia berputar, berayun, menari bebas tanpa rambu, dan ini nyaris mustahil didapat ketika jari sudah lebih dulu mengetik pertanyaan di Google atau prompt di ChatGPT.
Dalam eksperimen Oppenheimer & Patterson (2025), kelompok yang diminta menyelesaikan tugas kreatif tanpa akses internet justru menciptakan ide-ide yang lebih orisinal, beragam, dan efektif. Hasil mereka tidak lebih banyak, tapi lebih “hidup.” Mereka tidak terpaku pada jawaban populer atau solusi dari hasil pencarian. Sebaliknya, mereka membentuk ide dari asosiasi pribadi, pengalaman, dan imajinasi yang autentik.
Studi dari Oliva & Storm juga menguatkan temuan ini. Ketika peserta diminta mencari inspirasi lewat internet untuk menghasilkan ide produk baru, hasilnya justru kurang bervariasi dan sangat terikat pada contoh yang mereka temukan secara online. Bahkan, dalam tugas seperti "kegunaan lain dari kancing baju", kelompok yang tidak membuka Google menciptakan ide yang jauh lebih eksentrik dan liar karena mereka tidak “terjangkit” apa yang sudah dikenal secara umum.
Apa yang bisa kita tarik dari sini bukan bahwa Google atau AI adalah musuh kreativitas. Mereka adalah alat. Namun, layaknya semua alat, efeknya tergantung bagaimana dan kapan kita menggunakannya. Ketika kreativitas dimulai dengan pencarian, yang kita dapatkan adalah jawaban orang lain. Tapi ketika dimulai dengan hening, kita memberi ruang bagi gagasan yang benar-benar milik sendiri untuk muncul.
AI dan Google bisa sangat bermanfaat di fase akhir dengan memperkaya, menyusun ulang, atau menyempurnakan, tetapi mereka bukan titik awal. Titik awalnya masih, dan mungkin akan selalu, ada di dalam kepala kita yang sedang kosong dan menunggu digerakkan untuk merajut imajinasi.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id