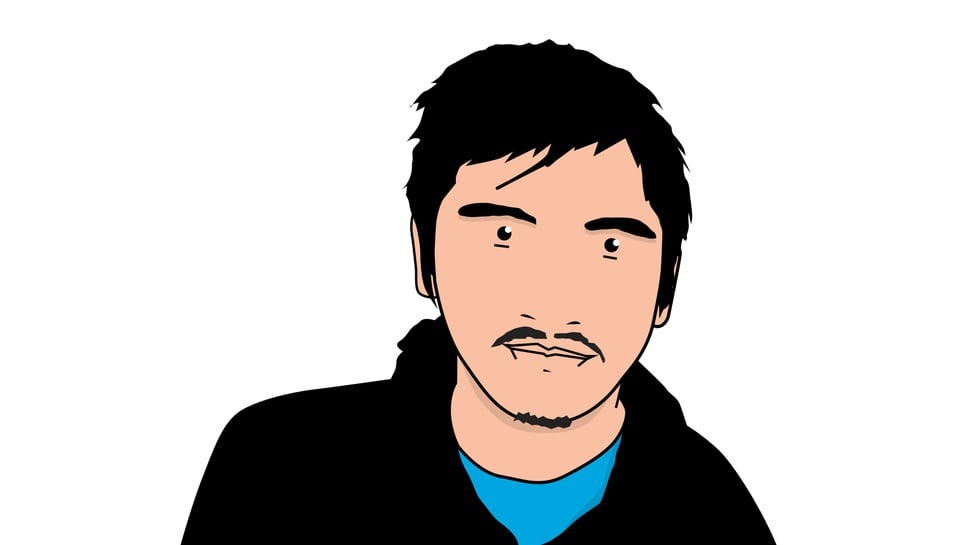tirto.id - Video pendek yang merupakan teaser reportase panjang di Pandeglang dibuka dengan pekik takbir. Pekik itu tidak dalam rangka aksi #BelaIslam atau Pilkada Jakarta, melainkan dalam aksi #BelaMataAir. Warga dari beberapa desa di Pandeglang menggelar perlawanan terhadap salah satu anak perusahaan Mayora Grup yang mendapatkan konsesi penguasaan sumber mata air di kampung halaman mereka.
Tentu saja demonstran dalam video tersebut tidak membawa-bawa, apalagi menyebarkan, spanduk dan stiker "pribumi" sebagaimana terjadi pada Aksi Bela Islam 313 yang lalu. Padahal, jika kepribumian ditakar berdasarkan durasi tinggal di sebuah kawasan, misalnya, apa yang kurang pribumi dari masyarakat adat atau para petani Kendeng, suku Amungme atau para petani di Kulonprogo dan Sukamulya (Majalengka) yang sawahnya dibuldozer untuk membangun bandara? (laporan khusus: Bertahan di Antara Patok-Patok Bandara).
Klaim-klaim kepribumian justru membuncah di kota-kota besar, khususnya Jakarta, dan bukan di kalangan masyarakat adat atau masyarakat desa yang sedang menghadapi konflik agraria dengan berbagai proyek infrastuktur dan investasi. Dalam banyak kasus, klaim kepribumian, apalagi jika diembel-embeli dengan jargon nasionalisme, memang tidak menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial-ekonomi.
Baca juga: Pejabat dan Tokoh yang Pernah Mengungkit Istilah Pribumi
Warga suku Amungme, misalnya, sama sekali tidak tertarik dengan jargon-jargon nasionalisme dalam tarik-ulur antara pemerintah Indonesia dengan Freeport. Saat banyak orang-orang di kota menyambut sikap keras rezim Jokowi yang ingin mengambilalih saham mayoritas, dan dengan demikian nasionalisme ekonomi tampak menemukan pengejawantahannya, mereka tetap bersuara keras. Alasannya sederhana: tarik ulur itu tidak pernah melibatkan orang-orang Amungme.
Menguasai saham mayoritas, dan dengan demikian membuat kendali eksplorasi Freeport ada di tangan pemerintah Indonesia, bagi suku Amungme, tidak bermakna apa-apa. Ini hanya kemenangan bagi Jakarta, bukan bagi mereka. Jakarta yang memandang dan yang menentukan, dan suku Amungme hanyalah penonton di tanahnya sendiri (baca: Suku Amungme dan Komoro Terabaikan di Bumi Emas dan Tembaga).
Memandang Pribumi
Sepekan sebelum Aksi Bela Islam 313, beredar video yang dianggap memperlihatkan sosok manusia kerdil di pedalaman Aceh. Seperti suku Amungme, sosok yang diduga manusia kerdil itu dipandang dari jauh, dari (perspektif) Jakarta. Videonya beredar dengan cepat, dan media memantulkannya dengan segala kesan heboh, takjub, heran dan penasaran.
Jika memang sosok dalam video itu adalah orang kerdil, ada juga yang menganggapnya orang Suku Mente, pernahkah terlintas di kepala bahwa merekalah yang justru pribumi di tanah itu? Dapatkah kita menerimanya?
Cara pandang terhadap sosok dalam video tersebut mengingatkan saya kepada perspektif kolonial.
Salah satu bagian buku Dutch Culture Overseas karya Francess Gouda, khususnya bab 4, mengisahkan bagaimana koran-koran pada awal abad 20 di Hindia Belanda senang betul, dan bahkan penuh semangat, melaporkan kesaksian orang-orang yang bertemu dengan “manusia kerdil” di belantara Sumatera di sekitar Jambi.
Perhatian terhadap kesaksian-kesaksian tentang manusia kerdil menyiratkan bagaimana orang Eropa di Hindia Belanda saat itu masih terobsesi dengan konsep missing link dalam teori evolusi dan bahkan sampai pada tahapan mencoba meyakini bahwa ada kemiripan yang sahih antara manusia pribumi dengan kera-kera besar yang ditemukan di belantara Sumatera dan Kalimantan.
Prasangka, atau bahkan kekasaran, rasialis itu seringkali dibungkus dengan kosa kata yang terlihat ilmiah. Gouda sempat mengutip pernyataan seorang psikiater Belanda yang bekerja di Jawa pada 1920-an. Dia bilang: “Laki-laki dan perempuan Jawa dewasa masih memperlihatkan kelemahan psikologis khas anak-anak karena kaum inlanders itu masih berada pada tahap awal perkembangan evolusi mereka.”
Simak juga kutipan ini: “Siapa yang berani memanggil makhluk-makhluk ini (pribumi)? Yang matanya lebih menyerupai kera daripada orang-orang berkulit merah di (Amerika Utara) yang jinak.”
Pribumi di Hindia Belanda, dalam kutipan di atas, bahkan disebut lebih mirip kera ketimbang orang-orang Indian di Amerika. Kutipan di atas berasal dari roman Number Elf (Nomor Sebelas) karya Paulus Adrianus Daum, roman yang terbit pada 1889, setahun setelah Haji Wasid, dkk., menggelar perlawanan legendaris para petani Banten (baca: Kehidupan di Zaman Hindia Belanda).
Daum lahir di 's-Gravenhage, Belanda, pada 3 Agustus 1850. Dia berkiprah di Hindia Belanda, tepatnya Jawa, sebagai jurnalis dan penulis. Ia setidaknya pernah bekerja di tiga surat kabar, De Locomotief di Semarang, Het Indisch Vaderland dan di Bataviaasch Nieuwsblad yang ia sendiri yang mendirikan.
Karya-karya fiksi Daum, baik yang berupa roman maupun lakon, banyak memuat karakter nyai -- termasuk Number Elf. Jika pada awalnya ia sangat mudah melihat orang-orang Jawa dengan pandangan negatif, karya-karya terakhirnya, termasuk Number Elf, mulai lebih simpatik membicarakan orang-orang Jawa (Gerard Termorshuzen, "P.A. Daum on Colonial Life in Batavia").
Akan tetapi, bias Eropa, atau bias kolonial, tetap tidak terhindarkan. Mela Sutedja-Liem menyebut roman Daum itu "memenuhi kebutuhan kolonial untuk mempertajam perbedaan (ras) antara orang berkulit putih dan penduduk setempat. Nyai dipergunakan sebagai lambang degenerasi, lambang peruntuhan masyarakat kolonial. ("Menghapus Citra Buruk 'Njai' dalam Karya-Karya Fiksi Berbahasa Melayu", Jurnal Wacana Vol. 10 no 2, Oktober 2008).
Kutipan seorang psikiater maupun kutipan Daum di atas, jika ditulis ulang dalam kalimat yang bernada Darwinian, kira-kira akan menjadi begini: "Para inlanders itu masih berada pada tahap transisi sebagai kera besar yang memulai proses menjadi homo sapiens."
Dari obsesi terhadap manusia kerdil, bingkai negatif kepada para nyai, hingga berbagai stereotipe lainnya kepada penduduk pribumi. Yang paling masyhur adalah mitos pribumi malas. Atau mitos pribumi jorok.
Rudolf Mrazek, pada bab 1 buku Engginers of Happyland, membedah bias kolonial dalam prasangka pribumi jorok sekaligus menjlentrehkan obsesi kolonial untuk membersihkan bumi Jawa dari kejorokan yang tanpa tedeng-tedeng aling. Saking jijiknya, seorang penulis Belanda, Henrik Tillema, bahkan dengan telengas menyebut Jalan Raya Daendels sebagai sebuah "jamban raksasa" karena para pribumi dengan seenaknya berak di pinggir jalan atau membuang tai dari rumah-rumah ke pinggir jalan.
Tillema mensejajarkan pribumi yang sakit (karena jorok) dengan jalan-jalan yang juga kotor dan penuh penyakit. Dikutip dari Mrazek, beginilah Tillema menyusun penyejajaran: "Tepat seperti kami siap untuk memberi obat kepada penduduk di sini yang sakit, maka seharusnya begitu pula dengan jalan-jalan yang sakit."
Segala spekulasi yang mencuat dari teori evolusi memungkinkan bias kolonial bekerja menyusun hierarki kebudayaan dan peradaban, bahwa peradaban mereka lebih tinggi dan peradaban pribumi lebih rendah.
Niscaya segala pandangan itu akan menjengkelkan para pemimpin pergerakan. Orang seperti Agus Salim, yang menjadi nomor satu dalam ujian akhir sekolah elit HBS, mengalahkan termasuk seluruh murid-murid Eropa, pasti jengkel bukan main. Saya membayangkan bagaimana jengkelnya perasaan para pemimpin pergerakan kalau membaca kutipan-kutipan itu.
Akan tetapi jebakan teori evolusi ini memang tidak terhindarkan, bahkan bagi para pemimpin pergerakan sekali pun. Salah satu contohnya adalah Tjipto Mangoenkosoemo, orang yang sangat berani, bukan hanya kepada pemerintahan kolonial namun juga dalam menghadapi wabah pes. Dalam salah satu pidatonya di Volksraad yang (kalau saya tidak salah) membicarakan tentang Bali, ia berkata bahwa kemerdekaan adalah “kondisi utama dan penting bagi proses evolusi kaum pribumi”.
Bedanya, barang kali, cukup banyak para pemimpin pergerakan yang tidak hanyut pada dikotomi pribumi dan non-pribumi. Dan Tjipto adalah salah satunya. Bersama Soewardi Soerjaningrat, yang saat itu belum menyandang nama Ki Hadjar Dewantara, ia setuju untuk bergabung dengan Douwes Dekker untuk mendirikan Indische Partij, atau Partai Hindia.
Ini partai yang sangat progresif pada masanya. Didirikan pada 1912, Indische Partij ini banyak mengakomodasi orang-orang Indo-Eropa yang menganggap Hindia sebagai tanah airnya. Hindia untuk orang Hindia, begitulah semboyan Indische Partij. Siapa itu orang Hindia? Siapa pun yang lahir, besar dan mati di Hindia. Mau itu keturunan Belanda, Cina, Arab atau mana pun.
Saking pentingnya Indische Partij, sejarawan Takashi Shiraishi menyebut bahwa era modern perlawanan atas kolonialisme baru benar-benar dimulai sejak berdirinya Indische Partij, khususnya setelah organ ini menerbitkan pamflet "Andai Saya Orang Belanda" yang ditulis Soewardi Soerjaningrat.
Pamflet dahsyat itu, dengan cara yang cerdik sekali, dengan memaksimalkan fakultas imajinasi, mempermainkan prasangka kolonial yang dibentuk oleh teori evolusi: orang "pribumi" itu bisa menjadi Eropa, kok, dan orang Eropa pun bisa saja menjadi pribumi.
Melampaui Kepribumian ala Tirto
Langkah yang tidak kalah radikal, bahkan mencerminkan apa yang dikatakan Tan Malaka sebagai “lompatan kualitatif”, sudah diambil oleh Tirto Adisoerjo saat mendirikan surat kabar Medan Prijaji pada 1907, setahun sebelum Beodi Oetomo dan empat tahun sebelum pamflet “Andai Saya Orang Belanda” terbit. Medan Prijaji memilih kalimat “Suara bagi mereka semua yang terprentah” sebagai semboyannya.
Yang dimaksud “terprentah” adalah siapa saja yang terprentah, baik itu raja-raja, bangsawan, priyayi, bangsawan usul dan pikiran (intelektual/kaum terpelajar) hingga saudagar-saudagar dari, dengan mengutip Medan Prijaji, “bangsa jang terprentah laennja jang dipersamakan dengan Anaknegeri, di seloeroeh Hindia Olanda”.
Jadi para raja-raja dan bangsawan pun masuk kategori “terprentah”? Dalam pembayangan Tirto sebagai perumus, pendiri dan pemimpin redaksi, mereka bukan “yang memrentah”. Satu-satunya yang dibayangkan Tirto sebagai “yang memrentah” adalah pemerintah kolonial Belanda.
Lalu mengapa Tirto juga mengizinkan bangsa-bangsa Arab, India atau Cina sebagai mereka “yang diprentah”?
Pemerintah kolonial memang membagi kewarganegaraan ke dalam tiga kategori yaitu orang-orang Eropa, orang-orang Timur Asing (vremde oosterlingen) dan inlander (pribumi). Arab, India, dan Cina masuk ke dalam vremde oosterlingen (orang Jepang kemudian dimasukkan dalam kategori Eropa). Inilah segregasi rasialis bikinan Belanda.
Dalam politik kewarganegaraan kolonial itu, Belanda atau orang Eropa tidak masuk kategori sebagai “orang asing”. Tidak ada kosa kata vremde westerlingen (Barat Asing), yang ada hanya vremde oosterlingen (Timur Asing). Alasannya sederhana: Belanda, juga orang Eropa, adalah penguasa di tanah jajahan. Mereka ada di kelas yang melampaui asing atau pribumi, vremde atau inlander.
Jadi jika ada pertanyaan siapa lawan inlander atau pribumi, menurut Dhaniel Dhakidae dalam Cendekiawan dan Kekuasaan, jawabannya bukan orang kulit putih melainkan orang-orang yang masuk dalam kategori vremde oosterlingen, di dalamnya termasuk Arab dan India selain Cina.
Tirto melampaui semua itu. Pembelahan “bangsa yang terprentah” dan “bangsa yang memrentah” tidak berdasarkan kategori asal-usul ras alias politik identitas, melainkan kategori kelas: antara yang berkuasa dan yang dikuasai, antara tuan dan kawula (uraian lengkap tentang Tirto Adisoerjo, baca: Sang Pemula di Segala Lini Massa).
Dengan itulah Tirto hendak mengarahkan perjuangannya, melalui Medan Prijaji, bukan untuk menghancurkan supremasi rasial kulit putih, melainkan supremasi ekonomi dan politik kolonial. Yang ia lawan bukan Belanda/Eropa sebagai ras kuit putih, melainkan Belanda/Eropa sebagai pengeruk laba dan penguasa di tanah jajahan. Siapa pun yang menderita karena buldozer kolonial, merekalah bangsa yang terprentah, mau pribumi atau bukan, inlander atau vremde oosterlingen bahkan Indo dan orang Eropa sekali pun, ayo bergabung dalam satu barisan.
"Pribumi" vs "pribumi"
Saling silang antara kategori kelas dan kategori ras (politik identitas) di medan pergerakan nasional tentu saja tidak tuntas hanya semata oleh rumusan Tirto. Perdebatan tentang negara dan bangsa di zaman pergerakan memperlihatkan kelindan antara ras dan kelas itu terus berlangsung. Risalah perdebatan BPUPKI juga memperlihatkan soal kelas atau ras itu terus menjadi bahan perdebatan dan negosiasi.
Lebih dari seabad lampau, Tirto sudah berusaha melampauinya. Dan hari ini, pada 2017, kampanye soal pribumi dan non-pribumi kembali lagi kepada kategori rasial yang dikembangkan oleh cara berpikir kolonial. Tidak hanya mundur, namun juga menyederhanakan wacana kepribumian dalam kerangka politik elektoral Pilkada DKI.
Jebakan klaim kepribumian yang dipakai dalam politik elektoral ialah menyederhanakannya kepada figur yang menjadi kandidat. Adu jago elektoral ini, baik dalam Pilkada maupun Pilpres, nyaris tidak menyinggung persoalan genting yang sedang dihadapi masyarakat adat dan warga-warga desa yang sedang berusaha mempertahankan hak atas tanah dan aset-aset komunal lainnya.
Jika pun dalam politik elektoral ada yang bersuara, sering kali dibimbing oleh penalaran politik elektoral juga: karena semuanya terjadi, setidaknya kini, saat rezim yang berkuasa adalah lawan politik. Jika kubunya sendiri yang berkuasa, sangat biasa jika orang-orang yang meneriakkan klaim kepribumian ini akan bungkam juga.
Penyingkiran ras tertentu dari tampuk kekuasaan, pada akhirnya, belum tentu dapat menyelesaikan persoalan masyarakat adat dan warga-warga desa di berbagai tempat yang sedang mempertahankan tanah dan aset-aset komunalnya. Mereka, misalnya warga suku Amungme, tidak dianggap sebagai "pribumi" karena kepribumian itu, dalam bentuk nasionalisme ekonomi, telah dikuasakan secara manasuka kepada dan/atau oleh pemerintah yang menginginkan 51% saham Freeport.
Inilah kontestasi antara "Pribumi" vs "pribumi", antara "P" besar dan "p" kecil, yang hampir pasti akan dimenangkan oleh "Pribumi": mereka yang menjadi penguasa, yang memegang kendali aparat dan hukum, dan karenanya dengan mudah mendapatkan sokongan dari pemodal-pemodal besar yang berasal dari mana-mana, entah dari luar negeri entah dari dalam negeri, entah yang matanya sipit, matanya belo, matanya biru atau yang rambutnya keriting.
Bukankah Jokowi juga berkulit cokelat dan seiman dengan para peserta Aksi 313? Bukankah Bupati Rembang, yang menjadi tempat berlangsungnya konflik antara Yu Patmi, dkk., dengan PT Semen Indonesia, juga berkulit cokelat dan seiman para peserta Aksi 313? Bukankah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang ngebet membangun Bandara Kertajati yang menyingkirkan para petani Sukamulya pun berkulit cokelat dan seiman para peserta Aksi 313 (baca: Tak Ada Naga Bonar di Sukamulya)? Juga Bupati Pandeglang, baik pada periode sekarang dan sebelumnya, yang bertanggungjawab dalam perizinan operasi Mayora Grup adalah juga berkulit cokelat dan seiman dengan para peserta Aksi 313?
Tentu saja pribumi bukan monyet sebagaimana yang tersirat dalam prasangka rasialis orang-orang Belanda yang sudah saya singgung di bagian sebelumnya. Namun kehebohan menyaksikan video yang diduga memperlihatkan orang kerdil di Aceh menjelaskan satu hal penting: kepribumian hanyalah tentang "kita", tentang siapa yang sepaham dengan "kita", dan bukan tentang "yang-lain" yang tak dikenal -- mirip dengan cara pandang kolonial terhadap orang-orang Jawa sebagaimana dijlentrehkan Mrazek di atas.
Jangan-jangan memang tidak ada keseriusan dalam soal klaim kepribumian ini karena, en toch, masih menganggap orang-orang Papua berkoteka adalah terbelakang, menganggap Yu Patmi, dkk., tidak nasionalis karena menolak perusahaan semen BUMN, dan pada saat yang sama senang berkongsi dengan jaringan konglomerasi -- dari Harry Tanoe maupun Aguan hingga Cendana.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.