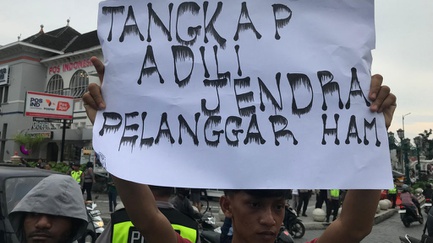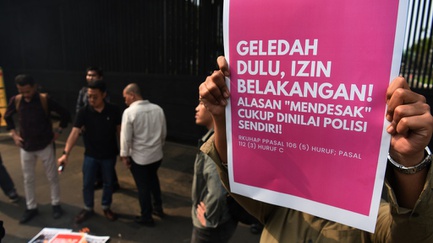tirto.id - Deanda Dewindaru masih berusia 29 tahun. Fisiknya terlihat bugar. Wajahnya juga segar. Namun ternyata, tubuhnya rapuh. Dia mengidap tiga jenis penyakit autoimun. Pergerakannya terbatas.
Kondisi itu yang membuat Deanda sempat putus asa. Saat hendak berobat ke rumah sakit, dia sulit mendapatkan perlakuan khusus karena kondisinya yang tersembunyi. Dia sakit, tapi sering kali dianggap sehat.
Riset terbaru dr Faisal Parlindungan dan tim dari Universitas Indonesia mengungkap fenomena yang dialami Deanda juga terjadi kepada pasien lain. Salah satu risetnya berfokus pada alasan pasien autoimun putus berobat (lost to follow up).
Penelitian tersebut mengamati lebih dari 300 pasien autoimun baru antara tahun 2021 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, ditemukan bahwa 25 persen pasien putus berobat. Pasien didefinisikan putus berobat jika tidak datang selama tiga bulan berturut-turut.
Melalui survei wawancara telepon, berbagai faktor penyebab diidentifikasi. Namun, setelah analisis mendalam menggunakan metode multivariat, akses angkutan umum menjadi satu-satunya faktor penentu yang paling signifikan.
"Kita jumpai ada satu faktor yang paling signifikan satu-satunya itu adalah akses akses angkutan. Nah ini membuat kami kaget, namun kenapa malah akses ini yang menjadi satu-satunya faktor yang signifikan pada analisis-analisis multivariat kami,” kata dr Faisal saat diwawancarai Tirto dalam program kueri, Agustus 2025 lalu.
Temuan ini mengejutkan karena Jakarta, sebagai ibu kota, seharusnya memiliki beragam pilihan transportasi umum. Namun, pasien justru menceritakan bahwa perjalanan ke rumah sakit menggunakan angkutan umum bisa membuat mereka pingsan atau terbaring lemas seminggu karena kelelahan.
Faisal menekankan bahwa meskipun tampak sehat, pasien autoimun mengalami gangguan fungsi yang nyata. Penyakit mereka di dalam tidak terlihat mata telanjang, namun efeknya, seperti kelelahan ekstrim akibat panas atau aktivitas fisik, menyebabkan gangguan fungsi yang nyata dan memenuhi definisi disabilitas.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkirakan ada 2,5 juta penderita autoimun di Indonesia. Jumlah ini diprediksi belum lengkap karena tidak banyak riset soal penyakit ini di Indonesia.
Kisah Deanda: Stigma, Penderitaan, dan Gugatan ke MK
Kisah Deanda memvalidasi riset Faisal dan tim. Wanita yang bekerja sehari hari sebagai dosen tersebut menderita Guillain-Barré Syndrome, Sjögren's Syndrome, dan Inflammatory Bowel Disease (IBD).
Kondisinya memburuk jika terpapar panas atau kelelahan, menyebabkan tubuh lemas, diare, atau kesulitan bergerak. Penyakit ini baru ia alami sejak setelah terkena COVID-19 pada 2020.
"Waktu itu di tahun 2022 pas lagi bangun tidur tuh enggak bisa jalan. Makin lama makin lama di situ ada suatu kondisi di mana benar-benar tuh enggak bisa gerak sama sekali gitu,” ucap Deanda.
Ia pernah harus berhenti berobat ke RSU Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) karena sulitnya akses dari Bekasi. Perjalanan yang mengharuskannya naik kereta dan transit di Manggarai, seringkali harus berdiri, berisiko membuatnya pingsan.
Deanda juga menghadapi stigma karena penampilannya yang terlihat sehat. Orang enggan memberinya tempat duduk prioritas, bahkan pernah dibilang, "Mbak, kan, masih muda".
Kondisi ini menjadi pendorong bagi Deanda, bersama Raisa dan Fauzi, untuk mengajukan uji materiil Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mengupayakan agar penyakit kronis seperti autoimun dapat secara eksplisit masuk dalam kategori disabilitas.
“Teman-teman yang sakit kronis khususnya misalkan autoimun itu tidak memiliki payung hukumnya nih. Sehingga terdapat beberapa kebijakan yang hanya bersifat diskresi aja,” ucapnya.
Mereka menuntut perubahan frasa "antara lain" yang sering diartikan secara sempit pada disabilitas fisik yang terlihat, agar tidak terbatas pada kondisi seperti lumpuh atau cerebral palsy.
Apa Fokus Selanjutnya?
Berangkat dari riset dan pengalaman pasien, dr Faisal dan timnya melanjutkan penelitian kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan komunitas autoimun. Salah satu temuan penting dari FGD adalah kebutuhan mendesak akan penanda khusus bagi penyandang disabilitas tak tampak.
"Harus ada penanda khusus setuju banget sih, apalagi kalau yang masih muda sih, Mas. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih muda, kayak saya ini, kan, enggak kelihatan sama sekali gitu, kan, padahal mungkin dalamnya udah rapuh gitu,” kata Deanda.
Sebelumnya, istilah "hidden disability" tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Melalui kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI, dr. Faisal berhasil mengusulkan padanan istilah "disabilitas tak tampak" yang kini resmi tercantum di KBBI.
"Alasannya apa ketika kita mau advokasi bahkan kita sudah mikirin, nih, kalau kita mau advokasi bahkan mengubah undang-undang mesti ada dong istilah yang baku. Tapi istilahnya masih istilah asing,” ungkapnya.
Inisiasi untuk mengenali disabilitas tak tampak di Indonesia datang dari para dokter. Dr. Faisal dan timnya telah memulai advokasi dengan TransJakarta (TJ), yang menyambut baik gagasan ini.
Pada Mei 2024, mereka meluncurkan program percontohan dengan TransJakarta, menciptakan logo dan lanyard khusus sebagai identifikasi bagi penyandang disabilitas tak tampak. Simulasi penggunaannya telah dilakukan di Stasiun Cawang pada Agustus.
Dalam simulasi tersebut, petugas diharapkan mengenali lanyard dan memberikan akses prioritas layaknya penumpang lain. Meski ini adalah langkah awal yang penting, Dr. Faisal mengakui bahwa masih membutuhkan waktu panjang untuk sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan agar semua petugas dapat mengenali penanda ini.
Inisiatif ini merupakan upaya konkret untuk memastikan pasien autoimun dapat menjalani pengobatan secara teratur, mengurangi risiko putus berobat, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat tanpa hambatan yang tidak perlu.
Editor: Farida Susanty
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id