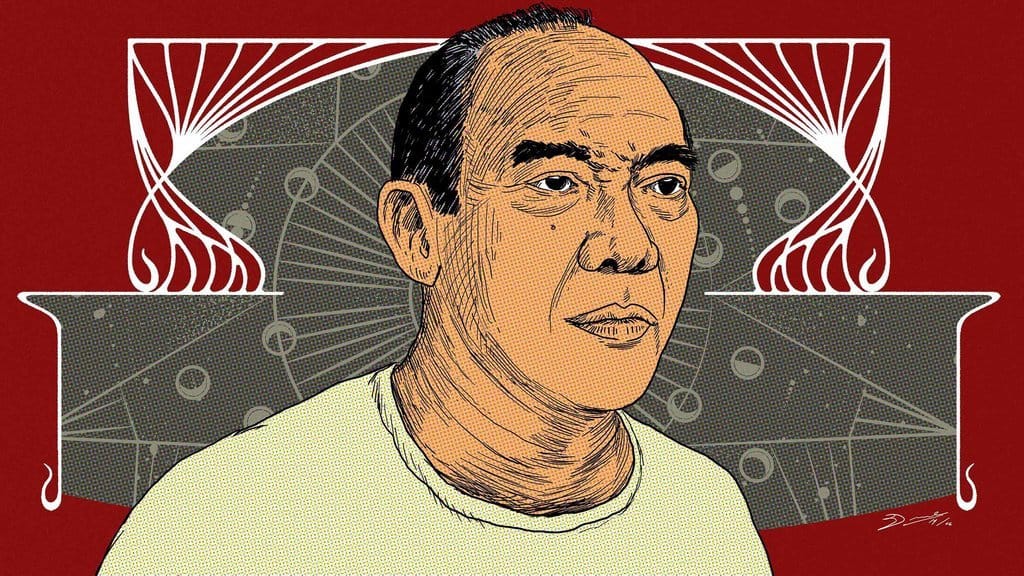tirto.id - Pada 6 Juni 1970, Sukarno merayakan ulang tahunnya yang ke 69. Kelima anaknya dari Fatmawati, Hartini dan dua anaknya, Bayu dan Taufan, hadir di Wisma Yasoo di hari bahagia itu. Namun, tak ada lagi karangan bunga, ucapan selamat, atau hadiah-hadiah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang ada hanyalah Sukarno yang semakin ringkih digerogoti penyakit dan depresi.
Di hari bahagia itu pun, Sukarno tak bisa beranjak dari tempat tidur karena kondisi kesehatannya yang sudah sangat mundur. Siapa nyana, hari itu ternyata jadi ulang tahun terakhir Sukarno. Pada 11 Juni, Sukarno dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisi kesehatannya memburuk.
Di rumah sakit, Bung Karno diopname di bagian intensive care. Di saat seperti itu pun, penjagaan ketat atas diri si Bung Besar tak dikendurkan sama sekali.
“Sukarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit, bercat kelabu. Untuk mencapai kamar itu harus melalui beberapa koridor yang dijaga militer dengan persenjataan lengkap,” tulis Peter Kasenda dalam Hari-hari Terakhir Sukarno (2013, hlm. 230).
Hari Kamis, 18 Juni 1970, Sukarno masih sadar, meski kesulitan bicara. Sukarno ingin menulis sesuatu bagi Megawati, tapi urung karena dia sudah tidak punya daya lagi. Malam harinya, Sukarno mengalami koma.
Esoknya, Sukarno kedatangan tamu yang barang kali memberinya sedikit kelegaan hati. Tamu itu adalah sahabat lamanya, Mohammad Hatta. Sebagaimana anak-anak Sukarno, Hatta pun musti lebih dulu dapat izin dari Soeharto untuk datang menjenguk.
Dua proklamator yang pecah kongsi sedari 1956 itu akhirnya bertemu dalam momen yang amat menyentuh. Sejak mereka berpisah, Hatta menjadi salah satu kritikus Sukarno yang paling vokal.
"Hatta dan aku tak pernah berada dalam getaran gelombang yang sama," tutur Sukarno dalam autobiografinya.
Tapi, perbedaan jalan politik tak melunturkan persahabatan mereka. Bagaimanapun, dua orang itu pernah menghadapi masa sulit bersama-sama. Kisah pertemuan dua tokoh Dwitunggal itu, sebagaimana dituturkan oleh putri Bung Hatta Meutia Farida Swasono-Hatta, dapat disimak dalam Bung Hatta: Pribadinya dalam Kenangan (1980, hlm. 57-58).
Begitu diperbolehkan memasuki ruang perawatan Sukarno, Hatta langsung menghampiri tempat tidurnya.
“Aa, No, apa kabar?” sapa Bung Hatta.
Sukarno hanya diam memandangi Hatta beberapa lama. Dengan susah payah Bung Karno akhirnya buka suara juga.
“Hoe gaat het met jou? (Apa kabar?),” balas Bung Karno.
Bung Karno terlihat menitikkan air mata ketika Bung Hatta memijiti lengannya. Tak ada kata-kata lain yang terucap di antara keduanya. Beberapa saat kemudian, Bung Karno minta dipasangkan kacamata supaya bisa memandang sahabat lamanya itu lebih jelas.
“Tak ada kata-kata lebih lanjut, namun kiranya hati keduanya saling berbicara. Mungkin juga beliau mengenangkan suka-duka di masa perjuangan bersama sejak puluhan tahun yang silam, masa-masa pergaulan bersama dan mungkin saling memaafkan,” tulis Meutia.
Kedatangan Ratna Sari Dewi
Di hari itu juga, keluarga Sukarno mendapat kabar bahwa Ratna Sari Dewi akan datang menjenguk Sukarno. Saat itu, dia masih tertahan di Singapura karena belum dapat izin dari rezim Soeharto. Baru keesokan harinya Dewi mendapat izin.
Rachmawati Sukarnoputri, begitu bungah mendengar kabar itu. Dia tahu benar perempuan jelita itulah yang bisa melipur hati Sukarno yang lama kering. Setidak-tidaknya di saat terakhir ada seketip kebahagiaan untuk bapaknya.
Dewi membawa serta buah hatinya dengan Sukarno, Kartika Sari Dewi. Kala itu, Kartika yang lebih akrab disapa Karina baru berumur tiga tahun. Karena lahir di Jepang, Sukano belum pernah melihat anaknya hingga saat itu.
“Karina ke sini, ini Bapak, this is your father, Karina,” kata Dewi ketika keduanya akhirnya bertemu lagi.
Antara sadar dan tidak, tangan Sukarno bergerak seakan ingin menggapai putri kecilnya. Sayang sekali, Sukarno sudah tak punya daya apa-apa lagi. Bahkan, untuk mempertahankan kesadaran adalah perjuangan baginya kala itu.
Usai kedatangan Dewi dan Kartika kesadaran Sukarno berangsur hilang. Menjelang tengah malam ia kembali mengalami koma. Arkian, hari Minggu pagi, titimangsa 21 Juni 1970, Ketua Tim Dokter Kepresidenan Mahar Mardjono menginsafi bahwa Sukarno telah sampai ajalnya.
Jenazah Sukarno lantas dibaringkan di Wisma Yasoo, sebagaimana instruksi rezim Orde Baru Soeharto. Sebelumnya, Fatmawati telah meminta agar jenazah mantan suaminya itu disemayamkan di rumahnya, tapi ditolak.
Fatmawati pun enggan datang ke Wisma Yasoo—rumah yang dipersembahkan Sukarno untuk Dewi. Menurut M. Yuanda Zara dalam Sakura di Tengah Prahara: Biografi Ratna Sari Dewi Sukarno (2008), Dewi menampilkan diri di sebelah tempat persemayaman sebagai janda nan berduka. Begitu pula Hartini, yang menerima pernyataan bela sungkawa sebagai seorang janda.
Haryati, janda Sukarno yang lain, juga datang ke Wisma Yasoo. Namun, dia tidak tinggal lama karena Dewi memperlakukannya dengan begitu tidak sopan. Yurike Sanger yang secara resmi masih berstatus istri Sukarno, tidak datang.

Pemakaman
Hari itu, berita wafatnya Sukarno tersebar dengan cepat dan orang-orang segera bertanya, di mana Sukarno akan dimakamkan.
Cindy Adams mengisahkan dalam bukunya Sukarno My Friend (1971), Sukarno pernah menyatakan ingin dikubur di bawah batu nisan nan ugahari, yang hanya bertulis, “Di sini beristirahat Sukarno, penyambung lidah rakyat Indonesia.” Akan tetapi, Sukarno tidak pernah menyebut dengan pasti di mana dia ingin dipusarakan. Dia pernah menyebut di Bandung, di daerah Priangan, tapi pernah juga minta di tanahnya di Batutulis.
Meski begitu, Dewi dan Hartini lantas mengajukan permohonan untuk memakamkan Sukarno di Batutulis. Soeharto menolak permohonan itu. Malahan, menurut Soeharto, sama sekali tidak ada kesepakatan di antara keluarga Sukarno tentang tempat peristirahatan terakhirnya.
Dengan ironis, Soeharto menuturkan dalam otobiografinya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi Soeharto, Seperti Dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. (1989), “Kalau saya menuruti kehendak mereka, pernyataan itu pasti tidak terjawab.”
Menurut Soeharto lagi, Sukarno semasa hidupnya amat mencintai ibunya. Dulu, Sukarno tak pernah alpa untuk sungkem dan minta doa restu ibunya setiap hendak bepergian jauh. Maka Soeharto memutuskan untuk memakamkan Sukarno di Blitar, di dekat pusara ibunya.
Melalui sebuah rapat kabinet yang dipimpinnya sendiri, Soeharto juga memutuskan pemakaman akan dilakukan dengan upacara kenegaraan dan akan diumumkan masa berkabung selama satu minggu.
Senin, 22 Juni 1970, Soeharto menyerahkan jenazah Sukarno kepada Pejabat Panglima Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Jenderal Panggabean. Dialah yang akan mengantarkan Sukarno ke tempat peristirahatan terakhirnya. Soeharto mengucapkan kata-kata khidmat yang terdengar getir bagi sekalangan orang yang mengenal Sukarno.
“Atas nama rakyat, pemerintah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, saya kembalikan Anda, Ir. Sukarno, wafat pada 21 Juni 1970, kepada tanah air. Semoga jiwa Anda diterima di sisi Tuhan. Dan semoga semua perbuatan dan pengabdiannya menjadi contoh bagi kita semua.”
Puluhan ribu orang memenuhi jalanan Jakarta, dari Wisma Yasoo hingga Lapangan Udara Halim Perdanakusumah, untuk memberi penghormatan terakhir kepada Bung Karno. Begitu pun ketika jenazah Sukarno tiba di Jawa Timur. Arak-arakan duka tak putus kira-kira sepanjang 40 kilometer, dari Malang hingga Blitar.
Sebuah barisan pengawal kehormatan yang terdiri dari empat angkatan bersenjata melepaskan tembakan kehormatan ketika almarhum, sesuai hukum Islam dihadapkan wajahnya ke arah Makkah dan ditutupi dengan bendera merah-putih, lalu diturunkan dalam liang kubur yang digali di samping pusara sanga ibu. Requiescas in Pace—Semoga Engkau beristirahat dalam ketentraman—Bung Karno.
==========
Muhammad Iqbal adalah sejarawan kelahiran Amuntai, Kalsel. Sehari-hari ia mengajar di IAIN Palangka Raya dan menjadi editor penerbit Marjin Kiri. Baru-baru ini ia menulis buku berjudul Menyulut Api di Padang Ilalang: Pidato Politik Sukarno di Amuntai 27 Januari 1953.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id