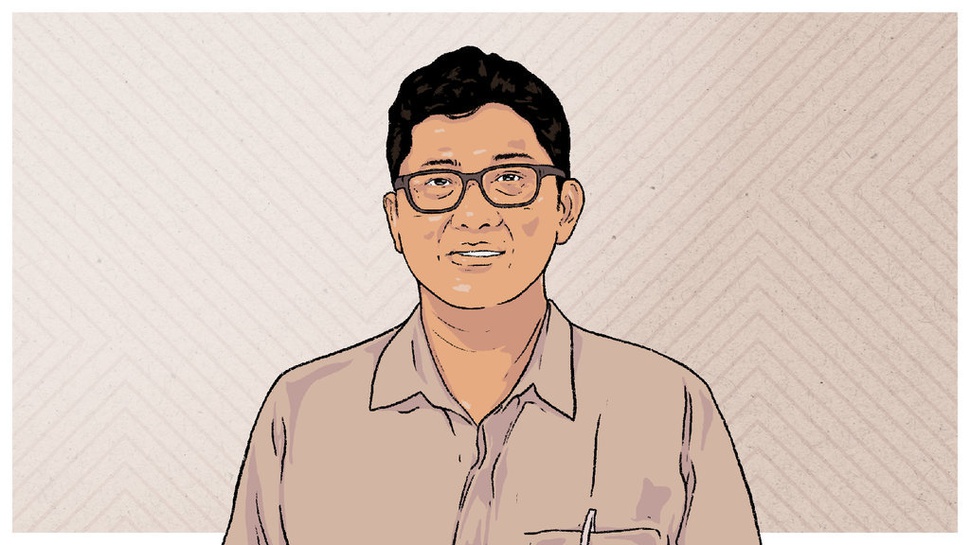tirto.id -
Putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia capres cawapres ini meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman, untuk melenggang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Dalam putusan tersebut, MK menyatakan syarat cawapres “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."
MK menilai permasalahan umur tidak menjadi masalah untuk menjadi capres atau cawapres selama sudah pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Mahkamah beranggapan bahwa mereka yang sudah dipilih lewat pemilu bisa maju di pilpres.
Pakar Hukum Tata Negara, Herlambang P Wiratraman, menilai keputusan MK tersebut jelas menodai demokrasi di Tanah Air. Praktik kotor ini sama dengan mengacak-acak sistem politik dan demokrasi di Indonesia.
"Kalau ini dibiarkan cara-cara berpolitik melalui kekuasaan Yudisial itu sudah merusak sendi atau pondasi dasar dari negara hukum," kata Herlambang dalam acara Podcast For Your Pemilu, di kantor Tirto beberapa waktu lalu.
Kejadian ini, menurut Herlambang, membuat legitimasi Pemilu 2024 menjadi patut dipertanyakan publik. Sebab, Pemilu 2024 berangkatnya saja sudah dinilai bermasalah.
Kepada Tirto, Herlambang memberikan pandangannya terkait putusan MK hingga putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) dan situasi politik serta demokrasi di Indonesia saat ini. Berikut petikan wawancara Tirto dengan Herlambang:
Setelah putusan MKMK yang ramai kemarin, bagaimana Mas Herlambang melihat nasib legitimasi Pemilu kita di 2024?
Kita melihat ini bukan soal sederhana. Bukan sekedar pencapresan Gibran. Bukan juga sekedar bahwa ada masalah prosedur formal yang ditabrak. Tapi ini lebih kepada sistem politik dan demokrasi kita yang sedang diacak-acak, sehingga membuat kami 15 akademisi itu harus melakukan sesuatu bareng-bareng untuk mengingatkan kepada penyelenggara kekuasaan. Kalau ini dibiarkan cara-cara berpolitik melalui kekuasaan yudisial itu sudah merusak sendi atau pondasi dasar dari negara hukum.
Kalau kita mendaku negara hukum di Indonesia kan mestinya dijaga pilar-pilar kekuasaannya. Di situ sebenarnya tantangannya adalah kita tahu bahwa pemilu itu salah satu instrumen politik yang bekerja di dalam sebuah negara demokrasi. Namun, tantangannya tidak bisa dipandang lagi sebagai instrumen ketika sistem politiknya menggunakan alat sebagai kepentingan politik yang sebenarnya sangat tidak sehat.
Bukan saja soal yang orang banyak menyebut Mahkamah Keluarga, tetapi saya sendiri melihatnya lebih dari soal Mahkamah Keluarga. Ini sudah kartelisasi politik yang bekerja melalui yudisial atau kekuasaan kehakiman. Ini yang menjadi masalah dan lebih-lebih berkaitan dengan pemilu. Jadi legitimasinya menjadi patut dipertanyakan pemilu kita yang berangkatnya saja bermasalah seperti itu.

Menurut Mas Herlambang kasus ini akan mempengaruhi pemerintahan Jokowi di tahun terakhir pemerintahannya?
Oh tentu. Ini memperlihatkan refleksi melemahnya demokrasi. Merefleksi bagaimana relasi kuasa otoritarian yang sebenarnya dengan tampilnya model baru yang diperlihatkan itu semakin mengkonfirmasi dan mengafirmasi situasi-situasi yang dulu saya agak khawatir di tahun 2018.Saat itu di bulan November, saya masih ingat ketika mempresentasikan kekhawatiran situasi pemilu yang dipakai alat yang kemudian melahirkan rezim otokratik. Judul tulisan saya buat waktu itu 'Pemilu dan Neo-Otoriterianisme'.
Satu masalah yang mendasar waktu itu electoral threshold berkaitan bagaimana ambang batas yang dipakai alat untuk melegitimasi pemilu.
Sekarang ini problem kita selain soal ambang batas rupanya diperbuat dengan posisi politik kekuasaan yang menanggung keuntungan dari proses pemilu yang sekarang ini. Dan tentu Jokowi sedang memperlihatkan posisi politik yang mengkonfirmasi begitu banyak ilmuwan yang sudah mengatakan demokrasi decline atau demokrasi setback atau authoritarianturn. Itu tidak mengejutkan. Tapi Jokowi sedang mengkonfirmasi itu semua.
Kalau begini berarti apakah akan menjadi skandal ke depannya?
Kartelisasi itu sendiri sebenarnya sebuah skandal. Sampai pada titik saya harus menulis MK itu Mahkamah Kartel. Sebab, tanda-tanda kartelisasi di dalam sistem politik sekarang tidak hanya di pilar eksekutif dan legislatif tapi sudah masuk ke pilar kekuasaan kehakiman. Dan itu bahkan sudah saya tulis dalam sebuah jurnal tentang yudisialisasi politik terutama menyimpang kekuasaan oligarki.
Skandal itu sekarang bertumpuk dan bertambah terus. Sayangnya, memang catatan-catatan yang seharusnya mendasar ini tidak pernah menjadi persoalan serius di kalangan politik kita. Itu karena politik juga lemah tidak ada oposisinya. Tidak ada cukup kuat kontrol terhadap kekuasaan yang sebenarnya sudah abusive. Media lah yang punya peran penting itu sekarang.
Kalau melihat keputusan MKMK soal Gibran berarti ada sangkut pautnya dengan dinasti politik?
Kondisi di atas jelas mempengaruhi legitimasi secara menyeluruh bukan hanya soal pemilu, tapi sistem politiknya. Apakah kita dalam situasi sekarang mengizinkan politik dinasti semacam itu? Kalau tidak ada kesadaran politik untuk menggugatnya, atau paling tidak mengubah situasinya, atau proses pembiaran ini terjadi, maka sebenarnya kita hanya mendefisitkan nalar sehat di dalam politik Indonesia hari-hari ini. Ini yang saya agak khawatir. Karena dampaknya itu bukan besok bukan lusa tetapi panjang.
Jadi saya sedang melakukan penelitian tentang betapa politik oligarki itu semakin melekat dalam sistem kekuasaan formal. Itu memang muaranya pemilu.
Kalau kita tidak pernah serius dengan urusan pemilu, permisif terhadap persoalan yang mendefisitkan nalar sehat tadi, maka kita akan menuai hasilnya itu sekian tahun berikutnya akan terlihat akan disaksikan.
Jadi barangkali kita hanya akan mengulang kisah rezim otoritarian militer Soeharto yang sebenarnya represif hari-hari ini semakin menguat dan disaksikan dengan cara "demokrasi kita punya observasi otokratik legalisme".
Di zaman Soeharto itu buruh dihentikan suara kritisnya dengan cara diculik, disiksa, [dan] dibunuh. Sekarang cukup dibikinkan Undang-Undang itu sudah melemah sendiri dia. Dengan begitu ini merefleksikan ada kekuatan yang bekerja untuk mundur atau memerosotkan kualitas demokrasi kita.
Dinasti politik itu apakah masih wajar? Karena pemerintah kita juga dari dinasti politik turun menurun. Tapi karena praktik nepotisme ini yang kemudian terlihat dari kasus MKMK kemarin?
Dinasti politik yang dimaksudkan kalau itu kekeluargaan ya dan dinasti kekeluargaannya Jokowi saja, saya kira-kira ini satu masalah yang memang mengganggu dalam demokrasi kita.Tapi jangan lupa pertanyaan yang sederhana apakah mungkin dinasti politik yang membawa keluarga istana ini, itu bisa terjadi tanpa posisi politik atau sistem yang mengizinkan itu?
Ini yang sebenarnya cara bacanya harus dilihat dengan mendetailkan relasi kuasa yang bekerja. Bagaimana bisa partai-partai politik yang begitu banyak mengusung ide-ide perubahan, pembaruan, upaya mengubah situasi tiba-tiba tunduk begitu saja dengan pencalonan cawapresnya Gibran.
Seakan-akan tidak menjelaskan di mana posisi perubahannya kalau itu justru mengkonfirmasi politik dinasti yang justru merosotkan kualitas demokrasi.
Apa bedanya kalau lihat dinasti politik Gibran dengan dinasti politik yang lain?
Jadi pemilu kita menjadi masalah karena satu sumber kuasa otoritarian dalam konteks hari ini. Kedua, Pemilu kita itu menjadikan situasi korupsi itu semakin kuat. Banyak penelitian yang sudah menjelaskan bahwa menguatnya korupsi di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem pemilu yang memang berbiaya mahal.
Kultur dinasti politik ini masih ada, mungkin tidak dibersihkan dan bagaimana caranya untuk membersihkan kultur dinasti politik?
Kultur dinasti politik ini bertumbuh dengan struktur sosial masyarakat. Kita ini masih percaya betul dengan simbol-simbol. Ya, orang berburu profesor, makanya ada profesor kehormatan. Orang berburu apa honoris kausa, karena dengan memiliki posisi itu, simbolnya dia punya relasi kuasa tertentu. Artinya, struktur sosial membentuk simbolisasi menjadi penting.
Kedua, kita tahu bahwa jabatan masih menjadi prestige. Orang enggak usah bicara politik di luar kampus ya, di dalam kampus aja kalau sudah ada yang menjabat itu seakan-akan dirayakan layaknya sesuatu yang istimewa sekali.
Jadi berpolitiknya itu berpolitik simbolisasi dan tentu pada titik tertentu maka mereka yang berkuasa pun berkepentingan untuk mendapati posisi yang menempati struktur sosial yang tinggi itu.
Karena itu tidak mengejutkan sebenarnya kalau orang berkuasa kemudian mengajak anaknya, sanak familinya bergabung dalam relasi kuasa yang menempati struktur sosial itu. Karena itu bukan sekedar simbol tetapi itu juga resources, karena kepentingan akumulasi modal menjadi dimungkinkan lebih mudah karena struktur sosial itu.
Jadi bagaimana cara menghentikannya? Berarti politik simbol harus dikritisi itu, satu. Kerja-kerja kebudayaan tentunya. Karena kita tidak boleh silau dengan gelar, karena kita tidak boleh silau dengan jabatan, biasa saja, dalam masyarakat kita walaupun itu susah ya dalam konteks Indonesia.
Kedua, kita juga tidak boleh diam atas posisi jabatan publik. Artinya, dia harus bisa diminta pertanggungjawaban dan harus didesak untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap terjaga.
Apa yang kita saksikan seperti sekarang ini, semacam pendidikan yang tidak mencerdaskan untuk publik. Ketika Anwar Usman misalnya diberi sanksi berat atas etikanya, itu harusnya mundur dia walaupun sanksinya diminta tidak mundur. Begitu juga Gibran harusnya punya rasa malu atas proses yang memungkinkan dia untuk naik jadi cawapres karena persidangan ditemukan oleh MKMK ada masalah.
Inilah yang disebut keadaban politik. Ketiga, ini tantangannya besar. Dan saya berharap ke depan pendidikan itu juga lebih menguatkan soal pikiran-pikiran keberpihakan terhadap keadaan itu.

Keputusan MKMK tetap melanggengkan Gibran untuk jadi cawapres, banyak pihak juga yang berdalih kalau Gibran tidak jadi cawapres, tapi itu untuk masa depan generasi muda?
Politik anak muda itu harusnya juga tidak luput dengan politik upaya membangkitkan kesadaran kritis mereka atas problem demokrasi. Politik anak muda itu juga memperlihatkan upaya yang diperoleh dengan kerja keras, kemampuan untuk mendedikasikan, kemampuan untuk menguji menempa dirinya dalam situasi situasi tertentu sehingga mereka tangguh pada posisi yang usianya masih muda.
Pelajaran sejarah kan memperlihatkan anak-anak muda itu sudah bertarung dengan gagasan kolonial melawan imperialisme pada saat itu sangat kuat di Hindia Belanda. Atau juga mereka menerbitkan buku, menerbitkan tulisan, bahkan tidak pernah berhenti memikirkan propaganda politik yang lebih adil bicara soal hak asasi manusia kedaulatan masyarakat untuk bebas dari penjajahan dan seterusnya.
Anak muda itu harusnya punya pikiran-pikiran bertarung seperti itu. Jadi bukan sekedar berpangku tangan melahirkan kesempatan yang sebenarnya karena politik kekuasaan yang mengizinkan dia untuk ada di posisi-posisi tertentu. Saya kira bukan itu anak muda juga perlu mengajarkan bagaimana berpolitik yang sehat sekaligus punya adab.
Yang ideal seperti apa kalau memang tujuannya untuk anak muda?
Banyak hal sebenarnya. Kita tentu melihat politik anak muda tidak selalu masuk dalam posisi-posisi politik dalam arti partisipan di partai atau menjadi jabatan-jabatan tertentu. Anak-anak muda sekarang jauh lebih dahsyat dalam berpikir kritis.
Saya lihat mereka juga menginovasikan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Seperti mengkreasi berbasis keilmuan yang dia miliki atau mereka juga mendayagunakan kemampuan komunitas-komunitas untuk memikirkan perubahan-perubahan di tengah masyarakatnya. Itu juga berpolitik.
Politik yang harus dibangkitkan anak muda itu kan bukan politik partisan tapi politik kemanusiaan, politik yang membangkitkan kesadaran warga untuk mengubah supaya warga lebih memastikan proses kecerdasan publiknya jalan.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Maya Saputri