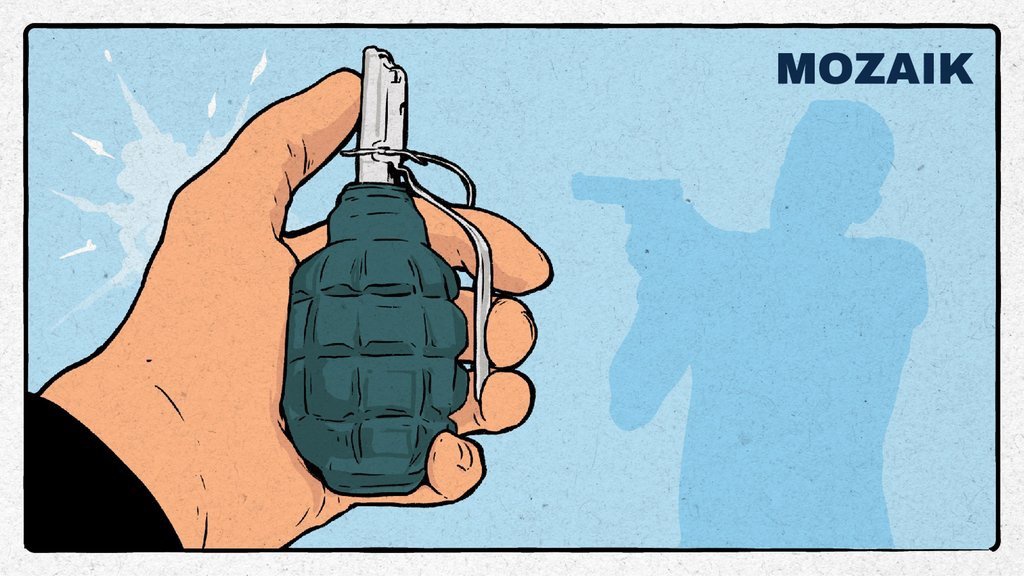tirto.id - Di Gedung Kesenian Jakarta, malam hari 26 Mei 1952, Dipa Nusantara Aidit yang saat itu belum genap 30 tahun naik ke atas mimbar. Sebagai sekretaris jenderal, Aidit mewakili Politbiro membuka perayaan ulang tahun ke-32 PKI dengan sambutan cukup panjang.
"Dalam pernjataan PKI bulan Maret 1951 didjelaskan bahwa PKI menghendaki pemerintah koalisi di Indonesia, jaitu pemerintahan jang terdiri dari partai2, golongan2, dan djuga orang2 tak berpartai jang demokratis. Kita mau mengachiri diktatur satu atau beberapa partai, karena dari pengalaman Rakjat Indonesia membuktikan diktatur sematjam itu telah menimbulkan bentjana dengan didjalankannja Razia Agustus oleh pemerintah Sukiman-Wibisono-Subardjo,” tukas Aidit dalam pidato yang disebarkan sebagai brosur Menempuh Djalan Rakjat (1952, hal. 16).
Setidaknya sampai PKI berhasil mendulang 16 persen suara pada Pemilihan Umum 1955, Razia Agustus 1951 menjadi jurus yang ampuh saat Aidit menyitirnya di berbagai kesempatan, mulai dari pidato ulang tahun partai, sambutan Kongres ke-V partai di bulan Maret 1954, hingga di buku putih Lahirnja PKI dan Perkembangannja (1955).
Belakangan, Aidit mengubah nama "Razia Agustus" menjadi "Razia Sukiman", penamaan peyoratif untuk menunjuk hidung orang yang dianggap paling bertanggung jawab yang menyebabkan guncangan serius bagi perahu partainya, hanya beberapa bulan sesudah ia memangku jabatan sebagai orang nomor satu di PKI.
Bermula dari Pemogokan
Akar Razia Agustus 1951 tidak sepenuhnya bermotif ideologis, bahkan cenderung merupakan respons eksesif terhadap aksi-aksi pemogokan buruh yang telah aktif dilaksanakan oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)--salah satu sayap PKI--sejak revolusi fisik masih berkecamuk.
Salah satu pemogokan terbesar dilakukan oleh 30.000 buruh pabrik karung di Delanggu, Surakarta, yang dimulai pada 26 Mei 1948, diikuti buruh perusahaan-perusahaan di sekitar Klaten.
"Aksi tsb. menurut Sentral Biro SOBSI berjalan sesudah pihak BTN (Badan Tekstil Negara) ternyata tidak melayani ajakan berunding dari PP Sarbupri (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) mengenai tuntutan-tuntutan buruh yang dipertimbangkan dengan alasan-alasan yang sehat dan konstruktief,” catat Warta Berita Antara, 28 Mei 1948.
Pemogokan dilakukan selama sepekan hingga pemilik perusahaan mau berunding dengan disaksikan Kementerian Perburuhan dan Kementerian Sosial.
Keberhasilan pemogokan buruh Delanggu menjadi tonggak Sarbupri menggencarkan aksi-aksi serupa di berbagai daerah, bahkan memimpin pemogokan 700.000 buruh perkebunan Deli Planters Vereeniging pada November 1950 demi tuntutan upah layak.
Sejumlah perdana menteri dari Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang gerah tak pelak menggolongkan masalah pemogokan buruh sebagai masalah keamanan dalam negeri, satu gerbong dengan pemberontakan DI/TII sejak Agustus 1949, teror Angkatan Perang Ratu Adil, dan separatisme Republik Maluku Selatan pada 1950.
Puncaknya, Kabinet Natsir menerbitkan dekret larangan pemogokan buruh yang bekerja di sektor-sektor vital, dan semua sengketa diatur supaya diselesaikan Komite Penjelesaian yang beranggotakan menteri-menteri.
"Perusahaan vital yang dimaksud mencakup telekomunikasi, kereta api, pelabuhan, rumah sakit, apotek, percetakan negara, perminyakan, hingga bank," tulis Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962, hal. 174).
Menindaklanjuti kebijakan Natsir untuk bersikap keras terhadap pemogokan-pemogokan, Soekiman Wirjosandjojo yang terpilih sebagai perdana menteri pada April 1951 memukul rata dengan mulai mengerahkan aparat keamanan dari tentara, polisi, pamong praja, hingga kejaksaan untuk bertugas "...mendjalankan ketentraman negara seisinja, dan bertindak kepada siapa jang melanggar kehormatan dan keamanan negara."
Fraksi PKI di parlemen berang atas kebijakan ini. "Dengan menugaskan Staf Keamanan untuk mengendalikan keamanan di dalam negeri, hal itu tidak berbeda dengan sistem kolonialis Belanda yang menerapkan Politieke Inlichtingen Dienst yang menekan gerak kaum revolusioner. Dengan alasan itulah fraksi PKI menolaknya," tulis Tarma Mariana dalam skripsi Razzia Agustus 1951: Konflik Nasionalis Islam dan Komunis yang disusun untuk Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (1989, hal. 49).
Tak menghiraukan protes keras di parlemen, Soekiman memilih jalan terus. Aparat negara dijadikan kaki tangan pemerintah untuk menghalang-halangi dan mempersulit kegiatan yang diprakarsai oleh PKI maupun ormas-ormasnya. Pembekalan dan latihan spionase politik bahkan turut diberikan untuk sejumlah agen-agen polisi yang bertugas di lapangan.
Pada peringatan hari ulang tahun PKI ke-31 pada Mei 1951 di Palembang, Sumatra Selatan, seorang aktivis partai yang menjabat Kepala Jawatan Penerangan Kota Palembang, Zaikadir, dicopot karena pidato yang menyebut Peristiwa Madiun sebagai "teror putih".
Sebelumnya, saat PKI menyelenggarakan rapat akbar Hari Buruh 1 Mei 1951 di Surabaya, polisi menyita poster-poster dan foto-foto sejumlah tokoh komunis seperti Karl Marx, Vladimir Lenin, dan Friedrich Engels.
Pada kesempatran lain, polisi dan tentara memblokade akses masuk ke kantor pusat CC PKI di Kramat Raya, Djakarta, berdasarkan informasi intelijen bahwa tokoh senior PKI, Alimin, akan memimpin rapat persiapan infiltrasi partai ke instansi pemerintahan sipil.
Tiga Minggu yang Menggemparkan
Ketegangan-ketegangan di akar rumput antara pendukung PKI dan aparat pemerintah Soekiman semakin diperkeruh dengan isu hubungan gelap antara PKI dan Partai Komunis Tiongkok.
Desas-desus ini menyebut Tiongkok telah menyelundupkan senjata api melalui Singapura untuk membantu PKI membentuk tentara rakyat. Wikana, salah satu aktivis PKI dan eks-anggota pemuda Menteng ’31, konon diberi tugas untuk mengamankan senjata yang akan disimpan di Boyolali, Jawa Tengah.
Intrik berkembang menjadi semakin liar saat Kejaksaan Agung menyerahkan satu laporan rahasia kepada Soekiman tentang rencana pembunuhan berantai yang ditujukan kepada tokoh-tokoh politik dan militer antara Mei hingga Juli 1951.
Sejumlah nama tercantum dalam laporan itu, mulai dari Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Gatot Soebroto, hingga Sjafruddin Prawiranegara. Anehnya, nama Soekiman justru tidak tercantum di daftar yang entah dibuat oleh siapa dan siapa pula yang memberikannya ke Jaksa Agung.
Belum sempat Soekiman memberikan tanggapan, dua peristiwa menggemparkan terjadi dalam waktu hampir bersamaan pada hari Minggu malam, 5 Agustus 1951. Sekitar pukul 20.45, ledakan granat terjadi di pasar malam Kota Bogor, Jawa Barat, melukai 82 orang dan memantik kegemparan.
Satu jam sebelum ledakan granat itu, Asrama Mobile Brigade di Tanjung Priok diserang puluhan orang bersenjata yang datang dari arah Cilincing. Letupan peluru bermuntahan di gelap malam. Bala bantuan polisi yang datang membuat penyerang tidak dapat bertahan dan merebut asrama.
Satu setengah jam sesudah tembakan pertama meletus, gerombolan penyerang mundur teratur. Dua agen polisi, dua anggota Polisi Militer, dan tiga orang penyerang tertembak, sedangkan 30 orang penyerang berhasil dibekuk dan ditahan.
Hari berikutnya, Tanjung Priok pun diisolasi. Semua lalu lintas ke arah pelabuhan dialihkan dan aktivitas bongkar muat dibekukan sementara, demikian juga jam malam diberlakukan mulai pukul 7 malam hingga 5 pagi.
Kedua insiden yang terjadi di waktu yang hampir bersamaan itu masih diselidiki kepolisian saat koran-koran propemerintah seperti harian Abadi yang terafiliasi Masjumi menggelindingkan rumor bahwa di antara para penyerang ditemukan tanda-tanda berupa ikat kepala merah dengan lambang burung merpati dan palu arit.
Kontan pemberitaan ini ditepis oleh CC PKI sebagai suatu bentuk provokasi yang keji dan bertujuan mencemarkan nama PKI. Meski demikian, bola panas telah menggelinding jauh dari yang semula diperkirakan.
Dua hari sesudah insiden Bogor dan Priok, Kabinet Soekiman memanggil Jaksa Agung dan Kepala Staf Angkatan Perang untuk menerima instruksi pengamanan. Dalam keterangan kepada awak media sebagaimana dilansir oleh kantor berita Antara, Menteri Penerangan Arnold Mononutu mengatakan, "Pemerintah sekarang akan berbuat dan tidak lagi bitjara pandjang2. Tunggu sadja perbuatan pemerintah itu."
Sabtu dini hari, 11 Agustus 1951, polisi dan tentara menangkap 51 orang, termasuk dua anggota Seksi Comite PKI Sumatra Timur di Medan, yakni Abdulkarim M.S. dan Jusuf Adjitorop, serta tokoh-tokoh pentolan eks-Negara Sumatra Timur yang didirikan Belanda selama periode revolusi.
Beberapa orang keturunan Tionghoa, termasuk eks-jurnalis kawakan dan pendiri Partai Tionghoa Indonesia, Liem Koen Hian, ikut ditangkap.
"Sebagian besar dari etnik Tionghoa yang ditangkap karena terlibat dengan aktivitas pro-Beijing berasal dari kalangan totok," tulis Taomo Zhou dalam Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa 1945-1967 (2019, hal. 130).
Kelak, setelah dibebaskan, Liem menolak kewarganegaraan Indonesia yang dia perjuangkan sejak era penjajahan Belanda. "Walaupun saya sudah memilih jadi warga negara Indonesia, kita masih saja bisa disembelih," ucap Liem getir kepada media.
Pertanggungjawaban aparat yang melakukan razia menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai pembersihan yang ditujukan pada anasir-anasir yang mengacaukan ketertiban umum. Tak ubahnya setelan kaset, aparat keamanan kompak menyangkal bahwa aksi razia tersebut "ditudjukan kepada sesuatu golongan atau aliran politik", meski yang terjadi adalah penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI.

Dari Medan, razia meluas ke Jakarta. Pukul 02.00 dini hari 16 Agustus 1951, kantor pusat CC PKI dan Central Biro SOBSI digeledah Polisi Militer. Sejumlah pejabat politik digelandang yang berwajib, antara lain Tjugito dan Nj. Moedigdo dari PKI; Maruto Nitimihardjo dan Pandu Kartawigoena dari Partai Murba; serta sejumlah anggota DPR seperti Sidik Kertopati, Siauw Giok Tjhan, Supranoto, Suhardjo, dan wartawan A. Karim D.P, Ang Jan Goan, Roestam Effendi, hingga pemimpin redaksi Java Post Surabaya, Go Tjing Hok.
Ir. Sakirman selaku Ketua Fraksi PKI di parlemen melancarkan protes keras terhadap aksi-aksi penggeledahan dan penangkapan yang disertai penyitaan terhadap dokumen-dokumen di kantor partainya.
Bungkamnya Kejaksaan Agung dan pihak militer mengakibatkan situasi tambah kalut, sedangkan nasib orang-orang yang ditangkap juga masih abu-abu. Akibatnya, beberapa sesi rapat di parlemen terpaksa ditangguhkan sementara karena penangkapan atas anggota DPR menyebabkan tidak tercapainya kuorum untuk pengambilan keputusan.
Pernyataan resmi pertama akhirnya disampaikan oleh Perdana Menteri Soekiman dalam sidang pembukaan parlemen pada malam hari 16 Agustus. Menurutnya, penangkapan itu adalah bagian dari beleid politik pemerintah dalam menegakkan keamanan dalam negeri.
Soekiman berdalih, semua yang ditangkap secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kejadian di Bogor dan Tanjung Priok, meski tidak ada penjelasan yang cukup meyakinkan sejauh mana keterlibatan mereka yang ditangkap dalam masing-masing insiden.
Beberapa hari setelahnya, penggeledahan meluas hingga ke sejumlah kota, mulai dari Bandung, Semarang, Solo, dan Surabaya. Razia pun dilakukan secara sistematis: mulai dari kantor-kantor Seksi Comite PKI, lalu kantor-kantor serikat buruh yang dipandang kuat di wilayah itu.
Penangkapan selalu disertai penggeledahan, dengan rupa-rupa alasan yang sumir dan sulit dipertanggungjawabkan. Berkali-kali aparat menyangkal bahwa razia ditujukan kepada golongan tertentu, tetapi yang terus disisir adalah eksponen dan aktivis PKI dan SOBSI.
Tajamnya reaksi di kamar sidang parlemen dan meluasnya kritik tajam di surat-surat kabar yang menggugat sumirnya alasan pemerintah melakukan razia menyebabkan aparat Soekiman mengendur.
Hanya sekitar sepekan setelah gelombang razia dilancarkan, para tahanan mulai berangsur-angsur dilepaskan, terutama karena indikasi keterlibatan yang tak berhasil diperoleh kepolisian maupun tentara dari mereka yang kadung diterungku.
Meski demikian, kurun tiga pekan yang menggemparkan perpolitikan Indonesia itu sukses menyegel permusuhan sengit PKI dan Masjumi selama bertahun-tahun, setidaknya hingga Partai Masjumi dibubarkan Sukarno pada 1960 karena dugaan keterlibatan dalam pemberontakan PRRI di Sumatra Barat dua tahun sebelumnya.
Penulis: Chris Wibisana
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id