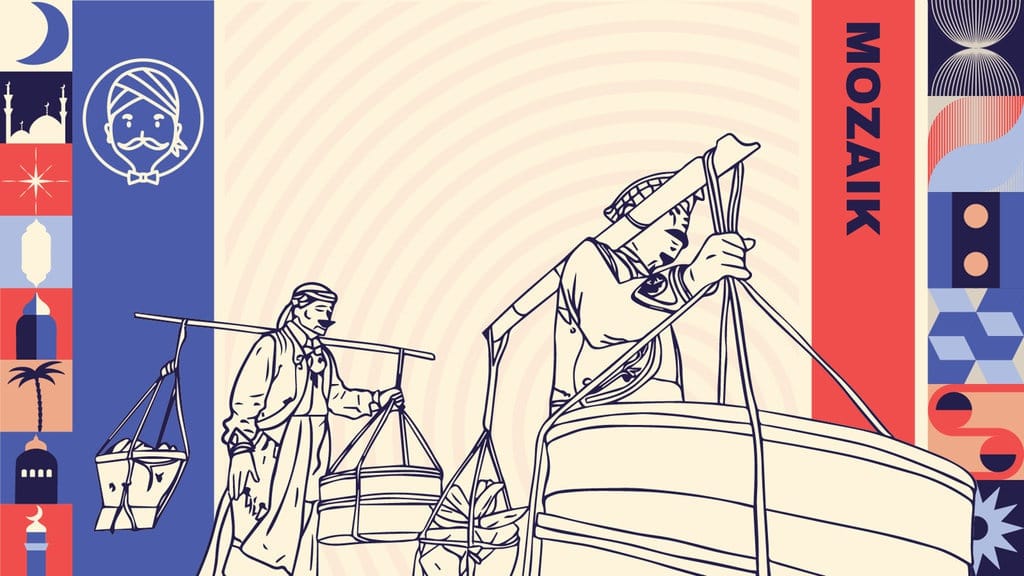tirto.id - Jejak penyebaran dan perkembangan agama Islam di Jawa Barat dapat dilacak sejak periode akhir Kerajaan Sunda. Seturut Uka Tjandrasasmita dalam Arkeologi Islam Nusantara (2009), penyebaran ajaran Islam di Tatar Sunda berdasarkan sumber historiografi tradisional bermula di daerah Cirebon dan Karawang.
Dalam Carita Purwaka Caruban Nagari, disebutkan bahwa Ki Gedeng Tapa—syahbandar Pelabuhan Muara Jati di Cirebon—merupakan salah satu pejabat Kerajaan Sunda-Galuh yang paling awal memeluk Islam pada abad ke-15.
Putrinya yakni Nyai Subang Larang, yang kelak akan menurunkan Sunan Gunung Jati dan raja-raja Cirebon-Banten, diceritakan berguru di suatu pesantren yang dipimpin oleh Syekh Quro di Karawang.
Rangkaian cerita yang menjadi titik tolak penyebaran Islam di Tatar Sunda ini mencapai klimaksnya pada masa Sunan Gunung Jati. Ia menyebarkan Islam di Jawa Barat bagian timur dan Maulana Hasanudin, anaknya, menyebarkan Islam di Jawa Barat bagian barat serta Banten.
Karena telah mengalami islamisasi sejak periode Kerajaan Sunda pada abad ke-15 dan ke-16, masyarakat Sunda memiliki tradisi yang unik dalam perayaan-perayaan keagamaan mereka, termasuk saat menjelang bulan Ramadhan.
Salah satu daerah yang memiliki tradisi unik menjelang bulan puasa adalah wilayah Priangan atau daerah pergunungan tengah Jawa Barat. Kendati islamisasi di daerah ini paralel dengan wilayah pesisir seperti Cirebon, corak keislaman masyarakat Priangan sebenarnya memiliki tradisi yang lebih khas.
Menurut Mumuh Muhsin Z pada "Priangan dalam Arus Dinamika Sejarah" (2011), Priangan merupakan daerah persimpangan antara kebudayaan Sunda dengan budaya Jawa Mataraman sejak abad ke-17.
Fenomena ini bukan hal aneh, karena sejak paruh pertama abad ke-17 Kerajaan Mataram Islam memang sudah menancapkan panji kekuasaannya di Priangan. Budaya Mataraman di Priangan tetap eksis kendati Mataram harus rela menyerahkan Priangan pada VOC pasca Pemberontakan Trunojoyo (1674-1680).
Budaya Mataraman lestari berkat para menak atau bangsawan Sunda yang tetap menjalankan cara hidup ala ningrat Jawa di pendopo-pendopo kabupaten.
Sadranan Menak
Prosesi nyadran atau sadran bagi kebanyakan masyarakat muslim Jawa atau Sunda mungkin suatu ritual yang lazim dilakukan. Sadran konon berasal dari kata Sanskerta, "sraddha" yang merujuk pada nama ritus dalam ajaran Hindu.
Sebagaimana disebut oleh L. D. Ratnawati M.F. dalam "Upacara Sraddha pada Masyarakat Tengger" (2001), sraddha dilakukan dalam rangka memberi penghormatan terhadap mendiang, 12 tahun setelah ia meninggal.
Prosesi sraddha kemudian bertransformasi menjadi sadran pada masa Islam. Upacara ini merujuk kepada ziarah ke makam sanak saudara atau leluhur pada saat menjelang suatu perayaan tertentu.
Di dalam historiografi sejarah kebudayaan Hindu-Buddha, Raja Hayam Wuruk melalui Kakawin Nāgarakṛtâgama dikenal sebagai sosok raja yang pernah melakukan sraddha di candi-candi pendharmaan leluhurnya sekitar abad ke-14.
Sementara itu menurut H. Djafar dalam "Prasasti Huludayeuh" (1994), masyarakat Sunda paling tidak terlacak telah mengenal tradisi sraddha sejak pemerintahan Raja Surawisesa (1511-1525).
Sang prabu disebut-sebut telah mendirikan Prasasti Batu Tulis di Bogor dan Prasasti Huludayeuh di Cirebon sebagai bentuk penghormatan terhadap mendiang ayahnya, yakni Sri Baduga Maharaja.
Sedangkan di kalangan para menak, tradisi sadran yang dilakukan adalah bentuk akulturasi antara budaya Jawa Islam dan Sunda Kuno. Menurut Nina Herlina Lubis dalam Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1942) (1998), sadran biasanya dilakukan pada bulan Ruwah (Syaban) atau Rajab dalam penanggalan Hijriah selayaknya yang berlaku di daerah Jawa.
Namun detail upacara sadran yang dilakukan, rupanya memiliki keunikan tersendiri. Kasus yang Nina Lubis maksud itu misalnya bisa dijumpai pada para Bupati Sukapura atau Tasikmalaya.
Para bupati Sukapura biasanya akan mendatangi kompleks permakaman khusus bupati dengan membawa beberapa jenis ubarampe (sesaji). Hal-hal yang perlu di bawa itu antara lain bunga rampai tujuh rupa, kemenyan, kendi air, dan sepotong kayu cendana.
Sang bupati lalu akan membacakan pelbagai doa dalam bahasa Arab dan Sunda untuk memohon berkah dari para leluhur sekaligus memberikan tanda syukur pada Tuhan. Setelah prosesi sadranan, lima atau tujuh hari kemudian dilakukan upacara ngaleunggeuh.
Pada upacara ini dibunyikan pelbagai alat musik, mulai dari lesung, angklung, bahkan salvo. Tujuannya, mengundang arwah para leluhur untuk datang dan memberi berkat, juga sebagai pertanda bahwa bulan puasa telah menjelang dan warga kabupaten diharap bersiap-bersiap untuk melaksanakan ibadah.

Mengganti Pagar Pangcalikan
Upacara menjelang bulan puasa (biasanya berlangsung bulan Ruwah) yang juga ada hubungannya dengan para karuhun atau leluhur yaitu ngikis, biasanya di Ciamis.
Upacara ngikis sama sekali tidak mengandung nuansa budaya Jawa Mataraman. Catatan akan tokoh menak yang pernah melakukan ritual ngikis adalah R.A.A. Kusumadiningrat yang berkuasa di Kabupaten Ciamis pada tahun 1839-1886.
Menurut Y. Sofiani dan C. Nurfadillah dalam "Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Biografi Bupati R.A.A. Kusumadiningrat (1839-1886) sebagai Sumber Belajar Sejarah" (2020), sang bupati memandang bahwa kegiatan ngikis ditujukan untuk menimbulkan semangat "membersihkan diri" di kalangan masyakarat sekaligus untuk menghidupi sejarah Raja-Raja Galuh sebagai nenek moyang para Bupati Ciamis.
Pusat kegiatan ngikis secara umum berlangsung di seluruh situs arkeologi di Ciamis yang menurut kepercayaan masyarakat merupakan peninggalan Kerajaan Galuh. Namun pusat ngikis biasanya berlangsung di Situs Karangkamulyan yang berada di Kecamatan Cijeungjing.
Upacara ngikis dilakukan di sana karena keberadaan dolmen yang oleh masyarakat dipercaya sebagai singgasana (pangcalikan) Raja Galuh.
Seperti dilampirkan oleh Sarip Hidayatulloh dalam "Nilai-nilai Kearifan Lokal Upacara Adat Ngikis di Situs Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis" (2019), upacara diawali dengan mapag atau menyambut bupati atau tamu kehormatan lain oleh Ki Lengser di pintu masuk situs.
Rombongan lantas diajak masuk ke area pelataran singgasana, lalu dilakukan ritual ruwat via penceritaan kisah Ciung Wanara dan sejarah singkat Kerajaan Galuh. Bersama dengan pembacaan riwayat kerajaan, kuncen sebagai pemimpin upacara kemudian membacakan rajah-rajah berbahasa Sunda Kuno.
Upacara diakhiri dengan doa dan tabur bunga ke atas singgasana dan tentunya ngikis itu sendiri, yakni mengganti pagar yang mengelilingi situs.
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id