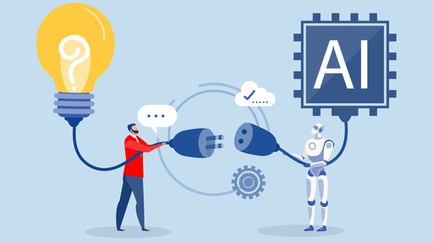tirto.id - Bayangkan Anda memiliki sebuah lahan peternakan kecil untuk sekadar mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian, lahan di sekitarnya dibeli oleh pebisnis untuk dijadikan tempat pembuangan akhir (TPA).
Segera area itu dipenuhi gunung sampah, bau menyengat, dan bising truk; semuanya mulai mengganggu peternakan Anda. Nahasnya, karena miskin, Anda tidak punya kendali untuk mengatasi itu, terlebih pemilik TPA adalah sobat wali kota, pengusaha, dan politikus.
Anda mencoba mengajak tetangga, yang juga peternak kecil, untuk berunding dengan pemilik TPA agar operasi dibatasi. Pemilik TPA keberatan. Dia mengatakan pembuangan sampah di tempatnya hanya akan dibatasi jika Anda juga mengurangi produksi sampah peternakan, yang berarti pengurangan produksi ternak.
Pemilik TPA juga menjanjikan bantuan-bantuan kecil, seperti peminjaman uang untuk pembangunan tembok batas, pengadaan air bersih, atau apa pun, tetapi tetap tidak mau membatasi apalagi menyetop operasi bisnis.
Perundingan demi perundingan berjalan, tawarannya kurang lebih sama, namun syaratnya bertambah: Produksi Anda semakin lama harus dikurangi karena dianggap ikut menyumbang polusi sampah di area itu. Sementara area tersebut makin dekat untuk menjadi lahan mati, pemilik bisnis TPA tinggal nyaman di rumahnya yang nun jauh dari sana, dengan uang dari hasil bisnis kotor tersebut.
Menurut J. Timmon Roberts dan Bradley C Parks, kira-kira demikianlah analogi perundingan kebijakan iklim dunia yang telah terjadi setidaknya sejak isu pemanasan global pertama kali mencuat pada dekade 1980-an. Dalam buku A Climate of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy (2007) mereka menemukan bahwa negosiasi mengenai kebijakan iklim banyak didikte negara-negara kaya terutama di belahan bumi Utara.
Negara-negara kaya yang dominan mengeluarkan “sampah” gas rumah kaca malah banyak menuntut negara-negara miskin untuk ikut bertanggung jawab dengan porsi sama bahkan lebih. Pola itu muncul sejak pertemuan di Stockholm pada 1972, Nairobi 1982, de Janeiro 1992, Johannesburg 2002, dan seterusnya.
Saat Earth Summit di Rio, hal ini dilakukan Amerika Serikat, negara penyumbang emisi terbesar. Mereka menolak membatasi emisi jika negara-negara miskin tidak melakukan hal serupa. Begitu juga saat Bill Clinton menandatangani Protokol Kyoto pada 1997. Ketika itu Senat malah setuju untuk tidak mengurangi aktivitas industri kotor jika negara-negara miskin tidak melakukannya.
Sementara korporasi-korporasi raksasa penyumbang emisi dari negara kaya makin beringas, negara-negara miskin dipaksa membatasi pembangunan. Negara kaya juga tak mau repot keluar uang. Seperti ditulis Roberts dan Parks, saat Rio Earth Summit, negara kaya diharuskan menyumbang dana 20 persen atau memberi pinjaman dengan bunga rendah dari total biaya 62,5 miliar dolar AS per tahun untuk pembangunan berkelanjutan di negara miskin. Janji itu tak terpenuhi. Negara-negara kaya hanya menyumbang kurang dari satu per lima dari kewajibannya.
Negosiasi timpang seperti itu rupanya menghiasi pula Conference of Parties (COP) 26 di Glasgow yang baru saja berlangsung. Beberapa pemimpin dari negara miskin geram. Presiden Bolivia Luis Arce menyebut usulan yang disodorkan oleh negara-negara dari belahan bumi Utara jauh dari usaha nyata untuk menghentikan krisis iklim.
Arce keberatan dengan paksaan-paksaan negara kaya yang dianggapnya tidak akan berdampak signifikan, sebab nyatanya mereka masih menjalankan model bisnis yang menjadi biang dari krisis ini. Arce bahkan melabeli usulan seperti perdagangan karbon sebagai kolonialisme baru yang dijiwai kepentingan akumulasi laba alih-alih keberlangsungan bumi.
Kecaman juga diungkapkan oleh Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador. Ia menuding COP26 sebagai ajang unjuk kemunafikan.
Dari kalangan masyarakat adat, perwakilan orang Māori, India Logan-Riley, juga melayangkan keresahan yang sama. Menurutnya, permasalahan krisis iklim terletak pada keengganan negara Utara untuk menghentikan kebijakan imperialisnya dan membiarkan perusahaan multinasional leluasa tanpa kendali.
Kritik juga datang dari sudut-sudut jalanan Glasgow yang dibanjiri oleh ratusan ribu demonstran, di antaranya berasal dari warga belahan bumi Selatan dan aliansi masyarakat adat. Mereka menganggap COP26 sebagai arena unjuk kepentingan negara kaya tanpa mendengar dan melibatkan suara warga miskin dan masyarakat adat--kelompok paling rentan terdampak krisis iklim.
Biang Kerok Mencuci Dosa
Roberts dan Park mengatakan kondisi ini memperlihatkan bahwa “pemanasan global berkaitan dengan masalah ketidaksetaraan, tidak hanya tentang siapa yang paling menderita dari dampaknya tetapi juga siapa yang menciptakan masalah sejak awal.”
Tentu yang paling menderita adalah negara miskin. Contohnya, mengutipDeutsche Welle, Burundi yang hanya mengeluarkan 0,027 karbon per kapita akan terancam risiko krisis paling serius.
Warga Burundi diprediksikan akan mengalami kekeringan ekstrem yang berdampak pada kacaunya pertanian dan berujung pada kelaparan yang sebenarnya sudah terjadi saat ini. Secara lebih luas, krisis akan menyebabkan penurunan panen sebesar 25 persen selama beberapa dekade ke depan.
Belum lagi di Pasifik. Negara-negara kepulauan kecil terancam tenggelam, padahal, sekali lagi, mereka tidak menyumbang emisi dalam jumlah berarti.
Lusinan penelitian telah membuktikan bahwa negara-negara di belahan bumi Utara Jurnal Lancet Planet Health, atas kerusakan bumi. Bahkan itu telah dimulai jauh sebelum industrialisasi, yakni sejak masa kolonialisme.
Di abad ke-21, posisi itu belum banyak berubah. Antropolog Jason Hickel dalam artikel “Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary” (Jurnal Lancet Planet Health, Vol. 4, 2020) menemukan sekelompok negara maju, yakni AS, Kanada, Eropa, Israel, Jepang, Israel, Selandia Baru, dan Australia bertanggung jawab terhadap 92 persen emisi karbon di dunia berdasarkan hitung-hitungan dari 1970 sampai 2015.
“Mereka telah berhasil menjajah atmosfer global demi pertumbuhan industri mereka sendiri, dan demi mempertahankan tingkat konsumsi energi mereka sendiri,” ujar Hickel saat membahas hasil studinya kepada In These Times.
Dosa negara kaya berikutnya adalah mempromosikan solusi palsu seperti perdagangan karbon. Solusi seperti ini berpotensi menjadi sabun cuci tangan bagi mereka dan korporasi penyumbang emisi besar. Pengamat dan LSM menyebut usulan kebijakan ini sebagai bentuk greenwashing, yakni klaim ramah lingkungan untuk menutupi kegiatan yang sebenarnya tetap destruktif.
Skema perdagangan karbon menjadikan karbon sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan di pasar. Secara sederhana, perdagangan karbon memungkinkan pihak-pihak penyumbang emisi seperti perusahaan minyak untuk tetap terus membuang sampah asalkan membeli kredit karbon setara dengan emisi yang keluar. Kredit diperoleh dari membeli ke pihak yang memiliki area hutan yang dapat menyerap karbon atau menanam hutan sendiri.
Ini dianggap bermasalah karena memberikan celah pembiaran emisi, terlepas dari janji-janji para pemimpin negara kaya untuk terus menurunkan emisi di masing-masing negaranya.
Ditambah lagi, usulan ini dinilai cacat dari sudut pandang teknis dan ilmiah. Dalam artikel di The Conversation, Profesor Doreen Stabinsky, ahli politik lingkungan global, mengatakan kebijakan perdagangan karbon hampir sia-sia sebab hutan tidak akan mampu menyerap emisi yang akan terus meningkat.
Selain itu, hutan juga tidak bisa menangkap karbon secara permanen sebab ada fase saat pohon-pohon secara alamiah melepaskan karbon dalam jumlah banyak. Artinya, penangkapan karbon oleh hutan tidak bisa dibaca secara pasti apalagi didudukkan dalam logika pasar.
Stabinsky menilai kebijakan ini bak karpet merah bagi perusahaan penyumbang emisi seperti Shell untuk tetap menjalankan bisnis meski dunia terancam kiamat.
Shell berencana mengeluarkan emisi sebesar 120 juta ton karbon per tahun dan menggantinya dengan kredit karbon lewat penanaman hutan seluas 12 juta hektare. Jika rencana ini dikombinasikan dengan perusahaan lain seperti BP, Total Energies, dan ENI, jumlah lahan yang dibutuhkan amat fantastis: hampir setengah bagian AS.
Bagi Stabinsky, rencana itu akan sulit terwujud. Ditambah, karbon yang dibuang oleh perusahaan itu tidak terjamin ditangkap sepenuhnya oleh hutan yang ditanam mengingat faktor-faktor yang telah disebutkan Stabinsky sebelumnya.
Singkatnya, perdagangan karbon yang ditawarkan negara-negara kaya tidak betul-betul ditujukan untuk mengatasi krisis iklim, tapi menyelamatkan keberlangsungan model bisnis yang ada sambil berlagak menyelamatkan bumi.
Stabinsky mengatakan jika memang para pembuat keputusan berkomitmen, satu-satunya cara adalah memotong sumber emisi itu sendiri, yakni operasi perusahaan-perusahaan dan aktor penyumbang emisi besar lain, bukan tetap mengizinkannya melalui mekanisme penebusan dosa yang palsu.
Yang Rugi, Yang Tersingkir
Selain masalah teknis, kebijakan seperti perdagangan karbon juga berisiko menindas masyarakat adat dan pemilik lahan kecil. Laporan dari think tankOakland Institute membeberkan bahwa kredit karbon yang dibeli oleh Norwegia, Swedia, dan Finlandia pada 2014–2017 telah membuat ribuan warga perkampungan di Uganda tergusur dan mengalami krisis makanan. Lahan pertanian subsisten 12 ribu hektare yang dikelola warga di wilayah Kachung secara paksa diubah menjadi area pepohonan pinus untuk menggantikan emisi yang telah dikeluarkan.
Dengan kata lain, negara kaya dan korporasi leluasa melepas karbon di rumah, lalu merasa impas sebab telah berusaha menanam secuil hutan di tempat lain meski dengan cara yang berdarah-darah.
Laporan itu menyebut bahwa negara, perusahaan, dan organ PBB yang terlibat sadar betul akan dampak mengerikan proyek itu bagi masyarakat namun tetap melanjutkannya.
“Proyek cacat itu bisa berjalan dengan dukungan dari tiga pemerintah Eropa, beberapa badan-badan internasional dan perusahaan audit swasta,” tertulis di akhir laporan. “Hal ini menimbulkan pertanyaan serius di sekitar motif sebenarnya dari lembaga-lembaga tersebut serta tujuan dan fungsi perdagangan karbon secara keseluruhan.”

Di tengah kebijakan yang bias kepentingan seperti itu, si miskin dan masyarakat adat yang menanggung beban berat malah terus diabaikan. Dilaporkan The Guardian, banyak aktivis masyarakat adat mengaku dipersulit untuk terlibat dalam COP26.
Rachael Osgood, pengurus imigrasi COP26 Coalition, terdiri dari warga belahan bumi Selatan dan masyarakat adat, menyebut hampir dua per tiga orang yang ingin terlibat terhalang masalah administrasi, akreditasi, dan akses vaksin yang masih sulit di negara-negara Selatan. The Guardian juga melaporkan bahwa para aktivis dan masyarakat adat dari negara-negara Selatan mendapat sikap tidak mengenakan dari Departemen Dalam Negeri Inggris yang bertugas mengurusi partisipan.
“Yang kita ketahui secara pasti adalah bahwa ribuan orang dari belahan bumi Selatan disingkirkan, padahal mereka mewakili puluhan juta suara tak terdengar dari orang-orang di garis depan krisis iklim,” ujar Osgood 30 Oktober lalu kepada The Guardian.
“Saat ini kita sedang melihat negara-negara belahan Utara dengan tanggung jawabnya yang rendah menentukan keputusan bagi orang-orang yang paling kecil kontribusinya terhadap krisis iklim, tapi justru paling terdampak, dan hal ini tidak seharusnya terjadi dalam COP.”
Memang sejak COP pertama diselenggarakan di Berlin pada 1995, suara dari negara miskin dan masyarakat adat tidak pernah diterima dalam porsi besar. Meskipun saat ini posisi masyarakat adat secara legal diakui dalam Kesepakatan Paris sejak 2015, pusat kendali tetap dicengkeram oleh negara-negara kaya.
Para aktivis yang berkumpul di Glasgow juga melihat setelah Kesepakatan Paris pelibatan kaum pinggiran yang terdampak parah masih minim. Meski pengetahuan dan praktik lokal masyarakat adat kini mulai diperbincangkan, para aktivis menganggap hal itu sebagai kooptasi dan manipulasi sebab pada akhirnya keputusan masih ditentukan oleh sistem PBB yang eurosentris.
Kehadiran mereka di Glasgow dapat dibaca sebagai upaya untuk menggoyahkan pengambilan keputusan yang bias dan timpang tersebut.
“Kami di sini menawarkan solusi berkelanjutan untuk seluruh dunia yang memerlukan pergeseran ideologis,” kata Ruth Miller, perwakilan masyarakat adat Curyung dari Alaska kepada The Guardian. “Bukan tawaran industri hijau yang dibangun di atas kolonialisme dan represi.”
Penulis: Mochammad Naufal
Editor: Rio Apinino
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id