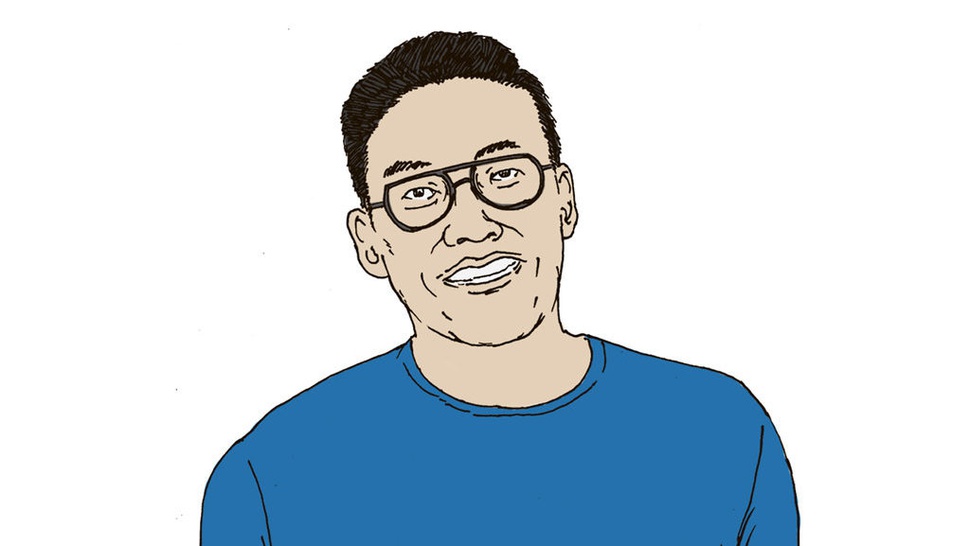tirto.id - Setiap orang dewasa wajib lapor pada negara bila seksualitasnya menyimpang.
Setiap istri wajib mengurus rumah tangga dan selalu tanggap memuaskan suami.
Setiap anggota keluarga wajib saling mengawasi satu sama lain.
Negara berwenang melakukan intervensi langsung pada setiap keluarga yang tak sejalan dengan norma.
Itulah yang akan terjadi bila Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga disahkan. Sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2020, RUU yang didukung oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar, Gerindra, dan PAN ini telah menuai kontroversi karena dianggap terlalu jauh mencampuri urusan pribadi. Apakah RUU ini merupakan ancaman baru?
Secara historis, domain keluarga sebagai bagian dari intervensi negara bukanlah perihal baru. Undang-Undang Perkawinan No.1/ 1974 turut mengatur peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam perkara reproduksi, suami bahkan diizinkan untuk beristri lebih dari seorang bila istri tidak mampu memberikan keturunan. Konteks perancangan UU ini tidak bisa dilepaskan dari ideologi gender Orde Baru (1966-1998) yang menjadikan keluarga sebagai pilar stabilitas nasional.
Dalam Ibuisme Negara, Julia Suryakusuma bertutur tentang bagaimana Orde Baru, baik secara ideologis maupun praktik kultural, mereduksi peran perempuan sebatas sebagai ibu. Melalui organisasi, seperti Dharma Wanita dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Orde Baru melanggengkan peran perempuan sebatas sebagai ibu pendukung suami dan pengampu keharmonisan keluarga. Dalam imaji Orde Baru, keluarga adalah simbol stabilitas nasional yang harus dipertahankan.
Tentu saja, istilah seperti sadisme dan masokisme seksual, kewajiban lapor terhadap Badan Ketahanan Keluarga, dan layanan rehabilitasi penyimpangan seksual belum muncul dan dijadikan wacana resmi dari tata kelola Orde Baru yang otoriter dan militeristik. Baru dalam RUU Ketahanan Keluarga yang berniat melindungi keluarga dari gerusan budaya asing akibat globalisasi inilah beragam terminologi itu, termasuk homoseksualitas, dimunculkan secara spesifik beserta kewajiban lapor pada negara terkait seksualitas pribadi.
Meski mengusung semangat yang hampir sama seperti Orde Baru untuk meregulasi ranah domestik, RUU Ketahanan Keluarga memanfaatkan narasi-narasi baru—'rehabilitasi’ (pasal 85), ‘pelaporan dan pengawasan’ (surveillance) (pasal 86), dan ‘krisis keluarga’ (pasal 85-124).Tujuannya untuk memastikan agar individu dan keluarga mendisiplinkan dirinya sendiri (self-discipline) dan saling mengawasi secara berkesinambungan.
Kegagalan Kriminalisasi LGBT
Betapapun Indonesia menjadi negara demokratis pada 1998, narasi keluarga sebagai institusi yang harus dilanggengkan tetap bertahan. Kali ini motor utamanya adalah kelompok konservatif religius.
Proses demokratisasi di Indonesia membuka pintu bagi kelompok politik Islam yang dulu direpresi oleh Orde Baru untuk merebut ruang politik yang kini terbuka lebar. Sebagai contoh, konservatisme agama terlihat dari bagaimana ormas Front Pembela Islam (FPI) dan ormas lain memanfaatkan narasi moralitas dan agama untuk melarang, bahkan melakukan sweeping, terhadap aktivitas yang dianggap bertentangan dengan moral.
Isu seksualitas menjadi jualan paling efektif menarik simpati dan memancing perhatian publik. Pada 2008, setelah melalui perdebatan panjang, UU Pornografi disahkan. Di dalamnya, homoseksualitas secara eksplisit mulai diperhitungkan sebagai salah satu konten pornografi.
Agaknya, kelahiran RUU Ketahanan Keluarga tidak dapat dilepaskan dari kegagalan upaya kriminalisasi homoseksualitas dan perzinahan pada 2017. Dimotori oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) yang tergabung dalam koalisi Gerakan Indonesia Beradab (GIB), proposal untuk merevisi KUHP agar menghukum homoseksualitas yang diajukan pada 2016 ditolak oleh Makhamah Konstitusi pada Desember 2017. Ini bukan berarti upaya kebencian terhadap komunitas LGBT memudar.
Wacana kepanikan anti-LGBT sudah telanjur menyebar di ranah publik, menjadikan terminologi ‘LGBT’ sebagai momok terhadap negara dan generasi muda. Tanpa banyak orang paham atas apa kepanjangan dari LGBT, politikus, media, dan kelompok konservatif menyamakan LGBT dengan ‘perang proksi’ (proxy war) untuk menghancurkan budaya Indonesia’, ‘abnormalitas’, ‘penyakit jiwa’, ‘penyebar virus HIV’, ‘predator anak-anak’, hingga ‘perilaku menular’. Maka, demi mencegah penyebaran ‘LGBT’, wacana konservatif yang dipromosikan oleh AILA dan para kroninya menempatkan kembali keluarga tradisional sebagai solusi utama.
Dalam wacana anti-LGBT baru-baru ini, keluarga kembai dianggap berada di tengah ancaman globalisasi dan nilai-nilai Barat, seperti feminisme dan hak-hak LGBT. Wacana tentang ancaman dari luar ini menjadi strategi produktif untuk menebarkan kepanikan atas bahaya LGBT. Untuk semakin menegaskan seolah Indonesia berada dalam bahaya, kelompok anti-LGBT menyebarkan asumsi bahwa LGBT menyebabkan merebaknya HIV/AIDS serta menuduh komunitas LGBT Indonesia berupaya melegalkan pernikahan sejenis.
Tidak sulit untuk menyaksikan bagaimana tuduhan-tuduhan itu menjadi semacam justifikasi atas beragam aksi antisipatif. Ia mendorong pemerintah dan publik mencegah agar tuduhan-tuduhan itu tidak jadi kenyataan. AILA bergerak membangun pengokohan keluarga melalui workshop, seminar, buletin, bahkan perluasan jaringan aktivismenya. Keluarga diposisikan sebagai benteng untuk melindungi generasi muda dari propaganda LGBT dan feminisme di era globalisasi.
Secara sengaja, kelompok anti-LGBT memanfaatkan imaji-imaji LGBT dari negara lain (seperti pelegalan pernikahan sejenis) untuk menyebarluaskan kepanikan dan menjustifikasi aksi pencegahan. Di Indonesia, meskipun komunitas LGBT tidak pernah memperjuangkan kesetaraan pernikahan, wacana preventif terhadap ‘penyebaraluasan LGBT’ telah menjustifikasi rencana sensor konten “berbau LGBT” dari Komisi Penyiaran Indonesia, pemblokiran situs “berbau LGBT” oleh Kemenkominfo, dan pemberian denda bagi komunitas LGBT di Kota Pariaman, Sumatera Barat.
Kini, lewat RUU Ketahanan Keluarga, wacana keluarga terus bermutasi sejak Orde Baru. Keluarga tak hanya dikontrol dan dijadikan ruang antisipasi pencegahan LGBT, melainkan dimiliterisasi sedemikian rupa sehingga setiap anggota keluarga berpotensi menjadi pengawas, pengintai, dan pelapor terhadap penyimpangan yang terjadi di keluarga. Persis seperti kelompok prajurit bersenjata yang saling mengawasi setiap anggotanya agar taat aturan dan disiplin.
Militerisme Keluarga
Militerisme tidak melulu menyangkut perang atau persenjataan. Tapi ia juga nilai dan kultur yang meresap dalam keseharian. Operasi drone oleh masyarakat sipil, sistem keamanan rumah dengan kamera CCTV, dan penggunaan teknologi Global Positioning System (GPS)—semua ini, bersama sistem dan naluri pemantauan saksama, mengukuhkan proses militerisasi berjalin kelindan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Logika militerisme dan keamanan (security) tak hanya berdasarkan pada aksi preventif, tetapi juga menangkal apa yang dianggap "krisis" dan "ancaman" yang terus menerus mengintai, sehingga harus segera diidentifikasi dan diselesaikan.
Hal itulah yang turut menjadi fondasi RUU Ketahanan Keluarga.
Pertama, terminologi seperti ‘krisis keluarga’ (keluarga yang tidak stabil dan tak tentu arah), ‘keluarga tangguh’ (keluarga yang dapat menangkal gangguan luar), dan ‘kelentingan keluarga’ (kemampuan keluarga untuk pulih kembali setelah krisis) menempatkan keluarga seperti medan militer.
Rasanya, cukup jelas penggunaan kata ‘krisis’, ‘tangguh’, dan ‘kelentingan’ membuat keluarga terdengar seperti kamp militer yang diharapkan tetap kuat, waspada terhadap ancaman, dan mampu untuk kembali ‘normal’ setelah tertimpa krisis. Arus globalisasi, penyimpangan sosial dan seksual, serta melunturnya “nilai-nilai luhur bangsa” sengaja di-framing sebagai ancaman yang terus-menerus mengintai. Anggapannya, bila dibiarkan bebas, keluarga Indonesia dijamin akan hancur lebur.
Kedua, RUU Ketahanan Keluarga mendorong tata kelola pengawasan (surveillance) antaranggota keluarga. Pasal 86 menyebutkan, “Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi…” Di sini, ruang domestik disulap menjadi medan pengintaian untuk kemudian dilaporkan kepada negara.
Ketiga, kedisiplinan tak hanya beroperasi lewat pengintaian oleh pihak ketiga, tetapi oleh diri sendiri (self-discipline). Pasal 87 menyebut, “Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi…” Sedikit berbeda dengan di atas, ia meminta individu mendisiplinkan diri. Lewat narasi ‘rehabilitasi’ (bukan narasi penghukuman), seseorang diminta meregulasi diri untuk melapor dan mencari ‘solusi’ demi menyembuhkan diri dari “penyimpangan seksual.”
Keempat, setelah proses pelaporan, Badan Ketahanan Keluarga bertindak seolah komando tertinggi di bawah presiden yang akan memberikan solusi untuk semua perkara tersebut. RUU ini mengatur bagaimana struktur birokrasi Badan itu akan dijalankan.
Pasal 121 menyatakan Badan Ketahanan Keluarga “merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden”, dan “wajib membuka perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.” Ruang pribadi masyarakat sipil—termasuk ranjang dan keluarga—kini diatur dalam kerangka birokrasi yang ajek, bahkan langsung tersambung dengan kuasa presiden.
Rasanya, tak berlebihan bila hantu Orde Baru dan ideologi gendernya masih terus bercokol dan kini bahkan berevolusi menjadi bentuk baru. Ia semakin kasat mata. Bukan hanya karena tertulis jelas dalam RUU Ketahanan Keluarga, melainkan karena diberikan wujud berupa piranti organisasi dan birokrasi yang padu.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.