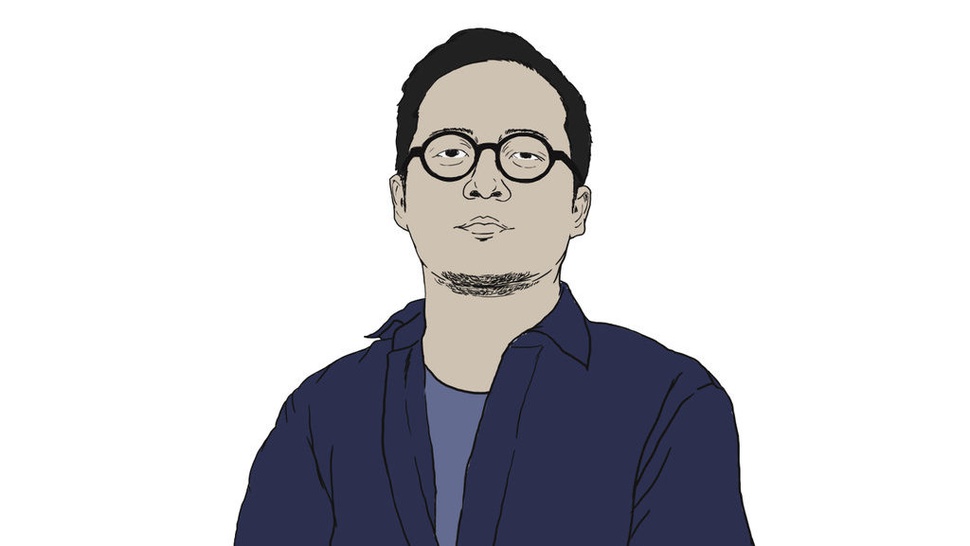tirto.id - Jauh sebelum kemunculan Bali: Beats of Paradise, Bali sudah lama tersohor, bahkan kerap kali lebih dikenal ketimbang negara yang menaunginya. Demikian pula gamelan yang sudah dimainkan di mana-mana ratusan tahun sebelum kelahiran Livi Zheng, pembuat film Bali: Beats of Paradise. Dan akhirnya, maestro gamelan Bali I Nyoman Wenten sudah malang melintang di kalangan seni sebelum geger Livi Zheng di media.
Wenten adalah seorang seniman dan pendidik gamelan yang telah lama melanglang buana. Setelah Livi Zheng membuat Bali: Beats of Paradise, tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan masyarakat akan I Nyoman Wenten melonjak. Sayangnya, di tengah kontroversi seputar sang sutradara, reputasi Wenten sebagai seniman, komposer gamelan, koreografer, sekaligus pelaku diplomasi budaya di kancah internasional justru terabaikan.
Saya tertegun membaca kisah Wenten ketika ia diwawancarai untuk penulisan biografi Hidup Untuk Tari (full disclosure: saya menyunting buku ini) yang terbit dua tahun silam. Dari situlah saya percaya Wenten lebih besar dari yang diperlihatkan Livi di filmnya.
Pada 1965, ketika masih menempuh sekolah di Kokar (Konservatori Karawitan) Indonesia di Bali, Wenten mengikuti sebuah program misi kebudayaan bertajuk Cultural Exchange besutan Presiden Sukarno. Program yang dimulai pada 1964 itu mengirim seniman untuk mengenalkan budaya Indonesia ke sejumlah negara. “Kita Indonesia itu perlu disorot dan diketahui oleh mata dunia, sebab kita tidak dikenal, dan kamu-kamu [para seniman] ini yang harus mengenalkan Indonesia,” tutur Wenten menirukan Bung Karno. Misi kebudayaan itu memang didesain untuk menyatakan bahwa Indonesia negara yang merdeka serta mengenalkan kebudayaan Indonesia. Keterlibatan Wenten di dalamnya mengantarnya ke Cina, Korea Utara, Thailand, Jepang, Kamboja, hingga Mesir.
Karena gejolak politik 1965, sambutan publik atas kepulangan Wenten tak besar.
Setelah menamatkan studi di Kokar, Wenten memutuskan untuk berkeliling ke sejumlah daerah dan selanjutnya mendaftar di Akademi Seni Tari Indonesia, Yogyakarta, pada 1968. Rekan seangkatannya adalah Sal Murgiyanto dan Sardono W. Kusumo. Di ASTI Yogyakarta inilah Wenten mempelajari tari Jawa.
Setelah dua tahun tinggal di Yogya, ia ikut menari di Sendratari Ramayana Prambanan bersama Ben Suharto dan Sal Murgiyanto. Beberapa repertoar seperti wayang Golek menak, Sugriwo, dan Wiroguna ia tarikan. Wenten juga menari di beberapa kota lain, misalnya di Solo atas undangan Sentot Sudiharto. Tak hanya itu, ia pun mengajar tari di Saraswati, persatuan putra Bali di Yogyakarta. Dari menarilah—dan terkadang menjual kain Bali—Wenten bisa menyambung hidup, mengingat kiriman wesel dari sanak keluarga tak selalu datang tepat waktu.
Wenten adalah mahasiswa ASTI yang rajin. Ia juga menjadi asisten dosen. Setelah jam kampus usai, Wenten dan Sal Murgiyanto kerap mendatangi rumah dosen untuk belajar. Dari sinilah Wenten banyak menimba ilmu kesenian. Pada 1971, Wenten menamatkan studinya dan memperoleh undangan dari Dr. Robert Brown untuk mengajar gamelan di summer school di California Institute of the Arts (CalArts). Wenten bertemu Dr. Robert Brown di Yogyakarta yang kala itu tengah mempelajari karawitan kepada seorang seniman bernama Pak Cokro. Setelah melihat kemampuan Wenten, Brown memintanya mengajar di summer school. Selama delapan minggu, Wenten mengajar mahasiswa dari pelbagai universitas, antara lain Wesleyan, Washington, Chicago, dan Michigan. Setelah summer school, Wenten dan grup mahasiswa tersebut pergi ke Bali untuk hidup di Ubud selama tiga bulan.
Setelah program tersebut usai, Brown kembali mengundang Wenten di tahun berikutnya, 1972. Brown mengharapkan agar Wenten melanjutkan studi dan mengajar di tempat CalArts. Ajakan itu diamini Wenten yang akhirnya lulus dengan gelar master pada 1975. Setahun kemudian, Wenten ditugaskan untuk mengajar di Universitas Wisconsin bersama Pak Cokro dan Nanik (istri Wenten). Selain mengajar tari Bali, ia juga memberikan mata kuliah tari Jawa dan berkolaborasi dengan banyak seniman untuk menjajaki musik dan tari kontemporer. Salah satunya dalam sebuah pentas dramatari Ramayana di New York pada 30 Maret 1990. Bersama Gamelan Kusuma Laras pimpinan Anne Stebinger, Wenten menari sebagai Rahwana, sementara Ben Suharto memerankan Rama, Endang Nrangwesti sebagai Sinta, Sal Murgiyanto sebagai Hanuman. Menurut pengakuan Wenten, pertunjukan tersebut mendulang kesuksesan dan mendapatkan perhatian dari pelbagai kalangan.
Dari secuil cerita di atas, saya percaya cerita perjalanan I Nyoman Wenten dalam menumbuhkan gamelan di Amerika lebih kompleks dan diperlukan ketimbang tayangan endorsement para pejabat di awal film, serta proses dan hasil video klip di akhir film.
Sangat disayangkan, antusiasme penonton tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan Wenten saat difilmkan. Kualitas sang sutradara yang dipertanyakan rupanya lebih menarik perhatian. Sayangnya, memang, tak banyak sosok seniman Indonesia yang difilmkan. Kebanyakan sutradara dan produser hanya tertarik memfilmkan artis atau seniman yang sedang ramai di televisi, padahal masih banyak seniman yang memiliki kontribusi besar bagi pengembangan kebudayaan.
Pelupaan atas I Nyoman Wenten—bukan film Bali: Beats of Paradise—adalah sentilan betapa tragisnya nasib kebanyakan seniman di Indonesia. Kita merayakan seniman hanya ketika karyanya diakui dunia Internasional (baca: Barat) dan melupakan bagaimana proses mereka berkarya. Inferiority complex itu nampaknya dipahami betul oleh Livi Zheng yang kelak memanfaatkannya.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.