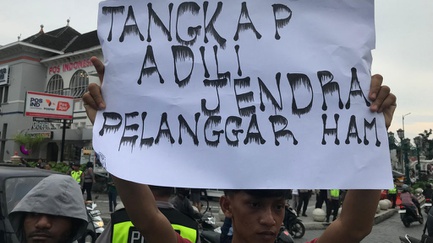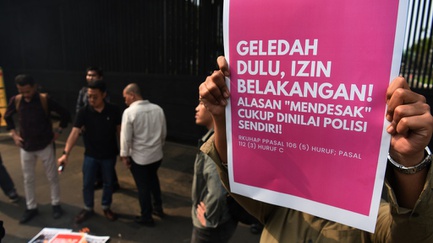tirto.id - Mobilitas adalah nadi dari kehidupan urban. Ironisnya di Indonesia, hal itu pula yang menjadi beban hidup tambahan bagi para pekerja komuter di kota. Total biaya transportasi per bulan bahkan mampu menguras seperempat dari pengeluaran rumah tangga, dan bisa menembus setengah dari gaji bulanan bagi pekerja bergaji rendah.
Ika (31), asal Kota Depok, mengaku menghabiskan sekitar Rp80.000 per hari untuk pergi ke tempat kerjanya di Jakarta Barat. Meskipun menggunakan transportasi publik berupa KRL Commuter Line, ia masih harus merogoh kocek tambahan untuk biaya transportasi daring.
Musababnya, jarak rumah Ika menuju stasiun terdekat saja perlu menempuh waktu sekitar 25-30 menit dengan sepeda motor. Sementara dari stasiun tujuan ke tempat kerja, jaraknya tidak memungkinkan ditempuh berjalan kaki. Dengan ojek daring dari stasiun tujuan, minimal ia harus menghabiskan Rp18.000-Rp25.000, tergantung situasi jalanan, untuk sampai ke kantornya.
“Kayaknya sekitaran Rp70 ribu sampai Rp80 ribu [per hari]. Soalnya udah pasti harus pakai ojol juga, karena kan saya Depok-nya perbatasan Kabupaten Bogor jadi mayan jauh,” ujar dia kepada wartawan Tirto, Senin (4/8/2025).
Situasi serupa juga dialami oleh Nanda (29), asal Kota Bekasi. Meskipun dari rumahnya bisa menggunakan KRL atau mass rapid transit (MRT), ia tetap mengeluarkan biaya tambahan untuk ojek daring. Tak heran, per hari, dia bisa menghabiskan ongkos sampai Rp55.000-60.000, untuk sampai ke tempat kerjanya di bilangan Jakarta Selatan.
Dengan gaji per bulan hanya tembus secuil dari angka UMR, ia mengaku untuk ongkos dan operasional harian saja bisa memakan seperempat dari gaji bulanannya.

“Ya memang segituan rata-rata buat ongkos doang. Mungkin karena nyambung-nyambung kendaraan umum tapi tetap pakai ojol dari stasiun akhir ke kantor,” ujar ayah satu anak ini kepada wartawan Tirto, Senin (4/8/2025).
Kendati begitu, tidak sedikit juga pekerja komuter metropolitan yang memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan harapan akan memangkas waktu tempuh dan biaya. Nyatanya, apabila dihitung biaya total pendukung untuk bensin, perawatan rutin kendaraan, tarif parkir, hingga pajak kendaraan. Angka akan lebih besar jika pekerja komuter itu memakai mobil.
Faisal Arif (25) misal, pekerja di Tanah Sareal, Kota Bogor, mengaku memilih motor untuk ke tempat kerja, dari rumahnya di daerah Tangerang Selatan. Ia merasa tak ada transportasi publik yang memadai dan efektif untuk sampai ke daerah kerjanya selain kendaraan pribadi.
Perjalanan komuter ke tempat kerjanya sekitar 36 kilometer, jika menggunakan transportasi umum seperti angkot, kata Faisal, bisa memakan waktu hampir dua jam. Dengan motor, dia mampu menuju kantor paling lama 50 menit.
Namun, Faisal belakangan menyadari, bahwa dari segi biaya, memakai transportasi pribadi pun juga tak sedikit memangkas gaji bulanannya. Rerata untuk ongkos, ia bisa menghabiskan sampai Rp1 juta, termasuk perawatan rutin.
“Untuk ongkos jujur nggak berarti hemat emang, belum capek di jalan. Tapi mau gimana lagi kan transmum lama banget, belum kalau angkot biasanya ngetem lama,” kata Faisal kepada wartawan Tirto, Senin (4/8/2025).
Tiga kota satelit Jakarta yakni Depok, Bekasi, dan Bogor, memang masuk dalam daftar lima kota teratas dengan biaya transportasi termahal di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini, kota Depok menempati urutan teratas kota dengan biaya termahal dengan Rp1,8 juta per bulan atau setara 16,32 persen dari biaya hidup sehari-hari.
Bekasi berada di urutan kedua dengan ongkos transportasi per bulan tembus 14,02 persen dari biaya hidup. Sementara biaya ongkos transportasi bulanan Kota Bogor mencapai Rp1,2 juta atau setara 12,54 persen dari biaya hidup. Di luar Jabodetabek, ada Surabaya (13,61%) dan Jayapura (12,45%) yang masuk dalam posisi lima teratas.
Transport Mahal, Tabungan Tipis
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai jika lebih dari 10 persen pendapatan bulanan digunakan untuk transportasi artinya semakin kecil porsi masyarakat untuk menabung atau bahkan mengumpulkan dana darurat. Biaya transportasi memang memegang peranan penting karena dikeluarkan secara rutin.
Namun, ketika pengeluaran ongkos bekerja ternyata membengkak, sudah pasti masyarakat akan sulit dalam berbelanja kebutuhan tambahan. Kondisi ini rentan dialami pekerja komuter yang saban hari harus melaju antarkota untuk pergi bekerja.
“Jadi kenaikan pendapatan pun juga hanya untuk menutupi biaya transportasi. Masyarakat akan cenderung stagnan standar hidupnya,” kata Huda kepada wartawan Tirto, Senin (4/8/2025).

Menurut Huda, seharusnya pemerintah mempunyai program yang bisa menurunkan ongkos transportasi pekerja komuter dengan cara memberikan subsidi atau skema sosial lainnya. Ia mencontohkan Pemprov Jakarta, lewat program biaya transportasi umum dengan subsidi.
Sayangnya, transportasi publik penghubung dari kota-kota satelit belum mendukung karena berbagai keterbatasan seperti ketersediaan dan waktu tempuh.
“Namun lagi-lagi, sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah masing-masing,” ujar Huda.
Sementara itu, pengamat tata kota M Azis Muslim, menilai besarnya biaya pekerja komuter sebagai akibat langsung dari belum tersedianya transportasi umum terintegrasi dan efektif. Meskipun sudah muncul transportasi feeder di sejumlah wilayah sekitar Jakarta, namun dari segi jumlah dan cakupan belum memadai untuk melayani pekerja komuter.

Azis menilai, risiko dari transportasi publik yang tak mendukung kesejahteraan kelas pekerja juga tak hanya mempengaruhi biaya hidup secara langsung, namun juga mengancam status kesehatan masyarakat pekerja.
“Memang [mesti] mampu menghadirkan transportasi yang efisien dan terintegrasi, yang juga mesti ke depan dipahami agar kota menjadi semakin inklusif dan berkelanjutan,” ucap Azis kepada wartawan Tirto, Senin (4/8/2025).
Pekerja komuter memang tak hanya terancam dari sisi ekonomi, kualitas kesehatan mereka juga semakin rentan karena perjalanan yang tidak ideal. Waktu tempuh panjang, jadwal dan ketersediaan moda transportasi publik yang mesti berebut, sampai risiko kecelakaan bagi pengguna kendaraan pribadi, memang menjadi momok pekerja komuter.
Dalam studi berjudul “Pola Perilaku Komuter dan Stres: Bukti dari Jabodetabek” yang ditulis dua peneliti Universitas Indonesia, disebut bahwa setiap kenaikan waktu tempuh dalam berkomuter sebanyak 10 menit, berasosiasi terhadap kecenderungan terkena stres sebesar 0,8-1,8 persen. Singkatnya, semakin lama durasi tempuh pekerja komuter sampai ke kantor, semakin rentan pula pekerja mengalami stres.
Sementara itu, hasil Survei Komuter Jabodetabek 2023 yang dikeluarkan BPS, menunjukkan terdapat sekitar 14,9 persen penduduk komuter dari 29,6 juta penduduk Jabodetabek yang berusia 5 tahun ke atas. Sebesar 72,0 persen komuter di Jabodetabek berada di kelompok umur yang sangat produktif (15–44 tahun), dan 38,7 persen komuter menempuh perjalanan antara 30 menit sampai kurang dari satu jam untuk mencapai tempat kegiatannya.
Sedangkan 35,5 persen komuter butuh minimal satu jam untuk sampai tempat tujuan. Hal ini menunjukkan masih banyak komuter yang butuh waktu lebih dari 60 menit untuk ke tujuan.
Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, sebagian besar komuter (75,7 persen) bekerja di sektor jasa. Sementara dilihat status pekerjaan utama, sekitar 80,0 persen komuter bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Dari sini tercermin urgensi transportasi publik semestinya menjadi prioritas pemerintah karena banyaknya pekerja yang bergantung terhadapnya.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa jika lebih dari 10 persen pendapatan rumah tangga habis hanya untuk biaya transportasi, dampaknya cukup besar bagi kesejahteraan keluarga. Dalam kajian ekonomi transportasi, angka di atas 10–15 persen sudah dianggap sebagai beban yang berat (transportation cost burden), sebab memaksa keluarga mengorbankan kebutuhan penting lain seperti makanan, pendidikan, kesehatan, atau biaya tempat tinggal.

Akibat panjangnya, banyak rumah tangga mengurangi pengeluaran yang produktif, berisiko terlilit utang, dan mengalami tekanan finansial. Situasi ini menciptakan kondisi yang disebut transport poverty, yaitu situasi di mana seseorang tetap bekerja, tapi penghasilannya habis untuk mobilitas, sehingga tidak bisa menabung atau memenuhi kebutuhan dasar.
Menurut Yusuf, fenomena ini merupakan bagian dari kemiskinan struktural, yang diperparah urbanisasi, ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta tata kota yang belum mendukung efisiensi perjalanan. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang terjebak sebagai working poor alias punya pekerjaan, tapi tidak mampu meningkatkan taraf hidup.
“Perlu perencanaan kota yang terpadu, seperti kawasan mixed-use yang membuat tempat tinggal, kerja, dan layanan publik berada dalam jarak dekat. Selain itu, subsidi transportasi atau insentif seperti perjalanan juga bisa membantu. Tidak kalah penting, kebijakan harus berbasis data misalnya dengan menggunakan indeks Transport Poverty Risk,” ungkap Yusuf kepada wartawan Tirto, Senin (4/8/2025).
Ketua Forum Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, menilai transportasi publik kita umumnya baru sebatas moda transportasi koridor utama atau backbone. Transportasi publik belum merambah ke kawasan pemukiman atau pelosok.
Sementara transportasi umum kawasan Bodetabek, seperti angkutan kota, sudah cenderung termarjinalkan dan bahkan banyak yang sudah tidak beroperasi. Ia menambahkan bahwa Jakarta menjadi satu-satunya kota yang sudah memiliki sistem angkutan pemukiman seperti Mikrotrans yang bahkan bisa diakses secara gratis melalui sistem kartu pintar.
Aditya menyebut kegagalan terbesar sistem transportasi nasional adalah tidak tersedianya angkutan kecil yang mampu menjangkau perkampungan dan wilayah pedesaan. Idealnya, akses transportasi umum seharusnya berada dalam jarak 200 hingga maksimal 500 meter dari rumah atau tempat aktivitas seperti sekolah, perkantoran, dan pasar.
Karenanya, penting membangun transportasi yang tidak cuma mengandalkan moda utama, tetapi juga moda pengumpan dan moda ulang-alik (shuttle), terutama di kawasan komersial, perkantoran, dan industri. Ia mengusulkan adanya integrasi sistem tiket dan tarif agar tidak membebani pengguna.
“Tarif seharusnya tidak kumulatif, tapi sudah dalam bentuk bundling antara tarif pengumpan dan tarif utama,” ucap Aditya kepada wartawan Tirto, Senin (4/8/2025).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Farida Susanty
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id