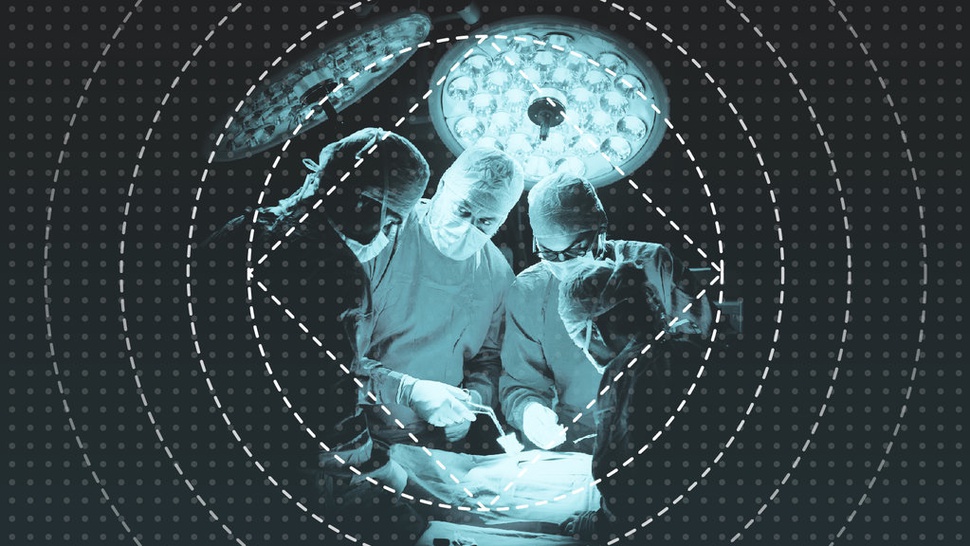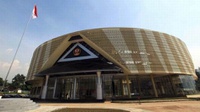tirto.id - Di tengah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berambisi membuka fakultas-fakultas kedokteran baru guna mewujudkan nisbah jumlah dokter yang ideal, tetapi mengesampingkan saran yang menyoroti sisi kualitas, sistem pendidikan kedokteran menciptakan lubang tersendiri yang menjerat lulusannya sulit bekerja secara ideal.
Salah satu muaranya, meski bukan satu-satunya, adalah pasal 36 Undang-Undang 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Ketika mulai diterapkan pada 2014, untuk kali pertama mahasiswa kedokteran harus menempuh Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Muda. Ujian tersebut menjadi syarat bagi mahasiswa kedokteran memperoleh sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, dan dipakai atau dianggap setara sebagai pengganti ijazah. Dampaknya, mahasiwa yang lulus pendidikan dokter belum tentu menerima ijazah karena gagal ujian kompetensi.
Atas dasar itu, pihak universitas punya kewenangan penuh menentukan kelulusan dan kelayakan seseorang menjadi dokter. Padahal pendidikan kedokteran di dunia mengacu pada World Federation for Medical Education. Lembaga ini mengatur kewenangan universitas sebatas pendidikan dasar medis. Sementara ranah profesi dipegang oleh kolegium.
Setelah Uji Kompetensi digelar dan melewati evaluasi, hasilnya bikin dahi mengernyit. Tingkat kelulusan sangat rendah. Banyak mahasiswa harus mengulang ujian, bahkan sampai 20 kali—disebut retaker. Akhirnya, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Ilham Oetama Marsis didapuk menjadi ketua penyelesaian masalah retaker. Ia berhasil menekan angka retaker dari 2.500 orang menjadi 110 orang.
“Tapi babak baru mulai, kini ada 2.700 retaker menumpuk. Jelas ada sistem yang salah di sini,” katanya.
Ketika itu fakultas kedokteran di Indonesia mencapai 75 negeri maupun swasta, dengan persentase akreditasi A sebanyak 23 persen, 37 persen akreditasi B, dan 40 persen akreditasi C. Artinya, fakultas kedokteran dengan akreditasi lapis terendah menyumbang persentase terbanyak.
Namun, bukannya berbenah meningkatkan kualitas akreditasi, Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir justru memberi izin pembukaan delapan fakultas kedokteran baru pada akhir Maret 2016.
Delapan perguruan tinggi ini Universitas Islam Negeri Alauddin dan Universitas Bosowa (Makassar); Universitas Khairun (Ternate); Universitas Surabaya; Universitas Ciputra (Surabaya); Universitas Muhammadiyah Surabaya; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Malang); dan Universitas Wahid Hasyim (Semarang).
Kementerian Ristekdikti mengabaikan penilaian Tim Evaluasi Program Studi Pendidikan Dokter dari sejumlah organisasi kedokteran. Tim Evaluasi mengusulkan Universitas Khairun berstatus afirmasi atau "diawasi pemerintah" selama dua tahun. Hanya UIN Alauddin dan Universitas Surabaya yang layak mendapatkan izin. Empat lain tak memenuhi syarat karena tersandung kendala jumlah dosen, fasilitas, dan modul pembelajaran.
“Sistemnya tidak betul karena undang-undang memberi kewenangan lebih ke kemenristekdikti,” tambah Ilham Oetama Marsis.
Sikap keras kepala Menteri Nasir untuk tetap meloloskan delapan fakultas kedokteran di kampus-kampus itu menuai kritik. Terus membuka izin tapi sekaligus membiarkan jumlah retaker menumpuk karena tanpa memperbaiki kualitas pendidikan. Akhirnya, pada Juni pada 2016, Kementerian memutuskan moratorium agar fakultas-fakultas kedokteran berakreditasi C berbenah diri, meningkatkan akreditasi, setidaknya menyandang akreditasi B.
Sayang, usia moratorium FK hanya satu tahun. Pada September 2017 keputusan itu dicabut dengan pertimbangan sudah ada peningkatan akreditasi dari delapan kampus dari C menjadi B. Persentase akreditasi berubah, dari 83 fakultas kedokteran, 17 di antaranya terakreditasi A, 34 akreditasi B, 22 akreditasi C, dan 10 lain mengantongi akreditasi minimal.
Izin penyelenggaraan program studi kedokteran diberikan Kementerian Ristekdikti kepada prodi dengan minimal dosen 26 orang serta memiliki rumah sakit pendidikan atau bekerja sama. Khusus untuk perguruan tinggi di daerah Jawa, sebanyak 20 persen mahasiswanya harus dari daerah-daerah yang mengalami kelangkaan tenaga dokter.

Moratorium Bukan Jawaban
Salah satu alasan yang dipakai Kementerian Ristekdikti ketika mencabut moratorium fakultas kedokteran adalah rasio dokter. Beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bagian timur Indonesia mengalami kelangkaan. Laman resmi IDI menyebutkan alasannya bukan karena jumlah dokter kurang, melainkan distribusi dokter tidak merata.
Hingga saat ini jumlah dokter di Indonesia bisa dikatakan cukup. Data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 9 Mei 2016 mencapai 110.720 orang. Artinya, satu dokter melayani 2.270 penduduk. Jumlah ini sudah mendekati rasio ideal dokter yang dipersyaratkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 1 : 2.500. Namun, Kementerian menargetkan rasio dokter Indonesia mencapai 1 : 2.000. Menurut kementerian, pada 2030, Indonesia diprediksi kekurangan dokter hingga 25.740 orang setiap tahun.
Sayang, kebijakan mencetak sarjana kedokteran tanpa diimbangi perbaikan sistem malah menciptakan masalah baru. Para mahasiswa kedokteran harus berjuang mati-matian agar lolos Uji Kompetensi. Cerita ini dituturkan dr. Saifullah yang menamatkan pendidikannya di Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 2016.
Untuk bisa memegang sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, mahasiswa kedokteran harus melakukan dua tes: Computer Base Test (CBT) dengan menyelesaikan 200 soal pilihan ganda dalam waktu 200 menit; dan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) alias ujian praktik atau klinis di depan dewan penguji dengan waktu terbatas.
Jamaknya, para calon dokter gagal pada ujian CBT karena kekurangan waktu serta standar jawaban berbeda, tergantung mazhab yang yang dipakai dalam ujian tersebut, mengingat tak ada jawaban yang salah melainkan peserta ujian harus mengisi jawaban yang paling benar. Sementara kegagalan pada ujian OSCE berawal dari ketidaksiapan mental yang harus menghadapi penguji dari dokter-dokter ahli. Dalam kasus Saifullah, ia dinyatakan lolos dalam satu kali ujian.
"Kami sering sharing dengan teman di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan lain-lain karena setiap kampus punya tata laksana penyelesaian penyakit yang berbeda-beda,” katanya.
Kesulitan para mahasiswa menjalani Uji Kompetensi ditangkap pula sebagai peluang bisnis oleh pelbagai pihak. Ada beragam jasa bimbingan belajar (bimbel) khusus menghadapi ujian kompetensi. Pihak fakultas biasanya menyediakan kursus dengan jumlah peserta 40-50 orang per sesi. Sementara kursus privat disediakan pihak luar, diisi para senior mereka, dengan peserta 10 orang dalam satu kelompok.
“Karena terkadang kami merasa bimbel dari fakultas tak cukup untuk mengejar target, kami ikut bimbel di luar dengan biaya Rp2-3 juta per sesi,” ujar Saifulllah, mengisahkan pengalamannya.
Guna membereskan sistem pendidikan kedokteran yang menghambat masa depan dokter muda, saat ini Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia bersama beberapa lembaga kesehatan lain tengah mengusulkan revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Ada sekitar 70 persen perubahan yang diajukan ke DPR untuk merevisi regulasi tersebut. Poin yang paling utama adalah mengkritisi wewenang absolut Kementerian Ristekdikti.
Termasuk yang perlu direvisi adalah menghapus retaker khusus, ujar Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis. Draf tersebut mengatur masa studi maksimal hingga dua kali Uji Kompetensi. Jika gagal, mahasiswa akan disalurkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Draf ini akan mengubah pola pendidikan dokter di Indonesia menjadi modern dan universal,” ujar Marsis.
Kementerian tak bisa asal memberi izin pembukaan fakultas kedokteran baru. Tim Evaluasi Program Studi Pendidikan Dokter akan memiliki hak setara untuk menentukan kelayakannya. Calon mahasiswa yang mendaftar fakultas kedokteran harus menjalani seleksi akademik dan psikotes, seperti umum digelar negara lain.
Tujuannya, selain menciptakan sarjana kedokteran yang mumpuni secara akademik, juga punya kondisi mental yang tahan banting. Harapannya sederhana: agar tiada lagi cerita mahasiswa yang harus depresi dan mengakhiri hidupnya saat menjalani perkuliahan, atau penolakan dokter-dokter ketika ditempatkan di pelosok daerah.
Impian yang mulai, meski agaknya jalan ke sana bakal panjang.
Penulis: Aditya Widya Putri
Editor: Fahri Salam