tirto.id - Angka empat puluh memberikan kesempatan baru pada kehidupan, dan begitulah angka itu selalu muncul dalam kitab-kitab suci yang hadir di Timur Tengah. Durasi banjir besar yang ditunggu dalam bahtera Nuh, jumlah tahun tatkala Bani Israel mengembara di padang pasir pasca-eksodus, lamanya malam yang dihabiskan Isa di alam liar—semuanya empat puluh.
Bilangan itu menandakan waktu perjuangan dan perpindahan untuk mempersiapkan sebuah awal baru. Bagi siapa pun yang cukup beruntung untuk hidup selama itu, empat puluh tahun menandai kesempurnaan waktu: melangkah memasuki takdir manusia.
Dan begitulah pada 17 Ramadan 610 M, seperti yang telah ia jalani beberapa tahun terakhir, Muhammad—yang berusia 40—mengasingkan diri di Gua Hira, tempat segala yang bersifat duniawi disingkirkan. Di dalam gua itu, ia bisa menjadi bagian dari keheningan; membiarkan keluasan yang tak terbendung merasuk ke dalam dirinya.
Apa yang sebenarnya terjadi di Gua Hira?
Kita mengetahuinya dari apa yang kelihatannya merupakan kata-kata Muhammad sendiri, namun kata-kata itu diriwayatkan melalui orang-orang lain, dengan beberapa perbedaan. Masing-masing periwayat berjuang untuk menafsirkan sesuatu yang tak dapat dilukiskan itu ke dalam istilah yang dapat mereka mengerti.
Lesley Hazleton dalam The First Muslim: The Story of Muhammad (2013) mendedahkan salah satu riwayat yang diceritakan Aisyah, perempuan termuda dan paling vokal di antara istri-istri yang Muhammad nikahi setelah kematian Khadijah.
“Muhammad mengatakan: ‘Ketika malaikat mendatangiku, aku baru saja berdiri, tetapi malaikat itu muncul di hadapanku saat aku memikirkan hal ihwal ini, dan berkata, ‘Muhammad, aku Jibril dan engkau adalah utusan Allah.’ Kemudian malaikat itu berkata, ‘Bacalah!’ Aku berkata, ‘Apa yang harus harus aku baca?’ Dia meraihku dan memelukku dengan erat tiga kali sampai aku nyaris kehabisan napas dan berpikir aku akan mati, dan selanjutnya malaikat itu berkata, ‘Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan, Dia meraihku dan memelukku dengan erat tiga kali sampai aku nyaris kehabisan napas dan berpikir aku akan mati, dan kemudian malaikat itu berkata, ‘Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan perantaraan kalam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (hlm. 92).
Kisah itu berlanjut dalam kata-kata yang dikisahkan salah satu sahabat Nabi, Ibnu Zubair, yang kembali mengutip langsung perkataannya:
“Aku membacanya, dan malaikat itu pun berhenti dan pergi. Aku terbangun, dan seolah-olah kata-kata itu sudah terpahat di dalam hatiku. Aku berpikir, ‘Aku pasti seorang penyair atau orang gila. Namun jika demikian, Quraisy tidak akan pernah mengatakan perihal ini tentang diriku. Aku akan mendaki ke puncak gunung, lalu melemparkan diri dari atas sana, dan menemukan peristirahatan dalam kematian.’ Akan tetapi, ketika aku sudah dekat dengan puncak gunung, aku mendengar suara dari langit mengatakan, ‘Muhammad, engkau adalah utusan Allah.’ Aku mendongak untuk melihat siapa yang bicara dan di sanalah Jibril dalam bentuk seorang pria dengan kaki mengangkangi cakrawala. Aku berdiri memandanginya dan hal ini mengalihkanku dari niat, dan aku tidak bisa maju ataupun mundur. Aku membalikkan wajahku darinya ke semua penjuru cakrawala, tetapi di mana pun aku memandang, aku melihat dia persis dalam bentuk yang sama” (hlm. 92-93).
Peristiwa yang Tak Mampu Dilukiskan dengan Kata-Kata
Menurut Karen Armstrong dalam Muhammad: Prophet for Our Time (2006), mereka ini adalah orang-orang dengan maksud baik yang berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk suatu keadaan yang tidak pernah mereka alami. Dalam proses itu, mereka menyederhanakannya: mengubah sesuatu yang metafisik menjadi sesuatu yang semata fisik, seperti dalam gambaran tentang malaikat Jibril yang mengangkangi pegunungan. Seolah-seolah momen itu adalah peristiwa yang penuh selubung, seakan-akan penjelasan yang terlalu mendekati apa yang terjadi pada malam itu berada di luar jangkauan nalar manusia. Dan persis begitulah Muhammad mengalaminya (hlm. 67-68).
Muhammad dibiarkan meringkuk di tanah, terkulai tak berdaya. Basah kuyup oleh keringat dan gemetar. Ia dirasuki kata-kata yang merupakan miliknya, tetapi sekaligus bukan miliknya. Kata-kata yang telah ia ulang-ulang dengan lantang ke dalam udara pegunungan yang tipis dan murni, ke dalam kekosongan dan kegelapan.
Mungkin ia merasakan sesuatu dalam dirinya bahwa kata-kata itu baru bisa hidup, baru dapat menjadi realitas, ketika diucapkan di hadapan manusia lain. Satu-satunya orang yang dapat ia tuju sebagai pelipur lara dalam menghadapi kekuatan yang melimpah ruah ini, yang mungkin dapat menyelamatkannya dari ketakutan akan kegilaan adalah Khadijah.
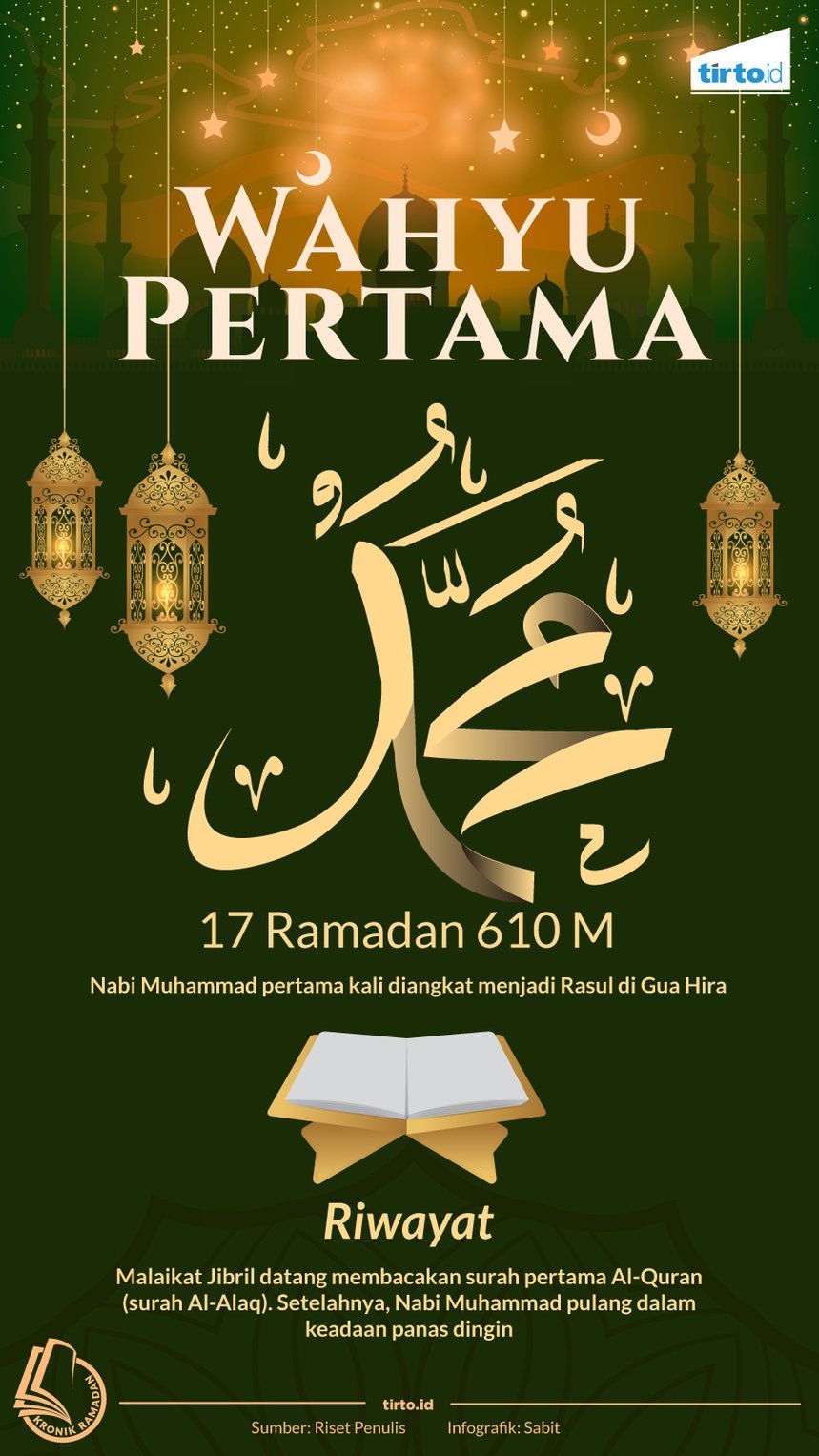
Setelah mengalami peristiwa paling menggetarkan dalam hidupnya itu, Muhammad terhuyung-huyung menuruni gunung, tergelincir dan meluncur di atas kerikil yang berjatuhan di sepanjang lereng. Napasnya panas dan serak, hingga dadanya seakan-akan hendak meledak. Jubahnya robek, lengan dan kakinya lebam terkena duri-duri dan bebatuan tajam di sepanjang jalan menuju rumah.
“Aku mengkhawatirkan jiwaku,” adalah kalimat pertama yang diucapkan Muhammad ucapkan sesampainya di rumah.
“Kupikir aku pasti sudah gila.”
Gemetar, menggigil nyaris tak terkendali, dia memohon kepada istrinya, Khadijah, untuk memeluk dan menyembunyikannya di balik selendangnya.
“Selimuti aku, selimuti aku,” dia memohon, kepalanya berada di atas pangkuan Khadijah.
Dan kengerian itu sendiri sudah cukup untuk meyakinkan Khadijah bahwa apa yang dialami suaminya benar-benar nyata. Ia memeluk suaminya, membuainya seiring langit malam mulai memucat di ufuk timur membawa harapan yang meyakinkan.
Menurut Kecia Ali dalam The Lives of Muhammad (2014), Khadijah yang begitu tenang semakin menguatkan Muhammad. “Demi Allah yang di tangan-Nyalah jiwaku berada, aku berharap semoga engkau adalah Nabi bagi kaum ini.”
Tatkala ia yakin suaminya tidak akan segera terbangun, Khadijah menggesernya pelan-pelan ke tempat tidur, membungkus dirinya rapat-rapat dengan kerudung, dan pergi ke luar. Ia menyambangi kediaman sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang hanif dan padri Kristen Nestorian, untuk bertanya apa yang sebenarnya sedang menimpa Muhammad.
Tanggapan sepupunya itu tidak kurang dari apa yang Khadijah harapkan: “Jika kau telah mengatakan kebenaran Muhammad adalah roh agung yang muncul di hadapan Musa pada masa lampau, dia benar-benar Nabi umat ini. Katakan kepadanya agar dia berteguh hati” (hlm. 203).
Dan jika Khadijah dan Waraqah benar, maka rasa hormat yang telah diperjuangkan Muhammad begitu lama dan dengan susah payah kini berada dalam bahaya. Muhammad akan menjadi orang luar lagi, bahkan orang yang terusir dari Mekkah. Bukan sekadar diabaikan, tetapi dihinakan dan dicemooh, kehormatannya ditolak, martabatnya dilanggar. Kedamaian nan sederhana dan bersahaja yang telah Muhammad gapai selama ini akan terenggut darinya (hlm. 204).
Maka demikianlah, Nabi Muhammad telah mendapatkan wahyu pertama dan peristiwa itu menjadi titik balik paling menentukan dalam hidupnya. Wahyu-wahyu yang datang kemudian menyerukan kepada Muhammad, sang Rasulullah, bahwa telah tiba saatnya untuk mewartakan kalam-kalam Tuhan kepada seluruh umat manusia.
Sepanjang Ramadan, redaksi menampilkan artikel-artikel tentang peristiwa dalam sejarah Islam dan dunia yang terjadi pada bulan suci kaum Muslim ini. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Kronik Ramadan". Kontributor kami, Muhammad Iqbal, sejarawan dan pengajar IAIN Palangka Raya, mengampu rubrik ini selama satu bulan penuh.
Editor: Ivan Aulia Ahsan












