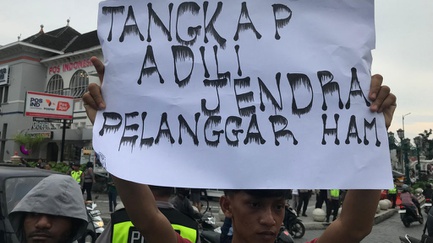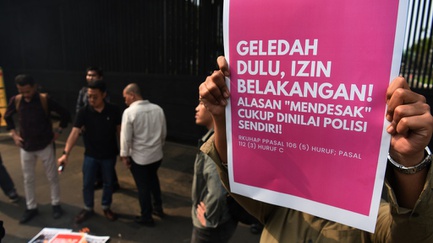tirto.id - Setiap tahun, ribuan bencana alam melanda Indonesia, menyebabkan kerusakan parah pada ribuan rumah dan fasilitas umum. Di tengah negara yang rawan bencana, membangun gedung yang mampu bertahan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Namun, banyak pemilik bangunan masih menganggap biaya tambahan untuk keamanan sebagai beban, padahal seharusnya dilihat sebagai investasi jangka panjang yang krusial.
Andri Setiawan, seorang peneliti struktur dari Technical University of Valencia, Spanyol, sedang mengembangkan sebuah metode revolusioner untuk bangunan tahan bencana. Penelitiannya tidak hanya menawarkan solusi inovatif, tetapi juga mengubah cara pandang kita terhadap biaya dan keamanan dalam industri konstruksi.
Menurut Andri, tantangan terbesar dalam dunia konstruksi saat ini adalah menyelaraskan dua konsep yang terkadang bertentangan: keberlanjutan (sustainability) dan ketahanan (resilience).
Upaya membangun gedung yang ramah lingkungan sering kali menuntut penggunaan material yang minimalis dan desain yang "seramping" mungkin. Namun, di sisi lain, desain yang terlalu optimal justru bisa membuat struktur menjadi rentan terhadap bencana.
Lalu, bagaimana solusinya?
Belajar dari Cicak: Konsep Revolusioner dalam Desain Gedung
Secara tradisional, filosofi untuk membuat bangunan tahan bencana adalah dengan mengikat setiap bagian gedung sekuat mungkin, mirip seperti pendaki gunung yang saling terhubung dengan tali pengaman (safety rope). Tujuannya, jika satu elemen struktur gagal—misalnya satu pilar runtuh akibat ledakan atau gempa—beban akan didistribusikan ke elemen lain, sehingga gedung tetap berdiri.
Namun, riset Andri dan timnya menunjukkan bahwa ikatan kuat ini bisa menjadi bumerang. "Kalau yang jatuh bukan satu orang, tapi delapan dari sepuluh pendaki, apa yang terjadi pada dua sisanya? Mereka justru akan ikut tertarik jatuh," jelas Andri dalam wawancara podcast "kueri".
Dalam kondisi ekstrem, satu-satunya solusi adalah memotong tali untuk menyelamatkan sebagian.
Fenomena inilah yang disebut kegagalan beruntun atau progressive collapse, di mana kerusakan kecil merambat dan menyebabkan keruntuhan total yang jauh lebih besar. Terinspirasi dari kemampuan cicak atau kadal yang bisa memutuskan ekornya untuk selamat dari pemangsa (autotomy), Andri mengajukan sebuah konsep baru: menciptakan ikatan pada gedung yang tidak terlalu lemah, namun juga tidak terlalu kuat.
Gedung dirancang dengan titik-titik sambungan khusus yang sengaja didesain untuk ‘patah’ atau putus secara terkendali saat menghadapi bencana skala besar. "Ini bukan berarti kita memperlemah gedung, tapi kita merancang di mana seharusnya kerusakan itu berhenti," tegas Andri.
Dalam sebuah uji coba skala penuh yang menelan biaya miliaran rupiah, timnya membangun gedung dua lantai lalu secara sengaja meruntuhkan tiga kolom utamanya. Hasilnya luar biasa. Ketika kolom ketiga dilepas, gedung tidak runtuh total. Keruntuhan berhenti tepat di "garis patahan" yang telah dirancang, membuktikan bahwa sebagian besar struktur bangunan berhasil diselamatkan.
"Pilihannya ada dua: menyelamatkan sebagian gedung untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan, atau membiarkannya runtuh seluruhnya," ujar Andri.
Ini adalah konsep kontrol kerusakan (damage control), bukan penghilangan kerusakan.
Asuransi Masa Depan: Mengapa Biaya Awal Bukan Segalanya
Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah: Mahal tidak teknologinya?
Jawabannya mungkin mengejutkan: penerapan metode ini tidak memerlukan biaya konstruksi tambahan yang signifikan. Andri menjelaskan bahwa yang dikembangkan adalah sebuah filosofi atau metodologi perancangan baru, bukan alat atau material berteknologi tinggi. Metode ini menggunakan material yang sudah ada di pasaran, sehingga tidak ada penambahan biaya dari segi material.
Biaya tambahan mungkin muncul pada tahap perancangan yang memerlukan waktu lebih lama dan analisis lebih mendalam. Namun, biaya ini seharusnya tidak dilihat sebagai pengeluaran, melainkan sebagai investasi—sebuah premi asuransi untuk masa depan.
Andri mengibaratkan membangun gedung tanpa memperhitungkan ketahanan bencana sama seperti menjalani hidup tanpa asuransi kesehatan.
"Kalau kita yakin 50 tahun ke depan tidak akan pernah sakit, mungkin biayanya murah. Tapi begitu ada 'sakit'—baik itu gempa kecil maupun besar—biaya perbaikan dan kerugian operasional akan jauh lebih mahal," paparnya.
Gedung yang dirancang dengan baik mungkin membutuhkan biaya awal 10-15% lebih tinggi, tetapi dalam jangka panjang, ia dapat terus beroperasi setelah bencana, sementara gedung lain lumpuh dan membutuhkan perbaikan mahal. Bagi fasilitas krusial seperti rumah sakit atau pusat data, nilai dari keberlangsungan operasional ini tidak terhingga.
"Kita harus mengubah pola pikir. Biaya bukan hanya biaya awal (initial cost), tapi biaya siklus hidup (life cycle cost) dari gedung itu berdiri hingga 50 tahun ke depan," tutup Andri.
Dengan menyadari bahwa kita tinggal di wilayah rawan bencana, berinvestasi pada keamanan sejak awal adalah langkah paling bijak untuk melindungi properti, bisnis, dan yang terpenting, nyawa manusia.
Editor: Farida Susanty
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id