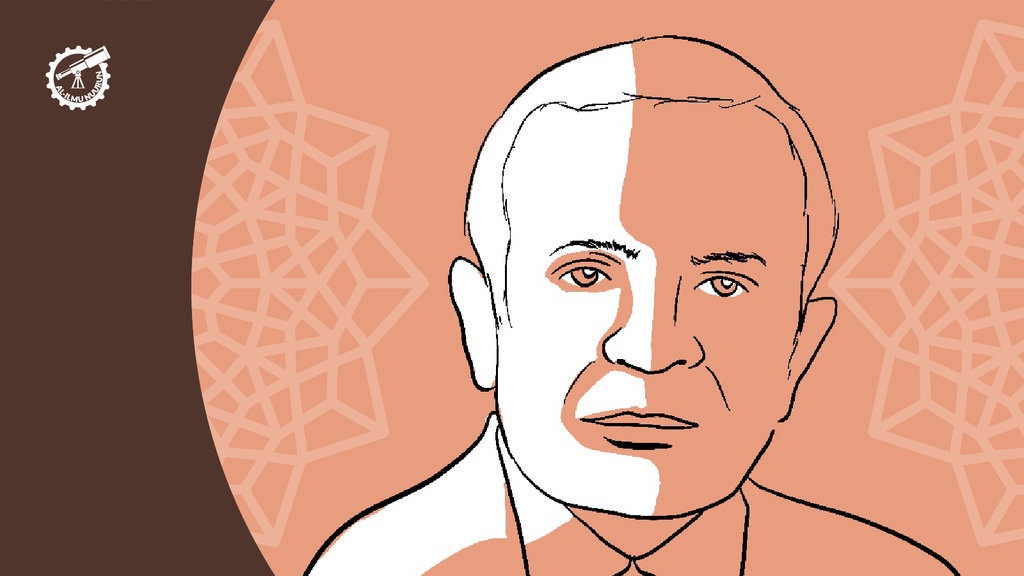tirto.id - Dalam cerita kuno Suryani, Gunung Lebanon (Jibal Lubnan) disebut Tur Levnon yang bermakna dasar ‘putih’. Gambaran ini mengacu pada salju yang menutupi pegunungan tersebut pada musim dingin.
Kahlil Gibran lahir di sana pada masa akhir kekuasaan Usmani. Kakek Salma Hayek dari garis ayah juga lahir di daerah itu. Bukankah 'salma' adalah nama Arab untuk ‘teduh’ atau ‘tenang’? Hayek memproduseri film animasi The Prophet (2014), yang diadopsi dari karya Gibran, untuk mencari jejak jati dirinya yang setengah Lebanon. Moyang pemikir terkenal, Nassim Nicholas Taleb, juga asalnya dari situ. Penyanyi Shakira—namanya bermakna 'perempuan yang bersyukur'—juga punya tautan dengan wilayah tersebut.
Bukan hanya figur Kristen dengan tradisi campuran Suryani dan Arab, dari gunung itu juga lahir banyak tokoh muslim terkemuka. Salah satunya Ridwan al-Sayyid. Latar belakang Gunung Lebanon dengan penduduk Kristen menjadi menarik dilirik. Pada masa Usmani akhir, wilayah ini merupakan titik pertemuan antara berbagai aktivitas misionaris Eropa dan Amerika. Dalam buku teranyarnya, The Age of Coexistence (2019), keponakan Edward Said, Ussama Makdisi, menyebut wilayah ini mewakili salah satu dari sistem kuota sektarian antara otoritas Eropa dan Usmani untuk menengahi perbedaan non-diskriminatif.
Ketimbang wilayah Balkan yang juga plural di bawah kendali Usmani, Gunung Lebanon jauh lebih heterogen dalam hal keagamaan. Bahkan wilayah ini menjadi medan perebutan kuasa dan hukum internasional antara reformasi Tanzimat Usmani dan pembelahan identitas keagamaan dari 1860 hingga awal abad ke-20. Makdisi menjadikan sejarah daerah ini sebagai kasus paradigmatik dari apa yang disebut sebagai ko-eksistensi. Lahir di lingkup budaya ini, Sayyid tumbuh dalam ruang multireligius dan multikultural.
Memihak Multikulturalisme Lebanon
Lingkup Lebanon yang plural memaksa sistem politik terbagi di antara berbagai identitas keagamaan: Suni, Syiah, Kristen dengan berbagai denominasinya, Druze, serta minoritas agama lain. Tidak ada intelektual yang tumbuh dari rahim ini ingin menghancurkan keindahan Lebanon yang, pada masa sebelum Perang Sipil, dianggap sebagai pusat intelektual dan mode Timur Tengah.
Hubungan Islam dan Kristen menjadi topik yang wajib diperbincangkan dan dipraktikkan dengan baik. Setelah Perang Sipil memporakporandakan sendi kehidupan plural dalam tiga dekade ini, upaya untuk memulihkannya tak pernah putus. Dua intelektual muslim yang paling aktif membangun dialog ialah Muhammad al-Sammak, pengarang buku Muqaddimah ila al-hiwar al-islami al-masihi (Pengantar untuk dialog Islam-Kristen), dan Ridwan al-Sayyid.
Posisi Sayyid sangat sentral dalam wacana intelektual di negeri itu. Ia pemimpin redaksi majalah al-Ijtihad dan direktur Lembaga Pendidikan Tinggi untuk Kajian Islam di Beirut. Ia memegang banyak peranan penting dalam dunia akademik dan politik di Lebanon, Yordania, dan perkumpulan orientalis Jerman di negerinya. Kini ia menjadi anggota biro politik di Partai Masa Depan (Tayyar al-Mustaqbal) yang berafiliasi ke Islam Suni dan mengkritik keras gerakan Hizbullah yang Syiah dan dianggap "teroristik". Sebelumnya ia menjadi penasihat bagi banyak perdana menteri, terutama Saad Hariri, Fuad Seniora, dan Rafik Hariri.
Ditambah lagi, Sayyid memiliki dua otoritas intelektual: lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo dan doktor dari Universitas Tübingen, Jerman pada 1977. Di Tübingen, Sayyid belajar pada orientalis Jerman yang sangat berpengaruh, Joseph van Ess, penulis berjilid-jilid Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra (sejarah pemikiran Islam pada masa awal Islam). Setengah berkelakar, van Ess bertanya kepada Sayyid saat ia datang ke Tübingen, “Mengapa Anda datang ke kami dari Al-Azhar untuk memperoleh gelar dalam Islamwissenschaft (studi Islam dalam orientalisme Jerman), sedangkan kami tak merasa butuh untuk pergi ke Al-Azhar guna belajar Islam klasik?”
Kelakar ini mengingatkan saya pada kecurigaan basi—dan bukan candaan ala van Ess—dari banyak orang yang mempertanyakan kenapa seorang muslim belajar Islam di Barat. Untuk menghindari debat kusir, saya selalu menjelaskan singkat, “Saya belajar sejarah dan filologi Arab.” Alles klar!
Karier Sayyid selama empat puluh tahun sebagai profesor kajian Islam di Universitas Lebanon tak terlepas dari perkembangan politik di negerinya dan Timur Tengah secara umum. Pada masa awal kariernya, dasawarsa 1980-an, Abed al-Jabiri dan Hassan Hanafi memberi pesan kepada Sayyid untuk berfokus pada pemikiran politik Islam terutama untuk dijadikan acuan bagi akademikus. Masukan ini diterima dan menjadi fokus intelektual utamanya.
Tak hanya filsuf Arab, Sayyid juga aktif berdialog secara personal dengan ulama tradisional khususnya dalam jaringan Suni Al-Azhar. Ia dekat dengan Ramadan al-Buti (m. 2013) dan Wahbah Zuhayli (m. 2015), dua syekh besar di Damaskus yang banyak dirujuk di Indonesia. Saat pengaruh ISIS muncul, Sayyid berkata kepada Zuhayli, “Kita ini tak hanya produk modernitas dan westernisasi, tapi juga fundamentalisme Islam.” Ketika Sayyid mengungkapkan bela sungkawa atas kematian Ramadan al-Buti, Zuhayli bilang, “Andaikan saya mati sebelum ini terjadi! Ridwan, katakan padaku, apa yang Malek Bennabi ungkapkan tentang hukum agama dan yurisprudensi kehidupan serta hubungan mutualisme di antaranya?”
Pemihakan Sayyid pada Lebanon yang multikultural dan tradisionalisme Suni Islam yang mengayomi keragaman membuatnya teguh menelaah krisis politik umat Islam. Ia membentangkan persoalan sosial politik terkini dengan penjelasan kebudayaan dan sejarah di seluruh karyanya, termasuk saat ia menulis di media massa Arab. Ketika menerima Penghargaan King Faizal Prize 2017, ia menegaskan krisis politik umat Islam muncul karena sikap memilah-milah atas interpretasi sejarah yang dipaksakan para pemimpin yang tak mengikuti perkembangan zaman dan tak memiliki kesadaran historis.
Ia melihat Islam selalu menjadi modal simbolis yang digunakan politikus, pembicara, dan kelompok agama terkait teori otoritas dan hubungan politik. Yang mesti disalahkan ialah kerancuan dan kerusakan makna baik di masa lalu maupun hari ini. Dunia Islam secara global karena itu tertantang tiga hal utama: menyelamatkan negara-bangsa, mereformasi keagamaan, dan memperbaiki hubungan dengan dunia lain.
Hal itu tampak jelas dalam karyanya, Al-Sira` `ala-l-islam (Pergumulan Islam, 2006). Melalui pengaruh intelektual kiri Pakistan di Inggris, Tariq Ali, Sayyid membahas hubungan rumit antara Timur dan Barat serta racun fundamentalisme yang menyebabkan teror. Bahasanya jelas: “alladhi hawwalathu al-usuliyyah al-islamiyyah ila mushkilah `alamiyyah, ismuha al-rasmi: al-irhab!” Maknanya: kecenderungan teror dan kekerasan yang sudah menjadi masalah global. Sembari mengajukan pandangan pluralisme budaya dan politik, ia memberi peringatan dunia Islam untuk mengambil inisiatif besar dalam reformasi dan membuka diri pada modernitas Barat tanpa mengikis pergumulan dinamis antara Barat dan dunia lainnya.

Menentang Sektarianisme Suni-Syiah
Sayyid adalah suara pragmatis dalam politik Suni Islam dan sangat anti atas politisasi agama. "Jika anda ingin Islam menjadi faktor pemersatu, maka tak usah membawanya ke dalam politik karena itu akan menjadi buruk bagi agama," tuturnya.
Dalam pandangan Sayyid, munculnya realitas politik velayat-e faqih di Iran dan politik Islamisme khilafah yang dengan teror diusahakan ISIS adalah produk narsistik dan skizofrenik dari jenis fundamentalisme Islam. Kedua produk politik modern ini akhirnya menyebabkan perpecahan yang kian meruncing antara Suni dan Syiah. Jika selama 1.400 tahun Syiah hidup tanpa teori vilayat-e faqih, ide khilafah baginya sangat menggelikan, diabolik seperti penyakit menular, dan tak dibutuhkan karena justru menghina Islam saat ini.
Dalam pengalaman Suni, konsep kenegaraan (dawlah) masa kekhalifahan sejak zaman Umayyah hingga Usmani ialah pragmatis dan sekular; mengikuti apa yang dibutuhkan negara. Para pemimpin menyebut mereka ‘khalifah’ tidak lain untuk menghindari imitasi pada dua imperium besar yang merupakan lawan peradaban Islam awal: raja-raja Persia dan para kaisar Bizantium.
Pemisahan antara yang duniawi (dunyawi) dan religius (dini) jelas ada. Sebab, dalam pengalaman politik Suni, tidak ada konsep imamah dan infalibilitas pemimpin (ma`sum) yang dipercaya Syiah. Ia menyerang baik kecenderungan politik al-Qaeda maupun pendapat berpengaruh dari Yusuf al-Qaradawi. Dalam pemikiran Suni tentang musyawarah para ahli (ahl al-hall wa-l-`aqd), negara berfungsi untuk mengatur urusan publik dan melindungi kebebasan beragama, bukan memaksakannya.
Konteks pemikiran politik Sayyid tak lepas dari impitan politik dan sektarianisme agama di negerinya. Pada satu sisi ada pembela velayat-e faqih dalam kelompok Syiah Lebanon yang cenderung keras, di sisi seberangnya ada yang terjerat fundamentalisme hingga terorisme ISIS. Keduanya sangat mencolok, meski tidak merepresentasikan Lebanon yang sesungguhnya. Dua kecenderungan ini baginya sangat berbahaya, karena selain mengekalkan perbedaan Suni dan Syiah sebagai invensi politik modern, juga memperuncing konflik horizontal.
Terlepas dari konteks ‘ko-eksistensi dan sektarianisme Lebanon’ itu, kita belajar banyak dari keseriusannya dalam menggali konsep pemerintahan, otoritas, negara, dan masyarakat dalam sejarah Islam. Dalam banyak hal, tema-tema yang dibahas Sayyid bersinggungan dengan eksistensi Islam di Indonesia.
==========
Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.
Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id