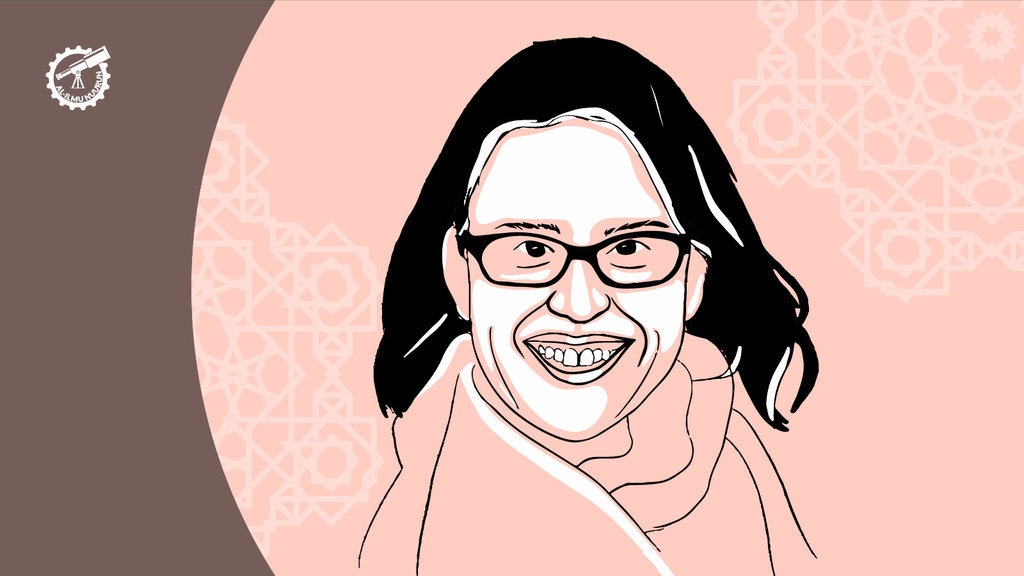tirto.id - Membahas wacana Islam kontemporer serta kajian Islam dan gender di Amerika tak lengkap tanpa menyebut Kecia Ali, profesor perempuan di Universitas Boston, Amerika. Apalagi dalam "rezim pengetahuan" di Barat yang melihat Islam melalui kacamata geopolitik dan sejarah, membahas sistem etika Islam dan mereformulasikannya dalam kehidupan saat ini seperti membendung arus. Ali, mengikuti jejak feminis muslim sebelumnya, banyak membahas soal etika yang terkait keadilan gender.
Itu wajar, sebab Ali banyak berkiprah di dalam departemen agama atau religious studies, bukan departemen sejarah atau kajian Timur Tengah yang lebih banyak menekankan perihal filologi dan pendekatan sejarah. Tapi tak berarti refleksi intelektualnya menihilkan analisis bahasa dan kesejarahan, terlebih dalam iklim akademik saat ini yang lintas-disiplin. Kiprahnya semakin diakui di dalam ruang lingkup The American Academy of Religion dan sejak 2014 menjadi presiden di The Society of Muslim Ethics in 2014. Di luar jaringan kampus, ia aktif membela dan mengadvokasi kaum papa dan masalah lingkungan.
Tulisan utamanya banyak membahas soal hukum Islam, gender dan seksualitas, serta biografi religius terutama soal Nabi Muhammad dan Imam Syafii. Jika di Indonesia sudah sekitar tiga dekade pembacaan ulang atas fikih perempuan berlangsung melalui penelaahan kitab kuning dalam tradisi pesantren, maka dalam konteks Amerika yang tidak sama, Ali pun melakukannya. Kali ini kita akan melihat karyanya yang terbit pada 2006, Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur’an, Hadith and Jurisprudence.
'Persetujuan' dan 'Mutualitas'
Satu elemen penting dalam penafsiran kitab suci bagi feminis dan reformis Islam mengacu pada prinsip keadilan dan tidak terpaut pada konteks khusus tertentu. Kecia Ali mengajak kita menyoal tradisi fikih yang tidak sesuai prinsip keadilan itu sendiri.
Seperti dalam karyanya mengenai biografi Muhammad untuk menengahi antara polemik di Barat yang menyudutkan sang nabi dan hagiografi di dunia muslim yang menyorot kehebatannya, Ali juga melihat kecenderungan serupa soal seksualitas dan gender. Di Barat, gambaran perempuan muslim adalah budak bercadar yang terkurung dalam harem. Sementara ulama muslim menangkis citra itu dengan argumen bahwa perempuan lebih dihargai dan aman di dalam Islam ketimbang agama lain.
Dalam dua iklim yang berseteru itu, ia ingin merefleksikan pengalaman pribadinya dalam melihat doktrin keagamaan dan hukum sekular yang terkesan "lebih netral dan adil". Dengan mengulas berbagai pendapat dari fukaha dan para penafsir Al-Qur’an, ia justru ingin membumikan gagasan adil itu dengan mempertentangkan berbagai tradisi yang sudah diterima dan, karena itu, tabu untuk dibahas.
Perempuan dalam etika Islam masa silam digambarkan sebagai makhluk dengan syahwat yang besar. Atas dasar ini, al-Ghazali menulis bahwa lelaki harus bertanggung jawab untuk memuaskan hasrat seksual perempuan. Penegasan lebih tertumpu pada kewajiban suami ketimbang hak istri, dengan alasan untuk menghindari malapetaka sosial manakala sang istri tidak terpuaskan.
Pendapat Ghazali itu umum dan menjadi rujukan muslim saat ini untuk memperlakukan perempuan. Pada umumnya, sebagaimana ditulis Ali, tradisi muslim klasik memandang perempuan tak pernah merasa puas secara seksual dan rentan untuk menciptakan kekacauan sosial. Asumsi bias ini mendorong fukaha untuk menulis jauh lebih banyak larangan bagi kehadiran dan aktivitas perempuan daripada lelaki yang dianggap mampu menguasai diri.
Pendapat dari ulama klasik mengenai batasan-batasan seksual perempuan, yang diambil dari teks kitab suci dan hadis kenabian, merembes ke dalam wacana muslim dan dianggap ajek. Bagi Ali, supaya hubungan intim tetap terpuaskan dan memenuhi etika yang adil, maka prinsip persetujuan (consent) dan mutualitas harus dijunjung tinggi antara suami dan istri. Kedua prinsip ini tentu tak bisa dipisahkan dari nilai-nilai kesetaraan dalam masyarakat Barat, namun tanpa harus mereduksi nilai keagamaan. Ia menganggap hal ini sangat mungkin diterapkan berdasarkan pada sumber-sumber tekstual keagamaan.
Tapi etika seksual yang egaliter tak dapat dibangun dari prinsip tebang pilih sesuai keinginan. Ia meminjam bahasa seni, yakni metode pastiche, untuk menyebut peniruan gaya masa lalu dalam membuat etika masa kini. “Yang kita butuhkan,” tulisnya, “justru pertimbangan yang lebih serius: apa yang membuat seks sah dalam pandangan Tuhan.”
Sah dalam pandangan Ali ini mencakup syarat persetujuan dan mutualitas kedua belah pihak, tidak ada paksaan, tidak berat sebelah, dan mempertimbangkan hak individual—terutama perempuan—dalam membangun keintiman yang menjadi bagian dari ajaran agama. Setiap individu dalam logika feminis ini memiliki hak yang sama untuk kebahagiaan seksual di dalam pernikahan, terlepas dari pilihan masing-masing untuk memiliki anak atau tidak.
Pengalaman hidup perempuan mesti dilihat sebagai seratus persen manusia, bermoral, dan makhluk seksual yang paripurna. Pandangan dan penafsiran agama yang menilai perempuan sebagai setengah segalanya tidak lagi relevan ditakar dari kacamata keadilan Tuhan.
Dalam struktur baru penikahan yang egaliter, terutama dalam konteks kehidupan modern, Ali menyorot soal mahar. Tudingan miring soal mahar ialah sebagai alat transaksi seksual. Sementara nilai positif dikemukakan banyak feminis dan neotradisionalis muslim yang memandang mahar sebagai sumber keamanan finansial untuk perempuan serta kemauan dan kemampuan suami untuk menyediakan nafkah. Relevansi mahar, dalam kehidupan Barat dengan hukum Islam yang tak mengikat secara resmi, dipertanyakan Ali sesuai dengan pilihan pragmatis.
Lagi pula, masih banyak yang menganggap mahar menempatkan lelaki pada posisi superior termasuk dalam hal perceraian. Mengikuti pandangan klasik, mahar banyak dipakai sebagai legitimasi seksual lelaki kepada istrinya, sesuai dengan istilah Imam Syafii yang menyebut mahar sebagai ‘harga kemaluan perempuan’ (thaman al-bud`ah).
Kenyataannya, praktik mahar di Amerika tidak bisa menjadikan perempuan mandiri secara finansial. Seiring dengan akses pekerjaan yang terbuka bagi perempuan dan suami-istri masing-masing punya akses dalam mengajukan perceraian, maka fungsi etis dari mahar itu pun berubah.
Memperjuangkan Etika Seksual
Ali tentu saja tak mereformasi pandangan klasik semaunya sendiri. Ia mengacu pada modifikasi hukum Islam klasik atas hukum Arab pra-Islam. Sehingga ia pun perlu memodifikasi pandangan lama. Sebagai bagian dari pemikir kontemporer, ia masuk ke dalam mazhab kontekstualis dalam menerjemahkan teks suci keagamaan.
Tapi menulis ulang fikih terkait perempuan bukan berarti tidak ada halangan dalam menentang penafsiran misoginis. Ia tentu memahami bahwa tafsir masa lalu dibangun atas asumsi mengenai budaya patriarki yang dominan sehingga memengaruhi berbagai produk intelektual yang muncul. Para penafsir feminis, menurutnya, tidak boleh dibutakan oleh komitmen mereka pada kesetaraan dengan asumsi bahwa kesetaraan ini wajib ditunaikan demi keadilan.
Tampaknya, Ali sedang membuat analogi bahwa keadilan tak terpenuhi hanya dengan menyesuaikan ajaran Quranik dan hadis profetik ke dalam nilai yang sedang berkembang, tanpa mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada di belakang budaya tertentu yang mungkin jauh dari keadilan. Kesetaraan gender yang diinginkan dengan demikian bukan slogan belaka, tapi bekerja dengan melampaui berbagai keterbatasan budaya di mana sang penafsir hidup.
Atas dasar refleksi feminis pribadinya, Ali mendorong suatu reinterpretasi kolektif yang bisa lebih diterima publik. Ia tidak terbawa pada utopia yang penuh optimis dalam memandang transformasi sosial dalam tradisi umat muslim, sama ketika ia tidak meromantisasi tradisi masa lalu. Ia tidak tertarik pada pemilihan ayat-ayat yang mengacu kesetaraan dan mengenyahkan lainnya yang bertentangan. Baginya, sikap ini tak jujur dan menghindari pengujian sistematis atas struktur wacana di dalam wahyu.
Kegigihannya dalam memperjuangkan etika seksual dan keadilan gender dalam Islam tak terpisah dari reformasi dalam kehidupan individual dan sosial. Agar fungsi keluarga maksimal dalam perspektif amar makruf nahi munkar, maka nilai-nilai etis perlu diterapkan terkait soal tubuh dan seks. Ali tampak sedang mengembalikan bahasa Quranik yang lebih netral dan setara, yakni ‘manusia’ (insan), supaya nilai keadilan dalam Islam membumi dalam ruang kesejarahan yang melibatkan agensi berbagai pihak.
Tidak berlebihan bahwa Ali juga memperjuangkan keadilan gender dalam ruang akademik di Amerika. Dalam salah satu artikel terbarunya, “Politics of Citation” (2019), Ali menelisik politik gender dalam kajian Islam di dunia akademik. Dalam telaahnya, serentetan kajian keislaman di dunia akademik Barat menunjukkan bias, rasisme, dan berat sebelah dalam hal gender.
Karena kutipan ialah mata uang yang berharga dalam dunia akademik saat ini, maka, demi menentukan kesarjanaan yang lebih sah dan adil, ia mengundang para sarjana untuk memperhatikan berbagai karya yang ditulis perempuan serta berdialog dengan argumen yang perempuan tulis. Bukan hanya dalam hal menulis, tapi juga dalam hal panel seminar dan kegiatan ilmiah lainnya termasuk menulis jurnal, keterlibatan perempuan perlu diperhatikan secara luas.
Kritik feminisnya yang tajam atas berbagai tulisan ‘lelaki’ seperti What is Islam? (2015), karya fenomenal Shahab Ahmed, berupaya untuk menumbuhkan ekosistem pengetahuan dengan cara berpikir, membaca, dan menulis. Ini berbeda dari sebelumnya: semua digeneralisasi sebagai bias gender.
==========
Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.
Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id