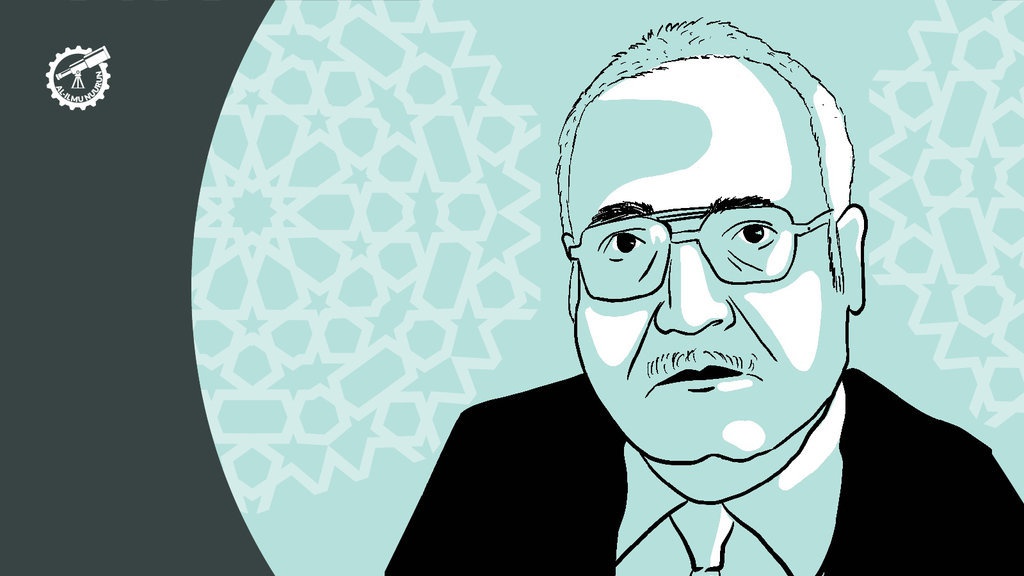tirto.id - Kita tak tahu almarhum Didi Kempot ingin bagaimana dan bertemu siapa saat meninggal dunia begitu cepat kemarin. Tapi kita bisa tahu apa keinginan Hassan Hanafi, pemikir Mesir berpengaruh itu, sesudah mati. Dalam autobiografinya, Dhikriyyat 1935-2018 (2019), Hanafi ingin mati yang mudah, terang bercahaya, lalu bertemu kerabat dekat dan orang-orang yang ia tulis: Fichte, Bergson, al-Afghani, dan Iqbal. Ia juga ingin bertemu dua guru filsafatnya: Usman Amin dan Jean Guitton; serta dua muridnya yang mendahului: Nasr Hamid Abu Zayd dan Ali Mabruk.
Deretan nama yang sudah meninggal ini banyak memberi kita informasi mengapa mereka begitu penting dalam karier intelektual Hanafi. Usman Amin berjasa dalam memperkenalkan filsafat kepada Hanafi dalam periode formatifnya di Kairo. Pada masa awal 1950-an ketika Hanafi masih aktif sebagai anggota al-Ikhwan al-Muslimun dan kepincut dengan gagasan fiqh al-waqi` atau ilmu realis baru dari Sayyid Qutb, Amin memberinya asupan filsafat dan yang terpenting ialah modernisme Muhammad Iqbal.
Gagasan khudi atau diri Iqbal yang kuat dan kreatif memberikan dorongan subjektif kepada Hanafi. Bukan saja Hanafi menulis biografi Iqbal sebagai filsuf dhati, bersifat zat atau diri, filsuf Pakistan itu benar-benar mengubah haluan hidup Hanafi dari ketertarikannya kepada Qutb. Gagasan ijtihad Iqbal sebagai prinsip gerakan dalam struktur Islam menarik perhatian Hanafi dan menjadikan Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam sebagai model pertama dari proyek intelektualnya di kemudian hari: tradisi dan pembaruan (al-turath wa-l-tajdid). Hanafi seolah-olah sedang menarik benang kebangkitan peradaban sejak Jamaluddin al-Afghani dan dilanjutkan lebih serius oleh Iqbal, lalu dirinya.
Fikih Bukan Hanya Legal Teknis
Dari 1956 hingga 1966 Hanafi menggali filsafat lebih dalam lagi di Sorbonne, Paris. Ada titik persinggungan antara Mohammed Arkoun, Ali Shariati, dan Hanafi. Nuansa kajian Islam oleh Louis Massignon dan muridnya Henri Corbin ikut memperkaya khazanah pengetahuan ketiganya. Bahkan atas saran Massignon, Hanafi menjadi fokus untuk mengkaji usul fikih sebagai landasan menelaah investigasi filosofis Islam. Iklim sosial-politik di Paris juga ikut memengaruhi ketiganya.
Dalam hal itu, Shariati dan Hanafi lebih dekat karena mereka terpicu oleh wacana dekolonisasi di Paris sekaligus percikan global dari solidaritas Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok, serta sekelumit gairah pembebasan dunia ketiga. Dengan kata lain, Shariati dan Hanafi terpicu oleh energi revolusi. Tapi Hanafi mencurahkan energinya pada revolusi keilmuan untuk membangkitkan gairah Islam peradaban yang dinamis, ketimbang ideologi Shariati yang tidak mementingkan aspek kebudayaan.
Genealogi intelektual yang meliputi berbagai pembacaan rakus Hanafi atas filsafat Jerman dan Perancis, termasuk di antaranya fenomenologi Husserl, disentuh oleh mentornya, Jean Guitton. Guitton, murid langsung dari Henri Bergson, adalah seorang profesor filsafat dan pembaharu Katolik. Menurut Hanafi, Guitton benar-benar mentor yang membimbingnya dalam pencarian intelektual dan strategi untuk menjadi intelektual publik yang efektif.
Keduanya saling berdialog secara apik dalam tradisi masing-masing: Islam dan Kristen. Namun, ketika menjelaskan filsafat, Guitton bisa keluar dari tradisi agamanya dan bermula dari titik nol atau apa yang oleh Kant disebut sebagai ‘akal murni’. “Seperti Muhammad, ia [Guitton] adalah ikonoklas,” kata Hanafi.
Hanafi menyebut periode pascasarjana di Paris ini sebagai ‘jihad kecil’. Carool Kersten dalam Cosmopolitans and Heretics (2011) dengan canggih menafsirkan jihad kecil Hanafi melalui penelusuran silsilah intelektual yang berbelit dalam iklim pengetahuan pada masa itu. Dengan bimbingan Guitton, Hanafi semakin yakin untuk mengikuti metode filsafat Kant dalam mencari ‘metode Islam umum’ dalam penggalian filosofis.
Perkenalan dengan Iqbal oleh Usman Amin juga diperdalam di Paris. Dijadikan sebagai sandaran utama, pemikiran Iqbal memantik Hanafi untuk membangun sebuah metode Islam dari investigasi filosofis. Ini menarik karena Hanafi sebenarnya berpihak pada fenomenologi Husserl melalui pembacaan Paul Ricoeur yang menjadi salah satu pembimbing Hanafi.
Disertasi doktoralnya, Les méthodes de l'exégèse:Essai sur les fondements de la compréhension “'Ilm usul al-fiqh”, terang ingin menafsirkan usul fikih dalam pengertian luas. Anak judulnya dengan jelas bermakna “dasar-dasar pemahaman”. Karena yang Hanafi cari ialah metode umum dalam tradisi Islam untuk filsafat, maka ia memperluas makna ‘fikih’ seperti pengertian dasarnya yakni ‘pemahaman’, bukan pada aspek legal teknis saja. Ini mengingatkan kita pada karya klasik Imam Abu Hanifah berjudul Fiqh al-akbar dalam pengertian teologi rasional atau harfiahnya ‘pemahaman yang besar’. Dengan tebal 900 halaman, Hanafi menganggap apa yang ia rintis sama-sama radikalnya dengan Imam Syafi'i.
Dan bisa dibilang, karyanya itu adalah al-Risalah masa kini, sebagai panduan untuk menerapkan berbagai doktrin Islam ke dalam praksis kehidupan sosial. Seperti keilmuan masa lalu yang secara kreatif mengadopsi dari tradisi Yunani, maka Hanafi dalam masa kini juga menggunakan instrumen pengetahuan Barat untuk menggali tradisi Islam. Tapi seperti yang ia jelaskan dalam Pengantar untuk Ilmu Oksidentalisme, Hanafi berposisi sebagai fakih lama yang terjepit di antara dua peradaban: Islam dan Barat.
Ia mewakili Islam tapi juga mengkritik Barat. Dalam waktu bersamaan ia berinovasi melalui keduanya demi realitas masa kini dan mendatang. Skema ini bisa terbaca dengan jelas dalam proyek besarnya, Tradisi dan Pembaruan, proyek panjang yang ia anggap sebagai ‘jihad besar’ setelah lulus doktor—sebuah semangat yang dalam pemikiran Yudian Wahyudi, pengkaji Hanafi, disebut sebagai ‘jihad ilmiah’. Itulah mengapa Kersten menyebut Hanafi sebagai seorang kosmopolitan yang memadukan peradaban berbeda, tapi juga bagi yang lain ia dianggap heretik karena dituduh menodai kemurnian Islam.
Jihad besar Hanafi tak bisa terlepas dari kondisi dan perdebatan dalam masyarakat Arab, terutama setelah kekalahan dalam Perang 1967. Ia menantang dua gelombang besar yang gagal menangkap realitas masyarakat Arab pascakolonial: sekularisme dan islamisme. Sekularisme, seperti misalnya diwakili oleh pendekatan Sadiq Jalal al-Azm, gagal menggali potensi dengan cara melakukan revolusi tradisi Islam untuk perubahan sosial. Bahkan yang sekuler cenderung elitis dan berjarak dengan massa. Sementara Islamisme menganggap autentisitas tradisi yakni ‘kembali ke asal masa lalu’ tanpa memandang perubahan historis dan dampak dari modernitas kolonial.

Kesadaran Historis Umat Islam
Dalam menghadapi warisan masa lalu umat muslim ditambah dengan beban keterjajahan, penindasan, kemiskinan, alienasi, perpecahan, dan keterbelakangan—kita teringat pada tesis ‘kolonisabilitas’ Malek Bennabi—Hanafi membutuhkan revolusi. Baik blok Islamisme yang marah dan sekularisme yang tertutup adalah tidak baik. Di sini, apa yang tak ada ialah ‘kesadaran historis’ dari kedua belah pihak yang kerap lari dari kenyataan.
Konsep ‘kesadaran historis’ itu dipinjam dari idealisme Jerman, terutama Fichte. Fichte di sini memang didambakan Hanafi seperti tersirat dalam keinginan di atas setelah ia mati. Hanafi sendiri menulis buku tentang Fichte sebagai faylasuf al-muqawamah (filsuf perlawanan) yang membangkitkan nasionalisme Jerman setelah dikalahkan Napoleon Bonaparte. Seperti halnya Fichte, Hanafi memosisikan dirinya sebagai filsuf revolusioner yang ingin membawa Mesir sebagai bangsa maju di zaman modern setelah lemah terkulai akibat krisis berkepanjangan.
Kesadaran historis itulah yang dibutuhkan untuk membangun sebuah cakrawala dari kemungkinan politik. Tak salah jika pengkaji Hanafi yang lain, Yasmeen Daifallah (2018), menganggap kesadaran sebagai inti dari turath atau tradisi, dari mana Hanafi melancarkan kritik peradaban. Dalam gambarannya, Mesir adalah pusat peradaban baru dan Hanafi, mengikuti khudi Iqbal, adalah ‘diri’ yang bertugas untuk merevolusinya berhadapan dengan peradaban Barat.
Ia dalam banyak bukunya merinci berbagai paradigma untuk menerjemahkan doktrin keislaman secara horizontal. Kesadaran historis itulah yang membuat Hanafi tak terlalu ingin untuk mengawang-awang secara teologis. Ia sedang membangun praksis politik yang membumi, termasuk apa yang ia formulasikan sebagai ‘kiri Islam’.
Sekali lagi, secara kontras kita bisa membedakan antara al-Azm dan Hanafi. Untuk mengatasi masalah nalar Arab yang tidak akrab dengan penjelasan metode ilmiah, al-Azm mengajukan tesis sekularisasi masyarakat Arab. Hanafi, sebaliknya, tidak merekomendasikan tesis itu. Dalam kacamata Hanafi, tajdid atau pembaruan tradisi adalah sesuatu yang diperlukan untuk memperbarui kesadaran Arab terkini. Atau bisa dibaca umum: memperbarui kesadaran muslim masa kini. Yang mendesak dilakukan ialah penafsiran kembali atas tradisi sesuai dengan pergumulan hidup zaman kiwari. Untuk alasan gamblang ini, kita bisa menduga kenapa Hanafi jauh lebih populer di Indonesia dibanding al-Azm.
==========
Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.
Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id