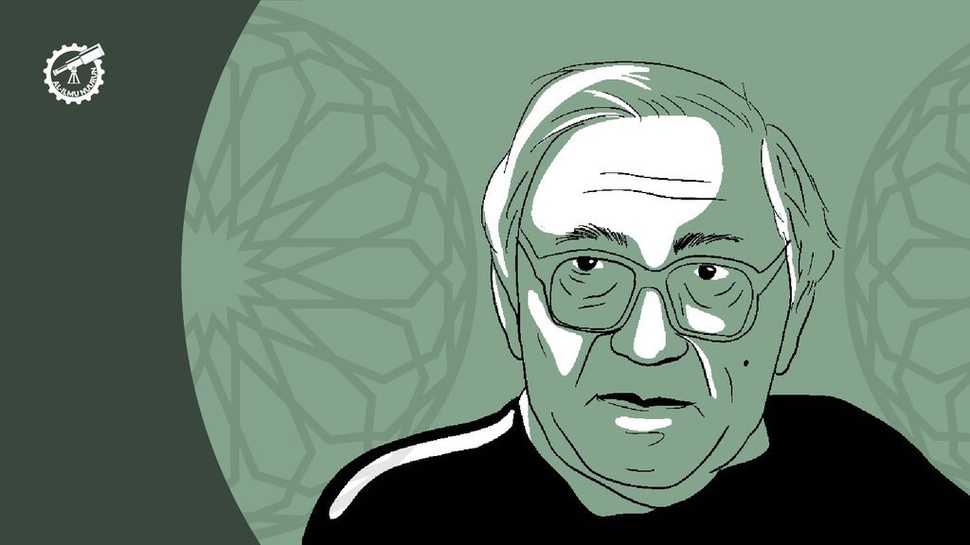tirto.id - Sejak gelombang Arab Spring melanda Suriah pada pertengahan 2011, tidak ada yang menyangka pendekatan rezim Bashar al-Assad akan begitu brutal. Dari luar Suriah, kita membaca konflik di negeri itu begitu rumit dan melibatkan berbagai aktor dalam negeri dan internasional. Tapi al-Assad, sang presiden dari suku minoritas Alawi, tak menyediakan ruang dialog.
Intelektual Suriah ternama bersuara. Penyair dan intelektual Adonis alias Ahmad Sa’id Asbar berteriak dari Paris. Dari Damaskus sendiri, sahabatnya, Sadiq Jalal al-Azm, sejak awal mendukung proses yang demokratis. Al-Azm kemudian terus bersikukuh tidak ada perang sipil di negerinya, yang ada adalah kekerasan sepihak. Biasanya ia kritis terhadap segala jenis manifestasi fundamentalisme dan islamisme dan menyuarakan sekularisme secara aktif. Kali ini, bersama seterunya, ia membela yang tertindas melawan musuh besar bersama.
Di mana pun ia tinggal, ia betah sebagai warga dunia. Ia kerap bolak-balik ke Jerman dan Amerika untuk terus berkarya. Saat pindah ke Berlin di sekitar Stuttgarter Platz, ia ditawari sebagai peneliti tamu di Käte Hamburger Kolleg di Bonn, lalu di Wissenschaftskolleg zu Berlin, sebuah lembaga penelitian Jerman paling bergengsi. Dua tahun berikutnya ia ditawari posisi di Harvard dan Princeton, sebelum kembali lagi ke Berlin pada 2015.
Saya baru tahu keberadaanya di Berlin pada 2016, sambil berharap ia mengisi seminar publik. Memang, Berlin adalah tempat berlabuh bagi banyak intelektual, akademikus, dan seniman eksil dari negeri konflik. Bukan hanya itu, ribuan pengungsi Suriah juga mendatangi Berlin. Sayang sekali, pada akhir 2016 beredar kabar di Facebook bahwa al-Azm meninggal dunia. Keluarga, sahabat, dan kolega di Berlin pun mengenangnya penuh kesedihan.
Kritik Pemikiran Agama
Kendati al-Azm adalah pribadi kosmopolitan, tapi eksil bukanlah sesuatu yang diharapkannya. Ia sangat ingin dunia sosial-politik di negerinya dan seluruh negeri Arab menjadi ladang persemaian bagi kebebasan sipil. Sedari muda, usai lulus doktor bidang filsafat dari Yale, ia bergabung di Universitas Amerika di Beirut (AUB) dan aktif menyuarakan kebebasan. Libanon hingga masa 1960-an adalah mercusuar intelektual di Timur Tengah dan sering disebut Paris-nya kawasan itu.
Perang 1967 antara Arab (Mesir, Suriah, dan Yordania) dan Israel membuat bangsa Arab malu; tersayat sakit secara mental. Hampir semua intelektual besar di Arab masa itu kecewa. Adonis dan al-Azm, yang saat itu sering bertukar pikiran di Beirut, juga membicarakan hal ini. Setahun setelah kekalahan perang itu, al-Azm membukukan refleksinya dalam al-Naqd al-dhati ba`d al-hazimah yang berarti kritik diri setelah kekalahan. Al-Azm memperkenalkan istilah baru dalam Arab modern, yakni al-naqd al-dhati sebagai terjemahan dari self-criticism.
Ia berani menyerang reaksi resmi dari dunia Arab atas kekalahan yang mereka terima. Bangsa Arab mesti menerima itu sebagai kekalahan, meskipun pahit, terutama para pendukung sosialisme Arab bernama Nasserisme. Mengkritik Nasserisme—yang saat ini ada di ambang kemunduran—kala itu membutuhkan keberanian ganda.
Bagi al-Azm, kritik-diri itu menjadi erat dalam kemajuan Barat, sehingga dunia Arab juga membutuhkannya sebagai hal yang fundamental. Bangsa Arab seharusnya tak terus berlindung di balik kesedihan nakbah, kemalangan, kekurangberuntungan, menuding Israel sebagai “pengecut”, dan seterusnya. Inilah buku pertama di dunia Arab yang menggaungkan kritik diri. Kita tahu, setelah 1970-an banyak bermunculan karya-karya yang berani mengkritik tradisi dan menggemakan pembaruan di berbagai belahan dunia Arab.
Tak lama kemudian, muncul buku yang terkait dengan peristiwa kekalahan dengan judul Naqd al-fikr al-dini (Kritik Pemikiran Agama). Buku yang ia tulis saat berumur 35 ini berisi soal apa yang dalam bahasa kita disebut 'politisasi agama' oleh para pemimpin politik, pemuka agama, dan media. Dengan menggunakan pisau analisis marxis-materialis, ia mengkritik kecenderungan agama yang dipakai sebagai candu. Ia menyatakan bahwa rezim Arab menggunakan agama sebagai penopang yang dapat mereka gunakan untuk meninabobokan rakyat dan, hasilnya, bisa menutupi ketidakbecusan dan kegagalan mereka akibat kekalahan melawan Israel itu. Ia mengkritik rezim yang memanipulasi penjelasan agama dan spiritual.
Al-Azm mengendus kecenderungan manipulatif sekaligus hipokrit itu akan mereproduksi kebodohan, pengulangan mitos, keterbelakangan, ketergantungan, dan fatalisme. Sebaliknya, tidak ada hasil untuk membangun apa yang ia perjuangkan: nilai-nilai ilmiah, sekularisme, pencerahan, demokrasi, dan humanisme. Jika tak ada perombakan mengakar akan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Arab, tidak ada harapan dalam reformasi Islam.
Sejak diterbitkan pertama kali hingga saat ini, buku tersebut masih terlarang. Meski demikian, sebagaimana buku tersensor lainnya semacam novel Naguib Mahfouz Anak-anak Gabalawi (Awlad haratina) tahun 1950-an atau tetralogi Buru Pramoedya Ananta Toer tahun 1980-an, buku sejenis itu ada di mana-mana dibaca diam-diam.
Oleh pemuka Suni di Lebanon, al-Azm dituding menyebarkan kemurtadan, tradisi heretik, materialisme, ateisme, kekufuran, meracuni anak-anak muda, dan sebagainya. Peristiwa yang disebut 'afair al-Azm' ini membuatnya diberhentikan sebagai profesor muda di AUB, padahal ia belum genap masa enam tahun percobaan sebelum diangkat permanen. AUB sebagai kampus kebebasan terintimidasi oleh tekanan politik-keagamaan. Ia menyerahkan diri setelah disidang pengadilan in absentia, meskipun tak lama kemudian dibebaskan dengan alasan tidak ada perilaku kriminal.
Kritik Pemikiran Agama lalu menjadi klasik, tapi dalam sejarah oposisi dan suara kebebasan dunia Arab menjadi relevan sebab posisinya sebagai asal-muasal kritik diri dalam masyarakat Arab modern bermula. Al-Azm sendiri tidak menggunakan filsafat atau teologi Islam, sebagaimana ia akui, tetapi menggunakan kerangka pemikiran Barat yang sekular dan humanis untuk terlibat dalam suatu proyek pembaruan masyarakatnya sendiri.
Bukan saja ia terdidik dalam tradisi filsafat Barat modern sejak kuliah di Beirut hingga Yale, di mana ia memfokuskan diri pada Immanuel Kant, tetapi ia berasal dari kalangan aristokrat yang sekular. Ayahnya sezaman dan segenerasi dengan Mustafa Kemal Ataturk. Keluarga al-Azm yang berdarah Turki sendiri bermula dari cerita Ismail Pasha al-Azm yang ditunjuk pada 1725 sebagai penguasa Damaskus. Keluarga ini berhasil bertahan sebagai bangsawan dan masih berpengaruh bahkan ketika Suriah resmi merdeka.

Advokat Sekularisme & Demokrasi Liberal
Kecenderungannya untuk menggunakan materialisme historis tak berhenti pada kritik pasca-1967, masa ketika ia lebih tertarik pada ideologi kiri dan pembebasan Palestina. Setelah komunisme runtuh, ia menulis buku yang membela materialisme dan sejarah untuk menunjukkan percikan dari pemikiran progresif dan demokratisnya. Di sinilah ia cenderung lebih membela pada rasionalisme dan sekularisme secara umum.
Ia mengkritik Orientalisme karangan Edward Said dengan landasan bahwa Said juga melanggengkan esensialisme dalam memandang budaya Eropa. Demikian halnya, ketika Hassan Hanafi membuat pengantar untuk proyek intelektualnya bernama Oksidentalisme, yaitu ‘studi soal peradaban Barat’, al-Azm melancarkan kritiknya serupa dengan kritik atas Said. Pada masa ini ia membela apapun demi kejernihan intelektual.
Begitu pula, ia membela kebebasan intelektual saat karya Salman Rushdie The Satanic Verses dihujat di mana-mana. Sebagai bekas "narapidana" kasus sensor dan persekusi intelektual, ia tahu betul ke mana harus berpijak, meskipun ia tak selalu setuju dengan gagasan mereka yang ia bela. Mona Abaza (2016) mengungkapkan dengan kritik yang jujur dan apa adanya ini: al-Azm ingin mencari sebuah dialog tulen. Ini termasuk dialognya di Aljazeera bersama Yusuf al-Qaradawi yang menyoal agama dan sekularisme, sebuah dialog yang sengit tapi tetap berargumen dan seharusnya menjadi model bagi dialog serupa di dunia Arab.
Apalagi, kita sering melihat insiden perkelahian di forum dialog televisi negeri Arab—sesuatu yang tidak dilandasi pada niat baik berdialog sebagaimana sering ditunjukkan al-Azm. Al-Azm adalah filsuf sekuler yang disegani yang menganggap negara perlu campur tangan dalam urusan keagamaan demi kemaslahatan umum, tanpa penghilangan agama dari ruang publik ala Perancis sebagaimana ditakutkan banyak masyarakat beragama.
Pada perjalanan karier berikutnya, ketika al-Azm banyak membagi waktu antara Damaskus dan dunia lainnya, ia terus membela sekularisme dan demokrasi liberal sebagai masa depan bagi bangsa Arab. Ia tak setuju dengan segala jenis fundamentalisme, baik itu agama yang ia kritik sejak lama maupun jenis pembela sekularisme yang keras seperti Joseph Stalin, Ataturk, Habib Bourguiba di Tunisa, dan rezim Assad di negerinya. Di antara intelektual Suriah, suara sekularisme humanis al-Azm lebih banyak mendapatkan panggung di dunia Barat ketimbang misalnya eksistensialis Muta Safadi dan sosiolog sekaligus figur oposisi eksil bernama Burhan Ghalioun.
Apa yang sebetulnya diperjuangkan al-Azm tidak lain adalah pembelaannya pada pluralisme agama dan kebebasan hati nurani. Ia akan bersama mereka kendati pun berbeda, yang barangkali ia anggap sebagai dialektika pemikiran dalam latar belakang filsafatnya. Apa yang dilakukan al-Azm, menurut seorang kawannya, ilmuwan Jerman Stefan Wild (2011), ialah “berbicara kebenaran kepada kekuasaan sebagaimana mengatakan kebenaran melawan kekuasaan itu sendiri.”
Dalam bahasa hadis Nabi: “Katakan kebenaran meskipun pahit getir!” Takaran moralitas ini ada dalam tanggung jawab intelektual.
==========
Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.
Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.
Editor: Ivan Aulia Ahsan