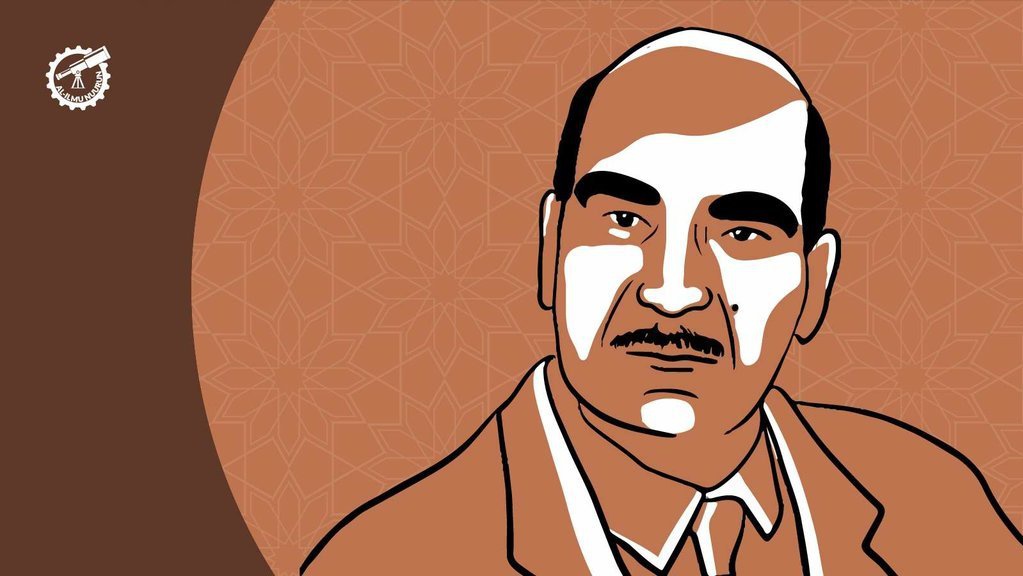tirto.id - Mohammed Abed al-Jabiri tak hanya menjadi filsuf yang paling banyak dikonsumsi anak muda di dunia Arab, tapi juga di kalangan intelektual Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Proyek intelektualnya yang berjilid banyak, “Kritik Nalar Arab,” menggugah generasi muda untuk bangkit. Pertanyaan retoris dalam jilid pertama proyek itu sekaligus mengandung makna terdalamnya: “Apakah mungkin membangun renaisans dengan akal yang tidak progresif?”
Syarat renaisans ialah intelek yang progresif. Apa yang diupayakan Jabiri, sebagaimana Hassan Hanafi, tak terlepas dari kebutuhan untuk membaca ulang tradisi Arab-Islam dalam berhadapan dengan modernitas. Ini masih dalam kerangka dekolonisasi pengetahuan dan mentalitas paruh kedua abad ke-20 supaya ‘pesona abadi dari modernitas’—meminjam ungkapan pakar semiotik Walter Mignolo (2002) yang diserap dari istilah Weberian—tidak menggerus tradisi yang ‘kehilangan pesonanya’.
Maka kedua tradisi yang hidup mesti dikawinkan: sang aku dari tradisi Arab-Islam dan sang liyan modernitas Barat. Ini dalam rangka membebaskan tradisi dari cengkeraman kolonialitas yang paling mendasar di tingkat estetik, budaya, dan epistemik, tak hanya dalam bidang ekonomi dan politik. Singkatnya: mengatasi kemunduran dan rasa rendah diri berhadapan dengan Barat.
Hanya, cara untuk membaca perkawinan tradisi dan modernitas itu berbeda-beda. Perkawinan di sini maksudnya adalah tajdid atau pembaruan. Jabiri mengikuti tradisi Kantian untuk menelaah nalar Arab dengan daya sentuh Foucauldian dalam merekayasa arkeologi pengetahuan yang berakar dari renaisans zaman al-Andalus.
Ibnu Rusyd vs al-Ghazali
Silsilah intelektual Jabiri bisa membuka mata kita mengapa ia sangat mendorong untuk mencari filsafat baru seideal Ibnu Rusyd. Ia dibesarkan dari keluarga yang mendukung Partai Istiqlal, partai yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan, sesuai namanya. Setelah Maroko merdeka dari Perancis pada 1956 ia ikut bekerja di al-'Alam, organ resmi partai itu. Ia pernah kuliah filsafat selama setahun di Universitas Damaskus, Suriah, namun kemudian pindah ke Universitas Rabat yang baru dibuka. Ia pernah dipenjara karena aktivitas politiknya yang dituding merongrong negara.
Sebelum menyelesaikan doktornya, ia mengajar filsafat di sebuah SMA—persis seperti tradisi pendidikan Perancis. Ia sempat membuat dua buku ajar mengenai pemikiran Islam dan filsafat yang banyak diacu hingga awal 1970-an. Pada 1967 ia menyelesaikan ujian doktor dengan tesis pradoktoral mengenai filsafat sejarah Ibnu Khaldun di bawah bimbingan filsuf dan novelis jebolan Sorbonne, Muhammad Aziz Lahbabi. Ujian doktoralnya, masih tentang Ibnu Khaldun, dibimbing Najib Baladi dan selesai pada 1970.
Tak lama kemudian, Jabiri mengajar di Universitas Muhammad V di Rabat. Seperti Abd al-Rahman Badawi, Jabiri adalah produk lokal negerinya dengan transmisi filsafat Perancis. Hanya saja Jabiri tak langsung dibimbing seorang filsuf Perancis seperti Badawi. Pada periode 1970-an ia mulai aktif berpolitik yang condong ke kiri dalam Union Nationale des Forces Populaires (UNFP) dan kemudian Union Socialiste des Forces Populaires. Aktivitas intelektualnya membuatnya dikenal hingga Mediterania bagian timur.
Jabiri lahir dari rahim pengetahuan kolonial. Pengetahuannya soal renaisans al-Andalus, selain terkait secara geografis dengan Magribi masa lalu, juga tak bisa dilepaskan dari orientalisme Perancis dan Barat pada umumnya. Anggapan umumnya ialah Ibnu Rusyd membawa kemajuan, hingga memengaruhi kemajuan Barat. Komentar filosofis atas fisika Aristoteles di al-Andalus mengalir ke dunia Kristen-Latin dan tradisi Ibrani-Yahudi disertai transfer rasionalisme lainnya. Inilah yang membuat Barat melek kepada pengetahuan Yunani kuno; dari zaman Descartes yang mengomentari fisika Galileo, Kant yang mengomentari fisika Newton, hingga Gaston Bachelard di era fisika kuantum dan relativitas.
Sementara dalam dunia Islam, Ibnu Rusyd hanya dipakai untuk menjawab persoalan keterkaitan antara wahyu dan akal, seperti penerimaan atas kitabnya, Fasl al-maqal. Al-Ghazali, sementara itu, menjadi hegemonik dan menyebabkan kemunduran. Tesis umum ini, meski banyak celahnya dan usang, masih ada bekasnya dalam pandangan masa kini soal warisan Ibnu Rusyd dan al-Ghazali bagi Barat dan Timur.
Untuk membongkar nalar berpikir, Jabiri menelisik bagaimana produksi pengetahuan Arab-Islam masa lalu bekerja. Ada tiga jenis nalar yang menurutnya perlu dibongkar supaya memberikan daya dobrak inovasi dan kemajuan. Nalar pertama terkait dengan penafsiran tekstual keagamaan alias bayani. Nalar berikutnya terpaut dengan penalaran secara deduktif pada ilmu alam, burhani. Nalar yang ketiga berkelindan dengan pengalaman batin mistis yang lebih terkait soal tradisi esoteris, 'irfani. Ketiga nalar ini mendominasi pengalaman pascarenaisans al-Andalus atau, dalam bahasa Malek Bennabi, pasca-Almohadisme.
Solusinya ialah dibutuhkan mentalitas Ibnu Rusyd yang dianggap setara Descartes dalam sejarah filsafat Arab-Islam. Ibnu Rusyd maju lantaran ia dianggap memberikan ‘patahan sejarah’—sangat Foucauldian—dengan cara memutus filsafat Islam dari Ibnu Sina. Sebab, filsafat Ibnu Sina dianggap tak cukup radikal dalam mengembangkan peradaban. Melalui pembacaan ini, via orientalisme Barat abad lalu, Jabiri sekaligus meneropong tradisi budaya masyarakatnya. Lalu, ia juga menyoal bagaimana menempatkan tradisi masa kini di hadapan modernitas Eropa.
Strateginya ada dua. Pertama, ia membaca masa lalu sebagaimana Ibnu Rusyd membaca sang liyan pada zamannya: warisan Yunani kuno. Kedua, menggunakan ‘spirit Ibnu Rusyd’, ia berpindah ke ruang dan waktu terkini: bagaimana menempatkan sang diri—dalam hal ini Jabiri berhadapan dengan teks hegemonik dari modernitas Eropa.
Dalam Al-Thabit wa al-mutahawwil (Yang Tetap dan Yang Berubah) yang pertama kali diterbitkan pada 1973, penyair Suriah Adonis berperan dalam menggali aspek kebangkitan pasca-1967 dengan menelisik berbagai mazhab non-ortodoks dalam Islam seperti Khawarij dan Sufisme. Dengan cara yang sama, Jabiri juga memberikan ruang bagi sejarah Khawarij, Syiah, dan Sufi untuk menampilkan diri sejajar dalam sejarah intelektual Islam, sebagaimana diteroka para ilmuwan Barat.
Maksud Jabiri memasukkan mazhab-mazhab non-ortodoks itu ialah supaya taklid tidak terus menjadi pegangan umat Islam, termasuk menyingkirkan nalar politik Islamisme yang mengarah ke pengafiran (takfir) yang pernah membuat mati sarjana Sudan Mahmud Muhammad Taha, membunuh Farag Fouda di Mesir, dan menyingkirkan Nasr Hamid Abu Zayd. Kaum muslim perlu sadar atas pluralisme sejarah masa lalu.
Kritik nalar Jabiri bertujuan akhir untuk mendorong pemikiran kritis dalam nalar Arab-Islam kontemporer. Simbol Ibnu Rusyd yang mematahkan landasan filsafat Ibnu Sina di Timur, dalam logika Jabiri, menjadi avatar renaisans.
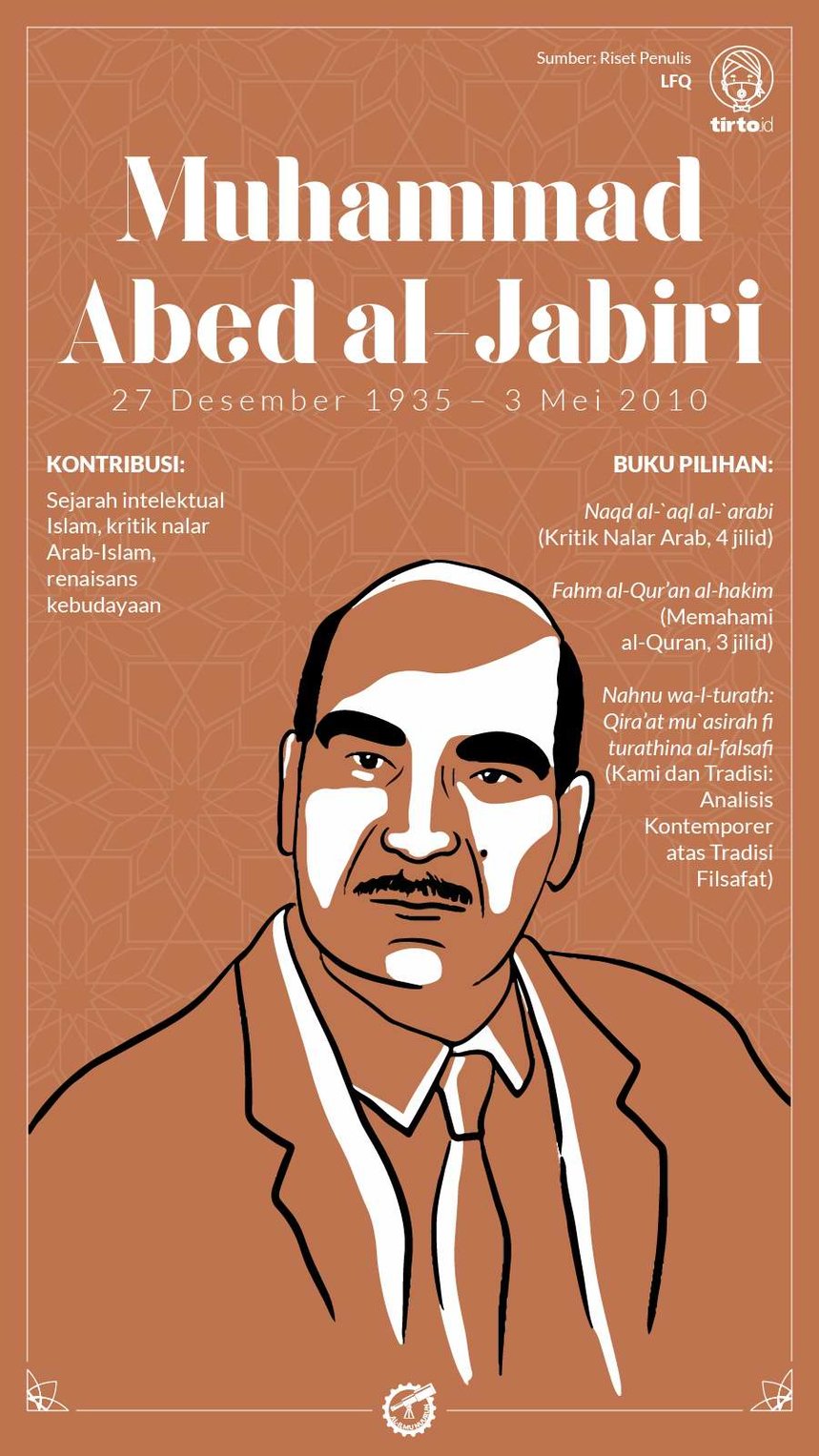
Inspirasi Para Intelektual NU
Terlepas dari kreativitas, inovasi, dan kedalaman Jabiri dalam menguak tabir nalar agama, baik secara sosial, politik, budaya, dan intelektual, pandangan Jabiri yang menghidupkan avatar Ibnu Rusyd mengandung bias orientalisme lampau. Pandangan Jabiri sama terbagi dengan pandangan Hassan Hanafi dan sarjana Turki penting Hussein Atay, penyunting kitab Dalalat al-ha’irin (Petunjuk bagi yang bingung) karangan filsuf-rabi Yahudi Maimonides.
Dalam kajian Ramadan NU Cabang Istimewa Jerman pada 18 Juni 2016, saya menulis esai pengantar bertajuk "Di Bawah Bayang-bayang Tradisi". Saya ikut mengamini kemajuan tak ditentukan warisan Ibnu Rusyd saja, melainkan bisa melalui Ibnu Sina atau al-Ghazali.
Jabiri barangkali menganggap ketiga nalar yang membelenggu itu warisan al-Ghazali, yang karya-karyanya kebetulan pernah dibakar di al-Andalus. Jika Jabiri menganggap perlu menghidupkan gairah keilmuan filsafat dan sains melalui Ibnu Rusyd, yang dianggap sebagai Descartes dalam proyeknya, maka skeptisisme dan pencarian akan kebenaran tertinggi (yaqin) tak bisa terlepas dari filsafat al-Ghazali. Sikap al-Ghazali ini, seperti bisa dilacak dalam al-Munqidh min al-dalal, menjadi penting dalam pemikiran kritis dan apa yang oleh Ebrahim Moosa dinamakan ‘the poetics of imagination’. Al-Ghazali adalah filsuf-teolog pertama yang dengan canggih mempertanyakan taqlid, yakni segala rupa tradisi yang menjadi habitus dalam berbagai mode sosial dan kultural (termasuk ateisme), demi suatu pencarian intelektual yang kokoh.
Lalu saya teringat pada buku tebal karya intelektual NU Ahmad Baso, Al-Jabiri, Eropa dan Kita (2018), yang belum sempat saya baca. Di tangan Baso, sebagian pemikiran Abed al-Jabiri pernah diterjemahkan untuk mendukung visi generasi muda NU pada pergantian milenium ketiga, yakni post-tradisionalisme, disingkat postra. Sebagaimana ditulis apik oleh Rumadi dalam Islamic Post-Traditionalism in Indonesia (2015), postra ialah gerakan intelektual untuk "lompat tradisi" sebagai hasil dari pengasahan tradisi Islam dan mendialogkannya dengan kekinian. Postra melanjutkan apa yang sudah disuarakan Abdurrahman Wahid dan Said Aqil Siraj sejak 1990-an.
Spirit Jabiri dihidupkan sebagian intelektual NU untuk menafsirkan kaidah dahsyat dalam NU: menjaga tradisi lama yang baik (al-muhafazah) dan mengambil tradisi baru yang lebih baik (al-akhdhu). Tapi yang Jabiri hidupkan adalah semangat Averrois, sementara dalam ruang epistemik Islam Nusantara ala NU, al-Ghazali lah yang menjadi payung teologis. Maka logikanya menjadi seperti ini: menjaga tradisi al-Ghazali yang baik dan mengambil tradisi Ibnu Rusyd yang baru yang lebih baik. Dalam bahasa Arab: al-muhafazatu 'ala Tahafut al-falasifah, wal-akhdhu bi-Tahafut al-tahafut.
Jika jalan postra ala Jabiri menempuh jalan ini, maka bisakah Islam Nusantara menjadi perkawinan dialektis antara Islam timur dan Islam barat, sehingga menghasilkan apa yang dinamakan Jabiri sebagai harakah tanwiriyyah (gerak pencerahan)? Ataukah Jabiri hanya digali metodenya untuk menempatkan Islam tradisional ala NU dan mengawinkannya secara kreatif dengan ‘yang lain’ baik itu tradisi Arab maupun modernitas Barat?
Asumsi pada pertanyaan pertama sangat kontradiktif, meski ada ruang rekonsiliasi. Sementara yang kedua membutuhkan energi ekstra: menguasai intelektualisme Nusantara, kebudayaan Islam di Timur Tengah, dan modernitas Barat. Apakah ini bisa disebut 'Revolusi Mental' seperti kehendak penguasa? Saya tidak tahu. Tapi ini jauh lebih mendalam dibanding "revolusi" yang birokratis itu.
==========
Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.
Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id