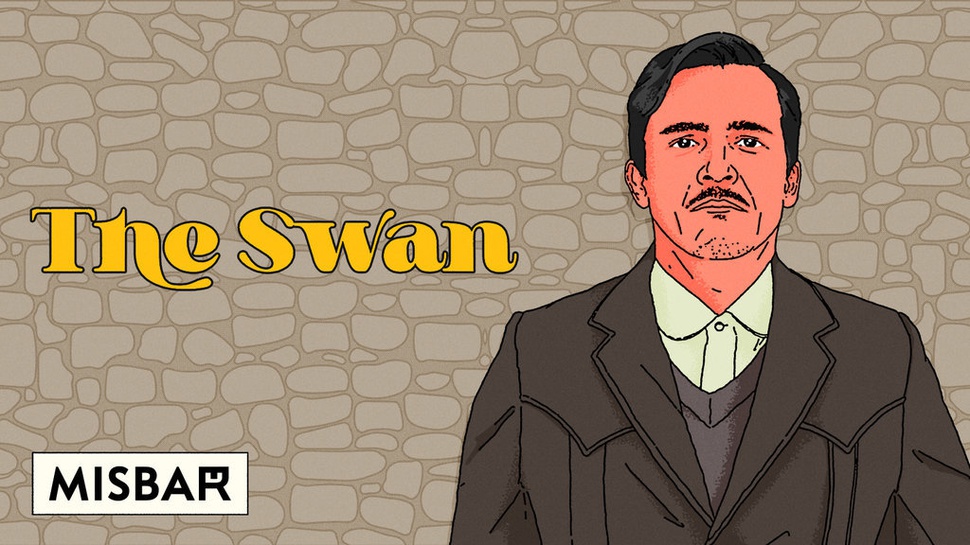tirto.id - Sang narator mengoceh, menyampaikan kisah perisakan yang sebetulnya dialami karakternya sendiri di masa lampau dengan kalem. Dengan mengesankan, Rupert Friend (yang memerankan narator itu), menirukan suara-suara dan intonasi berbagai karakter dalam ceritanya.
Dia akan berlalu sambil tetap mengoceh seraya menghadap kamera yang membuntuti. Dia memperagakan segala gerak dan adegan, memaksa penontonnya membayangkan sendiri—seakan membalik asumsi mapan bahwa film adaptasi mestilah menampilkan segamblang mungkin kisah yang diangkatnya.
Itulah The Swanarahan Wes Anderson yang ditayangkan di Netflix. Ia merupakan alih wahana dari cerpen berjudul samakarya Roald Dahl. Ia juga merupakan bagian dari empat seri film pendek yang juga alih wahana atas karya-karya Roald Dahl.
Dalam serial film pendek ini, Anderson memamerkan caranya membangun keunikan dari cerita yang sudah eksis. Pendekatan Anderson menjadikan film-film dalam serial ini tampak seperti audiobook dengan peragaan di studio, kadang diselipi animasi yang disengaja terlihat tak mulus. Dia seakan mengimitasi panggung teater—lengkap dengan stagehand-nya—ke medium film.
Dalam The Swan, Anderson hanya memberi “panggung” sempit untuk karakternya. Latar ruangnya sengaja dipagari dengan tanaman tinggi nan rapi, sementara para karakternya hanya bisa bergerak di tengah layar. Sebuah latar yang bisa ditafsir sebagai gambaran terbatasnya ruang gerak sang karakter yang merupakan penyintas kekerasan.
Secara umum, pilihan itu membantu terbentuknya atmosfer film yang distingtif—jugaterkesan lebih janggal—ketimbang film-film lain dalam seri ini. Bila dibandingkan dengan film-film panjang Anderson, The Swanbahkan terkesan didaratkan dari sekuens mimpi.
Dan tak ada yang berbicara di sana selain sang narator dan karakter Roald Dahl sendiri (dimainkan Ralph Fiennes). Sebagian besar yang muncul di layar ialah para non-speaking actors yang membantu menggambarkan penuturan sang narator. Selain sedikit musik saat adegan menari, film ini sama sekali tidak memakaimusic scoresehingga nyaris terasa hening.
The Swan jadi tak begitu mudah diikuti bila kau berharap akan banyaknya adegan aksi. Meski begitu, ia sekaligus tak begitu sulit dicerna jika kau memusatkan seluruh perhatianmu pada untaian kata sang narator.
Di sini, Anderson terasa tengah betul-betul bereksperimen dalam film. Eksperimentasi itu tentu terbantu oleh kerja-kerja kamera dan angle tak biasa dari DoP yang juga kolaborator tetapnya, Robert Yeoman.
The Swan bisa dibilang merupakan salah satu film Anderson yang mendekati kata keji. Boleh jadi, ia malah yang paling gelap. Kesan komedi yang biasanya mudah ditangkap hanya dengan pergerakan dan cara berbicara para karakternya bahkan terasa absen di sini, seakan patuh pada gelapnya nilai narasi kisah ini.
Sejatinya Menyoal Siklus Kekerasan
The Swan bertahan selama 30 tahun dalam buku rangkuman ide sebelum Dahl merampungkannya menjadi cerpen dan diterbitkan pada 1976. Kisahnya didasarkan dari kejadian nyata dan ditulis dari sudut pandang orang ketiga serba tahu.
Ketika telah merupa film, ceritanya berjalan dalam 17 menit. Padahal, cerpen The Swansebenarnya cukup panjang. Anderson mungkin bermaksud agar film inisetara secara durasi dengan judul-judul lainnya dalam seri ini, yakniPoison dan The Rat Catcher.
Bagian paling utama yang nyaris dipangkas habis oleh Anderson ialah perihal latar Ernie dan Raymond, dua karakter pelaku perisakan terhadap Peter Watson. Mereka berdua adalah anak-anak muda yang menjelma hooligan di Inggris. Mereka pun berasal dari rumah tangga yang sarat kekerasan.
Dahl sekilas menyoroti akar maraknya perundungan dan kekerasan di Britania sekalian berfokus pada ide bahwa pelaku juga bisa jadi korban atau sebaliknya. Singkatnya, kekerasan serupa siklus yang tiada akhir.
Beda dari materi aslinya, Anderson memilih untuk berpaling dari perspektif tersebut. Sebagai gantinya, dia berfokus menyoroti sisi penyintas. Dalam waktu yang sama, dia juga menyederhanakan narasinya—sesuatu yang jarang dia lakukan.
Di film, kekerasan ditampilkan dengan unik: hanya dibicarakan, sesekali dengan peragaan-peragaan canggung. Karakter Ernie dan Raymond juga dimainkan oleh aktor-aktor yang tampak dewasa. Penggambaran macam ini tampak berbagi kesamaan dengan The Rat Catcher yang juga menampilkan peragaan-peragaan imajiner.
Bedanya, dalam The Swan, cara itu boleh jadi diniatkan untuk menyingkirkan adegan perisakan anak—terutama bila mengingat adanya adegan penembakan dalam cerpennya. Sementara itu, dalam The Rat Catcher, adegan kekerasan diimplisitkan untuk mempertahankan energi cerpen sumbernya.
The Swan versi Anderson lantas terkesan jadi kisah yang “hanya” soal detail perisakan, sekadar menampilkan para perisak yang tak kunjung puas selama korbannya belum kenapa-kenapa.
Meski kekerasan telah dibuat implisit, kisah ini tetap saja menyakitkan. Bila Anderson memilih menyajikannya dalam paket visual khasnya yang menawan dengan sederet kecanggungan, Dahl bakal menyebut secara ironis bahwa karakter-karakter perisak dalam ceritanya memiliki “perangai lembut”.
Bila Anderson tampak sekadar tertarik pada detail perisakan dan menampilkannya dalam sekuens yang rada absurd, Dahl menjejalkan perasaan Peter Watson dengan perlahan ke dalam ceritanya. Si anak korban perisakan bakal merayakan kemenangan sekecil apa pun asalkan bisa menjauhi para perisaknya, kendati itu berarti menyongsong bahaya.
Dengan mempertahankan pengujung kisah sesuai sumber aslinya,The Swan pada akhirnya tetap menekankan langkah-langkah naratif yang bakal ditempuh Dahl ketika menulis cerita untuk pembaca dewasa. Ia tetap tanpa konklusi atau pesan apa pun selain menyoroti siklus kekerasan—kalau bukan mengaburkan “pesan moral” dalam visual dan estetika khas sang sutradara.
Setidaknya, penggambaran Anderson masih jadi adaptasi yang cukup layak ketika narasi mengantar kita menuju puncaknya: bahwa ada orang-orang yang kelewat degil untuk menyerah, yang untuk alasan tertentu tak akan pernah terkalahkan oleh perisakan atau apa pun, seperti Peter Watson.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi