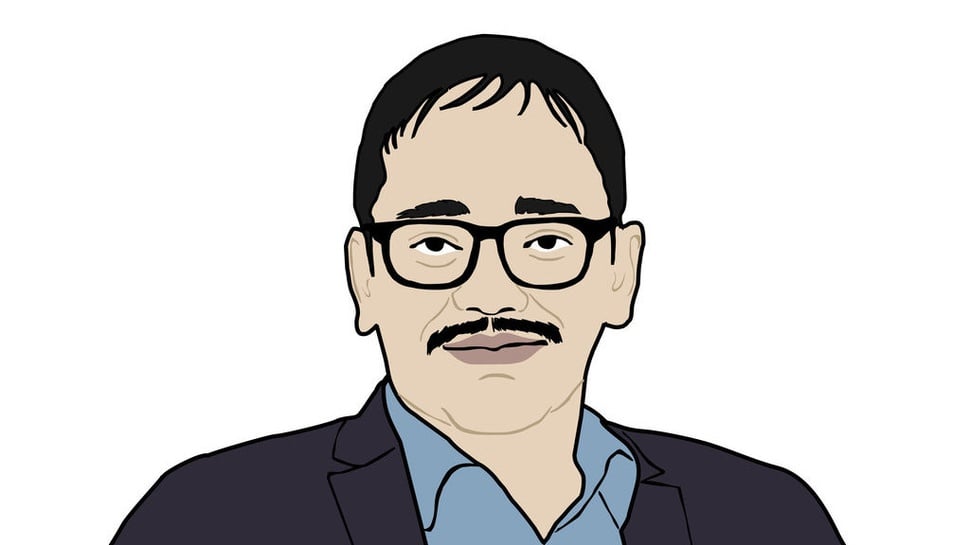tirto.id - Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Surat Keterangan Penelitian (SKP) memang sudah "ditangguhkan" sementara untuk direvisi ("membatalkan dulu Permendagri tersebut yang memang belum diedarkan dengan pertimbangan akan menyerap aspirasi berbagai kalangan"). Namun publik masih bisa bertanya: kenapa bisa peraturan yang mengekang itu sempat-sempatnya dikeluarkan pemerintah?
Pertanyaan itu tetap relevan kendati Permendagri karena kadung menjadi perbincangan, terlanjur keluar, dan dengan demikian telah menjadi "sejarah": bahwa pada satu masa pernah muncul Permendagri dengan substansi yang bisa dikatakan mengekang kebebasan akademik.
Mengapa bisa pemerintah pernah mengeluarkan beleid yang memberi beban tambahan yang baru bagi para peneliti Indonesia di tengah situasi kekurangan dana dan sumber daya pendukung? Bagaimana dapat pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, membuat kalimat: “dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian” seperti tercantum dalam Pasal 2 peraturan tersebut?
Perhatikan kata “diperkirakan akan timbul” dalam pasal tersebut. Ia mengingatkan diktum lama budaya politik otoriter bahwa “pemerintah senantiasa tahu yang terbaik” untuk warganya.
Sebelum sebuah kegiatan penelitian dilakukan, pemerintah—dan sekali lagi hanya pemerintah—akan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin penelitian dan melihat apakah ada potensi dampak negatif yang mungkin timbul seperti tercantum dalam Pasal 11 Ayat 5. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah dari tingkat daerah (kotamadya/kabupaten) sampai tingkat nasional, berwenang untuk menolak memberikan rekomendasi SKP tersebut.
Begitu juga untuk penelitian yang telah berjalan. Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah tidak akan memberi perpanjangan SKP apabila “penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” seperti disampaikan dalam pasal 15 ayat 4 butir c.
Tabiat Otoriter
Keseluruhan wewenang yang tercantum dalam peraturan itu seakan membalik arus sejarah gerak reformasi politik dua dekade lalu—sebuah rentang waktu yang pendek. Dua dekade lalu, tepatnya pada Mei 1998, sejumlah mahasiswa, buruh, petani, dan aktivis prodemokrasi, turun ke jalan menuntut turunnya Suharto dengan slogan kebebasan berserikat, menyatakan pendapat dan berpolitik. Sudah ada korban yang jatuh dalam perjuangan mencapai tiga kebebasan dasar dalam kehidupan politik Indonesia. Para peneliti di lembaga independen atau akademisi di perguruan tinggi turut menikmati capaian sejarah tersebut dengan peluang membuka hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu sebagai tema penelitian.
Presiden Abdurahman Wahid, seorang reformis yang mencoba menata kehidupan demokrasi di Indonesia, menyadari dampak buruk kontrol berlebih negara terhadap kegiatan warganya. Gaung semangat reformasi itu bisa dilihat dalam peraturan sebelumnya dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 yang -- walau pun masih dikritik terlalu birokratis -- setidaknya telah memangkas wewenang Kementerian Dalam Negeri sebagai clearing house. Permendagri tersebut tidak lagi menjadikan institusi tersebut berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga negara, menjadi sekedar menata laporan administrasi kegiatan penelitian—baik yang dilakukan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian independen—dengan hanya meminta kelengkapan berkas dari lembaga para peneliti berasal dan pihak berwenang di lokasi penelitian.
Dengan cara seperti ini pun sesungguhnya pemerintah telah memiliki sebuah instrumen administratif (yang tetap saja merepotkan bagi peneliti) untuk mengawasi agenda penelitian yang dilakukan warganya, termasuk juga warga asing.
Lalu pertanyaannya adalah mengapa pemerintah (pernah) merasa perlu mempersenjatai diri melihat kemungkinan “dampak negatif yang akan timbul” (sekali lagi bukan kejadian sesungguhnya) dari sebuah kegiatan penelitian? Apa yang salah di Indonesia sekarang ini?
Ada sejumlah spekulasi tentang mengapa Permendagri ini bisa lahir. Faktor paling utama adalah terkait beragam ancaman, baik nasional maupun global, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer. Munculnya fanatisme keagamaan, penyebaran terorisme global, sampai racun hoaks, adalah sejumlah fenomena yang muncul belakangan. Namun untuk menangkal itu semua, apakah pemerintah harus turut mengatur pula sebuah agenda penelitian dan mengira-ngira dampak negatif “yang diperkirakan akan timbul”?
Siapa yang memperkirakan? Apa landasan perkiraan itu? Tidak ada jawaban yang cukup jelas terhadap pertanyaan tersebut. Namun kita tahu bahwa di sini persoalannya bukan lagi argumen ilmiah yang melatari sebuah agenda penelitian.
Memang ada sebuah pengecualian yang memberi kelonggaran dalam peraturan tersebut. Pasal 5 Ayat 2 menyebutkan bahwa (a) penelitian untuk tugas akhir di lembaga pendidikan dan (b) penelitian yang dilakukan instansi pemerintah dengan sumber pendanaan dari APBN dibebaskan dari keharusan itu.
Anda bisa bayangkan sebuah survei statistik pemerintah yang dibiayai APBN akan menempuh jalur bebas hambatan dalam melihat peta kemiskinan di wilayah konflik. Sedangkan kegiatan yang dilakukan warga biasa harus terlebih dahulu memenuhi standar bebas dari kemungkinan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Kita tidak lagi bertanding data dan pengetahuan dalam sebuah perdebatan dalam satu persoalan. Poin ini sekali lagi mengungkapkan adagium “hanya pemerintah yang tahu hal terbaik buat warganya”.
Filsuf Italia Giorgio Agamben (2005) menyebutkan fenomena “kedaruratan” dalam ranah konstitusional menjadi bagian tak terpisah dari praktek pemerintahan sekarang ini. Peraturan yang baru muncul mengingatkan kembali bahwa kita sekarang tengah dibawa dalam situasi darurat tanpa pernah tahu kapan berakhir dan sejauh mana semua ancaman menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk membatasi aktivitas warganya.
Pada satu sisi kebijakan itu menunjukkan upaya pemerintah memperkuat diri dengan instrumen hukum yang dimilikinya. Namun di sisi lain Permendagri juga memberikan gambaran betapa gamangnya sistem politik kita yang mulai kehilangan kapasitas membangun kehidupan demokratis seperti yang dicita-citakan reformasi politik Indonesia.
Para peneliti, seluruh civitas akademik, patut mencermati revisi seperti apa yang akan dilakukan Kemendagri. Kemendagri selayaknya membuka diri pada masukan publik dalam proses revisinya. Jangan sampai revisi mengulangi hal yang sama, memuat substansi serupa, walau dengan kalimat yang berbeda.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.