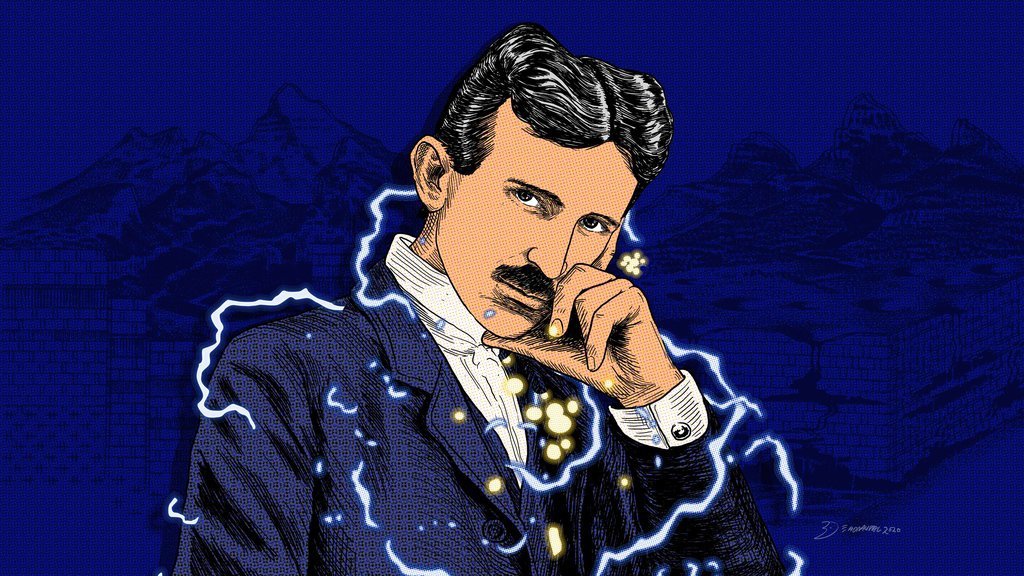tirto.id - Seorang lelaki lajang berumur 30-an, sebut saja namanya Didi, kerap ditanya soal klasik "kapan kawin" setiap lebaran. Didi selalu punya jawaban untuk pertanyaan untuk menunjukkan bahwa ia acuh-tak-acuh, misalnya: "Nanti, kalau Israel dan Palestina bisa hidup damai di dalam satu negara."
Namun, sebenarnya, ia tidak mau menggadaikan keutamaan berpikir dengan kehidupan rumah tangga yang, dalam kata-katanya sendiri, “prosaik.”
Jawaban alternatif lain dari Didi adalah sebaris kalimat yang dia (dan banyak orang lainnya) percaya berasal dari filsuf Yunani, Sokrates: “Apa pun yang terjadi menikahlah. Jika kamu menikahi perempuan yang baik maka hidupmu akan bahagia, tapi jika kamu menikahi perempuan brengsek, setidaknya kau akan jadi filsuf”.
“Dan saya,” sambungnya, “tak perlu pasangan brengsek untuk jadi filsuf.”
Petikan aslinya lebih metaforis. Teks Symposium hanya memacak kalimat “…penunggang kuda yang paling ahli, tak pernah memelihara kuda jinak.”
Kutipan tersebut bisa berlaku buat laki-laki maupun perempuan untuk menjalani kehidupan paripurna sebagai intelektual: orang-orang yang dalam kehidupan pribadinya lebih banyak berpikir—dan kehidupan berpasangan, dalam pelbagai bentuknya, sering kali memang jadi sumber masalah.
Kenyataannya, Sokrates memang menikah dan sebelumnya sudah menjadi filsuf. Xanthippe, istrinya, ia nikahi karena satu alasan: perempuan itu terkenal cerdas, bertemperamen tinggi, jago debat, sehingga kalau ia bisa bersilat lidah dengan Xanthippe, niscaya ia pun bisa adu bacot dengan seantero penduduk Athena.
Tapi, bisakah kemungkinan lain terjadi: menjadi pemikir, intelektual, atau filsuf tanpa perlu "pasangan brengsek" seperti dikatakan Didi?
Sejarah menjawab bisa, dengan nada optimis.
Khazanah intelektual Barat punya daftar panjang pemikir dan ilmuwan yang jadi bujangan seumur hidup. Di abad ke-20 ada seseorang yang paling menonjol, yaitu Nikola Tesla, yang meninggal pada 7 Januari 1943, tepat hari ini 77 tahun lalu. Orang Amerika kelahiran Kroasia ini dikenang berkat penemuan mekanisme alternating current (AC) dalam bidang kelistrikan dan prediksi jeniusnya tentang dunia nirkabel. Kini orang-orang bahkan melihat namanya ada di mana-mana: sebagai Satuan Internasional (SI) dari intensitas magnet dan merek dagang perusahaan mobil elektrik.
Dari abad-abad sebelumnya, deretan ilmuwan lajang bisa lebih panjang. Sebut saja Leonardo da Vinci, Copernicus, Newton, Hume, Descartes, Leibniz, Voltaire, Spinoza, Pascal, dan Immanuel Kant.
Sains, etika, pengetahuan modern—dari empirisisme, rasionalisme, hukum gravitasi, prinsip negara hukum, hingga listrik dan komputer—sebagian berasal dari buah pikiran orang-orang yang memilih jalan pedang untuk terus seorang diri sepanjang hayat.
Sains vs Rumah Tangga
Sebutir apel jatuh di kepala Newton muda yang sedang duduk di bawah pohon, lalu lahirlah teori gravitasi. Hikayat ini sungguh terkenal hingga hari ini, sampai-sampai tidak ada pertanyaan: Apakah dia tidak sedang berasyik-masyuk di bawah pohon? Kalau ya, dengan siapa? Kalau sendirian, siapa yang dia bayangkan?
Sains, sayangnya, memang mengabaikan hal-ihwal remeh semacam itu. Newton (1643-1727) meninggal dalam keadaan perjaka, tak pernah pacaran, apalagi menikah. Ada yang berspekulasi bahwa Newton seorang homoseksual, aseksual, atau sekadar tak mampu mentolerir keberadaan orang lain di sekitarnya.
Namun kehidupan melajang bukan sesuatu yang ganjil pada era Newton. Sistem pendidikan tinggi, termasuk di Oxford dan Cambridge (tempat Newton mengajar) mewarisi kultur monastik abad pertengahan yang mewajibkan dosen dan mahasiswa untuk mengambil kaul selibat. Mahasiswa adalah calon padri, yang diajar oleh dosen-dosen yang seumur hidup tinggal dalam komunitas mirip biarawan.
Demikian dalam suasana seperti itu, musuh pengetahuan bukanlah iman, melainkan (godaan) berumah tangga. Menikah, beranak, lalu membina keluarga bisa menurunkan produktivitas olah pikir—sesuatu yang sejatinya masih relevan untuk zaman kita.
Bagi para pemikir perempuan sebelum abad ke-20, situasinya berbeda: sulit untuk memilih lajang di tengah masyarakat yang memahami berumah tangga dan kerja domestik sebagai takdir semua perempuan. Namun pada tahun 2006, penelitian National Science Foundation menemukan, 66 persen ilmuwan perempuan di Amerika cenderung memilih melajang.
Science Magmencatat pada 2006 Satoshi Kanazawa, psikolog dari Universitas Canterbury, Selandia Baru, menganalisis 280 biografi matematikawan, fisikawan, ahli kimia, dan biolog—mayoritas laki-laki. Dari 280 ilmuwan itu, yang paling sedikit mengalami penurunan produktivitas berkarya pada usia akhir 50-an adalah yang tidak menikah.
Pada kelompok yang sama, penurunan produktivitas juga lebih lambat. Adapun ilmuwan yang menikah semakin sedikit meneliti dan menulis pada usia 50-an, dengan penurunan volume publikasi yang sangat drastis. "Produktivitas ilmuwan laki-laki cenderung menurun setelah menikah," ujar Kanazawa.
Tapi dua abad lalu, kehidupan Immanuel Kant justru baru dimulai di pengujung usia kepala lima. Itu pun bukan karena dia kawin, tapi lantaran menerbitkan karya puncaknya, Kritik atas Nalar Murni di usia 57. Dalam Kant, A Biography (2002) Manfred Kuhn mencatat rutinitas sang filsuf Jerman sejak usia 30an.
Tiap pagi, Kant bangkit dari peraduan pukul 5, dilanjutkan minum secangkir dua cangkir teh sambil merokok, lalu menulis sampai pukul 7 dan memberikan kuliah hingga pukul 11. Selanjutnya ia menulis, tidur siang, jalan-jalan sore, menghabiskan waktu bersama kawannya John Green yang pedagang asal Inggris itu, ditutup dengan membaca sampai tidur.
Tak ada cinta-cintaan dalam usia panjangnya yang menghasilkan karya-karya babon seperti Dasar Metafisika Moral (1785), Dasar Metafisik Ilmu Pengetahuan Alam (1786), Kritik atas Nalar Praktis (1788), Kritik atas Penilaian (1790), Metafisika Moral (1797), yang sampai sekarang memengaruhi manusia modern dalam memahami negara, seni, dan iman.

Masalah Psikologis
Sebagian pemikir yang tidak terkungkung dalam tradisi monastik memilih membujang dengan alasan-alasan berbeda. Trauma yang hebat, juga kegamangan menjalani hidup bersama orang lain, kadang menjadi penyebabnya.
Blaise Pascal, matematikawan dan penemu kalkulator analog, barangkali tidak akan selibat seandainya tidak mengalami kecelakaan kereta kuda dan merasa mendapat wahyu dari Tuhan lalu mengabdikan diri untuk paguyuban Jansenis, sekte gurem dalam Gereja Katolik yang dibubarkan Vatikan.
Contoh lain yang paling legendaris adalah Søren Kierkegaard. Pada 1840, filsuf Denmark itu sudah tunangan dengan Regina Olsen. Namun, karena tak yakin mampu menjadi suami yang baik, Kierkegaard memutuskan pertunangannya. Sang gadis pun kawin dengan orang lain. Dengan kesadaran penuh, Kierkegaard memutuskan jadi ‘Imam Besar Generasi Menolak Move On’ sampai mati.
Tiga tahun setelah pertunangannya kandas, Kierkegaard menulis bak orang linglung:
"Jika kau kawin, kau akan menyesal; kau tidak kawin, juga menyesal ... kau mempercayai seorang gadis, kau akan menyesal; kau tidak percaya, juga akan menyesal ... kau gantung diri, kau menyesal; tidak gantung diri juga menyesal ... kau gantung diri atau tidak gantung diri, kau akan menyesali keduanya. Inilah, tuan-tuan, puncak dari segala kearifan praktis" (Either/Or, 1843).
Lain cerita dengan Nikola Tesla. Dia tidak menikah—dan mati sebagai perjaka—lantaran benci perempuan. Tesla sempat berujar “Kujunjung perempuan tinggi-tinggi … Aku bersimpuh di hadapan mereka, dan layaknya tiap pemuja sejati, aku merasa diriku tak layak di hadapan obyek yang kupuja.”
Namun, puja-puji Tesla diungkapkan sebelum perempuan Amerika Serikat mendapatkan hak pilih secara nasional pada 1920. Setelahnya, pandangan Tesla tentang perempuan mirip-mirip orang yang percaya bahwa kiamat sudah dekat karena perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya.
Ketika diwawancarai koran lokal Galveston Daily pada 1924, ia mengatakan: “Dunia ini sudah mengalami banyak tragedi, namun menurutku tragedi terbesar adalah kondisi ekonomi saat ini dimana perempuan bersaing melawan laki-laki, dan pada banyak kasus benar-benar merampas kedudukan laki-laki dalam pekerjaan dan industri."
Tak semua bujang-pemikir misoginis seperti Tesla, yang konon pemalu dan memilih mengumpani rombongan merpati di luar kamarnya ketimbang bersosialisasi dengan manusia. Kopernikus, yang mengembangkan teori heliosentris (bumi mengitari matahari), tidak menikah tapi punya beberapa pasangan. Begitu pula Galileo.
Yang paling menarik adalah Voltaire, yang berjasa besar mewariskan pada kita cara menulis satir-satir fantastis. Voltaire tidak menikah, tapi punya banyak affair, termasuk dengan Madame du Chatelet, partner intelektual sekaligus keponakannya sendiri yang jarak usianya 14 tahun lebih muda.
Karena sudah menikah dengan seorang bangsawan yang membayar Voltaire untuk mengajari Madame du Chatelet bahasa Inggris, mustahil bagi Voltaire untuk melamar sang pujaan hati. Namun kecerdasan perempuan yang gandrung aljabar dan fasih berbahasa Latin itu pun akhirnya membuat Voltaire mempertahankan hubungan gelap itu—sambil tetap membujang.
Tentu tidak semua orang bakal konsisten dengan kaul selibat. Namun pengalaman-pengalaman para pemikir-bujang ini memberikan amunisi yang mumpuni menjelang lebaran. Pernyataan yang tepat bukanlah "mereka sukses meskipun tidak pernah kawin," melainkan, "mereka sukses justru karena tidak kawin."
==========
Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 24 Mei 2017 dengan judul "Mengapa Banyak Ilmuwan dan Pemikir Melajang Seumur Hidup?". Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Maulida Sri Handayani & Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id