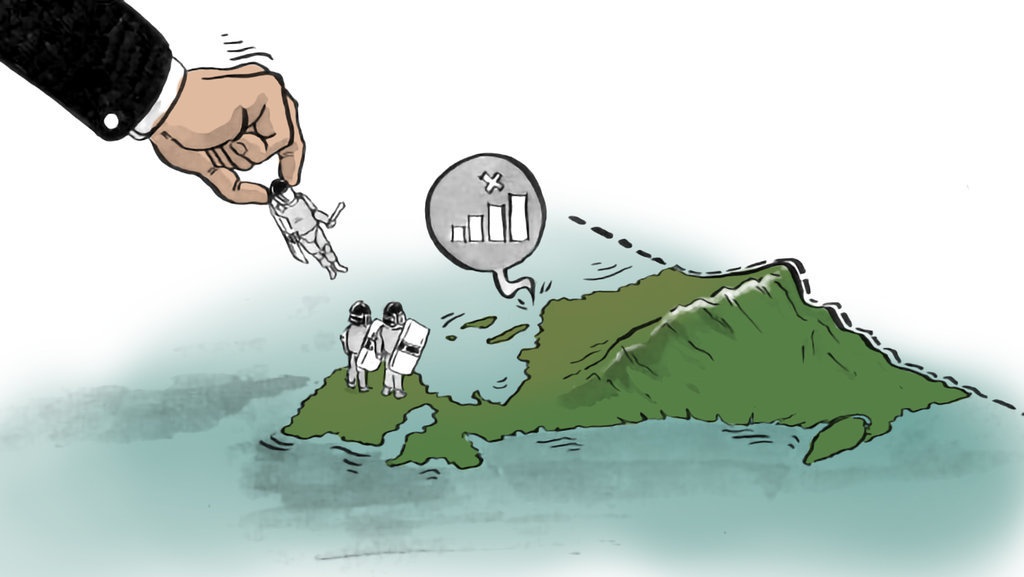tirto.id - Jumat, 13 Juli 2016, adalah hari yang mungkin tak bisa dilupakan oleh Obby Kogoya, mahasiswa Papua di Yogyakarta. Di depan asrama Kamasan di Jalan Kusumanegara, tanpa tahu apa salahnya, ia dikejar-kejar, ditendang, dipukuli, lalu ditangkap polisi Indonesia.
Peristiwa itu diabadikan oleh fotografer lepas Suryo Wibowo. Kameranya menangkap kepala Obby diinjak oleh polisi, ada pula foto ikonik mengabadikan perlakuan rasis aparat keamanan Indonesia terhadap orang Papua: kedua hidung Obby ditarik oleh kedua jari seorang polisi dan tangan Obby diborgol.
Tapi, keributan itu segera dilupakan publik. Ormas yang turut mengepung asrama bersama polisi juga terlupakan. Polisi daerah Yogyakarta berdalih: tidak ada kericuhan di asrama Papua Yogyakarta; kondisi di Yogyakarta kondusif; foto Obby Kogoya adalah hoaks. Bahkan, polisi berkata akan memburu penyebar foto itu. Masalah selesai. Obby justru diseret ke meja hijau dan diadili.
Keributan kembali terjadi dua tahun kemudian di Surabaya. Saat itu mahasiswa Papua dikepung ormas dan polisi di asrama Kamasan di Jalan Kalasan. Sejak pagi, mahasiswa Papua yang belajar di Jawa dan Bali, tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua, menggelar aksi demo memperingati 1 Desember, dianggap sebagai hari kedaulatan Papua.
Mereka melakukan aksi jalan kaki dari Monumen Kapal Selam menuju Gedung Grahadi. Aksi itu berujung pada kericuhan. Mahasiswa dilempari batu oleh ormas, mengakibatkan tiga mahasiswa bocor kepalanya.
Bukan menangkap para pelaku pelempar batu, polisi Indonesia justru memulangkan mahasiswa dan membiarkan kasus kekerasan itu menguap. Persis seperti apa yang terjadi di Yogyakarta. Publik Indonesia dengan cepat melupakannya.
Kejadian Luar Biasa
Kekerasan ormas dan pengepungan polisi, lalu mayoritas publik Indonesia melupakannya, adalah semacam formula saat pemerintah lewat aparatur kepolisian berhadapan dengan mahasiswa Papua. Formula ini diterapkan pada kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus lalu.
Ormas mendatangi asrama, melempari mahasiswa dengan batu, memaki mahasiswa Papua dengan ujaran rasis, sementara polisi dan aparat TNI cuma diam. Bukan menangkap para anggota ormas itu, polisi justru menyerbu asrama dan menemabakkan gas air mata dengan dalih "pengamanan."
Kekerasan terhadap mahasiswa di asrama itu pun didiamkan saja. Sehari setelah kejadian, pemerintah dan aparat Indonesia tetap diam. Seakan tak punya salah terhadap para mahasiswa Papua. Anggota ormas tanpa tersentuh hukum setelah meneriaki dengan kata-kata rasis terhadap mahasiswa Papua.
Namun, kali ini, pemerintah dan aparat kepolisian Indonesia salah perhitungan.
Formula itu sudah tidak mempan. Dua hari usai kejadian, tindakan rasisme itu direspons luar biasa di Papua.
Tepat sehari setelah negara ini merayakan kemerdekaan ke-74, Papua bergolak. Dari Jayapura, Manokwari, Nabire, Sorong, lalu menyusul Fakfak dan Mimika. Ujaran rasis di Surabaya memicu kemarahan. Mereka melakukan aksi besar-besaran. Membakar. Merusak. Bahkan, di Fakfak, terjadi pertikaian di jalan antara orang Papua dengan orang Papua, salah satunya mewakili milisi pro-NKRI.
Respons Gagap Pemerintah Indonesia
Sehari setelah ujaran rasis, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa sibuk dengan peringatan kemerdekaan RI ke-74. Pagi itu ia menjadi inspektur upacara pengibaran bendera Merah Putih di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dalam pidatonya, Khofifah sama sekali tidak menyinggung rasisme terhadap mahasiswa Papua di daerahnya.
Sore hari, Khofifah mengundang tukang becak, anak yatim dan yatim-piatu, difabel dan lansia, sebagai tamu khusus dalam upacara penurunan bendera. Malam hari peringatan kemerdekaan, ia menggelar kemeriahan dengan hiburan penyanyi dangdut Via Vallen. Dari sore sampai malam, tidak ada pernyataan apa pun dari Khofifah terkait rasisme itu.
Barulah sampai esok hari, setelah Papua bergolak, Khofifah angkat bicara soal rasisme di Surabaya. Ia didampingi Kapolri Jendral Tito Karnavian mengucapkan permintaan maaf terhadap warga Papua atas ujaran rasisme yang terjadi di wilayahnya.
"Saya ingin menyampaikan bahwa itu sifatnya personal, itu tidak mewakili masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas nama masyarakat Jawa Timur. Sekali lagi, itu tidak mewakili masyarakat Jawa Timur," katanya.
Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga merespons rasisme di Surabaya yang berakibat kerusuhan di Manokwari: “Saudara-saudaraku, pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah saling memaafkan."
Polisi segera merespons isu rasisme. Namun, masih menggunakan formula lama. Alih-alih menangkap pelaku rasisme atau meminta maaf, polisi sempat menyangkal rasisme itu dan berencana memburu penyebar video ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua.
"Mana yang rasis? Tidak ada tindakan rasis," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo."Justru kami evakuasi agar tidak terjadi bentrokan dan jatuh korban. Itu yang penting."
Saat demonstrasi besar-besaran di Papua, Dedi menutupi situasinya dengan berkata para pendemo hanya terprovokasi media sosial. Dengan logika itu, maka Tim Siber Bareskrim melakukan profiing pemilik akun penyebar informasi. Per 20 Agustus 2019, sudah ada lima akun yang "didalami" polisi.
Pada saat bersamaan, polisi merespons aksi di Papua dengan menambah pasukan. Dedi mengatakan kepolisian Indonesia akan menambah 6 satuan setingkat kompi—setara 600 personel—demi "mengamankan objek vital" di Papua.
Sementara polisi menambah jumlah pasukan, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperlambat jaringan internet di beberapa wilayah di Papua. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, throttling itu atas "permintaan dari Polri."

Respons yang Dibutuhkan Warga Papua
Mikael Kudiai, seorang demonstran di Nabire, hanya geleng-geleng kepala atas pemerintah Indonesia merespon rasisme terhadap orang Papua. Menurutnya, apa yang terjadi di Papua sekarang adalah akumulasi atas luka akibat rasisme terhadap orang Papua di Indonesia.
“Ini ibarat luka infeksi tapi cuma diobati dengan diplester," katanya pada Rabu kemarin. "Lukanya tambah membesar. Rasisme ini sangat menyakiti kami. Ini menjatuhkan martabat orang Papua."
Selama ini, menurutnya, peristiwa ini sudah terjadi berkali-kali tapi tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat kepolisian.
“Permintaan maaf belum bisa mengobati. Sesudah berkali-kali tidak ada tindakan tegas, tidak ada permintaan maaf juga sebelumnya. Kali ini karena aksi masa besar-besaran, pemerintah baru minta maaf,” katanya.
Respons pemerintah dan polisi atas rasisme ini menurutnya tidak menyelesaikan akar masalah di Papua. Sebab, ormas-ormas rasis dan aparat rasis belum dihukum, ujar Kudiai. Sebaliknya, polisi justru mengincar penyebar video ujaran rasis, bukan pelakunya.
“Kalau kita kita bicara keadilan ada jalur hukum. Ini polisi justru menambah jumlah anggota dikirim ke Papua, itu bukan yang kami butuhkan. Kami tidak butuh polisi datang,” katanya.
Hal serupa diungkapkan oleh Mama Yosepha Alomang, tokoh perempuan Amungme, di Mimika. Pendekatan penyelesaian masalah rasisme, ujar Mama Yosepha, tidak bisa dengan gaya militer atau pengamanan polisi. Ia berkata dialog harus dikedepankan untuk menyelesaikan masalah ini.
“Tapi, bagaimana mau dialog kalau orang-orang kami dikasih mati? Jadi ide-ide itu [dialog] harus ditaruh di otak. Lalu kita bicara secara manusiawi. Tidak bisa kalau kalian tidak manusiawi,” kata Yosepha kepada Tirto, Rabu kemarin.
"Jadi kami tra terima kemarin dibilang kera berjalan. Itu dong pu bahasa yang kasar," tambahnya.
Mama Yosepha mengingatkan ada banyak orang Papua yang tinggal atau belajar di luar Papua. Sebaliknya, banyak pula orang dari luar Papua yang mencari penghidupan di Papua. Karena itu sudah seharusnya orang-orang saling menjaga.
“Kami jaga kalian, kalian jaga kami juga,” katanya.
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id