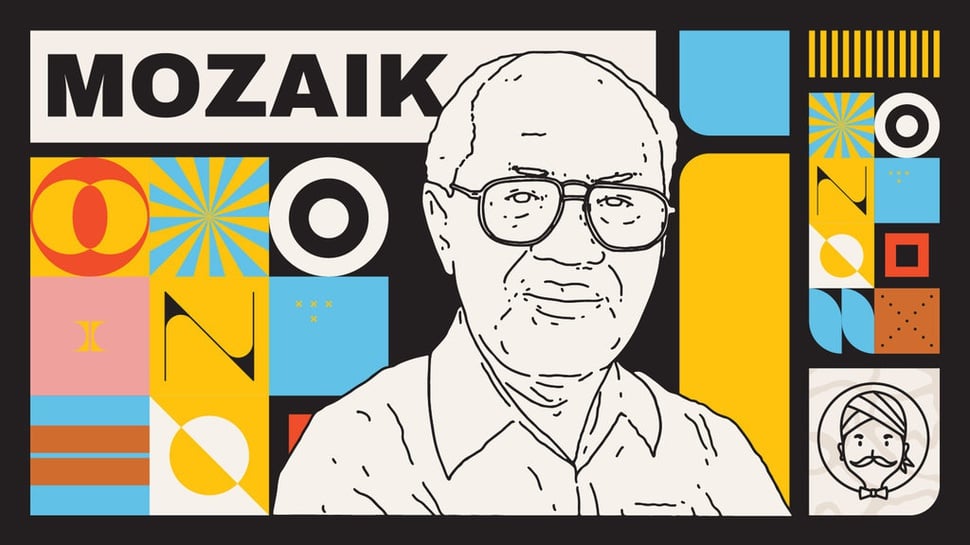tirto.id - Ignas Kleden berangkat menuju Tuhan. Filsuf dan sosiolog ini meninggalkan warisan berupa ratusan, mungkin ribuan, tulisan sejak 1970-an yang memperlihatkan keluasan bacaan dan ketajaman telaah yang dipayungi integritas kecendekiawanan.
Semua kualitas itu dibangun dari belia. Perihal bacaan, pria kelahiran 19 Mei 1948 itu akrab dengan khazanah literatur dunia sejak remaja. Saat kelas 2 SMA di seminari, Ignas menyimak kumpulan tulisan John F Kennedy, Profiles in Courage. Ia juga membaca hal-hal terkait presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Bahkan, ia hafal salah satu pidatonya, Gettysburg Adress.
Untuk urusan menulis, sebulan sekali, ia dan teman-temannya menerima tugas composition dari guru bahasa Inggris. Panjangnya dua halaman buku tulis. Bahan dicomot dari karya sastra yang mereka baca, lalu dituliskan kembali.
Pada pertengahan 1960-an itu, Ignas tinggal di Flores Timur, NTT, dan belajar di seminari menengah Ledalero. Di seminari, sekolah calon rohaniawan Katolik itu, bahasa asing wajib dipelajari, yakni bahasa Inggris, Jerman, dan, terutama bahasa Latin.
"Tidak ada pelajaran lain yang diberi enam jam pelajaran setiap minggu seperti bahasa Latin dan ini masih ditambah dengan pekerjaan rumah setiap hari," kenangnya dalam esai "Sastra Indonesia dan Saya" (Horison, XXXVI/9/2002).
Ketika di SMA, ia mulai meminati kesusastraan Indonesia. Guru bahasa Indonesia membawa buku Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai karya HB Jassin. Dari buku itu, ia tergerak mencari karya Pramoedya Ananta Toer, Chairil Anwar, Asrul Sani, Idrus, Hamka, dan sejumlah nama lain.
Masuk seminari tinggi, bacaannya kian jembar. Ia menyimak biografi para santo dan menerjemahkan karya-karya teologi untuk penerbit Nusa Indah, Ende. Pun mulai mengirim tulisan ke majalah-majalah di Jawa, seperti Basis dan Budaja Djaja.
"Semenjak di Flores, saya mempunyai hubungan surat-menyurat dengan Ajip Rosidi, yang menerbitkan beberapa esai saya di majalah Budaja Djaja dan saya merasa amat bahagia ketika sebuah esai pendek saya bahkan dijadikan tajuk utama majalah tersebut," tulisnya.
Batal Jadi Pastor
Pada 1973, ia memutuskan batal menjadi rohaniawan. Setelah beberapa tahun di seminari, Ignas mulai menimbang-nimbang. Jika menjadi pastor, ia mesti berkhotbah padahal merasa tidak bisa menjadi pengkhotbah yang baik.
Sementara, dengan penguasaan berbagai bahasa secara mumpuni, ia yakin mampu menyampaikan gagasan dengan menulis. Ignas pun hengkang dari seminari, padahal tinggal satu tahun lagi ditahbiskan. Keluarga sempat kecewa.
"Tapi, bagaimana lagi? Untuk menjadi imam harus ada kemauan dari beberapa pihak. Kemauan dari saya yang melamar, kemauan dari pimpinan serikat yang menerima, dan kemauan dari gereja,” tutur Ignas kepada Pusat Data dan Analisa TEMPO (PDAT).
Ia pun pindah ke Jakarta. Sehari-hari ia bekerja sebagai editor di Yayasan Obor yang dipimpin jurnalis cum sastrawan Mochtar Lubis. Juga menjadi staf di Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial yang dipimpin Bapak Sosiologi Indonesia, Selo Sumardjan.
Ignas semakin rutin mengirim tulisan ke Kompas dan TEMPO. Ia mulai dikenal sebagai intelektual publik--mereka yang rutin menyiarkan gagasan ke khalayak ramai, bukan sekadar akademisi di kesunyian laboratorium atau perpustakaan.
Perburuan ilmu tak berhenti. Ia berangkat ke Jerman untuk melanjutkan studi filsafat di Hochschule Fuer Philoshopie di Muenchen. Gelar MA diraihnya pada 1982 dengan tesis tentang pemikiran Karl Popper.
Sepulang dari Jerman, ia aktif menulis di jurnal yang prestisius di zamannya, Prisma. Beberapa tulisannya dihimpun dalam Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (1987). Pada akhir 1980-an sampai awal 1990-an, sebagian aktivis mahasiswa merasa "naik kelas" jika terlihatmenenteng buku bersampul ungu tersebut.
Ia juga kerap diminta menyajikan kata pengantar untuk sejumlah buku. Sebut saja untuk Etika Pembebasan karya Soedjatmoko, Mempertimbangkan Tradisi karya Rendra, atau Perspektif Pers Indonesia karya Jakob Oetama. Semua ditulis dengan pijakan teoritis yang kokoh dan penggunaan bahasa yang efektif.
Ignas kembali ke Jerman untuk S3 pada 1989. Lima tahun kemudian, ayah seorang anak ini memperoleh doktor sosiologi dari Universitas Bielefeld. Disertasinya mengkritisi studi-studi antropolog termasyhur, Clifford Geertz, tentang Indonesia secara holistik.
"Sampai sekarang sudah ada lebih dari 40 publikasi ilmiah tentang studi Geertz mengenai involusi pertanian saja. Masih banyak lagi studi kritis tentang penelitiannya mengenai sektor-sektor lain. Umumnya studi-studi sekunder itu bersifat sektoral, hanya meninjau satu sektor tertentu (misalnya pertanian) tanpa banyak memperhatikan hubungannya dengan sektor lain (misalnya perdagangan). Dalam studi saya, saya berusaha mendekati studi-studi Geertz secara keseluruhan,” kata Ignas kepada Kompas, April 1995.
Dua Wajah Akademisi
Ia terus menulis untuk publik luas. Dalam pengantar untuk kumpulan tulisannya, Menulis Politik: Indonesia sebagai Utopia (2001), Ignas mengatakan, godaan serius bagi penulis akan datang justru ketika dia mempunyai reputasi dan mendapatkan pengakuan publik. Reputasi itu dapat digunakan untuk membela kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok.
Bukan berarti tidak boleh berpihak. Tapi, apa syarat pemihakan itu? Ignas menyatakan, sebagai penulis, secara instingtif dirinya akan cenderung memihak individu atau kalangan yang menderita atau dirugikan kekuasaan.
Ignas menyadari, di Indonesia, pendapat para pakar begitu didengar dalam membicarakan everyday life, baik menyangkut ekonomi maupun politik. Di negara-negara maju, pembagian kerja politikus dan para ilmuwan sudah demikian baku, sehingga para ilmuwan dan peneliti tidak begitu terlibat dalam isu aktual, tetapi bergulat dengan riset mereka.
"Yang menyangkut isu aktual mengenai ekonomi dan politik (juga bidang lainnya) ditanggapi para politikus di parlemen atau partai politik yang bertugas mengawasi pemerintah… Terlibatnya para pakar Indonesia dalam aktualitas politik dan ekonomi menunjukkan bahwa keahlian untuk kedua bidang ini belum seluruhnya terwakili secara memadai di kalangan politisi,” tulis Ignas dalam esai “Produksi Pengetahuan dan Produksi Kekuasaan” (2001).
Keadaan ini berkembang demikian jauh sehingga para akademisi, terutama dalam bidang ekonomi dan politik, harus lebih mempersiapkan diri untuk melayani pertanyaan khalayak atau menjawab pertanyaan media, ketimbang menekuni penelitian secara serius.

Saat diwawancarai Kompas pada April 1995, Ignas melontarkan kritik senada. Bahwa kaum akademisi di Indonesia punya satu kemewahan yang tidak ada di negara lain: begitu lulus sekolah dan menjadi doktor, dengan mudah masuk ke dunia selebriti. Sekadar bicara di beberapa seminar, cepat sekali populer seperti bintang film.
"Di negara maju, seorang pengajar di universitas yang selama setahun tidak menghasilkan satu tulisan pun akan gawat posisinya. Mungkin dia turun pangkat atau kehilangan pekerjaan. Jadi betul-betul berlaku asas penelitian, publikasi atau binasa!" ujar Ignas.
Sekali lagi, tulisan yang dimaksud tentu adalah kajian serius dengan metodologi dan pencarian data yang valid. Jika boleh diringkas: menjadi intelektual publik silakan, tapi aktivitas riset tetap dikerjakan.
Atas semua pencapaiannya, Freedom Institute memilih suami antropolog Ninuk Probonegoro ini sebagai penerima Penghargaan Achmad Bakrie 2003 untuk pemikiran sosial. Dalam penjelasannya, Freedom Institute juga menunjuk kontribusi penting Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (1987) untuk ilmu sosial di Indonesia.
“Fokus utamanya bukanlah bagaimana mengoperasionalisasikan suatu teori dan pemikiran sosial tertentu dan bagaimana agar output dari operasionalisasi tersebut bisa relevan dan berguna untuk masyarakat luas, melainkan bagaimana menguji landasan epistemologis dari pemikiran sosial tersebut dengan cara memeriksa secara kritis klaim kesahihan (validity claim) dari pemikiran tersebut, yang biasanya hanya diandaikan secara taken for granted,” tulis Freedom Institute.
Selain Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (1987), tulisan-tulisan Ignas terkompilasi dalam beberapa antologi. Misalnya, Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka (2020)yangmemuat17 esai mendalam tentang sejumlah tokoh, dan Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan (2004) yang memuat kajian-kajian bernas tentang sastra.
Ignatius Nasu Kleden telah pergi, meninggalkan warisan yang abadi.
"Jejak pikirannya adalah cahaya," tulis penyair Goenawan Mohamad di sebuah grup WA.
Requiescat in pace.
Penulis: Yus Ariyanto
Editor: Irfan Teguh Pribadi