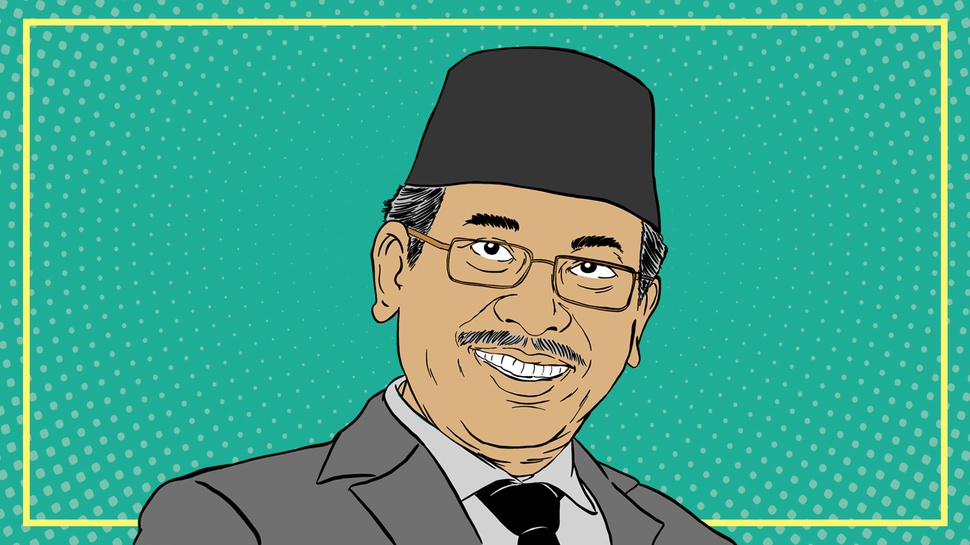tirto.id - Pagi menjelang siang, Senin 8 November 2021, awak redaksi Tirto Riyan Setiawan dan Ivan Aulia Ahsan serta videografer Aris Widiarto mengunjungi Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di kediamannya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kami disambut oleh asistennya dan dipersilakan duduk di atas karpet yang di atasnya terdapat beberapa camilan dan air mineral--bukti kehadiran kami sebagai tamu disambut baik oleh pria yang akrab disapa Gus Yahya itu.
Tak lama setelah kami meregangkan tubuh, Gus Yahya keluar dari kamarnya menggunakan gamis dan sarung hitam beserta peci putih. Kami pun bersalaman dan kembali duduk di atas karpet bersama kakak dari Menteri Agama Ri saat ini, Yaqut Cholil Qoumas. Raut wajahnya terlihat semringah.
Meski menyambut dengan senyuman lebar, wajahnya jelas tampak kelelahan. Sebelum menemui kami, dia baru saja melakukan safari politik ke sejumlah pimpinan wilayah dan cabang NU untuk meminta dukungan demi memuluskan jalan menjadi ketua umum organisasi Islam yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari itu. Ya, putra Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cholil Bisri ini adalah kandidat terkuat Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34 yang rencananya akan diselenggarakan pada 23-25 Desember nanti.
Menurutnya NU harus berhenti menjadi pihak yang berkompetisi dalam politik praktis. “Biar kami bisa menjadi jembatan di antara perbedaan,” katanya. Karena itu pula dia tegas menyatakan tidak akan mencalonkan diri baik sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dia juga mengatakan siapa pun yang hendak maju, “sebaiknya jangan ikut PBNU.”
Tak hanya tentang NU dan strateginya menjelang Muktamar ke-34, dalam wawancara itu dia juga menceritakan tentang kehidupannya, kariernya dalam berorganisasi termasuk ketika menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, juga tentang politik luar negeri, isu yang selama menjabat di NU merupakan fokusnya.
Berikut kutipan wawancara kami.
Bisa ingatkan kami soal perjalanan hidup Anda?
Di Pondok Pesantren Krapyak tahun 1979. Saya pindah kelas 2 SMP. Di Rembang itu saya sekolah diniah sore, menunggu diniah lulus baru pindah [ke Krapyak]. Tinggal di sana sampai 1994, baru pulang [ke Rembang]. 1996 diajak [naik] haji. Tinggal di Makkah setahun. Di sana menumpang dengar saja beberapa syekh, nimbrung majelis. Itu-itu saja. Terus pulang, bantu mengajar santri (ayahnya, K. H. Cholil Bisri, adalah pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, -ed). Itu saja.
Terus Reformasi, kawin, disuruh jadi Wasekjen PKB, juru bicara. Di Jakarta 6 tahun, 1998-2004. Anak pertama lahir di Rembang, kedua di Jakarta.
Hidup di Jakarta itu, gimana, ya. Saya ingat pesantren. Waktu ayah saya wafat (2004, -ed), saya pulang ke rumah, saya putus dengan segala dinamika Jakarta. Setelah Muktamar Makassar 2010, saya ditaruh PBNU jadi salah seorang katib, lalu dikasih katib bidang HI, disuruh kontak internasional. Kebetulan Gus Dur itu sejak 2008 seperti mengalihkan pekerjaan ke paman saya, karena secara fisik Gus Dur sudah kurang sehat. Tahun 2011 saya diajak ke Eropa, Amerika, sesudah itu saya disuruh berangkat. Sampai sekarang ini, saya jalani.
Kakek Anda, Kiai Haji Bisri Mustofa, menulis kitab tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Jawa berjudul al-Ibriz. Bagaimana ceritanya?
Beliau sejak awal berpikir diperlukan penerjemahan kitab-kitab untuk lebih mengakrabkan dengan kalangan santri; membantu belajar. Makanya segala kitab diterjemahkan ke bahasa Jawa. Al-Ibriz itu menjadi salah satu yang dikenal oleh kalangan NU. Gus Dur berkomentar al-Ibriz itu ditulis dengan bahasa percakapan; bahasa sehari-hari untuk semua kalangan. Siapa pun [yang] baca paham.
[Dikerjakan] mulai 50-an, selesai tahun 60-an. [Pengerjaan tafsir] sendirian. Kalau kiai tarekat itu yang banyak wirid. Nah, beliau wiridnya menulis itu, sampai-sampai di mobil. Pergi ke mana-mana bawa senter kecil sambil nulis.
Motivasinya untuk mendekatkan kitab-kitab ke masyarakat santri di pesantren dan NU. Kedua, menghidupkan kembali berbagai wacana yang sudah hampir lenyap dari memori kolektif sehingga kalau dicari referensi sudah tidak ada. Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang, kitab andeng-andeng, di mana letak tahi lalat [yang] menunjukkan karakter orang. Itu dari pengetahuan kolektif saja.
(Kisah hidup Bisri Mustofa yang lebih lengkap dapat dibaca pada tautan berikut).

Nama Anda mulai dikenal masyarakat luas ketika menjadi Juru Bicara Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Bisa ceritakan pengalaman tersebut?
Banyak hal tentang keputusan Gus Dur terhadap diri saya tidak terlalu jelas, termasuk jadi jubir.
Saya kenal Gus Dur pertama 1987. Lalu bertemu lagi setelah Gus Dur berkunjung ke Rembang, Semarang, ketemu Gus Mus (Ahmad Mustofa Bisri, om-nya). Sekitar awal 90-an Gus Dur menawarkan saya ke Jakarta, katanya akan dibuatkan lembaga. Saya minta izin ke ayah saya tidak boleh.
Setelah Reformasi, bikin PKB, saya dilakukan (diangkat jadi) Wakil Sekjen. Sejak itu saya ke Jakarta, lalu disuruh jadi anggota Komisi Pemilihan Umum [perwakilan PKB]. Lalu pemilu. Setiap calon mendaftar dari kabupaten, saya dari Kudus. Waktu itu hasil pemilihan PKB dapat 13 kursi. Nomor 13 itu Pak Alwi Shihab dari daerah pemilihan Wonosido, saya 14. Tapi kemudian Gus Dur jadi Presiden dan Pak Alwi jadi Menteri Luar Negeri. Nah kursi DPR kosong, harusnya saya naik, tapi tidak dikasih ke saya tapi ke Umam (Khatibul Umam Wiranu).
Bagaimana perasaan Anda?
Kaget sih iya, [tapi] itu sudah biasa, saya nurut saja. Saya tidak nanya juga sama Gus Dur, tapi kayanya karena saya ke mana-mana pakai kopiah. Tapi aslinya saya tidak tahu.
Apa momen yang paling Anda ingat saat mendampingi Gus Dur?
Banyak hal, karena Gus Dur hadir dengan kuat. Setiap jadi jubir kami tidak pernah di-briefing, tidak pernah dikasih arahan. Kadang kami ngomong di media saja tidak pernah ditanya sama Pak Presiden.
Biasaya Gus Dur memberikan statement kenegaraan habis salat Jumat. Waktu itu Gus Dur jumatan, habis itu kasih statement. Statement-nya itu tidak pernah di-briefing ke kami. Kadang-kadang kalau enggak ikut jumatan sama Gus Dur, pas habis salat kami kelabakan [sebab] wartawan minta komentar statement Presiden apa. Awal-awal mules, tapi lama-lama ya sudahlah, sama-sama ngarang ini.
Apa pernyataan yang paling berkesan?
Banyak dan selalu gempar, tapi masih bisa ditelusuri di media. Selebihnya enggak ada kerjaan lain.
[Jubir] yang lain itu Pak Wimar (Wimar Witoelar). [Dia] agak jarang [datang], yang paling sering saya. Pekerjaan utama saya menemani Presiden kalau enggak ada tamu. Ngobrolin banyak, apa saja. Yang paling unik, Gus Dur kalau ketemu saya itu pakai bahasa kromo inggil. Kalau menyebut saya “panjenengan” bukan “sampean”. Saya tidak tau apakah ada teman saya yang diperlakukan seperti itu juga. Pas dipilih jadi jubir, saya melapor dengan bahasa Indonesia. Terus Gus Dur bilang “lah jenengan…” Saya jadi tidak enak.
Saya pernah sekali diperintah Gus Dur buat pernyataan. Waktu itu Minggu, biasanya libur. Enggak tahu kenapa saya datang ke Istana pengin menengok Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur bilang ke wartawan bahwa “Bimantoro (S. Bimantoro, mantan Kapolri) ini mengadu domba Presiden dengan Wakil Presiden (ketika itu dijabat Megawati Soekarnoputri, -ed).” Saya bingung, langsung masuk kamar dia, dia enggak jelasin apa-apa.
Waktu itu saya pakai kaus pendek. Saya harus konferensi pers, kok pakai [pakaian] begini? Akhirnya saya ke kamar, ada baju batik Mas Adi yang ditinggal di situ. Itu yang saya pakai. Terus saya bilang ke wartawan: “Saya akan menyampaikan pernyataan Pak Presiden dan akan saya sampaikan persis seperti yang beliau katakan dan saya tidak membuka tanya jawab. Jadi Presiden mengatakan ‘Pak Bimantoro mengadu domba antara Presiden dengan Wakil Presiden.’ Terima kasih.” Langsung ramai. Sekali-sekalinya saya diminta, eh, tidak dikasih alasan.
Saya dikejar wartawan. Saya bilang tidak membuat tanya jawab. Dikejar tiap hari, saya jawab yang sama.
Wartawan juga nanya, bagaimana waktu baca dekret. Saya bilang ya biasa saja, isinya kan bukan tanggung jawab saya, tidak banyak pikiran (Maklumat Presiden RI pada 23 Juli 2001 tersebut menyatakan pembubaran MPR dan DPR, pembekuan Partai Golkar, dan pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, -ed).
Pembacaan dekret Itu inisiatif Gus Dur?
Waktu itu Gus Dur mengundang banyak orang, diajak ngobrol habis magrib. Seingat saya waktu itu ada Mahfud (Mahfud MD, saat itu Menteri Kehakiman dan HAM), Todung Mulya Lubis (pegiat HAM), Marsilam (Marsilam Simanjuntak, Jaksa Agung). Lalu Gus Dur nanya bagaimana dengan keadaan seperti ini. Ada yang menyarankan begini begitu. Setelah semuanya sudah, langsung Gus Dur bilang, “sudah, saya langsung ke kamar.” Jadi tidak ada diskusi. Lalu Gus Dur masuk, saya di situ nongkrong saja.
Tahu-tahu sudah ada draf untuk ditandatangani Presiden. Gus Dur masuk kamar dan lalu orang-orang boleh masuk dan saya masuk. Gus Dur tanda tangan naskah itu. Awalnya Pak Mujib (Mujib Manan, Sekretaris Presiden) diperintahkan baca. Lalu Pak Mujib bilang, “aku nih enggak tegar, kurang tegar hati saya. Bagaimana kalau Gus Yahya saja?” Lalu saya baca. Sesederhana itu. Saya terima saja, tidak berani bantah. Saya pikir cuma baca saja.
Sebelumnya Gus Dur kasih pengantar, “Saya di sini akan mengantarkan maklumat dan akan disampaikan oleh juru bicara saya, saudara Yahya Cholil Staquf.”
Gus Dur menulis dekret?
Saya tidak tahu Gus Dur didiktekan atau gimana, tapi sudah ada dekretnya.
Apakah Anda tahu bahwa dekret itu serius?
Saya analisis, ini ke mana arahnya. Tapi saya tidak punya akses informasi tentang yang berkembang di luar Istana. Saya berhari-hari ke luar Istana, tidak tahu apa yang berkembang. Akhirnya saya menyerahkan kepada pilihan Gus Dur.
Awalnya ngomong sama Muhaimin (Muhaimin Iskandar) dan Saiful (Saifullah Yusuf), Mereka mengeluhkan pembisik-pembisik yang dianggap memberikan informasi yang tidak akurat. Tapi kalau saya bilang, yaa… siapa yang tidak punya pembisik? Saya saja punya pembisik. Tapi kan yang membuat keputusan Presiden. Jadi masih percaya enggak sama Presiden? Kalau masih percaya, ya, bismillah, kami ikut. Kalau enggak percaya, ya, mau gimana lagi? Saya sudah sampai titik itu. Saya tidak punya pertimbangan alternatif, ya, ikut saja.
Ketika itu Gus Dur ditekan banyak pihak dan dekret yang muncul banyak dianggap berbagai kalangan sebagai perlawanan terakhir. Bagaimana Anda sendiri melihat posisi dekret?
Itu menegaskan posisi moral beliau. Saya tidak mau ditawar mulai dari hal kecil sampai besar. Misalnya wartawan Istana diusulkan dibikinkan ruangan dan makan siang. Kata Gus Dur, kalau kita kasih fasilitas ke mereka, nanti mereka jadi bias, tidak independen, seolah-olah bekerja untuk Istana, PR (humas) Istana. Pada waktu itu banyak yang gerundel, “pelit banget Gus Dur ini.” Ya, mau gimana? Pak Mahfud juga sudah sering cerita, waktu itu ada tawaran Gus Dur jadi Presiden dengan pembagian kekuasaan dan lain sebagainya. Gus Dur menolak karena tidak sesuai dengan Konstitusi.
Dekret itu sebenarnya termasuk posisi moral, secara moral, makanya ditulis di situ membekukan Partai Golkar sampai ada keputusan MA, membekukan DPR/MPR dan mempercepat pemilu. Itu kan sebenarnya diktum yang normal secara hukum. Soal kalah menang, saya lihat, saya melakukan refleksi, pertarungan sudah sejak detik pertama Gus Dur jadi Presiden. Mulai pertarungan meruntuhkan Gus Dur. Kalau saya pikir sekarang, itu pertarungan yang tidak mungkin dimenangkan oleh Gus Dur. [Gus Dur] terlalu lemah, apalagi kemudian selama jadi Presiden dia tidak mau membuat aliansi politik dengan kekuatan strategis. Dengan TNI normatif; polisi normatif.
Saya lihat yang dilakukan oleh Gus Dur hanya dua hal: diplomasi internasional yang agresif, kedua menegaskan posisi moral menurut idealisasi Gus Dur mengenai Presiden. Ya, Presiden harus seperti ini.
Apa pelajaran yang Anda tarik selama bersama Gus Dur?
Sama Gus Dur cuma 10 bulan, mulai dari September sampai Juli. Tapi, saya itu kenal Gus Dur langsung mulai 1987. Saya sudah mendengar dan mengagumi beliau sejak Muktamar Situbondo 1984. Saya merasa bahwa Gus Dur itu mengubah cara berpikir saya tentang Islam. Saya di pesantren belajar kitab klasik. Dulu cara berpikir Islam saya sangat konservatif, kira-kira mirip FPI, lah. Tapi kemudian kenal Gus Dur, banyak belajar dari pandangan beliau. Saya banyak berubah.
Saya tidak sendirian. Orang NU pada generasi saya yang mengenal Gus Dur saya lihat mengalami transformasi yang sama. Apalagi setelah ikut Gus Dur 10 bulan, itu pengalaman intelektual saya.
Saya menemani Presiden kalau tidak ada tamu bisa 4-5 jam setiap hari. Pagi-sore. Pada kesempatan itu Gus Dur bicara banyak hal, ragam pandangan fikih dan kaidah-kaidahnya, novel-novel, para penulis dan perbedaan gayanya, teori-teori politik, strategi perang, intelijen. Sampai klenik juga beliau ceritakan.
Saya mendapatkan banyak masukan dan tidak ada waktu untuk mencerna. Selama itu saya menyadari saya lebih mudah mengingat melalui audio visual dibandingkan membaca.
Saya mencoba memahami, itu masa pendidikan yang luar biasa buat saya. Masa 10 bulan bisa ekuivalen dengan 15 tahun.
Anda generasi ketiga setelah K. H. Bisri Mustofa. Gus Mus (generasi kedua) sekolah agama ke Kairo, tapi generasi anda (dan Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama, saudara kandung) mengambil jurusan umum, sosiologi, di Universitas Gadjah Mada (UGM). Apakah saat itu mengalami transformasi?
Kakek saya dulu mengarahkan supaya belajar bahasa Indonesia, karena kakek rajin menulis semuanya bahasa Jawa, dan nanti akan ada masanya bahasa Jawa kurang populer dan bahasa Indonesia lebih populer. Sampai ayah saya disuruh kuliah di IAIN supaya punya pengalaman bahasa Indonesia. Generasi ayah saya perlu mengembangkannya sehingga saya disekolahkan di sekolah umum.
Sejak kelas 2 SD saya ditaruh di Jogja. Ketika kelas 3 SD saya liburan di Pondok Pesantren Krapyak. Saya merasakan kehidupan pesantren yang berbeda dengan Rembang. Di Rembang, kan, sekolah tradisional. Ketika di Krapyak banyak mahasiswa dan metode pembelajarannya berbeda. Saya ditaruh di sana sama ayah saya ketika SMP. Saya merasakan betul perbedaan itu. Akhirnya saya harus belajar sosiologi supaya bisa memahami kenapa pesantren ini fenomenanya begini, meskipun saya SMA jurusan IPA—karena masalah gengsi saja itu.
Yang saya kejar selama kuliah itu, ya, pemahaman tentang dinamika pesantren di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Awal 80-an Gus Dur banyak sekali menulis tentang pesantren. Itulah hal yang membuat saya lebih dekat dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Sepertinya teori Gus Dur tentang pesantren, beliau menggambarkan pesantren sebagai subkultur. Gus Dur sendiri yang memunculkan wacana itu. Di [Jurnal] Prisma. Di kantor pos ada shopping center. Ada buku-buku yang dijual baik yang baru maupun loak. Saya selalu punya cadangan [uang] buat beli Prisma loakan.
Kiai Cholil mempersiapkan Anda sebagai pengganti di pesantren atau bagaimana?
Mungkin sengaja atau tidak, saya tidak diberi tahu. Tidak ada ungkapan verbal. Kalau disuruh mengaji, iya. Selebihnya enggak ada.
Saya merasakan sendiri, mendapatkan pemahaman itu dengan sendirinya. Ketika saya menggantikan kakek saya, diperlakukan sebagai “gus”, santri-santri tidak ada yang berani. Saya merasa jadi kiai. Itu yang membuat saya jadi terobsesi tentang pesantren.
Anda sekarang salah satu kandidat kuat Ketua Umum PBNU. Jika menang, Anda jadi ketua umum pertama yang sekolahnya umum.
Begitu ya? Mungkin juga. Gus Dur itu sekolahnya umum, lho. Di [Universitas] Baghdad itu jurusannya adab, budaya. Itu juga bukan universitas agama.
Apa yang banyak Anda lakukan di NU?
Memperkenalkan NU ke lingkaran internasional. Saya lihat itu yang dilakukan Gus Dur, Gus Mus. Saya tinggal melanjutkan saja. Jadi di mana ada simpul strategis, itu kita kejar supaya bisa terhubung.
Seiring berjalan, saya bicara tentang konten. Kalau memperkenalkan NU di lingkaran internasional, apa kontennya? Saya kepikiran dunia ini sedang ada di persimpangan jalan, terkait dengan tatanannya, dan NU punya sesuatu untuk disumbangkan untuk jalan keluar. Itu yang saya artikulasikan dan mendapatkan sambutan yang sangat positif.
Saya mulai artikulasi pada 2017. Awalnya standar aja, “NU moderat”.
Karena masalah internasional bukan cuma radikalisme, tapi kemapanan sosial politik sudah berada dalam kerawanan yang luar biasa—terbukti dengan Pilpres Amerika—moderat ini tidak lagi bisa kami jadikan isu utama untuk solusi internasional. Lalu saya mengajukan satu wacana alternatif, bahwa dunia ini membutuhkan konsensus baru terkait dengan nilai peradaban, untuk mengukuhkan, memperkuat tata dunia yang diimunisasi sejak Perang Dunia Kedua.
Supaya peradaban ini ke arah yang lebih baik, perlu dibawa konsesus lagi. Radikalisme, terorisme, dan lain-lain, itu merupakan dunia yang tidak bisa menerima tata dunia pasca-PD II. Maunya balik ke [zaman] dulu. Orang yang mau khilafah ini orang yang mau balik ke tata dunia Perang Dunia Pertama.
Semua pihak yang punya kehendak baik harus bersatu untuk memperjuangkan konsensus yang diperlukan, terkait nilai-nilai luhur yang bisa jadi potensi. Semua orang harus ikut dan terlibat di dalam perjuangan membangun konsensus ini.
Kita lihat [di] pilpres [terjadi] polarisasi. Itu bukan hanya fenomena di Indonesia, tapi terjadi di hampir seluruh dunia, malah menjadi tren dinamika global. Cara berpikir pro-Trump dan anti-Trump ini polarisasi yang berbahaya, orang jadi tidak rasional dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Kalau kita tidak membelokkan tren ini, berbahaya sekali bagi keutuhan peradaban. Semua pihak mau bekerja sama, mengonsolidasikan diri untuk membangun konsensus baru. Ini saya gaungkan sejak 2017.
Walau belum cukup kuat mengokupasi ruang wacana, tapi sudah banyak sambutan yang sangat positif. Misalnya ke Israel (pada 2018, -ed). Saya juga diundang ke London, bertemu presiden Uni Eropa, ke mana-mana. Sampai ada hubungan yang sedemikian rupa dengan [Mike] Pompeo (Secretary of State AS) sampai saya bisa undang dia datang ke Indonesia.
Waktu itu banyak yang protes kenapa undang dia karena orangnya Trump dan [menuduh] macam-macam. Saya jelaskan, saya ini cuma ajak main, kalo enggak setuju, ya, sudah. Main kok dilarang?
Tapi sebetulnya lebih dari itu. Saya sangat tertarik dengan gagasan yang dia kembangkan. Pompeo ini waktu itu buat suatu komisi yang dia namakan The Commission of Right, komisi tentang hak-hak yang paling asasi, hak-hak yang paling tidak boleh dilucuti. Ini merupakan gagasan yang mendiskusikan kembali isi dari Universal Declaration of Human Rights, karena belakangan ada kontroversi baru tentang hak-hak asasi manusia. Misalnya, apakah orientasi seksual itu hak asasi, sedangkan orientasi seksual ini cepat sekali perkembangannya. Tadinya cuma soal transgender, homoseksual, kemudian menjadi biseksual, belakangan ada pedofilia. Mereka mengaku itu hak asasi. Nah, ini menjadi kontroversi, dan di Eropa ini kontroversinya keras sekali.
Nah kita harus membuat konsensus baru soal ini. Apa, sih, hak asasi itu, kemudian orang mulai memaknai hak asasi ini arbitrer.
Kalau kita berpikir tentang konsensus nilai-nilai peradaban, maka konsensus itu harus mengenai hak asasi, karena kita mau bangun peradaban umat manusia yang merdeka dan harmonis berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya komunikasi dengan Pompeo soal ini. Kemudian dia setuju dan dia minta akhir Oktober itu. Saya bilang, saya mengundang Anda karena saya tertarik dengan Anda, bukan karena anda Secretary of State. Jadi kalau waktunya terlalu mepet pemilu, ya enggak apa-apa, tapi mungkin Anda bukan lagi Secretary of State.
Sampai situ menunjukkan bahwa artikulasi tentang visi besar ini diterima. Ini yang perlu saya bilang ke semua orang Indonesia, bahwa referensi di dunia ini bukan dari mana-mana, ini semua berasal dari UUD 1945. Saya yakin para pendiri bangsa mendeklarasikan NKRI ini bukan hanya sebagai negara yang berdaulat, tetapi dengan visi tentang peradaban. Sebetulnya kita ini mendapatkan mandat untuk memperjuangkan peradaban.
Soal isu internasional, kan, surut semenjak Gus Dur. Isu dominan yang saat ini saat ini masih menjadi core NU adalah soal moderat, antiradikalisme. Sepertinya hanya Anda yang fokus bahas soal isu internasional ini. Di akar rumput juga masih fokus isu moderat. Apa ini yang menjadi fokus Anda?
Karena ini soal wacana dan membangkitkan kesadaran, kita bisa pakai beberapa alternatif pendekatan. Dari basis untuk diperjuangkan sebagai sebuah struktur atau sebaliknya. Nah, kalau dimulai dari basis, karena skalanya luas sekali, ini bisa lama menunggunya. Sementara di suprastruktur, di lingkaran pengambil keputusan global, makin lama makin ngawur.
Saya kira tidak ada waktu untuk menunggu. Saya harus mulai bicara dengan lingkaran pembuatan keputusan global ini.
Saya ke sana ke mari datang ke acara untuk seremonial. Tapi sebenarnya yang saya lakukan bukan hanya itu, tetapi masuk ke dalam dinamika politiknya. Di AS saya ketemu dengan senator, baik dari Republik maupun Demokrat, terlepas mereka mau terima atau tidak itu soal nanti.
Dengan Pompeo kita sepakat soal human right. Di Inggris juga saya dalam kontak yang cukup dekat dengan lingkaran pengambil keputusan, di Uni Eropa, dsb. Ini yang saya bawa artikulasinya. Mereka terima. Kalau tidak melakukan sesuatu, nambah morat-marit dunia. Sekarang kalau Indonesia mau masuk dengan pembuka UUD 1945, dunia membutuhkan itu.
Saya bilang, syiah dan sunni di kita tidak ada urusan. Kalau di luar negeri itu keduanya pergulatan politik, di sini tidak ada. Kalau ditanya Indonesia itu Islam apa, Islamnya pembukaan UUD 1945. Saya kira ini kontribusi peradaban yang fundamental dan harus terus diperjuangkan.
Sekarang ini apakah wacana tersebut di NU masih minoritas?
Bukan hanya wacana ini yang tidak dikenal di NU. Banyak wacana penting lain yang tidak cukup dikenal dan diinternalisasi di basis. Misalnya wacana demokrasi, kesetaraan hak. Ini semua masih tanda tanya. Karena keseluruhan struktur NU belum struktur yang terkonsolidasi dan membawa agenda strategis ke basis.
Sekarang ini organisasi di NU entitas yang tidak terhubung satu sama lain. Cabang yang satu bikin apa, yang lain bikin apa, enggak [saling] tahu. Ini bukan soal manajemen, tapi tentang konstruksi organisasi yang memang memerlukan transformasi. Konstruksi NU ini belum berubah sejak 1952. NU ini 1926 organisasi eksklusif, ulama saja. Kemudian 52 parpol [bergabung] dan jadi organisasi massa. Ada untung ruginya. Ruginya NU jadi kehilangan koherensi. Kalau dibuat entitas struktural, enggak mungkin memelihara koherensi. Untungnya ada kaki tangan NU dan dipenuhi kepentingan politik. Dulu enggak terbayang ada NU di Minahasa.
Kalau sekarang konstruksinya seperti parpol. Ada massa, bertumpu pada kepemimpinan populer, bobot kepemimpinan besar. Ketika ini dimasukkan ke kerangka Orde Baru, ini menjadi semacam perangkap kematian pelan-pelan. Untung saja waktu itu ada momentum yang sangat luar biasa terkait dengan asas tunggal. 1972, waktu itu ada wacana keluar dari PPP, kami dukung asas tunggal tapi biarkan kami merdeka.
Sampai sekarang berpikir bagaimana dapat sumber daya dari daerah dan pusat. Ini juga terjadi di parpol sekarang. Parpol punya slot untuk mengakses sumber daya negara, kalau NU mindset-nya seperti itu tapi tidak punya slot. Kalau Jatim, NU-nya besar, bupatinya takut sama NU, sumber daya bisa dimanfaatkan. Sumber daya dari pusat dimanfaatkan, dikoordinasikan dari PBNU, lalu disalurkan ke cabang-cabang, maka cabang bisa jalan. NU punya 521 cabang di Indonesia, pemerintah bisa pakai ini, dan pengusaha juga, buat agenda nasional.
Saya contoh yang dipakai Muslimat NU, yaitu posyandu dari pemerintah, semua dari pemerintah, NU yang mengerjakan, buka lapak. Bisa digarap sektor peternakan dan lain-lain. NU bisa hadir untuk masyarakat, bisa jadikan 520 cabang ini jadi agen. Jadi NU bisa koherensi organisasi. Ini strategi yang saya buat ke depan. Keadaan di layer terbawa ini sudah terlalu tak beraturan.
NU harus melakukan repositioning politik. Harus berhenti menjadi kompetitor, menjadi pihak dalam kompetisi politik. Biar kami bisa menjadi jembatan di antara perbedaan dan menyelamatkan warga NU dari polarisasi. Akibat dalam kompetisi politik, di dalam NU terjadi pertikaian. Di Madura itu ada trademark mereka agamanya NU, sekarang mereka jadi anti PBNU. Ini perlu segera diperbaiki. Saya prihatin dan saya ingin nantinya tidak ada capres atau cawapres dari PBNU. Kiai Ma’ruf diusir. Itu Rais Aam, lho.
Sentralisasi dan struktur partai politik itu, kan, tidak sesuai dengan NU.
Saya terbukti bisa mengubah Ansor. Saya yang buat strateginya, yang mengeksekusi Nusron Wahid. Yang kami butuhkan strategi tepat dan komitmen betul. Makanya saya hormat kepada Nusron mau pegang komitmen.
Saya bikin metafora: Menuntaskan masalah di NU itu laksana meluruskan benang basah. Meluruskan benang basah itu bukan hal yang mustahil, itu bisa. Caranya di atas ada cantolan, di bawah dikasih bandul. Bandul itu aspirasi basis. Paku untuk cantolan enggak usah bagus, bekas saja.

Anda komunikasi ini semua ke pimpinan cabang?
Ini cepat banget. Saya bicara awal September, dan sekarang sudah lebih dari 400 pimpinan cabang setuju. Bisa dibayangkan. Mereka bukan orang bodoh, apes-apesnya mereka kepala sekolah. Mereka banyak jadi pejabat, cepat sekali nangkapnya.
Belum ada bentuk dukungan [untuk maju sebagai Ketua Umum PBNU] dalam bentuk SK. Sekarang PCNU bikin SK, itu gimana, masak kita bisa cegah?
Apa yang dilakukan selama konsolidasi?
Biasanya saya bicara sebentar. Ya, jelaskan program. Lalu cabang ngomong. Ada juga yang nanya soal Israel. Soal itu saya jawab gampang, “Kalian sudah kenal saya sekian lama, jadi tahu saya seperti apa.” Lalu yang kedua itu tadi, selain ke Israel saya juga ke tempat lain, lihat di Youtube saya bagaimana.
Ini antara NU dan PKB juga posisinya ada yang jabat di NU lalu ke PKB, begitu juga sebaliknya. Mereka sudah mengerti saya sejak zaman dulu.
Tadi Anda mengatakan diberi amplop, buat apa?
Saya kaya mubalig gitu. Mubalig, kan, kalau habis pengajian kayak gitu. Terima kasih. Tidak bisa ditolak juga. Ini donasi untuk kandidat (kelakar). Kadang-kadang ada cabang yang dekat sama bupati, bupati ngamplopin juga. Jadi lumayan.
Tapi, ya, ini tradisi, Sekarang saya masih bisa enak, karena saya belum ketua umum. Tapi nanti harus di-manage supaya baik.
Anda sudah mendatangi berapa cabang?
Jatim, Jateng, Banten, NTT separuh, Bali, Sumut separuh, Sulawesi semua, Kalimantan Timur sudah, Sumbar sudah. Yang lain belum saya datangi tapi mereka sudah ada yang menyatakan dukungan.
Berapa targetnya?
574.
Ketika konsolidasi apakah Anda sudah menjelaskan program?
Itu yang saya bilang tadi. Yang masuk ke cabang itu soal internasional. Mereka itu merasa bangga. Itu cukup, lah. Ya, sesuai sama tema tahun ini. Cabang juga pasrah saja, ikut saja.
Apakah ketika Anda jadi Ketum PBNU akan mencalonkan diri sebagai Presiden?
Ini absolut: Enggak bakal saya nyalon. Bukan cuma saya, saya akan perintahkan ke seluruh jajaran PBNU untuk tidak ada yang nyapres dan nyawapres. Kalau ada yang mau jadi capres dan cawapres, sebaiknya jangan ikut PBNU. Tapi saya bisa buat skema agar teman-teman bisa punya peluang jadi menteri. Tapi kalau capres-cawapres, enggak usah.
Saya sudah pernah jadi presiden dan itu enggak enak. Jadi, [dalam] konferensi OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di Qatar (tahun 2000, -ed), saya tidak bisa masuk ruang sidang. Pas sidang terakhir jam 10 malam, ada break sebentar, upacara penutupan. Gus Dur keluar dari ruang sidang, tiba-tiba minta ada yang menggantikan, “saya mau tidur saja… udah biar Gus Yahya aja yang gantiin.” Semua orang enggak ada yang berani bantah. Saya melongo juga. Saya masuk dengan Pak Alwi (Menlu). Di dalam ada dua kursi, satu untuk Menlu dan satu untuk Presiden. Saya duduk di kursi Presiden.
Di belakang podium ada televisi real time. Waktu [konferensi] berlangsung, kamera shoot semua. Sampai ke saya, lewat sedikit, berhenti, dan balik ke saya, Habis itu dia close up. Lalu saya bingung mau gimana, senyum, cemberut, atau gimana? Terus nametag saya di-shoot.
Saya sudah pernah jadi Presiden, enggak enak.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino