tirto.id - Ada banyak cara yang dipakai oleh pemerintah untuk melawan kelompok yang enggan memberikan suaranya dalam pemilihan umum—biasa disebut golput atau golongan putih. Pada masa Orde Baru, yang dilakukan adalah mengolok-olok hingga menahan.
"Seperti bau kentut. Rupanya tidak ada tetapi baunya ada," sindir Ali Murtopo, asisten pribadi Soeharto, merespons golput yang muncul pada Pemilu 1971.
Sementara Menteri Penerangan Budiardjo tak kalah sinis: "lha itu, kan, orang-orangnya sama. Yang itu-itu juga."
Penahanan dilakukan terhadap rombongan golput yang sedang berjalan kaki dari gedung Balai Budaya menuju Bapilu Golkar di Jalan Tanah Abang III. Alasan penahanan karena "mereka menyebarkan pamflet." Pada 9 Juni 1971, gedung Balai Budaya, tempat berkumpul pemuda golput untuk berdiskusi, dijaga polisi.
Rezim pun berganti, tapi respons dan persepsi mereka terhadap golput tak banyak berubah. Di era Joko Widodo, golput dipandang sebagai "ancaman faktual". Ini tertulis dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019 (PDF, hlm. 31).
Ancaman itu dianggap perlu dikikis. Caranya, seperti dikutip lengkap dari instruksi, adalah dengan "sosialisasi gerakan anti golput dalam menyelenggarakan pemilihan umum melalui media sosial, seminar, iklan layanan masyarakat, ceramah, dan dialog interaktif/diskusi."
Penanggung jawab itu adalah Sekjen Dewan Ketahanan Nasional dan Kemenkopolhukam, dengan instansi terkait seperti Kemendagri hingga Kementerian Agama.
Karena Tak Puas
Tak ada sebab tanpa akibat; tak ada pula asap tanpa api. Begitu pun dengan golput. Ia ada karena faktor tertentu, yang menurut Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, adalah karena masyarakat kecewa terhadap partai.
"Parpol harus koreksi diri. Akibat UU Parpol yang ada, demokrasi dan pemilu di Indonesia hanya didominasi oleh parpol. Mereka membikin sistem bahwa untuk jadi pejabat dan presiden harus lewat parpol. Akibatnya enggak bisa ada presiden jalur independen," kata Asfin kepada reporter Tirto, Rabu (30/1/2019).
Pendapat serupa juga sempat diungkapkan oleh Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)—serikat yang menyatakan akan golput pada pemilu nanti. Katanya, orang golput karena kecewa dengan elite.
Ia menilai janji-janji Jokowi banyak yang tidak terealisasi, sedangkan Prabowo, kata Nining, "terlibat pelanggaran HAM masa lalu. Jadi kedua-duanya, dalam pandangan kami, hanya berambisi berkuasa."
Asfin dan Nining tak asal bicara. Relasi golput dan ketidakpuasan terhadap penyelenggara negara punya landasan ilmiah, atau setidaknya pernah ditulis dengan standar akademik.
Sri Yuniarti dalam artikel yang tayang di Jurnal Penelitian Politik LIPI (Vol 6, No 1, 2009), menulis orang golput pada masa Orde Baru lebih ke soal politik, bahwa memilih tak memilih presidennya tetap Soeharto. Sementara pada masa reformasi lebih kepada "rasa kecewa masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik yang ada, baik parlemen maupun partai politik." (hlm. 32).
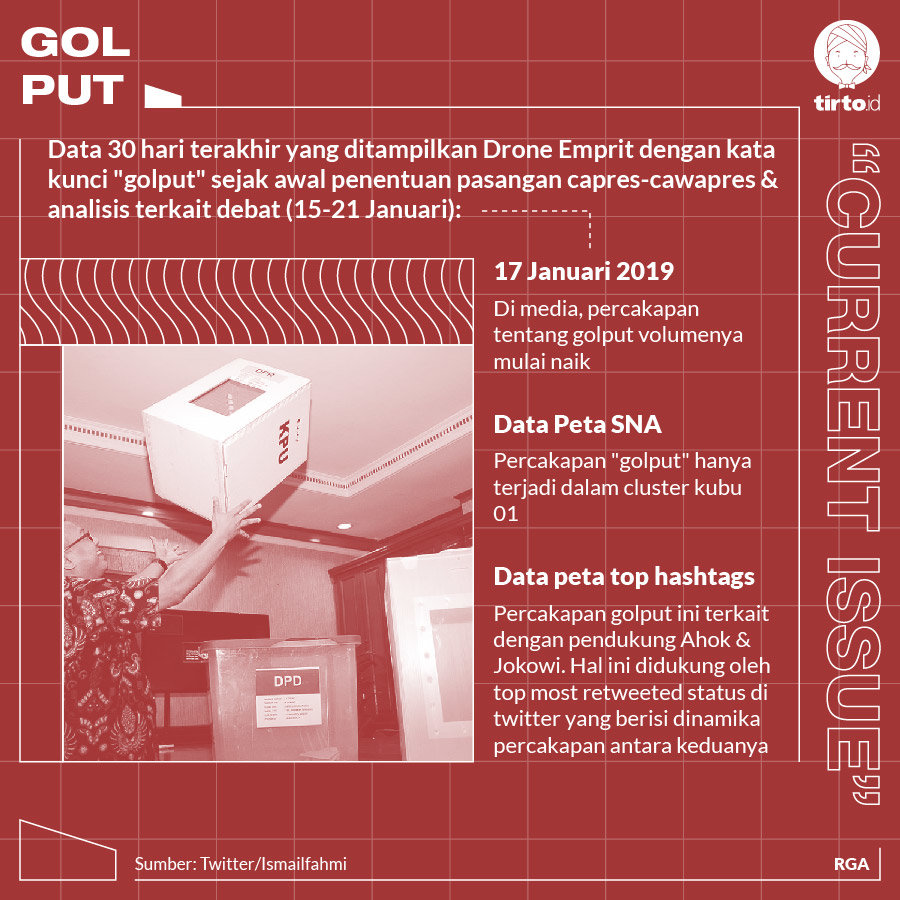
"Penilaian kinerja atas lembaga eksekutif dan yudikatif yang dianggap buruk juga jadi faktor pendorong masyarakat untuk tidak berpartisipasi."
Masa Transisi
Bagi Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong, menilai instruksi tersebut sudah tepat. Dengan dalil "Indonesia sedang masa transisi demokrasi", ia merasa eksekutif memang perlu mendorong orang memilih. Menurutnya ada relasi positif antara minimnya angka golput dengan kualitas demokrasi.
"Kita yang sedang masa transisi demokrasi perlu mendorong agar semua orang memilih, karena Undang-Undang sudah memberikan hak bagi masyarakat untuk memilih, berpartisipasi dalam pemilu," ujar Usman kepada reporter Tirto.
Usman juga mengingatkan, meski sebesar apa pun angka golput nanti, toh tetap ada presiden terpilih hingga periode 2024.
"Jadi enggak logis kalau tim kampanye membiarkan banyak golput," pungkasnya.
Penulis: Rio Apinino
Editor: Abdul Aziz
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id


































