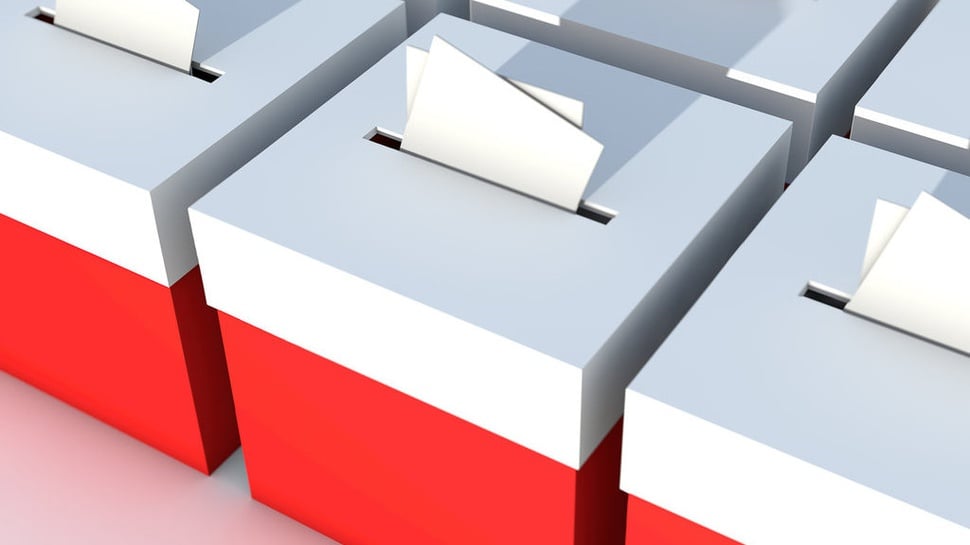tirto.id - Saat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2019 sudah diumumkan, muncul sejumlah ungkapan kekecewaan. Alasannya, mereka tidak cocok dengan dua pasang capres dan cawapres yang akan bertarung di arena Pilpres 2019. Kekecewaan itu beberapa di antaranya memicu kembali gagasan mengenai golput.
Dari kubu koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, misalnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief terus menyinggung soal "mahar politik" yang dinilai menggagalkan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres. Kendati mengatakan bahwa partainya tetap berkomitmen memenangkan Prabowo-Sandiaga, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai seruan golput, namun rentetan pernyataan Andi Arief yang dinyatakan melalui akun Twitter itu tak urung menjadi objek percakapan, perdebatan dan tentu saja pemberitaan (baca: Twit Andi Arief Bukti Demokrat Setengah Hati Dukung Prabowo-Sandi?).
Nada kecewa juga tampak dari para pendukung Jokowi karena pemilihan Ma'ruf Amien sebagai cawapres. Ada yang menganggap Ma’ruf terlalu sepuh, ada pula yang melihat rekam jejak Ma’ruf yang dinilai punya peran dalam meruyaknya perilaku intoleran dan persekusi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Percakapan tentang golongan putih (golput) kemudian menyeruak dari sana.
Istilah golput baru muncul menjelang Pemilu yang dihelat pada 5 Juli 1971. Pemilu itu adalah pesta demokrasi pertama di era Orde Baru. Kontestan partai politik jauh lebih sedikit dari Pemilu 1955. Sejumlah parpol dibubarkan, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Ada delapan parpol lama, satu parpol baru, dan satu organisasi peserta Pemilu, yang ikut Pemilu 1971. Parpol lama antara lain Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI)m Persatuan Tarbiah Islamiah (Perti), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Sementara parpol baru adalah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Muncul juga Golongan Karya (Golkar) untuk pertama kalinya sebagai peserta Pemilu.
Ungkapan Protes
Sekarang golput cenderung diartikan secara plastis dan lentur. Kadang mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan-alasan apolitis, seperti memilih berlibur, dipersamakan dengan mereka yang dengan kesadaran politis tertentu memilih tidak datang ke TPS atau datang ke TPS tapi merusak kertas suara.
Pada kemunculan pertamanya, istilah golput relatif merujuk sesuatu yang lebih spesifik. Menurut Ekspres edisi 14 Juni 1971, golput adalah sebuah gerakan untuk datang ke kotak suara dan menusuk kertas putih di sekitar tanda gambar, bukan gambarnya. Hal itu akan mengakibatkan suaranya jadi tidak sah, dan tak dihitung. Jadi, para pemilih tetap pergi ke bilik suara. Tidak pasif.
Gerakan ini dikumandangkan para pemuda dan mahasiswa yang memprotes penyelenggaraan Pemilu 1971. Mereka mendeklarasikan gerakan ini pada awal Juni 1971, sebulan sebelum pemilu pertama Orba itu. Kelompok pemuda ini juga membuat semacam simbol golput bikinan seniman Balai Budaya.
“Berbentuk segilima, mirip dengan simbol AURI, IPKI, dan Golkar. Namun, di tengahnya mirip sebuah lukisan abstrak tanpa coretan apa-apa. Cuma warna putih polos,” tulis Ekspres, 14 Juni 1971.
Mereka lantas memasang pamflet simbol tersebut di sejumlah titik di Jakarta. Sontak aksi ini menimbulkan masalah pada pelaksanaan Pemilu 1971.
“Di beberapa tempat di wilayah DCI (Daerah Chusus Ibukota) Jakarta antara lain di Kebayoran, Cempaka Putih, Jalan Thamrin, dan lain-lain yang isinya antara lain tidak sependapat dengan tertib penyelenggaraan Pemilu 1971,” tulis Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Jakarta Raya dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 di D.C.I Djakarta.
Ekspres, 14 Juni 1971, menulis, gerakan golput muncul setelah aksi-aksi gagal para pemuda, seperti Mahasiswa Menggugat (MM), Komite Anti Korupsi (KAK), Wartawan Generasi Muda, dan Komite Penegak Kedaulatan Rakyat (KPKR) pada 1970.
Rezim Orde Baru tak membiarkannya. Komentar-komentar sinis mereka muncul. “Lha itu, kan, orang-orangnya sama. Yang itu-itu juga. Itu, lho, seniman Balai Budaya, tempat yang selama ini digunakan untuk menentang pemerintah. Mereka adalah eks KAK atau MM,” kata Menteri Penerangan Budiardjo, seperti dikutip dari Ekspres, 14 Juni 1971.
“Seperti bau kentut saja. Rupanya tidak ada tetapi baunya ada,” kata Ali Murtopo, yang saat itu menjadi asisten pribadi Presiden Soeharto, dalam majalah yang sama.
Tindakan lebih jauh pun diambil rezim Orba. Menurut A. Samsuddin dan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia dalam Pemilihan Umum 1971; Seri Berita dan Pendapat, rombongan golput yang sedang berjalan kaki dari gedung Balai Budaya menuju Bapilu Golkar di Jalan Tanah Abang III dicokok aparat. Kejadian itu persis di depan gedung Kodim.
Suratkabar Kompas edisi 16 Juni 1971 menyebut alasan penahanan itu -- dengan mengutip pernyataan Kodim -- karena mereka sudah menyebarkan pamflet. Usaha kelompok golput untuk mengadakan diskusi bertajuk “Semangat Orde Baru” di Balai Budaya pun dilarang. Laporan Tempo edisi 19 Juni 1971 menyebut, larangan itu dikeluarkan Komdak Metro Jaya. Pada 9 Juni 1971, gedung tempat berkumpul 150 pemuda yang menyokong gerakan golput itu pun dijaga polisi.
Ekspres edisi14 Juni 1971 menulis, ajakan menjadi penonton atau tidak memilih dalam Pemilu 1971 akan ditindak oleh pemerintah. Ancaman hukumannya lima tahun kurungan.
Badan Koordinasi Intelijen (Bakin) menyatakan gerakan golput sebagai masalah kecil. Dalam Ekspres, 14 Juni 1971, Bakin menyebut, mereka menggunakan versi lama, dengan pelaku yang baru. Bakin mengendus, gerakan-gerakan yang muncul berasal dari rasa tidak puas yang berasal dari gerakan bawah tanah untuk mendiskreditkan pemerintah.
“Sekelompok pemuda-pemuda yang sekarang menonjol itu sebenarnya siap dijadikan korban oleh suatu kegiatan yang berpangkalan di Jawa Tengah. Dari sinilah semuanya diatur, dan dari situ pulalah pendalangan direncanakan,” sebut Bakin dalam Ekspres, 14 Juni 1971.
Aktor di Balik Golput
Tempo edisi 19 Juni 1971 menulis, deklarasi untuk “menjadi penonton yang baik” kala Pemilu 1971 sudah dimulai sejak akhir Maret dan awal April 1971 oleh Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), Max Wajong. Namun, Max belum menyebut gerakan itu sebagai golongan putih.
Istilah golongan putih muncul beberapa waktu kemudian, melalui tulisan Imam Walujo Sumali, bekas Ketua Ikatan Mahasiswa Kebayoran. Tempo edisi19 Juni1971 melaporkan, Imam menulis artikel “Partai Kesebelas untuk Generasi Muda” di harian KAMI edisi 12 Mei 1971. Tulisan itu dibuat setelah dua-tiga kali berdiskusi dengan tokoh-tokoh parpol dan Golkar. Inti tulisan itu adalah gagasan memunculkan partai kesebelas, selain sembilan parpol dan satu Golkar yang akan bertarung di Pemilu 1971.
“Partai kesebelas adalah satu partai politik yang ditujukan untuk menampung suara dari generasi muda serta orang-orang siapa saja yang tidak mau memilih parpol-parpol dan Golkar yang ada sekarang,” tulis Tempo, 19 Juni 1971.
Partai tersebut dinamakan Imam sebagai Partai Putih, dengan gambar putih polos. Di dalam tulisannya itu, Imam pun memberikan anjuran bagi yang memilih Partai Putih dalam Pemilu 1971 agar menusuk bagian putih yang ada di sela-sela atau di antara kesepuluh tanda gambar parpol dan Golkar. Bisa dikatakan, pencetus istilah golongan putih adalah Imam.
Imam mengaku pesimistis melihat Pemilu 1971. Dalam laporan yang ditulis Ekspres edisi14 Juni 1971, Imam mengatakan bahwa Golkar sama saja dengan parpol-parpol lainnya: memuakkan.
Dalam edisi 19 Juni 1971, Tempo melaporkan gerakan ini menjadi membesar. Sekelompok pemuda, seperti Arief Budiman, Imam Walujo, Husin Umar, Marsilam Simandjuntak, Asmara Nababan, dan Julius Usman, yang menamakan diri mereka Kelompok Oposisi, mulai bergerak. Lantas, Partai Putih, yang tanpa tanda gambar bermetamorfosis menjadi golongan putih yang memiliki simbol gambar segilima hitam di atas dasar putih polos.
Tokoh sentral golput adalah Arief Budiman, yang disebut Goenawan Mohamad sebagai “tukang protes profesional”. Menurut Goenawan, dalam tulisannya “Teater Arief Budiman; Sebuah Kritik” dalam Tempo edisi19 Juni 1971, meski sudah berusia 30 tahun, Arief masih ada dalam lingkaran Mahasiswa Menggugat dan Komite Anti Korupsi, aktif pula di Wartawan Generasi Muda. Dia pun menjadi salah seorang tokoh kunci golput. Kala itu, Arief sudah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Dia memilih tak masuk ke dalam kekuasaan, seperti kawan-kawan lainnya sesama aktivis 1966.
“Dia bukan orator dan bukan agitator. Tapi di samping puluhan tulisannya di suratkabar yang rata-rata memancing polemik, dia bisa bergairah menulis petisi-petisi, pamflet-pamflet, dan poster-poster serta ikut dalam rombongan-rombongan demonstran,” tulis Goenawan dalam Tempo edisi19 Juni 1971.
Tampaknya, aksi Arief dalam golput ini terinspirasi dari pertemuannya dengan Presiden Soeharto dalam aksi antikorupsi pada 1970. Dalam Tempo edisi19 Juni 1971, Arief pernah menanyakan kepada Soeharto soal apakah dibenarkan jika ada golongan yang tidak mau ikut memilih dalam Pemilu. Soeharto lantas menjawab, “Boleh, asalkan bertindak melalui saluran hukum.”
Arief sendiri mengemukakan alasannya. Menurut dia, seperti dikutip dari buku Kebebasan, Negara, Pembangunan; Kumpulan Tulisan 1965-2005, dengan membatasi jumlah parpol, pemerintah sudah melanggar asas demokrasi yang sangat mendasar, yakni kemerdekaan berserikat dan berpolitik.
“Apa gunanya pemilu kalau orang tak bebas berserikat dan berpolitik?” tulis Arief.
Belum lagi soal intervensi pemerintah. Salah satu hal yang dia kritik adalah masalah calon pemimpin PNI yang diseleksi pemerintah terlebih dahulu sebelum partai itu menentukan pemimpinnya. Selain itu, pemimpin Parmusi langsung ditunjuk oleh Soeharto. Arief juga menyoroti pembentukan Golkar, sebagai sebuah partai buatan pemerintah.
“Pegawai negeri (dan keluarganya) dipaksa masuk Golkar. Kalau tidak mereka akan dipecat dengan tuduhan tidak loyal kepada pemerintah,” tulis Arief.
Meski demikian, Goenawan Mohamad dalam Tempo, 19 Juni 1971 mengkritik gerakan Arief dan kawan-kawannya ini. Dia menyebut, gerakan itu seperti mengulang-ulang saja. Gerakannya merupakan replika dari gerakan sebelumnya.
“Ia (Arief Budiman) kini ibarat Franco Nero dalam film-film Western Italia: jagoan yang itu-itu juga, dengan cerita yang itu-itu juga dan dengan teknik yang itu-itu juga,” tulis Goenawan.

Hantu Pemilu
Namun gerakan ini tidak terlalu berhasil menjadi gelombang besar kekuatan politik. Intervensi pemerintah membuat masyarakat takut untuk tidak memilih. Menurut Sri Yanuarti dalam tulisannya “Golput dan Pemilu di Indonesia” di Jurnal Penelitian Politik Volume 6, Nomor 1, 2009, jumlah Golput pada Pemilu 1971 hanya sebesar 6,67 persen.
Kendati demikian, prediksi Menteri Penerangan Budiardjo pada 1971 keliru. Dalam Tempo, 10 April 1971, dia berujar bahwa tanpa dilarang pun Golput akan habis dengan sendirinya. Namun, nyatanya, meski tak ada gerakan membolisasi, dari Pemilu ke Pemilu jumlah golput kian meningkat.
Sri mencatat, pada Pemilu 1977 jumlahnya malah naik menjadi 8,40 persen. Bahkan setelah reformasi jumlah golput makin meningkat. Pada Pemilu 1999, angka Golput mencapai 10,4 persen. Pada Pemilu 2009, golput legislatif mencapai 29,01 persen. Golput pada Pilpres 2009 mencapai 27,77 persen.
Seperti sudah disebutkan sebelumnya, pengertian golput sekarang terhitung lebih lentur dibandingkan saat pertama kali muncul dalam Pemilu 1971. Angka-angka di atas pun menggunakan pengertian yang lentur itu tadi, yang menyamaratakan warga yang tidak memilih dengan kesadaran politis maupun yang bukan.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Luky Sandra Amalia mengatakan yang perlu diperjelas terlebih dulu adalah konsep golput. Mereka yang memilih golput beda dengan pemilih yang tak menggunakan hak suara. Mereka yang lebih memilih libur alih-alih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) misalnya, tak bisa disebut golput.
"Pemilih yang tidak memilih itu tidak sama dengan golput. Filosofinya beda. Sejarah golput dasarnya ideologi," ujar Luky kepada Tirto.
Apa pun pengertiannya, menurunnya partisipasi dalam pemilu ini menjadi semacam hantu bagi peserta pemilu. Meski dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasar 19 disebutkan memilih itu hak, bukan kewajiban, tetapi mengajak orang lain untuk golput atau tidak memilih bisa diancam hukuman pidana.
Editor: Ivan Aulia Ahsan