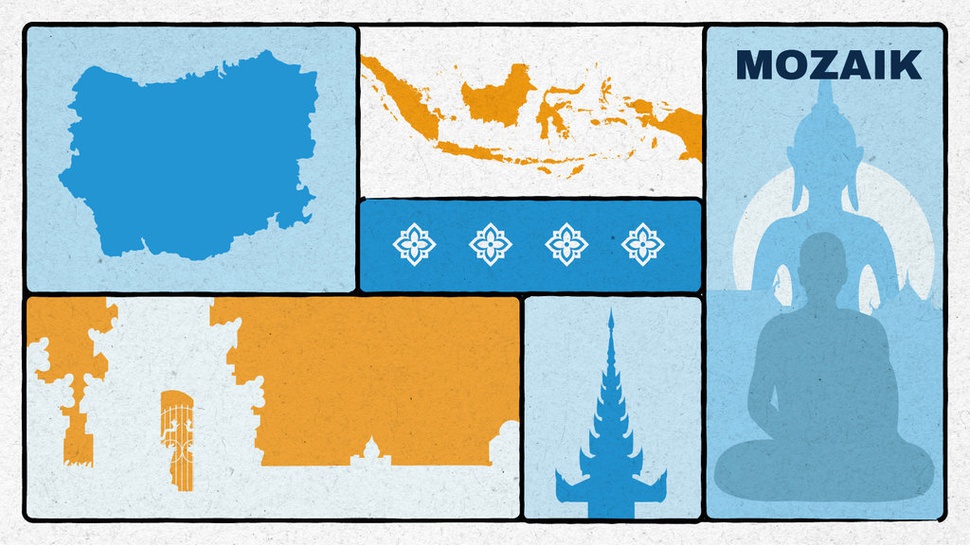tirto.id - Candi Borobudur atau Candi Prambanan mrupakan monumen peradaban Hindu-Buddha paling mewah di Pulau Jawa. Keduanya telah lama dinominasikan sebagai monumen keagamaan Hindu dan Buddha terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Agus Aris Munandar dalam "Borobudur Temple: The Interchange of Humanity Values and Ancient Architecture Development in Southeast Asia" (2018) menyebut bahwa candi-candi masa awal di pedalaman Jawa Tengah, di antara Lembah Kedu dan Prambanan, merupakan perwujudan dari puncak seni arsitektur Gupta yang terkenal.
Coraknya begitu kuat memengaruhi arsitektur bangunan suci di daerah Asia Tenggara daratan, termasuk candi-candi di Khmer seperti Angkor Wat.
Di sisi lain, tinggalan arkeologis periode Hindu-Buddha yang cenderung lebih tua dibandingkan dengan temuan-temuan di Kedu atau Prambanan justru terdapat di Jawa Tengah bagian pesisir. Walau tidak monumental seperti Prambanan atau Borobudur, keberadaannya sejak lama telah dijadikan tengara titik nol perkembangan budaya Hindu-Buddha di kalangan masyarakat berpenutur bahasa Jawa.
Anasir tinggalannya yang arkais ditandai dengan persimpangan antara bentuk-bentuk "prasejarah" dan suasana India yang uniknya malah lebih kental dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. Sejauh ditemukannya tinggalan arkeologi oleh para arkeolog hingga kini, area sebaran tinggalan masa awal Hindu-Buddha paling awal di Jawa Tengah ini berpusat di daerah antara Batang dan Semarang.
Dapunta Selendra, Leluhur Dinasti Śailendra di Batang?
Satu dari beberapa sumber tertulis tertua di alam kebudayaan Jawa Kuno yang paling misterius adalan Prasasti Sojomerto. Batu beraksara ini ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Raban, Kabupaten Batang.
Dibandingkan dengan prasasti-prasasti lain di Jawa Tengah, Boechari dalam "Preliminary Report on the Discovery of an Old Malay Inscription at Sojomerto" (1966) mendedah beberapa gejala anomali dari prasasti ini.
Dari segi aksara, misalnya, Boechari menyebut ada aksara pada Prasasti Sojomerto yang mirip dengan aksara Pallawa seperti pada prasasti-prasasti zaman Kerajaan Kutai dan Tārumānagāra, sedangkan aksara yang lain pada prasasti ini justru mirip dengan tipe aksara Śrīwijāya. Maka itu, walau Prasasti Sojomerto tidak menyajikan tarikh, secara paleografis Boechari menentukan usia prasasti ini pada abad ke-7 M.
Unsur bahasa dari prasasti ini rupanya tidak kalah "aneh". Setelah Boechari beserta dua asistennya—A.S. Wibowo dan Ayatrohaedi—membaca Prasasti Sojomerto, segera mereka sadari bahwa prasasti ini berbahasa Melayu Kuno.
Richadiana Kartakusuma dalam "Persebaran Prasasti-Prasasti berbahasa Malayu Kuna di Pulau Jawa" (1999), mengomentari beberapa aspek yang liyan dalam bahasa Melayu Kuno pada Prasasti Sojomerto dibandingkan dengan prasasti berbahasa Melayu Kuno lainnya di Pulau Jawa.
Bagi Kartakusuma, biasanya prasasti-prasasti berbahasa Melayu Kuno di Pulau Jawa sedikit banyak mendapat pengaruh diksi atau bahkan morfologi bahasa Jawa atau Sunda Kuno. Kasus demikian misalnya terjadi pada prasasti-prasasti Melayu Kuno dari abad ke-9-10 M, seperti Prasasti Dieng dari Wonosobo, Prasasti Sang Hyang Wintang dari Temanggung atau Prasasti Kebon Kopi II dari Bogor.
Dalam kasus bahasa Melayu Kuno pada Prasasti Sojomerto, menurut Kartakusuma sama sekali bersih dari pengaruh-pengaruh bahasa lokal Jawa. Dari hasil pengamatan akan fenomena aksara dan kebahasaan ini, Boechari dan Kartakusuma sepakat untuk mendudukan Prasasti Sojomerto sebagai sumber tertulis yang mungkin sekali memiliki keterkaitan langsung dengan Śrīwijāya.
Indikasi-indikasi aspek ekstrinsik Prasasti Sojomerto ini selanjutnya disangkutpautkan dengan isi prasasti tersebut oleh Boechari. Menurut hasil terjemahannya, Boechari mengatakan bahwa prasasti ini menyinggung soal keberadaan keluarga yang dikepalai oleh seseorang bernama Dapunta Selendra.
Sosok ini menarik apabila dikaitkan dengan kajian sejarah kuno Indonesia, karena dua unsur namanya mengindikasikan dua hal. Pertama, gelar Dapunta yang tersemat pada tokoh tersebut identik dengan gelar datuk Śrīwijāya yang disebut di Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo, yakni Dapunta Hyang.
Kedua, nama Selendra mungkin sekali ejaan asli Indonesia untuk kata Sanskerta “Sailendra” yang nantinya menjadi nama dinasti periode berikutnya. Atas dasar hal itu, Boechari beranggapan bahwa mungkin sekali Dapunta Selendra merupakan seseorang dari Śrīwijāya yang menjadi leluhur dari raja-raja Śailendra di Jawa.
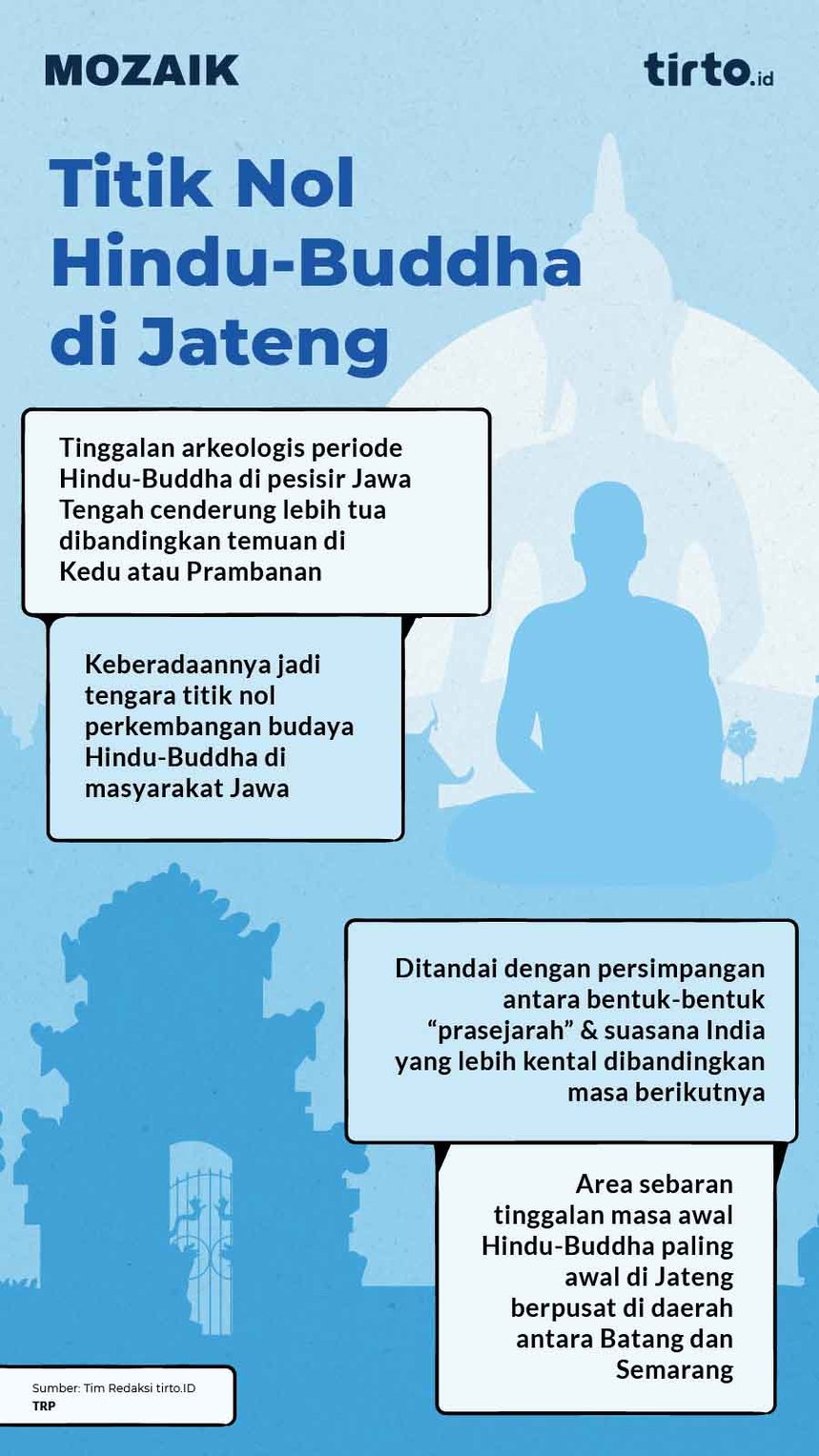
Arca-Arca di Luar kebiasaan, Candi Prototipe
Selain temuan Prasasti Sojomerto, aspek ikonografis arca-arca di pesisir utara Jawa Tengah juga terbilang unik. Hal ini misalnya dari temuan arca-arca Ganesha yang ditemukan di tiga kabupaten, yakni Pekalongan, Semarang, dan Batang.
Seperti disebut oleh Ashar Murdihastomo dalam "Ganesha tanpa Mahkota dalam Pusaran Religi Masyarakat Jawa Kuna: Sebuah Kajian Permulaan" (2020) dan Garin Pharmasetiawan serta A.A. Munandar dalam "Liminalitas Air: Pola Persebaran Pathirthān di Sisi Utara hingga Tenggara Gunung Ungaran" (2023), arca-arca ini dibuat dengan pola yang amat sederhana—cenderung mirip dengan arca-arca periode prasejarah. Secara lebih spesifik, umumnya arca-arca Ganesha dari ketiga daerah ini dibuat dengan tanpa mengenakan mahkota.
Murdihastomo menduga hal ini terkait dengan ide mitologi yang secara spesifik merujuk pada versi babon Ramayana yang berkembang di India, di mana minim kemungkinan pengetahuan akan mitologi ini tersebar luas di Jawa.
Ciri keperintisan kebudayaan Hindu-Buddha di daerah pesisir utara Jawa Tengah juga dijumpai pada gaya bangunan yang berkembang. Hal ini menurut Yohan B. Hutagalung bisa diamati pada Candi Ngempon, seperti disinggung dalam skripsinya Telaah Arsitektur dan Kronologis Percandian Ngempon, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (2018).
Kompleks percandian yang dekat dengan sumber air panas di kaki Gunung Ungaran ini dibangun dalam rangka pemujaan terhadap Dewa Śiwa, dan secara umum memiliki beberapa kemiripan dengan Candi Prambanan di Yogyakarta.
Kemiripan itu misalnya tampak pada penataan ruang bangunan yang terdiri dari candi induk dan candi perwara. Sebagaimana Candi Prambanan, di Candi Ngempon dijumpai satu bangunan induk tempat bersemayamnya Dewa Śiwa dengan dua bangunan lain yang mengapitnya sebagai tempat persemayaman Dewa Wisnu dan Brahma.
Ketiga candi tempat bersemayamnya dewa trimurti itu dilengkapi pula dengan masing-masing tiga bangunan tambahan di depannya yang isinya adalah wahana (hewan tunggangan) dewa-dewa tersebut. Kemiripan-kemiripan ini belum termasuk beberapa aspek ornamen pada Candi Ngempon yang samar-samar mirip dengan Candi Prambanan.
Tanda-tanda kemiripan ini bagi Hutagalung mengindikasikan pengimitasian Candi Ngempon yang mungkin sekali dibangun abad ke-8 oleh arsitek Candi Prambanan di sekitar abad ke-9. Dengan kata lain, Candi Ngempon merupakan purwarupa dari Candi Prambanan—yang tentu secara ukuran jauh lebih kecil dari "tiruan"-nya.
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Irfan Teguh Pribadi