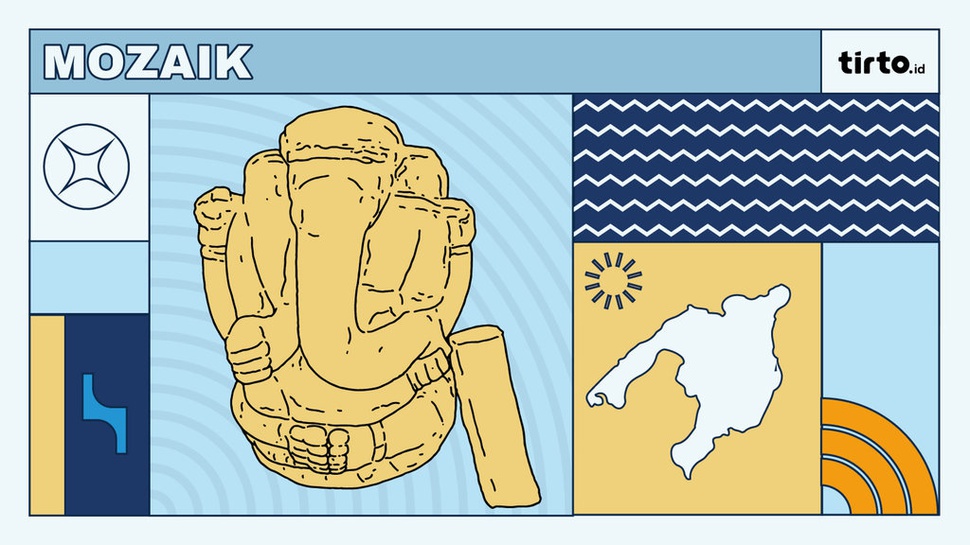tirto.id - Ujung Kulon adalah salah satu taman nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Mula-mula Frederick Wilhelm Junghuhn--ahli botani asal Jerman yang dikenal atas studinya yang mendalam terhadap varietas flora dan fauna di Ujung Kulon--membuat laporan perjalanan serta pengamatannya yang terbit pada tahun 1846 dan langsung menjadi perhatian banyak ahli lain di Eropa.
Setelah itu, para saintis Eropa dengan berbagai bidang studi mulai banyak berdatangan ke Ujung Kulon, salah satunya Sijfert Hendrik Koorders yang giat mempromosikan konservasi populasi badak.
Atas keprihatinannya terhadap kondisi perburuan hewan eksotik di Ujung Kulon, Koorders lantas menginisiasi pendirian Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) pada tahun 1912 dan berupaya mengadvokasi penetapan Ujung Kulon sebagai cagar alam.
Upaya Koorders baru membuahkan hasil pda 1921. Wilayah Ujung Kulon (luas: 37.599 ha) dan Pulau Panaitan (luas: 17.500 ha) dijadikan monumen alam (Natuurmonumenten) berdasarkan Besluit van den Gouverneur-General van Nederlandsch-Indië van 16 November 1921, No. 60, Staatsblad 1921. No 683.
Di luar sejarah perkembangan konservasi alam Ujung Kulon yang melegenda, ada kisah lain dari daerah ini, yakni sebagai pusat dari sebuah peradaban yang cukup penting di masa lalu. Letak geografisnya yang berada di Selat Sunda, menjadikannya sebagai tempat lalu-lalang kapal-kapal antarbangsa yang melintas.
Kisah kepurbakalaan di Ujung Kulon seluruhnya berpusat di satu pulau, yang menurut legenda masyarakat setempat menjadi titik nol keberangkatan peradaban mereka, yakni Pulau Panaitan atau Sanghyang Mahapawitra.
Keluarga Siwa di Sanghyang Mahapawitra
Jejak tamadun di Pulau Panaitan setidaknya bisa dilacak sejak masa Kerajaan Sunda (abad ke-9 hingga 16 M) atau bahkan sejak periode-periode sebelumnya.
Bukti arkeologis yang dianggap paling monumental di Pulau Panaitan adalah dua buah arca bercorak Hindu, yakni Arca Ganesha dan Arca Siwa yang berasal dari Gunung Raksa—gunung di Pulau Panaitan. Kedua arca ini pertama kali dilaporkan oleh Bupati Caringin, Raden Adipati Koesoemaningrat, pada tahun 1894.
Menurut Juliadi dkk. dalam Ragam Pusaka Budaya Banten (2015), Arca Ganesha dan Siwa dari Pulau Panaitan baru menjadi perhatian utama setelah tahun 1970-an. Penelitian kepurbakalaan di pulau tanpa penghuni itu dirintis oleh Universitas Padjadjaran pada 1977, dalam agenda survei mereka menemukan pula satu Arca Tipe Polinesia.
Arca Siwa dan Ganesha di Pulau Panaitan dari segi ikonografis mengindikasikan beberapa hal. Sebagaimana ditulis Agus A. Munandar dalam Kaladesa: Awal Sejarah Nusantara (2017), kedua arca ini tersebut memiliki gaya arca yang cukup asing karena seakan-akan keluar dari pakem pengarcaan yang umum.
Arca Siwa Panaitan digarap dalam bentuk mirip arca zaman megalitik, sedangkan Ganesha sang anak dibuat tanpa mahkota. Ciri arca yang demikian menurut Ashar Murdihastomo pada “Ganesha Tanpa Mahkota dalam Pusaran Religi Masyarakat Jawa Kuna (Sebuah Kajian Permulaan)” (2020) merepresentasikan gaya seni periode awal Hindu-Buddha Nusantara yang terpengaruh unsur budaya Dinasti Gupta India pada abad ke-7 M.
Dengan demikian, Arca Ganesha dan Siwa di Panaitan dapat dihitung sebagai salah satu arca Hindu tertua di Jawa, bersama dengan Arca Ganesha dari Batang dan juga Arca Wisnu dari Cibuaya.
Dari segi tekstual, signifikansi Pulau Panaitan dalam sejarah kuno lebih kentara lagi. Dani Sunjana dalam “Gunung sebagai Lokasi Situs-Situs Keagamaan dan Skriptoria Masa Sunda Kuno” (2019), menyebut kemungkinan Gunung Raksa di Pulau Panaitan merupakan daerah sakral pusat peribadatan sekaligus skriptorium.
Hal ini didukung dengan keterangan pada naskah Bujangga Manik, yang di dalamnya terdapat senarai nama-nama gunung suci Sunda, Panaitan kala itu berporos pada suatu peguron bernama Sanghyang Mahapawitra.
Dalam naskah lain seperti Carita Raden Jayakeling dan Tutur Bwana, mengklarifikasi bahwa daerah ini memang tempat bermukimnya para guru dan juga daerah suci. Tutur Bwana bahkan menyinggung Panaitan sebagai salah satu daerah pertama yang didirikan dewata ketika dunia ini terbentuk.
Sebagai suatu skriptorium atau tempat diproduksi naskah-naskah kuno, naskah produksi pulau ini yang masih bisa dijumpai sampai sekarang adalah Sanghyang Sasana Mahaguru.
Sebagaimana dilampirkan oleh Aditia Gunawan dalam “Membaca Teks Sunda Kuna Sanghyang Sasana Maha Guru” (2011), naskah berbahasa Sunda-Jawa Kuno dan berbahan lontar ini kurang lebih berisi soal ajaran terhadap para pengabdi darma (sewaka darma) atau dengan kata lain naskah didaktik keagamaan.
Di dalamnya disinggung ajaran-ajaran mulia para karuhun (leluhur), terutama dalam hal penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Uniknya, di dalam naskah ini disebutkan bahwa istadewata (dewa utama) dari para siswa di Panaitan memang Bhatara Gana atau Ganesha, ia dimitoskan sebagai pencipta alat tulis bagi para pelajar.
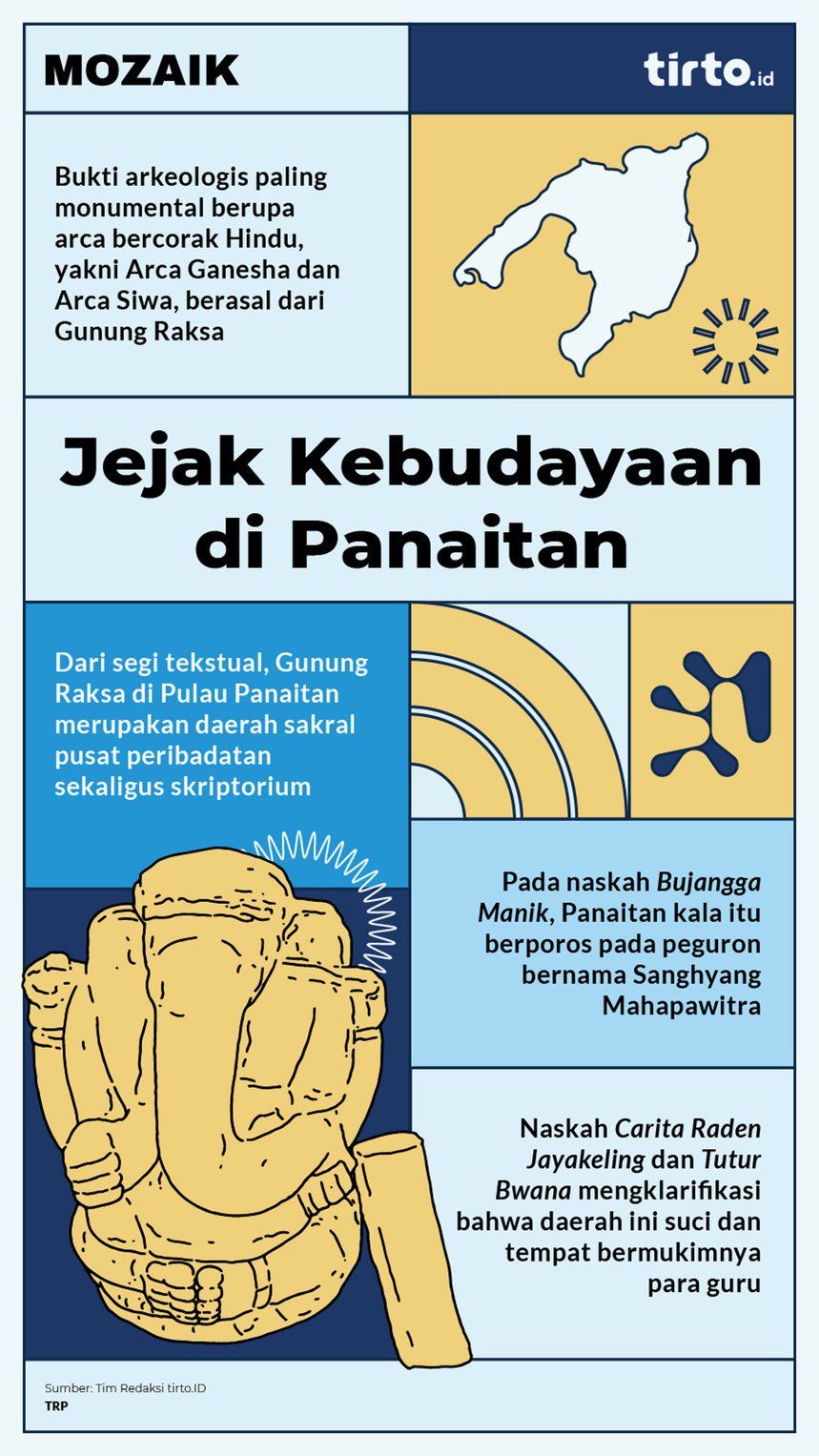
Nekropolis Panaitan
Memasuki periode Islam-Kolonial, catatan soal peguron di Panaitan semakin samar-samar. Sajarah Banten sebagai naskah babon wilayah Banten seperti diberitakan Titik Pudjiastuti pada tesisnya (1991) misal, menyebut bahwa para resi di Panaitan memiliki hubungan dengan para resi di Gunung Pulosari.
Kedua karesian ini secara terang-terangan menyatakan kesetiaannya kepada Maulana Hasanudin yang baru mengakuisisi Banten dari cengkeraman Kerajaan Sunda pada abad ke-16. Tunduknya kedua karesian ini terjadi karena Maulana Hasanudin sebelumnya melakukan semacam safari politik demi mendekati para ajar yang berdiam di wilayah karesian kuno di sekitar Banten.
Pada perkembangan berikutnya, agaknya para resi di Panaitan sebagian mulai memeluk agama Islam atau mungkin juga mulai meninggalkan pulau tersebut. Hal ini dibuktikan dengan catatan pelaut Inggris James Cook yang mendarat di Pulau Panaitan pada 1667.
Sebagaimana merujuk pada tulisan Kusumasumantri, di Pulau Panaitan Cook menjumpai suatu “kota” yang disebut sebagai samadang. Kota itu dihuni sekitar 300 rumah yang warganya seluruhnya memeluk agama Islam dan berbahasa Sunda.
Kurang dari dua abad setelah kedatangan Cook, terutama pada ekspedisi pembukaan lahan Jalan Raya Pos di Banten pada masa H.W. Daendels, Pulau Panaitan telah sepenuhnya ditinggalkan dan penduduknya berpindah ke Pulau Peucang. Kedua pulau ini baru benar-benar ditinggalkan setelah meletusnya Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883.
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Irfan Teguh Pribadi