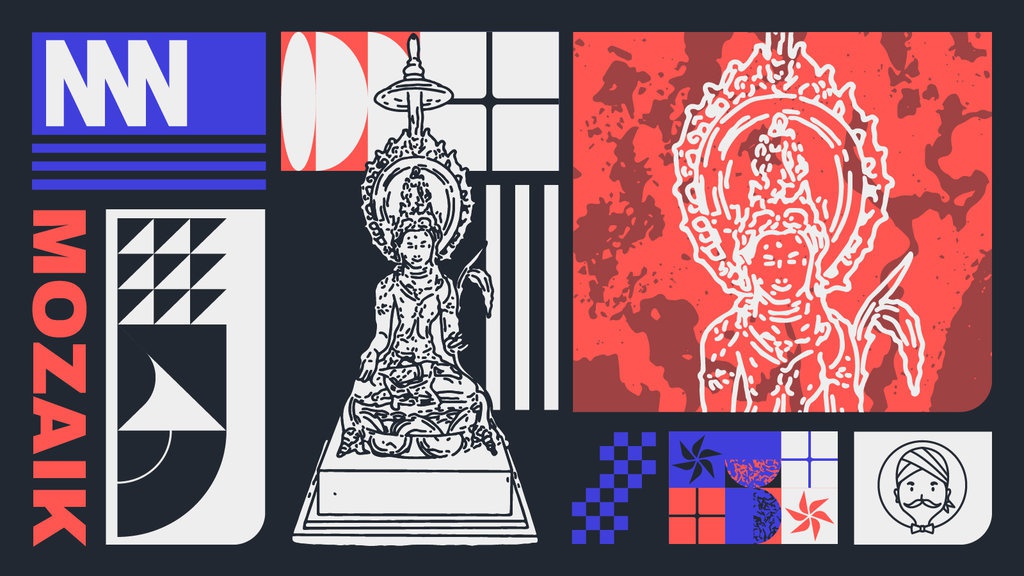tirto.id - Alkisah, di sekitar kawah gunung berapi di dataran Mandailing di Sumatera Utara, ditemukan tiga bongkah batu peninggalan masa kuno. Ketiganya bukan sembarang batu karena para arkeolog menjumpai goresan aksara yang menyuratkan suatu misteri dari masa lampau. Bahkan setelah para ahli berhasil membacanya, justru muncul pertanyaan lebih besar.
Arlo Griffiths dalam studinya “Inscriptions of Sumatra III: The Padang Lawas Corpus Studied Along with Inscriptions from Sorik Merapi (North Sumatra) and from Muara Takus (Riau)” (2014) menyebut bahwa ketiga prasasti tersebut beraksara Sumatera Kuno dan berbahasa Melayu Kuno.
Griffiths menyebut pula bahwa salah satu prasasti tersebut memuat angka tahun 1164 Śaka atau 1242 Masehi. Dari petunjuk itu, dia menyimpulakan bahwa ketiganya kemungkinan sama-sama berasal dari abad ke-13.
Ketiga prasasti tersebut memuat keterangan soal pemberian caitya—tanah, tempat, atau objek peringatan yang berkait dengan agama Buddha—oleh Mahasenapati Pamanan Ekalabira kepada anak perempuannya yang bernama Prajñavardhanī.
Di salah satu prasasti itu, terdapat inskripsi, “caitya bhagi dara nayana samyakaśam buddhanāṁ bhavati.” Jika diterjemahkan, ia berbunyi, “Sebuah Caitya diberikan kepada Dara Nayana. Dia gadis yang telah mendapat pencerahan sang Buddha.”
Griffiths tidak memberi keterangan lebih lanjut soal latar belakang mengapa peristiwa itu sampai perlu diabadikan melalui prasasti. Meski demikian, pemberian caitya atau objek suci kepada sosok perempuan tak hanya terjadi di Sumatera. Jejak yang lebih awal bisa kita temui dalam sumber-sumber epigrafi di Jawa.
Di Jawa Kuno
Sejauh ini, tercatat ada dua prasasti berbahasa Jawa Kuno yang mengabarkan peristiwa serupa. Prasasti dengan angka tahun paling tua yang menyebut soal pemberian hadiah caitya kepada tokoh perempuan adalah Prasasti Munggu Antan yang berasal dari 808 Śaka atau 886 Masehi.
Menurut Edhie Wurjantoro dalam terbitan transliterasi babonnya yang terkenal Anugerah Sri Maharaja: Kumpulan alihaksara dan alihbahasa Prasasti-prasasti Jawa Kuno dari Abad VII-X (2018), Prasasti Munggu Antan mengabarkan soal pemberian anugerah tanah lungguh oleh Śrī Mahārāja Rake Gurunwangi dari Kerajaan Mataram Kuno kepada bawahannya yang bernama Sang Pamgat Munggu.
Hadiah serupa juga diberikan kepada adik Sang Pamgat Munggu yang bernama Sang Hadyan Palutungan, seorang istri pejabat dari Pastika bernama Sang Dewata. Di tanah hadiah itu, nantinya bakal dibangun sebuah vihara.
Di titik dari tokoh-tokoh yang hadir, agaknya upacara serah terima daerah lungguh itu berlangsung cukup mewah untuk ukuran masa itu. Acara itu setidaknya melibatkan banyak saksi dari pejabat sekitar tanah lungguh tersebut, mulai dari para juru (sekarang mungkin setara dengan kepala dinas) dan hingga ketua karang taruna.
Prasasti kedua juga berasal dari periode Mataram Kuno. Tepatnya di era pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung, sekitar beberapa dasawarsa pascapemerintahan Gurunwangi. Prasasti yang dimaksud adalah Prasasti Rukam yang berangka tahun 829 Śaka atau 907 Masehi.
Richadiana Kartakusuma dalam studinya yang berjudul Prasasti Rukam (1981) menyebut bahwa Raja Balitung memerintahkan seseorang bernama Daksottama (adik ipar sekaligus sepupunya) untuk meresmikan kedudukan Desa Rukam sebagai desa otonom yang bebas pajak.
Sebagai balasan atas pembebasan pajak itu, penduduk desa diharuskan untuk merawat bangunan suci di daerah Limwung. Adapun bangunan suci yang dimaksud dalam Prasasti Rukam adalah hadiah dari raja kepada seseorang bernama Rakryan Sanjiwana Nini Haji.
Kartakusuma memperkirakan bahwa sang nini haji yang dimaksud itu adalah nenek Raja Balitung. Sementara itu, nama Sanjiwana kemungkinan besar terabadikan dalam nama Candi Sojiwan yang beranasir Buddha. Lokasi Candi Sojiwan terletak tidak jauh dari Candi Prambanan.
Mendapat hadiah dari raja, nenek raja itu tentunya bukan tokoh sembarangan. Hanya saja, identitasnya yang sebenarnya masih sumir.
“Apakah mungkin Rakryan Sanjiwana sama dengan Pramodhawarddhani, dan demikian pula berarti bahwa Candi Sojiwan merupakan tempat pendharmaannya? Sayangnya kita tidak mendapatkan cukup bukti untuk menjawab dugaan-dugaan tersebut hingga saat ini, dan kita pun tidak tahu pasti di mana sebenarnya tempat pendharmaan Sri Pramodhawarddhani,” kata Kartakusuma.
Perempuan dan Pembebasan Spiritual
Jika diperhatikan saksama, tiga peristiwa pemberian hadiah suci kepada tokoh perempuan tersebut punya benang merah. Ketiganya terkait dengan objek suci bernapaskan Buddhisme. Maka kita bisa menengarai bahwa hadiah-hadiah itu tidak melulu berkait dengan motif materialistis.
Berkenaan dengan konteks Buddhisme yang berkembang di masa Kuno, mari kita simak sedikit keterangan dari Archana Paudel dan Qun Dong dalam “The Discrimination of Women in Buddhism: An Ethical Analysis” (2017).
Penganut Buddhisme di era Kuno—saat patriarki begitu dominan—berpandangan bahwa perempuan menempati posisi inferior. Dalam Buddhisme Thai, misalnya, para perempuan dianggap lahir karena karma buruk yang ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Perempuan tak sempurna hingga ia berinkarnasi menjadi laki-laki. Perempuan juga dianggap dependen pada laki-laki dalam menuju pembebasan.
“Bukti atas gagasan itu dapat ditemukan dalam sebuah prasasti dari abad ke-14 tinggalan Kerajaan Sukhotai. Ia mengabadikan harapan ibu suri kerajaan itu bahwa pahala mendirikan biara dapat memperbesar kemungkinannya untuk dilahirkan kembali sebagai laki-laki,” terang Paudel dan Qun Dong.
Gagasan semacam itu juga sempat hidup di era Sriwijaya yang banyak masyarakatnya menganut Vajrayana. Petunjuk akan hal ini bisa dijumpai pada Prasasti Talang Tuo dari abad ke-7, sebagaimana diuraikan G. Coedes dkk. dalam Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi (2014).
Berhubungan dengan konteks ini, pemberian hadiah caitya seperti ketiga kasus tersebut boleh jadi berkenaan dengan para patriark yang memberi sarana bagi perempuan menuju pembebasan spiritualnya.

Namun, peristiwa-peristiwa itu bisa juga ditafsir lain seturut perspektif lokal yang berkembang sebelum masuknya Indianisasi ke Nusantara. Perspektif ini pun cenderung bertolak belakang dari konsep sebelumnya.
Sejak mula mekarnya budaya bercocok tanam di era Prasejarah, masyarakat Nusantara punya pandangan tersendiri atas posisi perempuan. Mereka menempatkan perempuan secara simbolik sebagai perwujudan dari kesuburan.
Simbolisasi itu salah satunya mewujud dalam bentuk penghormatan dan pemujaan terhadap dewi kesuburan, semisal Dewi Pwahaci dalam masyarakat Kanekes (Baduy).
Suku Amungme di Papua juga memiliki kepercayaan yang sama, sebagaimana disebut dalam Freeport, The Environment, and The Amungme: An Environmental History of The Freeport McMoran Copper and Gold Mine in Papua, Indonesia (2021). Orang Amungme menamai salah satu puncak Gunung Jayawijaya sebagai Nemangkawi Ninggok, sosok yang diasosiasikan dengan entitas “ibu bumi” yang selalu mengasihi mereka dengan limpahan kesuburan.
Konsep perempuan sebagai simbol kesuburan itu, sebagaimana diuraikan Roy Jordaan dalam “Tara and Nyai Lara Kidul: Images of the Divine Feminine in Java” (1997), terus eksis hingga masa sejarah bergulir di Nusantara, terutama di masa Klasik hingga Islam.
Menurut Jordaan, Dewi Tara dalam mitologi Buddha Vajrayana yang semula berkembang di India diadopsi oleh masyarakat Nusantara sebagai perwujudan kesuburan yang feminin. Bahkan, meski perlu ditelisik lebih lanjut, konsep ini berlanjut hingga zaman Islam dan bertransformasi menjadi sosok Nyai Roro Kidul.
Berlainan dari konsep pertama, perspektif kedua ini jelas menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih terhormat. Berdasar perspektif ini, pemberian hadiah caitya oleh para patriark di era Nusantara Kuno boleh jadi didorong oleh motif pragmatis-religius. Bahwa para penguasa maskulin itu mengharapkan adanya timbal balik berupa kemakmuran dan kesejahteraan dari dewata melalui dermanya kepada sosok perempuan yang dihormati.
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id