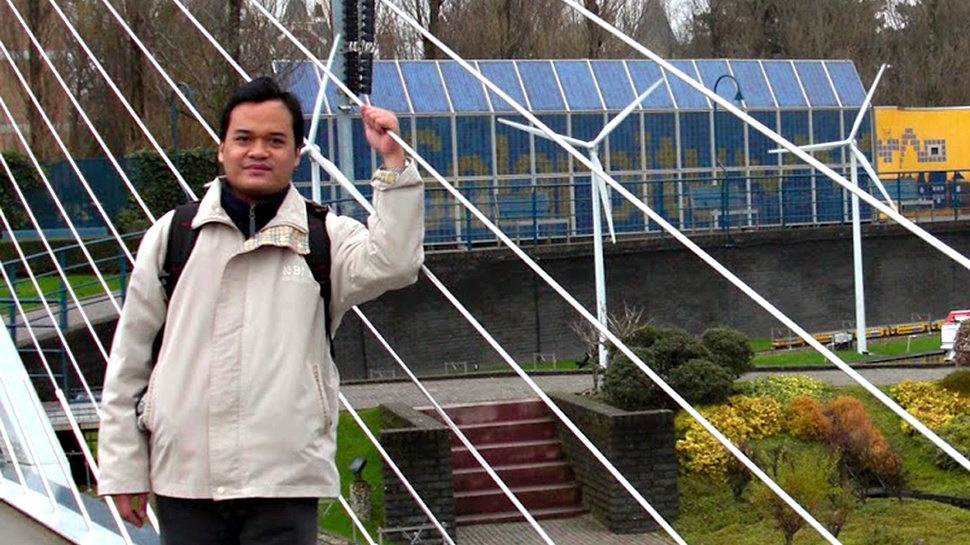tirto.id - Ada tiga faktor penting yang bisa dibaca dari keputusan akhir Megawati menjatuhkan pilihan kepada pasangan Ahok-Djarot. Salah satunya menunjukkan determinasi Presiden Jokowi.
“Bagaimana pun Jokowi harus dibaca sebagai faktor determinan,” kata Gun Gun Heryanto, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kepada Arbi Sumandoyo dari tirto.id, pada Sabtu (24/9/2016). Sebab dalam beberapa kesempatan, dia memfasilitasi komunikasi politik antara Ahok dengan Mega.
Apa dua faktor penting lainnya? Apakah Pilkada bakal berlangsung satu atau dua putaran? Siapa pasangan yang bakal menjadi penantang Ahok-Djarot jika terjadi dua putaran? Mengapa munculnya tiga pasangan calon di Jakarta justru menunjukkan kegagalan parpol dalam proes kaderisasi internalnya? Berikut petikan wawancaranya;
Megawati dan PDI Perjuangan disebut menjadi penentu dalam Pilkada DKI Jakarta?
Pertama jelas, posisi PDI Perjuangan menjadi menentukan dengan modal politik 28 kursi di DPRD. Tanpa harus bergabung dengan parpol lain, PDIP bisa mengajukan calon sendiri. Nah modal politik ini tentu dibaca oleh PDIP. Mereka punya kekuatan menjadi pengubah konfigurasi politik di Jakarta.
Saya melihat, posisi itu dimainkan PDIP sehingga sampai injury time baru menentukan sikap politik. Artinya apa, saya melihat PDIP memilih zona nyaman. Memilih konfigurasi kekuatan lama. Pasangan Jokowi-Ahok didukung oleh PDIP pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Jokowi kemudian digantikan oleh Ahok karena menjadi presiden, sementara posisi Ahok digantikan oleh Djarot.
Memilih zona nyaman seperti apa?
Artinya, peta harus dipertahankan dengan representasi PDIP ada di Djarot. PDIP tidak memilih menjadi petarung, tetapi justru lebih memperkuat posisi Ahok dan Djarot sebagai incumbent.
Maksud Anda tadi menyebut PDIP punya kekuatan mengubah konfigurasi politik?
Sebelum PDIP membuat keputusan mendukung Ahok, partai-partai lain menunggu. Kalau dia tidak mendukung Ahok, ada kans bagi PDIP menjadi lokomotif penantang Ahok. Dan saya yakin, jika PDIP kemarin tidak berada di kongsi Ahok, maka partai-partai di luar Ahok bakal konsolidatif di bawah PDIP. Tetapi itu sudah jadi sejarah karena sudah berlalu.
Jadi begitu PDIP masuk ke Ahok untuk memperkuat, mereka memiliki 52 kursi. Dan keputusan PDIP itu menyebabkan fragmentasi kekuatan politik di luar Ahok. Dari awal sebelum PDIP bersikap, Gerindra dan PKS yang memiliki 26 kursi memilih Sadiaga Uno dan Mardani Ali Sera. Sedangkan parpol lain dengan kekuatan 28 kursi lebih intens di Cikeas. Gerindra dan PKS tidak datang ke Cikeas sudah menjadi penanda.
Dan akhirnya terbukti, “Poros Cikeas” mengusung Agus dan Sylviana dengan dukungan 28 kursi di DPRD. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno didukung Gerindra dan PKS dengan kekuatan 26 kursi di DPRD. Jadi konfigurasi menjadi tiga pasang sangat dipengaruhi oleh Megawati dan PDI Perjuangan. Mega bukan hanya kingmaker, tapi juga vetoplayer untuk kebijakannya di PDIP.
Bagaimana Anda melihat keputusan Mega mendukung Ahok?
Sejak awal saya tidak pernah melihat Mega menunjukkan komunikasi politik antara dirinya dengan Ahok. Itu sebetulnya bisa dibaca sebagai sinyal politik. Saya tidak terlalu kaget ketika pada akhirnya PDIP dukung Ahok, sebab dari sudut komunikasi politik tanda-tandanya sudah jelas. Ahok diberi panggung saat peluncuran buku biografi Mega. Juga saat haul Taufik Kiemas. Dalam beberapa kesempatan, Ahok satu mobil dengan Mega dan Jokowi.
Jadi kalau memang ada problem komunikasi, Mega akan sangat ekspresif menunjukkan ke publik. Sementara Ahok, meskipun ada suara keras penentangan dari DPD, terutama Bambang DH atau Gembong Warsono, saya melihat tetap komunikasi interpersonal. Mega kemudian ikut dalam relasi antagonistis di antara mereka.
Faktor penting apa yang bisa dibaca atas keputusan Mega mendukung Ahok?
Ada tiga faktor. Pertama, Mega sebagai figur sentris di PDIP. Aktor-aktor lain melakukan hubungan dalam batasan afiliatif. Mereka tidak mau berbeda dengan tokoh utamanya. Kalau Mega sudah menentukan pilihan kepada Ahok, yang lain harus ikut. Kedua adalah faktor Jokowi. Bagaimana pun Jokowi harus dibaca sebagai faktor determinan. Sebab dalam beberapa kesempatan, dia memfasilitasi komunikasi politik antara Ahok dengan Mega. Saya melihat perjumpaan-perjumpaan mereka bertiga, baik saat ke DPP Golkar atau haul Taufik Kiemas, bukan tanpa konteks komunikasi politik. Saya yakin Jokowi menjadi faktor determinan.
Kemudian ketiga, faktor strategi planning PDI Perjuangan menjelang 2019 (Pileg dan Pilpres). Bagaimanapun juga harus membaca prospek probabilitas paling tinggi, yakni pemenangan wilayah strategis. DKI Jakarta adalah wilayah strategis, selain tentu saja daerah di Pulau Jawa lainnya. Jawa Tengah ada Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng). Kemudian di Jawa Timur ada Risma (Walikota Surabaya) dan di Banten ada Rano Karno (Gubernur Banten). Konfigurasi kekuatan daerah strategis ini bakal menjadi penetrasi PDI Perjuangan. Bukan saja di Pilkada DKI 2017, tetapi juga 2019.
Artinya memang strategi untuk Pileg dan Pilpres 2019?
Salah satunya iya.
Apakah PDIP mengusung Ahok terkait faktor ideologi?
Ya memang. Kalau bicara aspek itu, Ahok tidak punya barrier dengan PDIP soal ideologis. Sebab bagaimana pun, salah satu ciri PDIP adalah nasionalisme, keindonesiaan yang dibangun dari pluralisme, keindonesiaan yang dibangun dari kebhinekaan. Dan itu ciri bangunan dari nationalisme partai. Pada momen tertentu ketika kesulitan memunculkan kader karena proses kelembagaan di partai memang belum matang, tak menuup peluang memunculkan sosok di luar partai yang punya nilai elektabilitas, akseptabilitas dan popularitas. Modal dasar elektoral yang dimiliki oleh orang di luar partai tersebut pasti menjadi pertimbangan.
Dan bagi PDIP, pilihan pada sosok Ahok jauh lebih mudah dibandingkan pilihan kepada Yusril atau sosok-sosok lain. Mereka yang mendaftar sebagai calon-calon gubernur hanya dipakai semacam opsi oleh PDIP.
Artinya jauh hari sudah ada isyarat dari PDIP untuk mengusung Ahok?
Isyaratnya sudah banyak banget. Kalau pun ada riak-riak penentangan, lebih pada managemen kesan. Tetapi dalam realitas politiknya, semua ada di tangan Megawati. Secara kelembagaan, PDIP jauh lebih peduli mengelola winning opportunity structure (WOS) atau struktur peluang kemenenangan. WOS memang berpresfektif elite. Tinggal bagaimana memposisikan WOS punya bingkai nilai kebermanfaatan untuk publik. Misalnya, Ahok dan Djarot bukan hanya menjadi representasi kepentingan PDIP, tetapi kepentingan warga DKI yang ingin melihat perubahan.
Prediksi Anda akan berlangsung berapa putaran?
Satu atau dua putaran ditentukan tiga hal. Pertama, sejauh mana daya tahan dua kontestan di luar Ahok membangun soliditas pemenangan mesin partai pendukungnya dari pusat hingga ranting ranting di wilayah DKI. Jadi kalau koalisi yang dibangun adalah seremonial dan pragmatis, memang tidak akan sampai pada rasa memiliki. Apalagi pasangan calon di Pilkada Jakarta bukan kader partai. Agus Yudhoyono, meski anak SBY, bukan kader partai. Anies dan Ahok juga bukan kader partai. Jadi kalau Anies dan Agus tidak didukung dengan struktur pemenangan partai yang bergerak cepat, menurut saya Ahok akan menang.
Kemudian yang kedua, ditentukan oleh kemampuan Anies-Uno dan Agus-Sylvi dalam men-delivery program-programnya kepada pasar pemilih. Nah, saya memprediksi yang maju ke putaran kedua adalah Ahok-Djarot dan Anies-Uno.
Faktor ketiga yang menentukan adalah incumbent. Dua atau satu putaran akan sangat ditentukan oleh incumbent. Apakah incumbent stagnan, atau kecenderungannya turun dan bisa dikejar oleh pasangan lain. Atau memang mungkin ada problem, entah itu moral atau etik yang mampu mendelegitimasi incumbent. Apakah Ahok akan menang 50+1, sangat ditentukan oleh tiga faktor tadi. Saya sendiri berfikir Ahok ada peluang untuk satu putaran. Tetapi kalau dua kandidat mampu split pasar pemilih, itu akan berpotensi dua putaran.
Apakah Anda melihat penentuan kandidat calon di Pilkada DKI menunjukkan kaderisasi partai yang gagal?
Ya memang kritik saya paling substantif terkait munculnya para kandidat ini adalah peran dari lembaga politik di tubuh partai. Kalau boleh beri catatan, saya senang dengan tiga pasangan ini karena mereka memang punya portofolio bagus. Anies dan Agus adalah orang-orang terpilih. Tetapi membuka mata kita bahwa sudah jelas partai politik tidak siap dengan proses distribusi kadernya ke jabatan publik. Terutama di saat butuh orang terbaik partai.
Lihat saja, Ahok bukan orang partai, Anies bukan orang partai, kemudian Agus juga. Saya jadi berpikir, partai pada ke mana ya dalam proses metamorfosis dari konsolidasi dan penguatan partai politik? Masalahnya masih tetap, partai tidak cukup ajeg dalam memikirkan mata rantai kandidasi. Padahal seharusnya mata rantai itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari.
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti