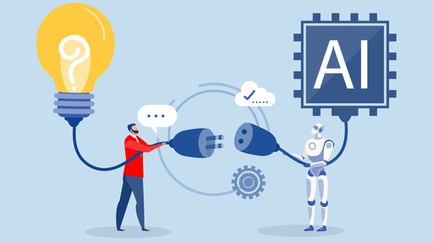tirto.id - Hujan baru saja mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu sore pekan lalu. Musim kemarau basah akibat La Nina ini membawa pesan tentang carut-marut tata ruang wilayah di Provinsi DKI Jakarta. “Banjir Jakarta”, begitu sebuah tanda pagar di lini masa Twitter, mulai menghiasi diskusi singkat para pengguna media sosial membicarakan rendaman Kali Krukut yang melumpuhkan wilayah Kemang.
Pendapat dari pelbagai pengguna Twitter disertakan foto-foto mobil-mobil mewah yang menjadi korban luapan Kali Krukut. Banyak juga yang berpendapat, peruntukan lahan di wilayah tersebut memang tak sesuai dengan tata ruang yang seharusnya. Intinya, mereka mengkritisi pengelolaan tata ruang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait banjir di kawasan elit Kemang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah (RTRW) DKI Jakarta sebenarnya telah diatur sejak 1965. Rencana Tata Ruang berdasarkan Keputusan DPR Gotong Royong DKI Jakarta No.9/P/DPR-GR/1967 itu, merupakan induk penetapan pertama yang mengatur peruntukan wilayah-wilayah di Jakarta.
Mengacu kepada pembangunan kota satelit yang ideal, RTRW itu mengatur pembangunan wilayah dari segala penjuru dengan jarak 15 kilometer dari titik nol kilometer Jakarta yaitu, Monumen Nasional. Dalam Rencana Induk itu, Ruang Terbuka Hijau telah ditetapkan 37,2 persen dari total luas Jakarta.
Namun, tata ruang Jakarta mulai berubah sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah DKI No.5/1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005. Menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, perda tersebut membuat perubahan secara masif tata ruang di Jakarta. Melalui perda itu juga, berbagai daerah di wilayah DKI Jakarta mulai berubah peruntukannya. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, 80 persen tata ruang di Jakarta mengalami perubahan peruntukan wilayah.
Puncaknya terjadi ketika Perda Nomor 6/ 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2000-2010 juga dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemutihan kawasan Ruang Terbuka Hijau pun terjadi ketika produk hukum itu dikeluarkan.
“RTH terus mengalami penurunan, dari 37,2 persen kemudian 25,89 persen dan turun lagi menjadi 13,94 persen,” ujar Nirwono Joga kepada tirto.id, pada Selasa (30/8/2016). Dia pun menambahkan, saat ini Ruang Terbuka Hijau di Jakarta hanya tinggal sekitar 9 persen.
Lahan Basah Ruang Terbuka Hijau
Menggiurkannya lahan ruang terbuka hijau di Jakarta untuk dikomersialisasi, dimulai ketika diberlakukan Undang Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah). Sejak saat itu, Pemprov DKI berupaya mengambil aset yang selama ini dikelola oleh pemerintah pusat. Sebut saja kompleks Gelora Bung Karno seluas 280 hektar, bekas Bandara Kemayoran seluas 480 hektar, pelabuhan laut seluas 912 hektar, atau jalan tol Jakarta sepanjang 136 kilometer dengan lahan hijau sekitar 500 hektar yang merupakan aset menggiurkan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Jika aset-aset itu dikuasai, menurut Nirwono, Pemprov DKI mendapat tambahan RTH sebesar 2.132 hektar. “Kalau mau konsisten, setiap tahun kembalikan 1 persen. Maka selama 15 tahun sampai 2010 RTH bisa tambah 15 persen,” ujarnya.
Namun, dia menegaskan pengambilan aset ternyata disalahgunakan dan bahkan memperparah peruntukan tata ruang.
Penyalahgunaan fungsi tata ruang di beberapa daerah di Jakarta, sebetulnya sudah berpuluh-puluh tahun terjadi. Dimulai keluarnya RUTR 1985-2005 yang merupakan pintu masuk munculnya Peraturan-Peraturan Daerah yang secara tidak langsung melegalisasi perubahan tata ruang di Jakarta.
Nirwono menyebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki andil besar dalam setiap perubahan setiap peruntukan daerah di Jakarta. Kemang misalnya, daerah yang dulunya banyak dijumpai pohon -Magnifera Kemangcaecea- (cikal bakal penyebutan nama Kemang), sejatinya memang bukan untuk kawasan komersial. Kemang merupakan daerah resapan air, sama seperti kawasan Pondok Indah. Namun, sejak masuknya ekspatriat menghuni wilayah ini pada tahun 1970-an, secara perlahan Kemang mengalami perubahan.
Berdasarkan penelitian berjudul “Urban Regime di alih Fungsi Lahan Jakarta”, dijelaskan bahwa daerah Kemang mulai berubah peruntukan dari kawasan hunian menjadi kawasan komersial. Pada tahun 1980, mulai berdiri hotel, restoran, kafe dan minimarket. Kini, bangunan-bangunan tempat hiburan, hotel dan tempat nongkrong anak muda semakin ramai. Ramainya tempat hangout ternyata menambah permasalahan baru bagi warga Kemang.

Selain Kemang, daerah yang juga peruntukannya berubah adalah Kelapa Gading di Jakarta Utara. Daerah yang dulunya merupakan areal persawahan, kini berubah menjadi kompleks perumahan elit berharga miliaran, lengkap dengan fasilitas pusat perbelanjaan mewah dan sekolah bertaraf internasional. Perubahan fungsi lahan menjadikan wilayah Kelapa Gading acap kali diberitakan kebanjiran. Saban musim hujan tiba, daerah ini menjadi lautan kolam berwarna cokelat.
Salah satu wilayah yang juga dikenal daerah resapan air adalah Pantai Indah Kapuk. Daerah yang kini dikenal pemukiman elit itu pun merupakan salah satu wilayah yang telah berubah peruntukannya. Padahal sesuai Rencana Induk Djakarta, merupakan daerah hutan lindung. Perubahan wilayah-wilayah itu pun merupakan produk legal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Nirwono, banyaknya lahan terbuka hijau yang kemudian menjadi daerah pemukiman hingga komersil, memang sengaja dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sepanjang perubahan Rencana Tata Ruang sejak 1965 sampai saat ini, peruntukan lahan hanya berpihak kepada para pengembang. “Namanya pengembang, mereka juga perlu kepastian hukum ketika mau melakukan investasi. Dan inilah awal mulanya perubahan tata ruang menjadi parah sampai sekarang,” katanya.
Bunuh Diri Ekologi
Puncak permasalahan tata ruang Jakarta sejatinya memang mulai terasa saat ini. Banjir, macet, kemudian polusi udara dan ketersediaan air tanah, juga mulai dirasakan warga Jakarta.
Menurut Nirwono, dampak berkurangnya RTH di Jakarta juga menyebabkan bencana ekologi yang kini mau tak mau harus dihadapi oleh warga. Sebab, berkurangnya lahan terbuka hijau membawa dampak bencana lingkungan yang kini menjadi hantu bagi penghuni Jakarta.
Jika pembenahan tata ruang tidak segera dilakukan, DKI Jakarta secara perlahan akan mengalami bunuh diri ekologi. Sebuah bencana lingkungan yanh disebabkan salah mengelola tata ruang sebuah kota. “Kalau tidak segera dilakukan, kita akan menghadapi bunuh diri ekologi,” kata Nirwono.
Sebetulnya, tanda-tanda bencana lingkungan melanda Provinsi DKI Jakarta sudah lama terlihat. Pembangunan gedung-gedung bertingkat, termasuk juga izin pembangunan pusat perbelanjaan yang tidak sesuai dengan tata ruang, secara tidak langsung juga menambah permasalahan di Jakarta. Selain kemacetan dan meluasnya daerah banjir, Jakarta juga mengalami penurunan muka tanah yang lambat laun berdampak bagi para penghuninya.
Pada “Peta Amblesan Tanah” di DKI Jakarta yang dibuat Badan Geologi pada 2009, antara kurun waktu 1982 hingga 1997, terjadi penurunan tanah lebih dari 180 sentimeter. Penurunan muka tanah paling kentara terjadi di daerah Cengkareng, Kapuk, dan Penjaringan. Sedangkan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, penurunan muka tanah terjadi lebih dari 120 sentimeter.
Begitu juga dengan pencemaran air tanah, ekstraksi air tanah berlebihan yang dilakukan pengelola gedung-gedung bertingkat juga berdampak pada kualitas air di Jakarta. Akibat ekstraksi air tanah secara berlebihan dan kurangnya Ruang Terbuka Hijau, air di Jakarta pun 90 persen mengandung bakteri e-coli.
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Kukuh Bhimo Nugroho
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id