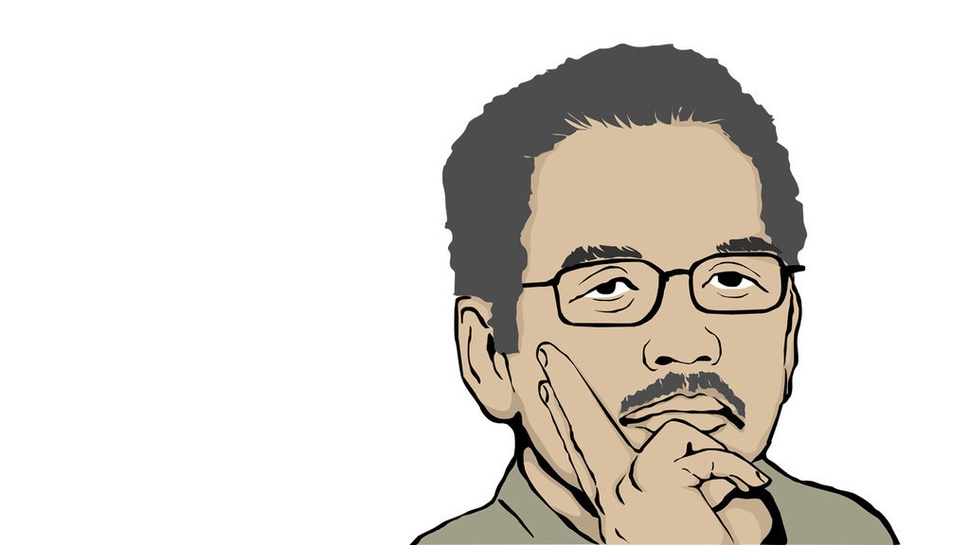tirto.id - Abdul Munir Mulkhan punya perhatian besar terhadap sejarah awal Muhammadiyah. Ia seorang guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang banyak menulis tentang sepak terjang Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah.
Dari tangan Munir, beberapa karya dilahirkan, di antaranya Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam perspektif perubahan sosial (1990), Islam sejati: Kiai Ahmad Dahlan dan petani Muhammadiyah (2003), dan Islam kultural Kiai Dahlan: mengembangkan dakwah dan Muhammadiyah secara cerdas dan maju bersama Kiai Ahmad Dahlan (2013).
Kami menemui Munir di kediamannya di Perumahan Kementerian Agama Yogyakarta pada Senin sore, 20 November 2017. Munir berbicara banyak mengenai spirit Ahmad Dahlan saat mendirikan Muhammadiyah.
Menurut Munir, Ahmad Dahlan digerakkan oleh pemikiran dunia Islam saat itu, kolonialisme, dan kondisi masyarakat Islam di Hindia Belanda. Dari situ Dahlan bermimpi mewujudkan masyarakat Islam berkemajuan.
Apa yang mendasari Ahmad Dahlan Mendirikan Muhammadiyah?
Untuk memahami itu, kita mesti melihat konteks sosial budaya pada tahun-tahun awal abad 20, tahun 1900-an. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia Islam yang boleh disebut sebagai puncak-puncak kenadirannya—seluruh dunia dalam penjajahan. Pikiran Dahlan pada waktu itu bukan hanya Islam (di) Indonesia tapi dunia. Sementara ia berada dalam situasi kultural Kerajaan Islam, berada dalam cengkeraman pemerintah kolonial Belanda.
Aspek lain, kalau orang membaca, bacaan Dahlan mendunia, karena ia baru saja pulang dari Mekkah, tempat pertemuan bangsa-bangsa Muslim dari seluruh dunia. Pada saat yang sama sedang terjadi kebangkitan Islam. Itu dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani danMuhammad Abduh.Dunia Islam sedang bergerak walaupun berada pada cengkeraman kolonialisme.
Pada aspek satunya lagi, ketika orang membaca ajaran-ajaran Islam, betapa indahnya, betapa heroiknya, betapa “provokatifnya” agar orang kreatif, agar orang sukses, peduli sesama.
Jadi, memang [kita] harus [melihatnya] multiaspek dan memberi makna bagaimana kelahiran Muhammadiyah.
Di sisi lain lagi soal bagaimana orang Islam pada waktu itu.Justru yang terjadi sebaliknya: saling tidak peduli, saling menyakiti diri sendiri, seperti lari dari dunia objektifnya. Enggan menerima kenyataan bahwa mereka sedang berada dalam puncak ketidakberdayaan, kemudian menikmati “penderitaannya”.
Mungkin, kalau sekarang agak sulit bagi anak muda melihat masyarakat Islam pada saat itu. Lari ke kuburan, lari ke kekuatan-kekuatan magis yang dianggap bisa mengubah, menciptakan kehidupan sehat, sejahtera. Tapi justru hal itu lari dari keadaan sebenarnya.
Di saat yang sama Kiai Dahlan berada di pusat kekuasaan Islam dan kekuasaan Belanda, karena berada di lingkungan Keraton. Jadi ada dua hal yang saling berhadapan di depan matanya.
Seperti tadi saya katakan, ada provokasi ketika dia membaca ayat-ayat suci Alquran, membaca surat Nabawi. Lalu dia melihat di pusat peradaban saat itu, Yogya benar-benar sebuah suatu titik lampu di tengah-tengah hutan belantara, benar-benar kelihatan betul pusat kehidupan itu ada di Yogya, di Keraton itu.
Lantas, ketika keluar dari Keraton, dia melihat masyarakat yang mestinya punya agama, yang hebat itu, hidup di dalam puncak-puncak penderitaan, kelaparan, saling menikam, saling bertengkar.
Dia juga belajar bagaimana orang-orang Belanda, orang-orang Katolik, orang Kristen, mengelola dirinya. Kalau sakit, mereka tidak pergi ke kuburan, tidak pergi ke pohon beringin. Tapi konsultasi ke dokter, ke rumah sakit. Mereka mengelola anak-anak kecil mempersiapkan masa depannya dengan sekolah. Semua ini dia alami karena berada di Yogya.
Dia berontak kepada dirinya sendiri. Bukan karena ingin bersaing dengan Kristen, tapi justru bagaimana dia mengubah nasibnya dengan jalan kebudayaan. Karena itu, pekerjaan pertama kali yang dilakukannya adalah melalui pendidikan, santunan kepada orang-orang yang menderita. Dahlan bahkan membuat pasukan penanggulangan bencana, semacam Satgas Kebakaran.
Saya bayangkan situasi saat itu chaostic.Di mana-mana ada orang meninggal, keleleran di tengah jalan karena memang Yogya itu pusat ekonomi, pusat peradaban, tempat paling aman, sehingga Yogya menjadi tumpuan, tempat pelarian.Tapi kemudian orang enggak dapat apa-apa di Yogya.
Kalau saya bayangkan, banyak orang kemudian meninggal di jalan, pengemis yang kemudian telantar di jalan.
Maka, dalam sejarah, meski saya enggak menemukan dokumennya sampai sekarang, yang sering saya sebut legenda, adalah tentang pengajian Al-Ma'un. Kasarnya, harusnya orang Islam itu peduli sesama, saling membantu, tapi mengapa orang Islam salat tetapi enggak peduli terhadap sesama? Kalau begitu semua orang ini pendusta. Mengabdi kepada Tuhan tapi membiarkan orang lain sengsara. Itu diulang-ulang dalam pengajian Al-Ma'un.
Waktu itu Kiai Dahlan jadi pusat perhatian karena orang ini aneh, wong ngaji kok ngurusi orang-orang yang menderita, ngaji kok kemudian bertanya apa yang kamu lakukan untuk orang yang menderita. Sehingga orang yang datang kepadanya datang dari mana-mana, karena aneh pemikirannya, tidak sesuai dengan tradisi zamannya.
Singkat cerita, mulailah dia mendirikan apa yang dikenal dengan sekolahan, tapi jangan dibayangkan sekolahan itu ada gedungnya. Sekolahan itu di rumahnya. Dikenallah kemudian, karena banyak orang menderita, muncullah gagasan untuk mengumpulkan anak-anak yang keleleran itu.
Orang datang dari mana-mana, dari Magelang, Purworejo, Purwokerto, karena apa yang disampaikan Kiai Dahlan berbeda dengan model-model pengajian di masyarakat.
Sampailah apa yang diberikan Kiai Dahlan menarik minat kalangan elite, orang-orang yang berpendidikan, yang kaya. Dia terlibat dalam Sarekat Islam yang lahir terlebih dahulu.Lalu Boedi Oetomo dan macam-macam—kumpulan orang pergerakan, orang-orang pribumi yang lebih berorientasi pada politik, sebagian didasarkan pada rasa kemanusiaan.
Mereka melihat Kiai Dahlan menarik, tidak seperti dulu yang namanya khotbah itu tidak dimengerti karena pakai bahasa Arab; sementara Kiai Dahlan berbeda.
Di dalam dinamika itulah kemudian ada suatu gagasan untuk disusun dalam organisasi. Singkat cerita, diberilah nama Muhammadiyah.
Karena sifatnya gerakan kebudayaan, pertama-tama bukan menempatkan diri sebagai gerakan yang “melawan penjajahan”. Ini karena memang awalnya gerakan penyadaran—enlightenment.
Dalam kisah-kisah awal itu, sampailah kemudian orang mendengar ada organisasi yang ketuanya disebut presiden. Ini, kan, menimbulkan pertanyaan. Maka, diberilah penjelasan-penjelasan. Bahkan penghulu Keraton yang tadinya kurang mendukung, jadi mengerti maksudnya.
Singkat cerita, Ahmad Dahlan mengajukan izin ke pemerintah Hindia Belanda. Surat itu diajukan seperti yang diperingati sekarang: 18 November 1912.Tapi izin itu baru keluar dua tahun kemudian.
Dulu anggotanya ada tiga macam. Pertama, yang disebut anggota biasa—ya seperti saya, Pak Haedar Nashir (Ketua PP Muhammadiyah 2015-2020), Pak Yunahar Ilyas (Wakil Ketua Umum MUI Pusat 2015-2020). Itu anggota biasa, orang-orang Islam yang mempunyai komitmen, setuju terhadap tujuan Muhammadiyah.
Kedua adalah anggota istimewa: siapa saja, bangsa siapa saja, agama apa saja, sepanjang orang itu punya jasa besar terhadap Muhammadiyah; mereka diberi kartu anggota Muhammadiyah. Tetapi orang ini beda, tidak boleh dipilih dan tidak boleh memilih.
Ketiga disebut anggota donatur: siapa saja, agama apa saja, yang memberi bantuan donasi pada Muhammadiyah tiap bulan, dia boleh menjadi anggota Muhammadiyah, tetapi dia tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih.
Kembali ke masa awal pendirian Muhammadiyah, pada waktu itu masih tidak lazim mendirikan gerombolan-gerombolan, atau kalau sekarang disebut ranting. Dulu Muhammadiyah hanya di Yogyakarta, kemudian melebar di Hindia Belanda, di daerah di bawah kekuasaan Belanda.
Yang dikerjakan itu sekolah. Waktu itu aneh. Orang Islam kok sekolah, apalagi pakai bangku. Itu luar biasa. Bagi masyarakat itu aneh.
“Islam kok koyo ngono, kafir itu, niru orang Belanda.”
Di saat yang sama, Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, rumah sakit—waktu itu namanya poliklinik—didirikan tahun 1923. Saat itu Kiai Dahlan sudah meninggal.
Kemudian Sukarno tertarik pada pemikiran-pemikiran Kiai Dahlan, atau dalam bahasa Muhammadiyah sekarang, "Islam yang berkemajuan." Boedi Oetomo juga tertarik pada Muhammadiyah.
Ini kok Islam tapi ngurusi orang-orang yang menderita, berdasarkan welas asih? Kalau Anda baca buku saya yang diterbitkan Kompas tahun 2010, Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan, yang namanya etika welas asih itu isi pidato Dr. Sutomo.
Dulu yang namanya mencari ilmu itu ya orang datang ke guru. Kiai Dahlan enggak begitu. Dia jalan; guru keliling. Sering saya lukiskan seperti tukang jamu, tukang obat. Datang ke mana-mana ke banyak orang, lalu disampaikanlah ajaran-ajaran Islam. Waktu itu juga dikritik habis-habisan karena melecehkan ulama karena dituduh "ngecer agama."
Terakhir, saya kira, setelah didirikan PKU, akronim dari Penolong Kesengsaraan Umum, siapa saja kalau memang menderita harus ditolong, maka muncullah yang namanya asas PKU.
Muhammadiyah itu berjuang, bekerja, menolong, mendidik, mengobati; bukan dengan maksud mengubah agama yang bukan Islam jadi Islam, yang bukan Islam Muhammadiyah jadi Muhammadiyah—bukan begitu. Semua dilakukan Muhammadiyah semata-mata demi kemanusiaan, berdasarkan ajaran Islam. Itu yang namanya asas PKU.
Ahmad Dahlan juga mendorong perempuan yang dulunya macak, masak, manak harus keluar rumah, untuk bekerja, mencari ilmu. Itu yang kemudian berdiri secara resmi 'Aisyiyah pada 1917.
Begitulah kira-kira suasana awal [sejarah] Muhammadiyah.
Tentu yang sebenarnya jauh lebih kaya, lebih detail, lebih rumit dari sekadar cerita saya. Dan tidak terlalu tepat kalau kelahiran Muhammadiyah itu untuk melawan Kristenisasi. Tapi justru Kiai Dahlan belajar pada orang-orang Kristen.
Jadi betapa revolusionernya pemikiran-pemikiran Kiai Dahlan karena melawan arus tradisi yang berkembang di masyarakat.
Jadi kalau bisa disederhanakan, Kiai Dahlan ini punya bayangan sebuah tatanan baru dalam masyarakat Islam?
Tatanan baru karena memang tidak sesuai dari yang ada di masyarakat. Itu bukan baru, tapi itulah Islam. Tapi waktu itu sesuatu yang baru. Misalnya, Kiai Dahlan-lah yang memulai ceramah-ceramah dengan bahasa Jawa.
Membumikan Islam?
Iya. Waktu itu dianggap melecehkan Islam karena Alquran di-bahasa Jawa-kan. Bagi Dahlan, ini gimana kitab suci yang jadi pedoman, kok, tidak dimengerti banyak orang? Guru keliling itulah yang menjadi bibit kawit yang tidak ada di negara-negara Islam lain.
Pada awal berdiri, Kiai Dahlan jadi anggota Boedi Oetomo, apakah ini upaya Muhammadiyah untuk dibantu mendapatkan izin dari kolonial?
Ini yang secara logis saya tidak punya dokumennya, seolah-olah Boedi Oetomo tidak penting; bukan begitu. Tapi Kiai Dahlan itu yang ditarik sana-sini dan Kiai Dahlan juga tertarik. Di tengah pergaulan dengan Boedi Oetomo itulah muncul gagasan untuk membuat organisasi.
Pengalaman organisasi Boedi Oetomo ini yang menjadi inspirasi untuk gagasan kebersatuan dalam organisasi. Jadi, bukan sekadar masuk Boedi Oetomo untuk mempermudah izin.
Kalau gagasan tatanan baru pemikiran-pemikiran organisasi pada abad itu, apa yang paling membedakan dari Kiai Dahlan?
Pencerahannya, enlightenment. Itu yang tidak ada di Boedi Oetomo dan organisasi lain. Ini gerakan bawah, mengumpulkan orang-orang yang menderita, lalu kemudian disadarkan.
Tapi Muhammadiyah sendiri berangkat dari golongan elite?
Iya, tapi kemudian yang digarap adalah orang-orang bawah. Ini yang tidak ada di Sarekat Islam, tidak ada di Boedi Oetomo. Orang-orang yang kudisan, korengan, kan, enggak diopeni oleh yang lain, tapi diopeni [ditolong] oleh Kiai Dahlan.
Pendirian Muhammadiyah cenderung didasarkan pada gerakan Wahabi atau kondisi sosial saat itu?
Waktu itu bukan hanya Wahabi. Saya sering melukiskan Kiai Dahlan itu berbeda dari Abduh. Abduh tidak punya ratusan rumah sakit. Walaupun memang Abduh memberikan inspirasi pada kita. Walaupun saya juga mengkritik pada aktivis Muhammadiyah sekarang karena tidak menangkap ruhnya gerakan sosial Dahlan. Sehingga yang ditangkap itu mendirikan sekolah, lalu mendirikan rumah sakit—ya itu bagus. Tapi sekolah itu mendorong perubahan apa? Itu yang tidak ditangkap pada pengelola-pengelola sekolahan.
Kemudian rumah sakit itu mendorong perubahan apa? Karena ini kepedulian kok kepada mereka-mereka yang gagal sehat itu. Dulu itu gratis. Tentu saya bukan menolak rumah sakit berbayar, tapi spiritnya itu, loh.
Kiai Suja’ ya yang mengembangkan?
Iya, yang kemudian mengorganisir adalah Kiai Suja’, tapi idenya, kan, dari Kiai Dahlan.
Jadi Kiai Dahlan menggarap pendidikan, kesehatan, karena tidak digarap organisasi lain?
Kalau tidak disentuh organisasi lain, ya memang tidak ada dulu organisasi Islam selain Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama belum, Persatuan Islam juga belum, Sarekat Dagang Islam di kalangan elite. Soal pendidikan ini kunci untuk mengubah cara pandang. Islam itu harus berpikir produktif, harus berkarya bagi kemanusiaan. Berkali-kali saya mengatakan, Muhammadiyah itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemanusiaan.
Maka saya juga mengkritik tujuan pendidikan Muhammadiyah untuk mencetak kader—itu tidak bisa, itu omong kosong. Wong yang masuk itu orang macam-macam, kok, lalu masuk lima tahun lalu jadi kader. Enggak. Tujuan yang terutama itu manusia yang baik, Muslim yang baik, lalu sebagian kecil jadi Muhammadiyah yang baik. Sebab, kalau [untuk tujuan] kader itu ya gagal semua.
Dulu pernah jadi perdebatan apakah Muhammadiyah itu organisasi kader atau organisasi massa? Kalau dalam perdebatan itu, ya organisasi Muhammadiyah adalah organisasi kader: mencetak orang-orang—yang dalam sebuah dokumen itu disebutkan sebagai anggota Muhammadiyah—di manapun berada harus bisa mengubah masyarakat tanpa harus menggunakan embel-embel Muhammadiyah. Nah, kalau begitu, berarti organisasi kader.
Tadi Anda bilang, Muhammadiyah lebih cenderung gerakan kebudayaan, tapi di awal pendirian, Muhammadiyah tidak bisa lepas dari politik kolonial, terutama misalnya, Kiai Dahlan juga pernah terlibat di Sarekat Islam?
Memang kita bisa memperdebatkan apa maknanya, mungkin lebih pas kalau disebut kooperatif, walaupun tidak sesederhana itu. Jadi, kalau kita melawan begitu besarnya Belanda dan di belakang itu ada kolonialisme, kapitalisme, tidak hanya di Indonesia tapi dunia, maka jalan yang ditempuh adalah kooperatif.
Menggunakan kekuasaan Belanda untuk mengubah kesadaran baru—yang dalam kampanye dengan Jokowi dulu saya katakan, "Muhammadiyah itu sebetulnya menciptkan infrastruktur kebangsaan". Orang lalu sadar berorganisasi, orang lalu sadar tujuan hidupnya, sadar bagaimana orang harus bersatu, bergotong-royong.
Mengapa begitu? Karena Muhammadiyah lebih dulu ada daripada gerakan-gerakan yang lain.
Pada momentum apa terjadi perubahan gerakan kultural ke arah politik di Muhammadiyah?
Tentu sekali lagi penjelasan itu harus memilih, karena tidak semuanya dapat memilih. Itu dimulai ketika dibentuknya Majelis Tarjih yang memulai gerakan kebudayaan, tapi ditangkap kemudian sebagai gerakan Fikih. Fikih itu hukum, hukum itu politik. Saya punya dokumennya, yang Anda bisa baca, sesungguhnya itu didirikan Majelis Tarjih untuk mendamaikan pertengkaran antara orang-orang Islam yang berkaitan dengan bagaimana laku agama.
Muhammadiyah itu menempatkan diri sebagai saudara tua. Saya curiga, Jepang baca itu jadi menempatkan diri sebagai saudara tua, begitu dulu. Jadi bukan gerakan Fikih. Baru tahun 1930-an dan 1935-an itu jadi gerakan Fikih yang sebetulnya diperbarui oleh Muhammadiyah: Majelis Tarjih diubah lalu dibentuk delapan divisi.
Bersamaan itu ada gerakan kemerdekaan. Itu ada di disertasi saya yang diterbitkan Galang Press. (Marhaenis Muhammadiyah, 2010)
Embrio gerakan politik Muhammadiyah paling kentara pada kepemimpinan Kiai Ibrahim?
Saya tidak terlalu banyak membaca Kiai Ibrahim, tapi kalau kekuasaan itu menggunakan politik ya sejak Kiai Dahlan. Misalnya, Kiai Dahlan mengusulkan kepada pemerintah agar di tempat-tempat umum didirikan musala. Dulu mencari Musala itu susahnya bukan main.
Lalu dia usul pada pemerintah Hindia Belanda, kalau memeriksa orang mati, bila perempuan, ya harus dokter perempuan. Tapi bagaimana menangkap upaya-upaya politik ini dilembagakan? Nah, sekali lagi saya tidak terlalu banyak membaca soal Kiai Ibrahim.
Mungkin saya hanya melihat begini: Bersamaan Indonesia bergerak mencapai kemerdekaannya, sehingga kesadaran politik jadi kesadaran para aktivis pergerakan, termasuk Muhammadiyah, kemudian bergabung ke Masyumi; hanya Muhammadiyah tetap pada gerakannya. Dan itu jauh sebelum kemerdekaan terjadi.
Lalu ada istilah politik praktis. Itu kemudian dipercayakan kepada Masyumi. Sehingga Muhammadiyah jadi anggota istimewa Masyumi. Itu yang saya kritik sekarang. Karena Muhammadiyah jadi tidak jelas sikap politiknya. Karena bersumber pada dokumen lama yang diterbitkan sebelum Masyumi bubar, itu menjelang pemilu pertama yang namanya Mukadimah Anggaran Dasar, bersamaan keterlibatan Ki Bagus Hadikusumo di dalam menyusun UUD 45.
Jadi, gerakan Muhammadiyah ada dua sisi: politik yang diserahkan kepada Masyumi; dan gerakan dakwah yang sekarang ini. Namun, ini belum diperbarui. Usul saya: ini harus diredefinisi supaya “kerja politik” Muhammadiyah jadi jelas. Tidak seperti sekarang. Di satu sisi pengin kekuasaan, di sisi lain anti-kekuasaan—kan, jadi lucu.
Tapi ya terserah generasi muda Muhammadiyah bagaimana menangkap zaman. Kan saya sudah tua, saya sudah 72 tahun sekarang.
Ada perubahan enggak dari Muhammadiyah setelah Ahmad Dahlan meninggal?
Banyak sekali. Tadi pernah saya sampaikan, misalnya bagaimana Muhammadiyah menghadapi tradisi? Tidak sekasar sekarang. Itu sudah saya tulis di Museum Kebangkitan Nasional ketika memperingati 20 Mei 2016. Kiai Dahlan dulu mengubah tradisi gugon tuhon tidak langsung face a face tapi lewat penyadaran, lewat pendidikan; Muhammadiyah tidak kemudian bertabrakan dengan tradisi.
Itu kemudian juga dikritik oleh Kuntowijoyo: “Muhammadiyah itu gerakan kebudayaan tanpa kebudayaan”.
Muhammadiyah itu, kalau kritik Kuntowijoyo, seolah-olah mematikan tradisi tapi enggak menciptakan tradisi baru. Jadi, kami memimpin bersama Buya (Syafi'i Ma'arif) mengembangkan dakwah kultural. Tapi kemudian ditolak, seolah-olah Muhammadiyah itu mengadopsi tradisi. Tujuan kami bagaimana masyarakat menyadari dirinya sendiri, membawa dirinya sendiri berpikiran terbuka. Itu yang berangkali patut dicatat dalam peringatan Milad Muhammadiyah ke-105 tahun ini.
Jadi ini penyadaran. Gerakan kebudayaan itu penyadaran. Tidak struktural. Sehingga kesannya Muhammadiyah itu anti-seni, anti-tradisi. Dulu pakaian Muhammadiyah itu Jawa, justru yang di luar Muhammadiyah itu ke-arab-arab-an, pakai sorban. Muhammadiyah tu justru Jawa, karena memang gerakan kebudayaan tadi.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Fahri Salam