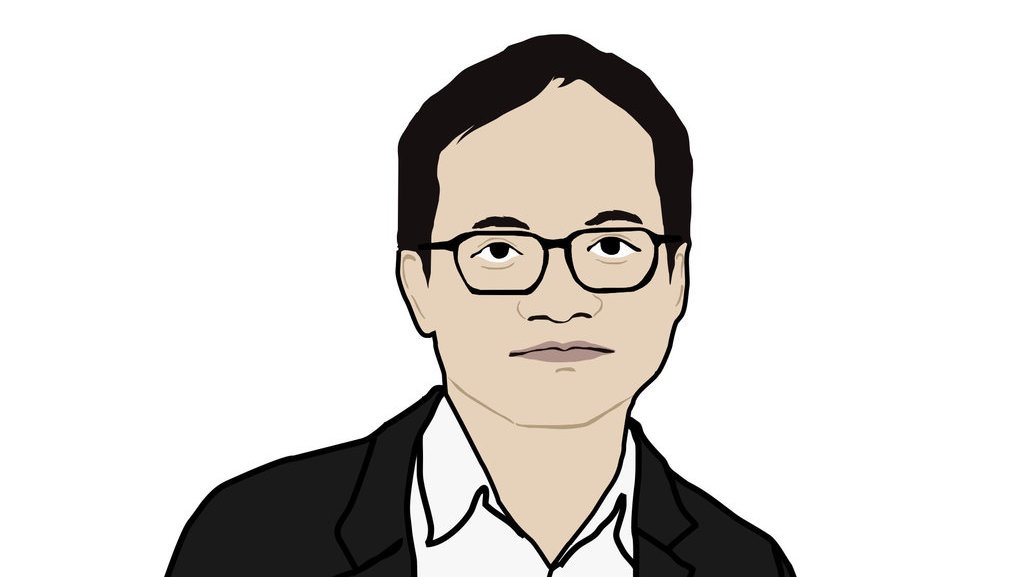tirto.id - “Mentari terbit dari timur”. Demikianlah Kairo memandang Jepang sebagai kekuatan baru, penentang kedigdayaan Barat, dan pendobrak kolonialisme-imperialisme kulit putih pada 1905. Kemenangan Jepang melawan Rusia dalam memperebutkan pengaruh maritim dan geopolitik di Manchuria dan Korea pada 1904-1905 melahirkan harapan di seluruh pelosok Asia dan dunia Islam. Rusia yang sering merepotkan Usmani akhirnya keok.
Di berbagai tempat yang dikuasai imperium Turki Usmani akhir, Jepang dielu-elukan, bahkan sempat diharapkan masuk Islam dan jadi pusat kekhalifahan baru. Asia Tenggara, yang kala itu masih disebut Jawah dalam buku-buku dan berita Arab, juga tak kalah girangnya. Bintang Hindia, sebuah koran penting yang membangkitkan nasionalisme beberapa tahun sebelum berdirinya Boedi Oetomo, menemukan momentum globalnya. Penjaga gawang Bintang Hindia, Abdoel Rivai, seorang intelektual pencibir kekolotan sukunya, layak disebut orang paling bahagia dengan warta kemenangan Jepang. Cita-cita kebangsaan tanah air yang disuarakannya semakin menggebu-gebu. Pan-Asianisme bergelora, Pan-Islamisme semakin menyala-nyala. Penulis biografi Abdoel Rivai pada 1938 dengan tangkas menangkap metafora, “undang-undang alam melakukan keadilannya.”
Atas kemenangan Jepang Cemil Aydin menulis, kaum intelektual Asia tak menganggap keterbelakangan masyarakat Asia berasal dari kombinasi nasib dan bawaan mutlak seperti ras, budaya, geografi, cuaca dan agama. Kondisi tersebut, lanjut Aydin, adalah sebentuk kemajuan tertunda yang mesti dijemput lewat serangkaian reformasi terstruktur seperti Restorasi Meiji yang dilakukan Jepang. Diramu dengan racikan pembaruan Islam—yang salah satunya disuarakan oleh Muhammad Abduh dan pengikutnya—kemenangan Asia itu bakal ditatap bangsa-bangsa Eropa sebagai momok.
Belanda mengamininya. Bahkan dalam Kongres Misionaris Kristen 1911, Islam ditakuti.
Antara 1900 dan 1911, kehidupan Ahmad Dahlan (terlahir dengan nama Muhammad Darwisy) bersentuhan dengan kebangkitan harga diri Asia yang mengglobal itu. Perlahan-lahan ia menyusun batu-bata gerakan pembaruan Islam. Dahlan bukan penulis, juga bukan intelektual garda depan. Tapi ia seorang penggerak.
Dalam dunia kepenulisan, ia memang tak serajin Hasyim Asy’ari, kawan sekelas Dahlan saat belajar di bawah bimbingan Kiai Saleh Darat di Semarang. Konon hanya dua kali sang kyai menerbitkan tulisan dan salah satunya membuat elit-elit Belanda terperangah. Tulisan itu, menurut catatan antropolog Belanda Bertram Schrieke (1922), berjudul “Tali pengikat umat manusia” yang lantas diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda “Het bindmiddle der menschen” dan terbit dalam sebuah buletin. Tak satu pun dari kita kini dapat menemukan jejak tulisan tersebut.
Pembaruan Islam
Pada 1962, Sukarno menyebutnya “manusia amal”—kira-kira seperti itulah Ahmad Dahlan dikenal. Ia ditulis dan dikisahkan oleh murid-muridnya karena tindakannya.
Ketika Islamofobia menyebar di Eropa, pada 18 November 1912 Muhammadiyah resmi berdiri. Prinsip yang teguh dipegang Dahlan sejalan dengan gagasan kemajuan era modern saat itu. Dirawayatkan dari seorang muridnya, Dahlan berkata, “Kita tak boleh memungkiri adanya gerak alam. Gerak itu ialah gerak menuju kemajuan. Kemajuan itu menuju keselamatan dunia.”
Sulit membuktikan apakah Dahlan ikut menyebarkan buku al-Islam wa al-ʿulum al-ʿasriyyah atau Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern karangan Tantawi Jawhari. Buku itu lahir dari lingkaran intelektual Abduh dan telah menjadi kurikulum sekolah dasar di Sumatra. Meski demikian, suluh pembaruan Dahlan tak dapat dipungkiri. Ia menjadi bagian dari apa yang disebut Michael Laffan “rasa kebangsaan Islam”.
Meskipun tak populer di kalangan intelektual progresif atau tradisional di Kairo atau Hijaz, keningratan Dahlan cukup dihormati di lingkaran Muslim Indonesia di luar negeri.
Dua kali Dahlan berhaji dan menimba ilmu di Mekkah dalam waktu yang tak terlalu lama. Ia berjumpa seorang ulama bernama Sayyid Abu Bakr Syatta, murid dari Ahmad Zaini Dahlan, profesor dan pemuka agama terkemuka di Mekkah yang fatwanya dirujuk lintas-bangsa, termasuk Asia Tenggara.
Sebagaimana lazimnya para haji saat itu, Syatta mengganti nama Muhammad Darwisy menjadi Ahmad Dahlan. Banyak yang menafsirkan pergantian nama itu sebagai upaya mencari berkah dari ulama Mekkah tersebut. Pada perjalanan haji yang kedua, menurut riwayat Ahmad Syuja, selama 18 bulan Dahlan belajar hukum, ilmu falak dan hadis dari Kyai Mahfuzh Termas dan sejumlah ulama Arab ternama lainnya. Dahlan juga mengakrabi para ulama Jawi di Mekah.
Ketika itu, spirit reformasi dan kemajuan dari Istanbul dan Kairo tersebar hingga ke tanah suci. Jaringan kaum cerdik-cendekia Jawi giat menelaah buku-buku Muhammad Abduh. Dahlan mendapatkan akses langsung ke buku-buku lingkaran Abduh dan berjumpa langsung dengan Rasyid Rida di tanah suci. Saat bertemu Ahmad Soerkatty di Jawa beberapa lama kemudian, konon Dahlan tengah membawa Tafsir al-Manarkarya Abduh dan Rasyid Rida. Sejumlah buku karangan Abduh dan Ibnu Taymiyyah dan beberapa karya mazhab Hanbali menjadi favorit Dahlan, mengilhami langkahnya untuk menyatukan aspek etis dan pergerakan sosial-progresif yang dibangun dari lingkungan masjid.
Dahlan pernah berpolemik dengan Hasyim Asy’ari tentang dinamika Sarekat Islam yang secara internal tidak dipandang cukup Islami. Polemik itu bahkan ikut ditanggapi Ahmad Khatib Minangkabawi ulama senior yang sudah lama tinggal di Mekkah.
Meski bukan penulis, Dahlan konsisten meneruskan perjuangannya secara kultural seraya menjaga hubungan baik dengan Sarekat Islam yang saat itu jadi kanal politik Islam, juga dengan Boedi Oetomo yang telah ia dekati meski sering tak menyepakati orientasi teosofis organisasi tersebut.
Jalan Dahlan
Di jalur kultural itulah Dahlan memiliki strategi yang unik.
Suatu ketika pemerintah Belanda didesak kalangan progresif dalam negeri agar menerapkan Politik Etis sebagai balas budi dan tanggung jawab moral kepada bangsa Hindia Belanda. Antropolog Snouck Hurgronje jauh-jauh hari sudah menasihati pemerintahan kolonial. Dalam bayangan Snouck, untuk menaklukkan berbagai pemberontakan dan pembangkangan massa, orang-orang Hindia Belanda perlu diberi pendidikan berorientasi Barat sehingga bisa mengemban tanggung jawab dan kewajiban sebagai calon administrator pemerintahan kolonial.
Diam-diam, sejumlah penganjur Politik Etis memang menyiapkan skema: kelak jika kaum Eropa mesti ditarik dari tanah jajahan dan kaum terpelajar Indonesia pada masanya dapat mengatur negerinya sendiri. Pada era di mana masyarakat Eropa semakin terkucil dan terpencil, kaum bumiputera terekspos buku-buku Barat yang menawarkan modernitas. Kelompok elit sekuler bermunculan, terutama dari kalangan nasionalis seperti Soekarno.
Dalam historiografi konvensional, Muhammadiyah muncul sebagai respons atas sikap acuh tak acuh (onverschillig)serta rasa kebencian di kalangan intellgentsia terhadap agama Islam. Elit sekuler yang terdidik Barat dan tidak memiliki akses langsung ke khazanah tradisi Islam mencibir agama ini “kolot” dan “tidak mengikuti perkembangan zaman”.
Anggapan ini dibenarkan oleh Dahlan. Diriwayatkan oleh Ahmad Syuja, menurut Ahmad Dahlan umat Muslim di Jawa “pada umumnya sangat daif dan jiwanya diliputi minderwaardehuidscomplex—keminderan.”
Muhammadiyah lahir dari rahim pendidikan kader bernama Fath al-asrar wa miftah al-saʿadah (“Penyingkap Tabir Rahasia dan Pembuka Jalan Kebahagiaan”). Dalam format forum, Dahlan sudah mendidik puluhan siswa/santri dengan model pendidikan modern ala Belanda.
Langkah yang diambil Dahlan mirip Abduh di Kairo. Keduanya tidak bersikap konfrontatif terhadap kolonialisme Eropa, alih-alih menempuh cara kreatif: modernisasi.
Jalan modernisasi kultural ini sebetulnya punya jejak panjang yang dapat dilacak hingga ke India dan Istanbul pada pertengahan abad ke-19. Di Hindia Belanda, meski berwatak lokal dan tidak diizinkan membuka cabang di luar Jawa hingga 1920, kemunculan Muhammadiyah adalah satu mata rantai transformasi global pada zamannya. Metode, buku, dan musik Barat diadopsi tanpa malu-malu. Meski kerap melayangkan tudingan bid’ah pada berbagai praktek tradisi Islam yang dianggap berlebihan, Muhammadiyah juga sempat dianggap bid’ah karena memperkenalkan do re mi fa sol la si do. Padahal, formula solmisasi ini diadaptasi Franciszek Meninski pada abad ke-17 justru berasal dari tradisi Arab abad pertengahan yang bernama durar mufassalat atau “mutiara yang terpisah-pisah”.
Demikian, saling pengaruh dalam seni dan musik antara Turki Usmani, Persia dan Barat sudah dipandang lumrah dan tidak mengandung beban permusuhan. Meski terlambat dalam konteks nusantara, Dahlan benar. Ia berupaya merespons Kristenisasi yang saat itu masif beriringan dengan kolonialisme. Kendati begitu, Dahlan berjiwa inklusif. Ia tak menolak sama sekali untuk menemui figur Jesuit seperti Van Lith dan Van Driesse, sebagaimana ia berusaha merangkul tokoh teosofis Dirk van Hinloopen Labberton dan elit keraton Ki Ageng Soerjomentaram.
Kendati tidak konfrontatif, bahkan sering sengit dengan kelompok kiri, Muhammadiyah berkembang dari situasi pasca diterapkannya kebijakan Goeroe Ordonnantie. Peraturan ini membatasi gerak-gerik para guru agama yang pada 1888 menggerakkan pemberontakan petani di Banten. Dahlan turut berusaha mempersiapkan kemandirian guru. Dengan jaringan sosial yang menjangkau para pengusaha dan lingkaran elit keraton, mudah bagi Muhammadiyah untuk merangkul apa yang kita sebut hari ini sebagai kelas menengah kota. Modal sosial inilah yang kemudian sangat berarti di kemudian hari sebagai mesin penggerak persyarikatan. Kecerdikan strategi ini kurang disadari oleh lingkaran penggerak Nahdlatul Ulama. Selama beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, sejumlah anggota NU bahkan masih menganggap sekolah umum sebagai tabu dan cermin dari kolonialisme dan/atau kekafiran.
Namun kita juga perlu awas dengan proses pengerasan hukum dan norma kemuhammadiyahan setelah wafatnya Dahlan. Dalam pergeseran sikap ini, Najib Burhani dalam Muhammadiyah Jawa (2016) menjelaskan bahwa gaya dahlan yang lentur dan supel segera segera digantikan oleh sebuah model yang lebih puritan. Jika Abduh adalah sumber inspirasi bagi Muhammadiyah, maka kembali mempelajari Abduh merupakan sebuah panggilan untuk kembali ke khittah intelektual-pergerakan. Abduh tak saja menyerap filsafat Yunani dan Islam dengan baik, tetapi juga tradisi Barat pada masanya.
Ruh dan gairah membumikan kesejahteraan sosial dan pendidikan ala Ahmad Dahlan memang masih menyala kuat. Namun mungkinkah semangat intelektual Abduh menyala kembali di dalam pikiran anak-anak muda Muhammadiyah hari ini, di tengah gempuran puritanisme yang anti-intelektual dan anti-pluralisme di awal abad ke-21 ini?
Transformasi Islam setaraf Reformasi Meiji bagi bangsa Indonesia belum juga muncul. Bisakah Muhammadiyah menjadi motornya?
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id