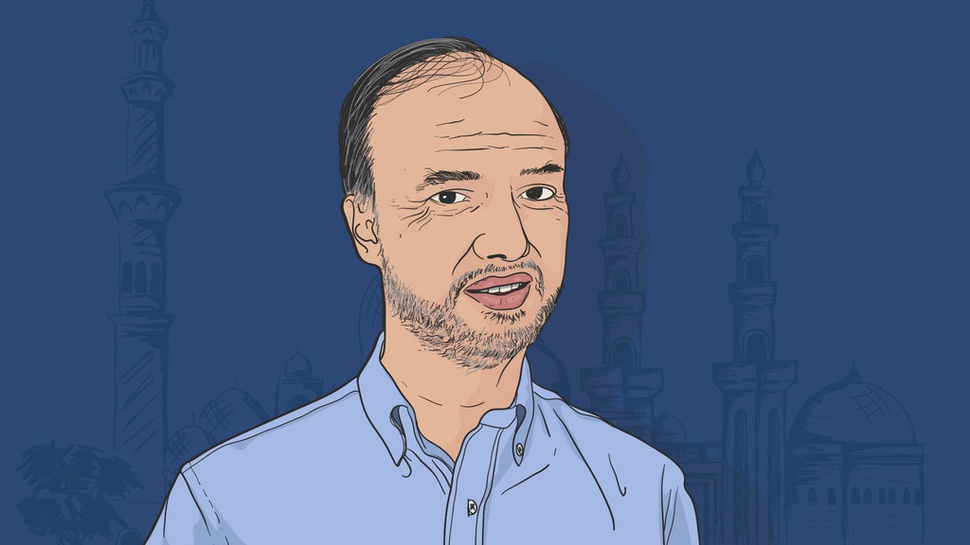tirto.id -
Sepuluh abad kemudian, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tergolong tidak sejahtera dibanding negara-negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Indikatornya, perang, konflik, pendapatan nasional bruto, tingkat melek huruf, lama masa sekolah dan tingkat harapan hidup. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki peringkat lebih rendah dibanding negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim pada sejumlah kategori tersebut.
Nilai-nilai intrinsik agama Islam dan kolonialisme kerap disebut sebagai dua alasan kemunduran dunia Islam sampai saat ini.
Tapi, dosen ilmu politik dari San Diego State University Ahmet T. Kuru menyangsikan dua alasan kemunduran itu.
Pada April 2021 lalu, Tirto berbincang dengan Kuru, penulis Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan (2021), melalui sambungan video. Ia menjelaskan panjang lebar soal pandangan-pandangan bermasalah terkait penyebab kemunduran negeri-negeri Muslim, faktor-faktor penyebabnya, hingga harapan bahwa dunia Islam sungguh punya potensi untuk kembali ke masa keemasan. Kuncinya, menurut Kuru, adalah memahami sejarah dunia Muslim sebelum abad pertengahan.
Berikut petikan wawancara dengan Ahmed T. Kuru.
Karya Anda menyoroti perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat dunia Muslim yang dampaknya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Contohnya anti-intelektualisme dan otoritarianisme. Buku Anda memaparkan perubahan-perubahan ini disebabkan oleh aliansi antara ulama, negara, dan kekuasaan militer. Bagaimana persisnya represi intelektual ini terjadi?
Saya rasa kita perlu melihat terlebih dulu kondisi dunia saat ini. Dari 200 negara, 49 di antaranya adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim. Negara dengan penduduk mayoritas Muslim punya masalah otoritarianisme dan ketertinggalan. Perkembangan intelektual di negara-negara tersebut juga terhambat.
Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan masalah ini muncul di negara berpenduduk mayoritas Muslim?
Para akademisi dan politisi, baik di dunia Barat maupun orang-orang di wilayah Timur Tengah, menyalahkan Islam. Mereka menganggap agama Islam sebagai sumber masalah di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim.
Saya menyikapi pendapat tersebut dengan serius dan membuktikan kelemahan-kelemahannya dalam buku. Pada abad ke-8 hingga 12, negara berpenduduk mayoritas Muslim adalah negara paling maju bila dibandingkan dengan negara lain di dunia termasuk Eropa Barat. Kejayaan tersebut mencakup bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan perkembangan ekonomi. Islam sangatlah kompatibel dengan kaum intelektual dan kemajuan ekonomi.
Sekarang, ada variasi dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Contohnya Indonesia, negara demokratis dengan pertumbuhan pada bidang sosial dan ekonomi. Di samping itu, ada pula negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang otoriter dan tertinggal.
Oleh karena itu, tidak tepat menempatkan agama sebagai alasan utama kemunduran.
Pendapat lain menyatakan imperialisme dan kolonialisme dari dunia Barat sebagai penyebab kemunduran negara berpenduduk mayoritas Muslim. Saya kembali menunjukkan bahwa pendapat ini problematis. Karena secara kronologis, ketika kolonialisme Barat dimulai pada abad ke-18, negara berpenduduk mayoritas Muslim sudah mengalami stagnasi ekonomi dan intelektual. Jadi masalahnya sudah ada sebelum kolonialisme.
Di samping itu, seandainya sumber masalah hanya difokuskan pada serangan dari pihak luar seperti invasi, kolonialisme, maka masalah internal justru tersisihkan. Agar bisa menyelesaikan masalah, kaum Muslim wajib fokus pada permasalahan domestik dan bagaimana cara mengatasi masalah dalam institusi Muslim dan ide-ide dari para penganut Muslim. Jadi, fokus pada aspek kolonialisme justru problematis.
Saya sendiri berpandangan bahwa kita perlu melihat relasi dari empat kelompok berbeda. Golongan agama, politik, intelektual, dan ekonomi.
Pada masa keemasan dunia Muslim abad ke-8 dan 12, ada golongan intelektual yang begitu dinamis seperti cendekiawan agama, Abu Hanifa; dan filsuf seperti Ibnu Sina, Farabi, Ibnu Haytham yang berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan.
Mereka mendesain formula matematika seperti algoritma, aljabar, dan lain-lain. Bilangan nol dan bilangan numerik lain juga diciptakan oleh intelektual Muslim. Mereka mempelajari hal tersebut dari India dan menyebarkan ilmunya sampai ke Eropa Barat.
Selain itu, dunia Muslim juga punya kaum pedagang yang juga bisa disebut kaum borjuis. Kelas pedagang ini melahirkan temuan-temuan yang masih dipakai oleh masyarakat Eropa Barat sampai sekarang misalnya cek dan beberapa hal lain dalam sistem perbankan.
Tapi, pada pertengahan abad ke-11, relasi kelas ini mulai berubah.
Pada abad ke-7-11, sebagian besar golongan ulama—cendekiawan Muslim yang mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan Islam—adalah sosok independen. Mereka bukan bagian dari birokrasi pemerintah.
Tapi pada abad ke-11, terjadi perubahan dalam berbagai aspek.
Sistem ekonomi berubah dari ekonomi pasar menjadi sistem iqta yang semi-feodal di mana negara mengontrol lahan, pajak atas lahan, dan perekonomian secara umum.
Secara politik, struktur negara menjadi lebih militeristik. Negara dan kerajaan militer seperti Ghaznawiyah di India Utara dan Seljuk di Asia Tengah, menegaskan penaklukkan dan peran militer dalam struktur kenegaraan.
Selain perubahan ekonomi dan politik/militer, ada pula perubahan di bidang agama.
Pada pertengahan abad ke-11, dua khalifah Abbasiyah, Qadir dan Qaim, ayah dan anak, mendeklarasikan aliran Sunni. Mereka mengkafirkan kaum Muktazilah (para filsuf rasionalis Muslim), beberapa aliran Syiah khususnya Ismailiyah, dan umat Islam yang tidak menjalankan salat lima waktu. Deklarasi ini juga menandai terbentuknya ortodoksi Sunni.
Ini adalah reaksi terhadap dinasti Syiah dan otoritas politik yang sudah menguasai Mesir di bawah pimpinan dinasti Fathimiyah, beberapa bagian di semenanjung Arab di bawah dinasti Qaramitah, Suriah bagian utara di bawah pimpinan orang-orang Hamdani, dan Iran juga Irak termasuk Baghdad di bawah dinasti Buwaihi.
Seruan khalifah Abbasiyah untuk menyatukan seluruh penganut Sunni dalam aliran Sunni ortodoks ini disambut dinasti Seljuk. Prajurit Seljuk yang nomaden datang ke Baghdad, mendirikan kekuasaan Sunni di Baghdad. Mereka menggunakan sistem iqta untuk mengontrol perekonomian dan untuk memberikan lahan kepada pimpinan militer.
Kemudian, Perdana Menteri Nizam al-Mulk mulai mendirikan sistem madrasah.
Jadi, ortodoksi Sunni dan kekuasaan militer membuat kelas pedagang termarjinalkan.
Mereka tidak lagi didukung oleh kaum intelektual Muslim. Kaum intelektual didukung oleh negara khususnya sistem madrasah yang dikenal sebagai madrasah Nizhamiyah.
Tokoh intelektual penting, Ghazali, juga membantu terbentuknya sistem baru ini. Ia menulis buku seperti Tahafut Al-Falasifa (Kerancuan Para Filsuf) yang isinya menyerang para filsuf. Ia juga menyerang sejumlah aliran Syiah.
Ghazali adalah figur yang kompleks. Saya suka beberapa bukunya. Tetapi ada aspek dari warisan pemikirannya yang sangat anti-intelektual. Pada bagian akhir buku Tahafut Al-Falasifa, Ghazali mengajukan pertanyaan hipotetis: “Mungkinkah filsuf seperti Farabi, Ibnu Sina, dianggap murtad dan bisakah pengikutnya dihukum mati?” Dia menjawab “Ya” dengan tiga alasan. Pertama, filsuf seperti Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain mengklaim bahwa dunia kekal. Alam semesta secara materil itu kekal. Kedua, kebangkitan setelah mati itu sifatnya spiritual, bukan lewat tubuh manusia. Ketiga, Tuhan memahami hal makro, hal besar, tetapi tidak peduli dengan detail.
Jadi karena tiga klaim di atas dan pemahaman Ghazali atas filsafat, para filsuf ini pun divonis murtad.
Setelah itu, ortodoksi Sunni memakai fatwa Ghazali dan ulama-ulama lainnya untuk menghukum para filsuf, memvonis mereka murtad. Ini menjadi alat represi politik untuk menghukum siapapun yang memiliki pandangan yang berseberangan, yakni pihak oposisi. Walhasil, filsuf dipandang sebagai profesi yang buruk.
Setelah abad ke-12, orang mulai takut disebut filsuf. Pola pikir anti-intelektual ini terus berlajut sampai sekarang.
Tentu saja ada banyak perubahan setelah abad ke-11. Namun, secara umum, apa yang saya sebut sebagai aliansi ulama-negara dibangun setelahnya. Ulama jadi bagian dalam birokrasi negara yang berkolaborasi dengan kekuatan militer. Lalu, muncullah reaksi keras terhadap filsuf dan kaum intelektual lain. Filsuf dan intelektual dianggap tidak cukup saleh dan bukan Muslim yang baik.
Sampai sekarang, pemahaman seperti ini membuat kehidupan kaum intelektual di dunia Muslim sangat stagnan. Inilah mengapa kita menghadapi berbagai masalah sampai sekarang.
Bisa Anda jelaskan bagaimana perubahan-perubahan ini bisa terjadi pada abad ke-11 dan apa yang menjadi penyebabnya?
Sebelum abad ke-11, jika kita membandingkan dunia Muslim dengan Eropa Barat, kehidupan publik di Eropa Barat didominasi oleh institusi Katolik dan aristokrat militer. Jika dibandingkan dengan dunia Muslim, di Eropa Barat saat itu tidak ada kelas pedagang dan intelektual.
Itulah mengapa pada abad ke-6-11, perekonomian dan kaum intelektual Eropa Barat sangat lemah dan stagnan. Sementara kondisi politik dan agama di dunia Muslim sebaliknya.
Saat itu, cendekiawan Muslim dan ulama berjarak dengan otoritas politik.
Mengapa dan bagaimana? Karena setelah Nabi Muhammad dan empat khalifahnya—yang memiliki karisma personal dan otoritas relijius—negara Muslim pertama dalam sejarah Islam dibangun oleh Muawiyah, pendiri dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dibangun berdasar persekusi anggota keluarga Nabi Muhammad, termasuk pembunuhan Hussein, cucu Nabi.
Itu menjelaskan mengapa penganut Syiah hari ini sangat tidak mengakui keabsahan dinasti Umayyah dan kaum Sunni pun tidak mengakui legitimasi para pemimpin Umayyah. Sebagian besar pemimpin Umayyah senang dengan hal itu. Mereka menganggap diri mereka raja. Faktanya, dalam sejarah Islam, Muawiyah adalah orang pertama yang memakai mahkota, singgasana, dan merekrut pengawal sebagai simbol negara.
Makna dan tujuan negara jadi hal yang sangat penting buat Muawiyyah. Oleh karena itu, kita melihat pemisahan antara otoritas agama dan politik. Para penguasa Umayyah dipandang sebagai penguasa politik dan karena mereka mempersekusi anggota keluarga Nabi, ini dimaknai ulama bahwa para penguasa politik, emir, raja, sultan itu korup, tidak bermoral, dan ulama harus menghindari kontak langsung dengan mereka.
Di bawah rezim Abbasiyah, tren yang sama berlangsung meski ada sedikit perubahan. Seperti yang kita lihat sekarang, ada empat mazhab utama Sunni: Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali. Para pendiri mazhab ini dipersekusi negara.
Abu Hanifah adalah pedagang sutra dan khalifah Abbasiyah memintanya untuk jadi hakim. Abu Hanifah menolak. Khalifah berkata, “Beri aku alasan.” Abu Hanifah bilang, “Aku tidak cukup kompeten.” Kemudian khalifah marah dan berkata, “Kau pembohong.” Abu Hanifah merespons, “Pembohong tidak akan pernah bisa jadi hakim.”
Sang penguasa mengirim Abu Hanifah ke penjara. Dia diracun sampai meninggal.
Malik disiksa dan dipukuli. Syafii ditahan dan dipersekusi. Bahkan Ahmad bin Hambal dipenjara dan divonis hukuman mati dan tak bisa menghindari hukuman tersebut. Dia dan banyak ulama lain mengharamkan cendekiawan Muslim menerima uang dari negara.
Hal ini akhirnya memunculkan keragaman dalam memandang agama dan filsafat. Di bawah dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pemimpin negara punya akses yang terbatas untuk mensakralkan otoritas mereka.
Mereka tidak pernah berhasil mengklaim kekuasaan mereka suci adanya. Tidak seperti di Eropa di mana raja bisa mengklaim dirinya suci dan utusan Tuhan, setidaknya sampai abad ke-11. Tetapi pada abad ke-11 terjadi transformasi besar pada dua wilayah tersebut.
Pada pertengahan abad ke-11 hingga pertengahan abad ke-12 di Eropa Barat, Paus mencoba mendominasi politik sementara raja mencoba menguasai Vatikan. Keduanya gagal dan akihirnya mereka melembagakan pemisahan kekuasaan negara dan gereja sebagaimana yang kita pahami sekarang. Secara historis pemisahan ini muncul pada abad ke-11.
Dalam sejarah Islam, hal sebaliknya terjadi pada abad ke-11. Setelah 4-5 abad pemisahan antara otoritas agama dan politik, “aliansi ulama-negara” muncul karena transformasi ekonomi, politik, dan agama di bawah dinasti Seljuk lewat otoritas militer Seljuk, ortodoksi Sunni dari Khalifah Abbasiyah, Nizhamiyah madrasah dari Nizam al-Mulk, dan Ghazali, cendekiawan penting yang merancang kolaborasi ulama-negara.
Tapi bahkan sebagai arsitek aliansi ulama-negara, Ghazali sendiri mengalami momen naik turun dan inkonsistensi selama hidupnya.
Pada usia 40, ia menyesali perbuatannya. Ia pergi ke makam Nabi Ibrahim dan berjanji tidak akan melakukan tiga hal yakni menerima uang dari penguasa, tidak akan terlibat dalam debat di dalam istana dan tempat-tempat milik penguasa, dan tidak akan mengajar di lembaga yang didanai negara seperti madrasah Nizhamiyah.
Jadi bahkan Ghazali tahu dan paham ia mesti menjaga jarak dengan otoritas negara dan agama.
Aliansi negara-ulama masih berlangsung sampai sekarang. Bila Anda bertanya tentang Islam dan Kristen pada hari ini, banyak orang akan mengatakan tidak ada pemisahan antara agama dan negara dalam Islam, dan ada pemisahan negara dan agama dalam agama Kristen. Ini keliru.
Sampai abad ke-11, ada pemisahan antara negara dan agama di Islam tapi tidak di Kristen. Situasi berubah setelah abad ke-11 karena berbagai alasan yang saya simpulkan di atas.
Apa dampak jangka panjang kekuasaan militer Sunni?
Setelah imperium Seljuk berdiri, model aliansi ulama-negara, khususnya kolaborasi ulama-militer, diulangi oleh dinasti dan imperium-imperium selanjutnya. Jadi, Seljuk, sejak pertengahan abad ke-11 hingga pertengahan abad ke-12, membentuk model aliansi ulama-negara di mana negara mengontrol pemasukan dari lahan dengan mental militeristik, dan dengan ortodoksi Sunni di Asia Tengah, Iran, dan Irak. Tetapi setelah pertengahan abad ke-12, muncul gejolak di belahan barat dunia Muslim seperti Suriah, Palestina, dan Mesir. Di Barat ada Perang Salib dan di timur ada ancaman dari Mongol.
Ketika terjadi pembunuhan berskala besar di negara-negara Muslim, invasi dari Mongol dan Perang Salib, mereka mencoba mencari perlindungan dari militer. Karena ketika Anda melihat pembantaian massal, Anda tidak bisa mencari keselamatan lewat musik, seni, atau ilmu pengetahuan. Anda ingin diselamatkan oleh militer. Pahlawan militer datang lewat sosok Saladin yang mengalahkan prajurit Perang Salib. Saladin membangun dinasti Ayyubiyah dan dinasti Ayyubiyah melahirkan dinasti Mamluk. Mamluk adalah dinasti di Suriah dan Mesir. Saladin, Ayyubiyah, dan Mamluk melembagakan kolaborasi ulama-negara di Suriah, Palestina, dan Mesir pada abad ke-12 dan ke-13.
Model aliansi ulama-negara ini berpindah dari Asia Tengah ke Afrika Utara. Selanjutnya, setelah Perang Salib dan invasi Mongol, dunia Muslim pulih secara militer dan politik. Mereka membangun tiga kerajaan besar yaitu Turki Usmani, Safawiyyah, dan Mughal. Turki Usmani di Timur Tengah dan Balkan, Safawiyyah di Iran, dan Mughal di seluruh anak benua Asia termasuk India.
Tiga kerajaan ini menunjukkan bahwa Muslim sangat kuat secara militer dan politik tetapi mereka tidak pernah pulih dalam aspek intelektualitas dan ekonomi karena ketiga kerajaan itu dipimpin oleh aliansi ulama-negara. Imperium-imperium ini adalah kerajaan militer. Ketika di Eropa terjadi kebangkitan kelas borjuis dan intelektual, imperium-imperium Muslim tidak memiliki kelas borjuis dan intelektual yang dinamis.
Ketika Eropa memasuki masa Renaisans, Reformasi, revolusi cetak, revolusi ilmu pengetahuan, Pencerahan, dan revolusi industri, mereka menggunakan banyak perangkat, khususnya senjata api, kompas laut, dan mesin cetak. Tetapi tiga kerajaan Muslim ini hanya memilih senjata api karena mereka dipimpin oleh perwira militer yang hanya mengetahui pentingnya senjata api. Mereka tidak peduli dengan kompas laut karena selain imperium Usmani, tak satu pun dari kerajaan-kerajaan ini yang punya angkatan laut yang signifikan. Yang terpenting, tiga kerajaan ini tidak memiliki mesin cetak.
Turki Usmani adalah kerajaan pertama yang menerima teknologi mesin cetak—300 tahun setelah Eropa.
Itulah sebabnya pada abad ke-18, ketika Usmani mencetak 50 ribu buku, Eropa Barat sudah bisa menerbitkan 1 miliar buku. Memasuki awal abad ke-19, perkiraan tingkat literasi di imperium Usmani hanya 1%. Di Eropa pada era yang sama, tingkat literasi diprediksi mencapai 31%. Ini terus berlanjut sehingga ada ketimpangan tingkat literasi dan pendidikan antara dunia Muslim dan Eropa Barat. Itulah mengapa imperium militer mengalami kemunduran intelektual dan ilmu pengetahuan karena kolaborasi ulama-negara meminggirkan intelektual dan pedagang.
Anda menyatakan bahwa sejak abad ke-11 sampai sekarang banyak intelektual Muslim yang memandang diri mereka sebagai bagian dari kelas penguasa. Dengan pasang surut politik Islamis di satu sisi dan menjamurnya intelektual Muslim liberal di sisi lain, bagaimana intelektual Muslim memandang diri mereka saat ini?
Abu Hanifah dan banyak intelektual Muslim berjuang melawan tekanan politik. Mereka menjadi teladan bagaimana ranah ilmu pengetahuan Islam mampu mandiri dari otoritas negara. Bandingkan hari ini, sangat mengejutkan rasanya melihat penguasa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mengontrol masjid.
Negara mengontrol sekolah berbasis agama dan pelajaran agama. Contohnya Turki. Di sana ada sekitar 100.000 masjid yang semua dikontrol negara. Setiap Jumat, imam masjid menyampaikan khotbah yang teksnya dikirim dari lembaga pemerintah. Imam tidak memiliki kebebasan untuk mengajarkan hal-hal yang ia percayai sebagai kebenaran.
Hal serupa terjadi di Mesir. Sebagian besar masjid ada dalam pengaruh negara. Syekh Al Azhar, rektor Universitas Al Azhar, dan kepala sekolah-sekolah agama adalah politisi. Presiden Mesir memilih rektor Al Azhar. Di Pakistan, hukum penistaan agama mencerminkan bagaimana negara—atau aliansi ulama-negara—mengontrol ekspresi keagamaan individu. Di Iran, para mullah menempati posisi tertinggi dalam lembaga negara seperti Velâyat-e Faqih dan sebagainya.
Hal ini menimbulkan dampak yang sangat negatif untuk ulama dan agama karena agama jadi alat untuk mencapai tujuan politik dan mengerdilkan peluang demokratisasi. Pasalnya, para politisi jadi lebih sulit dikritik karena diglorifikasi dan disakralkan oleh orang-orang saleh. Para pengkritik dikambinghitamkan, dianggap bukan Muslim yang baik, dan dilabeli murtad atau penista agama.
Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, Anda harus melihat asal usulnya. Sekarang, kaum Islamis dan para pembenci Islam di dunia Barat (kami menyebutnya islamofobik) sama-sama sepakat dengan anggapan bahwa tidak ada pemisahan kekuasaan antara agama dan negara dalam Islam. Bila Anda bertanya kepada mereka dari mana sumber pernyataan tersebut, mereka akan bilang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan “Agama dan negara adalah kembar. Agama adalah fondasi, negara adalah pelindung. Yang tanpa pelindung akan binasa, tanpa fondasi akan hancur.”
Saya menganalisis pernyataan ini dan menemukan bahwa ini adalah ide orang-orang dari kerajaan Sasaniyah yang tidak ada hubungannya dengan Nabi. Pernyataan tersebut diucapkan raja pendiri Persia, imperium Sasaniyah, Ardashir, yang hidup 300 tahun sebelum Nabi.
Tetapi setelah pertengahan abad ke-11, ketika ulama ingin menjustifikasi aliansi ulama-negara, mereka memalsukan pepatah kaum Sasaniyah ini sebagai “hadis” ini. Sejak itu, pepatah ini terus diulang-ulang dan banyak orang percaya bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan dalam Islam—yang sebenarnya tidak demikian.
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnah/hadits), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Alquran surat An-Nisa ayat 59).
Sebenarnya ayat ini tidak merujuk kepada ulama atau negara, tapi Ibnu Taimiyyah meyakini bahwa ayat tersebut meminta Muslim untuk tunduk pada umara (penguasa) dan ulama. Umara pada dasarnya sama dengan negara. Jadi, aliansi ulama-negara sejak zaman Ibnu Tamiyya sampai sekarang dianggap sebagai perintah dalam Quran.
Itulah sebabnya hal itu sulit diubah dan umat Islam mempercayai hal tersebut.
Kenyataannya, Quran tidak menyatakan hal itu. Jadi, ini tafsir belaka. Hadis agama-ulama adalah fabrikasi. Bahkan Ihya Ulumuddin karya Ghazali, arsitek aliansi ulama-negara, mengajak kaum Muslim untuk lebih berhati-hati terhadap orang-orang lalim dan penguasa yang korup.
Saya pikir agenda pemisahan kekuasaan agama dan negara bukan agenda liberal dari dunia Barat. Praktik ini ada dalam ajaran Islam dan terjadi pada masa kejayaan Islam pada abad ke-8 hingga 12. Andai Abu Hanifah dan para intelektual Muslim masih hidup sekarang, mereka pasti terkejut sekali mengetahui pemuka agama jadi pelayan negara.
Bisa Anda beri contoh bagaimana bentuk kontrol negara terhadap intelektual Muslim pada hari ini?
Ketika membandingkan sejarah Islam awal dengan hari ini, kita melihat perbedaan yang sangat besar. Pada 1970, Cohen pernah menulis sebuah artikel yang isinya hasil analisis terhadap 3.900 intelektual Muslim abad ke-8 sampai pertengahan abad ke-11. Hasilnya, 92% di antara mereka bekerja di sektor swasta. Hanya 8% yang bekerja di lembaga negara sebagai hakim atau jaksa atau pegawai negeri lainnya. Hari ini, di negara seperti Turki, Mesir, dan lainnya, Anda akan menyaksikan kebalikannya.
Sekitar 90% ulama dibayar oleh negara, sekitar 10% lainnya bekerja di sektor swasta.
Hal ini menjelaskan banyak hal terkait relasi kuasa dan stagnasi kaum intelektual.
Contohnya di Turki. Semua imam di masjid adalah pegawai negeri. Kalau Anda pegawai negeri, bagaimana Anda bisa mengkritisi pemerintah? Anda terus menjustifikasi, memberi pembenaran atas apapun yang dilakukan pemerintah.
Ketika Nasser mendirikan Republik Mesir pada 1950-an, ia ingin menantang Ikhwanul Muslimin dengan mendirikan Al-Azhar serta institut Islam lain. Ia menjadikan lembaga-lembaga tersebut bagian dari negara.
Di Pakistan, Zia-ul Haq beraliansi dengan ulama agar bisa mengesahkan Undang-Undang Penodaan Agama. Sebelum Zia-ul Haq, sebetulnya sudah ada undang-undang penistaan agama di Pakistan tetapi hukumannya terbatas. Zia-ul Haq ingin melegalkan hukuman mati dan ia beraliansi dengan ulama untuk memuluskan keinginan itu.
Seperti yang Anda lihat di Turki, Mesir, Pakistan, dan tentunya Iran, kombinasi kekuasaan negara dan ulama membatasi peluang berdemokrasi dan memunculkan berbagai hambatan seperti hukum penistaan agama dan kebijakan liberal lain.
Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai krisis dari pandemi sampai populisme kanan. Apa yang seharusnya dilakukan dunia Muslim? Ada diskusi tentang renaisans Muslim. Bagaimana modelnya?
Pembicaraan tentang “Renaisans Muslim” sudah jadi hal yang lumrah dan ini dikemukakan berbagai macam kelompok Islam yang tak jarang berseberangan. Ada kelompk yang membayangkan renaisans ini akan mengulang masa kejayaan intelektual Muslim, ada pula kelompok yang berpendapat bahwa masa kejayaan ini merujuk pada kekaisaran Turki Usmani. Hari ini kita hidup di zaman yang serba sulit. Ada pandemi, perubahan iklim, ekonomi global yang tidak stabil, sampai munculnya populisme sayap kanan. Apakah transformasi sosial budaya yang diperlukan bagi umat Muslim untuk merespons isu-isu ini?
Ketika saya tumbuh besar di Turki, ada pembicaraan tentang solusi terbaik yang bisa ditempuh Muslim: entah itu lewat kebijakan westernisasi atau kembali ke masa Usmani. Berkat sinetron dan serial televisi di Turki, sistem Turki Usmani kini populer di Pakistan dan negara-negara lain yang menyaksikan sinetron Turki tentang zaman Usmani. Tapi, bagi Muslim yang mendambakan kebebasan dan demokratisasi, yang menghendaki pembangunan dan kemajuan sosial-ekonomi, jalan yang tepat adalah adalah mereformasi gagasan dan lembaga. Kembali ke sejarah militer itu bukan solusi melainkan masalah.
Memang selama 600 tahun, Turki Usmani benar-benar mengalami ekspansi politik dan militer. Tetapi dari sisi ilmu pengetahuan dan filsafat, masa tersebut adalah masa stagnasi. Di dalam buku saya, ada paparan detail tentang sejarah Usmani, bagaimana mereka sukses secara politik dan bagaimana mereka sempat produktif dalam ranah filsafat. Tapi bila trennya dilihat secara keseluruhan, yang terjadi adalah kemandegan intelektual.
Jika dunia Muslim hari ini benar-benar ingin mencapai demokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi, yang mereka butuhkan adalah masyarakat yang demokratis, sistem meritokrasi, dan perekonomian yang kompetitif. Kita perlu pemisahan di berbagai bidang. Tidak hanya pemisahan kekuasaan agama dan politik tetapi juga pemisahan bidang politik, agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, seni, olahraga, dan lainnya. Setiap bidang harus otonom dan berjalan berdasarkan kriteria-kriterianya sendiri. Jika kita mencampurbaurkan agama, politik, dan ekonomi, hasilnya adalah korupsi.
Jika seorang dosen mengevaluasi mahasiswa berdasarkan agama mereka, maka ia adalah dosen yang korup. Bila seorang dosen menilai berdasarkan uang, maka ia guru yang korup. Dosen harus menilai murid dari sisi akademik saja. Hal yang sama berlaku untuk pimpinan agama. Ia mesti mengikuti panduan agama. Percampuran agama, politik, ekonomi, dan sebagainya adalah masalah besar.
Ketika orang seperti saya muncul dan mengajak kaum Muslim untuk mendirikan sistem yang demokratis, masyarakat terbuka, meritokratik, kompetitif, biasanya kami langsung dikritik dan dituduh membawa agenda Amerika, agenda Barat. Ini keliru karena apa yang berupaya kami sampaikan tentang demokrasi dan pembangunan itu sangat kompatibel dengan Islam dan pesan Nabi. Ini sangat kompatibel dengan sejarah Islam abad ke-8 sampai 12 ketika Muslim membangun masyarakat yang lebih terbuka dari masyarakat Eropa. Muslim, Kristen, Yahudi bekerja bersama antara abad ke-8 dan 12 di saat orang-orang non-Kristen di Eropa Barat tidak punya kesempatan hidup, selain ada pula kaum Yahudi yang dipersekusi di Eropa. Hasilnya, Muslim memiliki masyarakat dinamis, kota-kota besar, para filsuf terdepan, ilmuwan, dan perkembangan ekonomi.
Jadi, sekali lagi, kita perlu berpikiran terbuka, menjunjung keragaman, kreatif, kompetitif, dan toleran. Ortodoksi menghancurkan heterodoksi dan ini hal yang keliru. Bila kaum Muslim mesti memilih, jalan progresif atau melestarikan tradisi, mereka harus mengingat bahwa tradisi mereka, sejarah mereka amat kaya gagasan yang bisa dipakai untuk membentuk masyarakat demokratis dan sistem meritokratik. Muslim tidak perlu meniru model Barat bila mereka memahami sejarah, jika mereka paham pencapaian Islam selama lima abad pertama. Itulah inspirasi untuk mereka dan itulah jalan untuk mencapai renaisans Muslim hari ini.
Editor: Windu Jusuf