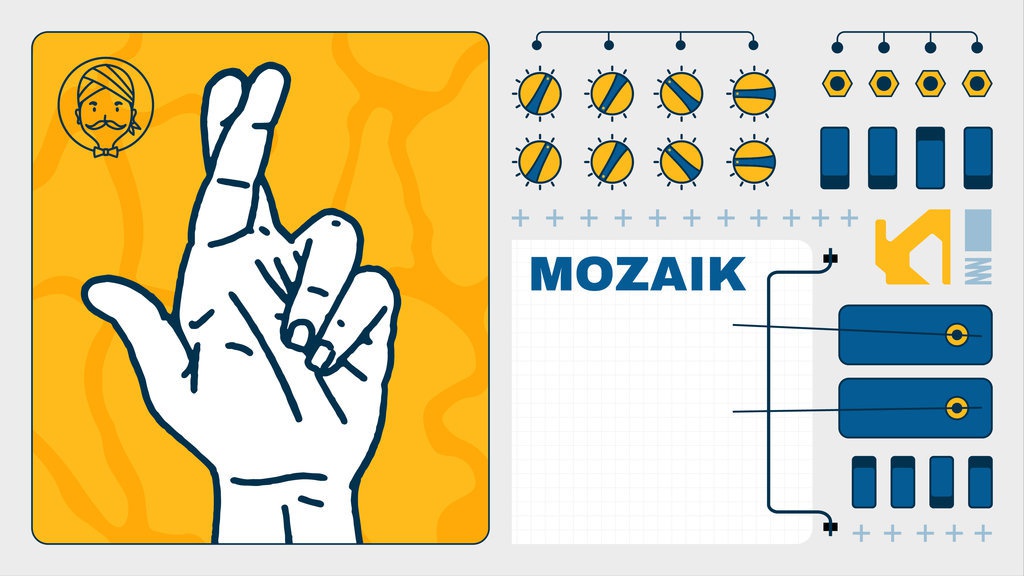tirto.id - Sebagai langkah validasi pernyataan para tersangka dan saksi pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat, penyidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan uji kebohongan lewat poligraf pada Selasa, 6 September 2022.
berdasaran bentuk tengkorak sebagai bagian dari scientific investigation. Tujuannya untuk memberikan hasil penyelidikan yang objektif, ilmiah, dan transparan sehingga dapat dipertanggungawabkan kepada publik dan masyarakat ilmiah.
Poligraf adalah alat pendeteksi kebohongan yang kerap digunakan kepolisian untuk menyelidiki kebenaran pernyataan dalam kasus. Melalui alat ini akan diketahui kejujuran seseorang yang didasarkan reaksi fisiologis, sehingga membantu menentukan hasil suatu perkara.
Kehidupan dan Kebohongan
“Berbohong adalah bagian dari kehidupan manusia sehari-hari,” ujar psikolog Aldert Vrij dalam Detecting Lies and Deceit (2008).
Menurut Virj, sulit bagi manusia untuk tidak melakukan kebohongan. Biasanya, manusia berbohong untuk menghindari kerugian atau mendapatkan keuntungan. Bisa untuk membuat kesan positif atau untuk menjaga harga diri.
“Berbohong kenyataannya bisa menjadi senjata untuk bertahan hidup,” imbuhnya.
Hal ini membuat manusia cenderung nyaman dan terus-terusan berbohong. Bahkan, setiap hari rasanya tidak mungkin manusia tidak berbohong.
Meski demikina, tulis Kerry Mallan dalam “Lies of Necessity” (2013), “Mengatakan yang sebenarnya berada di atas segalanya. Akan selalu dihargai sebagai tindakan moral, dan jelas lebih baik.”
Memisahkan perkataan jujur atau tidak dari mulut manusia memang cukup sulit. Dari sini, muncul berbagai cara untuk membuktikan kebenaran ucapan manusia yang melahirkan beragam metode untuk membongkar kebohongan.
Dari Nasi Kering sampai Pengadilan Tuhan
Seturut penelusuran Elizabeth B. Ford dalam “Lie Detection: Historical, Neuropsychiatric, and Legal Dimension” (2005), jejak tertua dari upaya manusia mengungkap dusta terungkap dari catatan peradaban Cina sekitar 1.000 SM.
Saat itu, orang-orang yang dianggap berbohong dipaksa memasukkan nasi kering ke dalam mulutnya untuk memvalidasi kebenaran. Nasi kering ini akan mendeteksi kejujuran berdasarkan air liur. Jika saat dikeluarkan nasi masih kering, maka orang itu terbukti berbohong.
Belakangan, penelitian kotemporer membenarkan metode tersebut bahwa orang yang berbohong pasti dilanda ketakutan serta kecemasan dan mengalami penurunan air liur, alias mulutnya menjadi kering.
Dokter Yunani Erasistratus yang hidup sekitar 300-250 SM juga pernah mencoba mendeteksi penipuan berdasarkan denyut nadi di pengadilan. Jika denyutnya cepat, maka orang tersebut diduga kuat telah berbohong. Dua Kasus di atas menjadi bukti awal bahwa ada pengaruh perubahan tanda fisiologis terhadap dusta.
Selain itu, di peradaban lain ditemukan pula cara klasik: bertarung untuk membuktikan siapa yang bohong.
Cara-cara ini kemudian digantikan oleh hal baru, yakni berdasarkan trial by ordeal—atau Pengadilan Tuhan. Ini terjadi ketika agama mendominasi kehidupan manusia, seperti yang terjadi di Eropa pada Abad Pertengahan.
Martina Vicianova dalam “Historical Techniques of Lie Detection” (2015) menyebutkan bahwa penggunaan metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan selalu menjunjung tinggi keadilan dan akan berada di sisi orang yang benar. Meski terdengar religius, metode ini kemudian melahirkan cara-cara yang cukup ekstrem.
Misalkan, untuk membuktikan seseorang berkata jujur, maka perlu memasukkan tangannya ke dalam air mendidih dalam waktu lama. Lalu, ada juga pembuktikan dengan membawa sepotong logam panas atau berjalan melintasi bara api. Jika melakukan hal tersebut, dan tidak ada luka atau ada luka tetapi cepat sembuh, maka orang tersebut dinyatakan tidak bersalah alias jujur.
Ini jelas tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Secara logika, ketika seseorang melakukan keduanya pasti akan menimbulkan luka. Namun, menurut argumen saat itu, di sinilah letak bantuan Tuhan. Ketiadaan luka menjadi mukjizat Tuhan—yang artinya Sang Pencipta tidak akan membiarkan umatnya berada di pihak yang salah.
Keputusan benar atau salah berdasarkan bantuan Tuhan jelas terbukti tidak efektif. Akhirnya, cara ini tidak lagi digunakan seiring perkembangan ilmu pengetahuan.
Fisiologis Menjadi Kunci
Dipercik kekecewaan terhadap agama dan kekaguman akan ilmu pengetahuan, masyarakat Eropa mulai menyiapkan bukti-bukti ilmiah untuk membuktikan kejujuran. Periode ini dimulai ketika masa kebangkitan kembali atau renaisans dimulai.
Ada banyak catatan atau buku yang ditulis oleh ahli tentang hal ini, tetapi semuanya masih berdasarkan pengamatan empiris. Salah satunya ditulis Daniel Defoe pada 1730. Dalam esainya, Defou berhasil mengidentifikasi seorang penipu. Caranya, “pegang pergelangan tangannya dan rasakan denyut nadinya.”
Meski demikian, tulis Don Grubin dan Lars Madsen dalam “Lie Detection and the Polygraph” (2007), saat itu sudah terbentuk satu pandangan bahwa “reaksi fisiologis yang terjadi dalam diri seseorang ketika dihadapkan dengan situasi tertentu pada akhirnya dapat menunjukkan gejala yang dapat dikenali.”
Deskripsi klinis tentang pandangan ini baru dilakukan pada tahun 1870 oleh Franz Joseph Gall. Ia adalah seorang dokter asal Jerman yang memaparkan adanya perubahan otak pada beberapa kondisi psikologis, termasuk ketika berbohong.
Secara sederhana, riset Gall mengungkap bahwa karakter seseorang dapat ditentukan berdasaran bentuk tengkorak. Pada saat itu, riset Gall memang membuka titik terang, tetapi masih banyak misteri yang menyelimutinya.
Ada tantangan besar bagi orang awam, yakni sulitnya memahami bentuk kepala orang lain dan menentukan kepribadiannya. Penelitian Gall ini yang kemudian melahirkan frenologi—ilmu membaca kepribadian orang berdasarkan bentuk kepala.
Sampai akhirnya ada dua orang yang berhasil membuktikan relasi kejujuran dan bukti fisiologis berdasarkan alat yang teruji ilmiah. Keduanya adalah Cesare Lombrosso dan Vittorio Benussi.
Lembrosso pada 1895 berhasil mendeteksi kebohongan dengan memantau perubahan tekanan darah melalui hydrosphygmograph (pengukur tekanan darah) untuk menyimpulkan kebenaran tersangka.
Lalu pada 1914 Benussi berhasil menganalisis tekanan darah, denyut nadi, dan embusan napas untuk mendeteksi kebohongan. Kedua orang ini menunjukkan satu premis sama: Jika ada anomali reaksi fisiologi yang berbeda, maka orang tersebut diduga kuat tidak jujur.
Berawal dari Lombrosso dan Benussi, alat pendeteksi kebohongan dikembangkan secara serius di Amerika Serikat. Pemrakarsanya adalah William Marston.
Pada 1915, Marston merancang tes penipuan berdasarkan tekanan darah sistolik. Tekanan darah diukur secara tidak tetap selama interogasi. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang berbohong memiliki fluktuasi tekanan darah.
Rancangan ini kemudian diteruskan oleh ahli forensik John Larson. Ia berhasil menciptakan instrumen poligraf modern pertama pada tahun 1921.
Instrumen tersebut memuat rekaman atas tiga proses fisiologi: tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi. Purwarupa ini langsung diujicoba untuk membongkar suatu kasus di salah satu asrama putri.
Alkisah, di tahun yang sama ketika Larson menemukan alat tersebut, terjadi pencurian di asrama mahasiswa. Seluruh orang di tempat kejadian dianalisis oleh Larson melalui alat buatannya. Prosesnya mudah. Larson hanya menanyakan kepada tiap individu tentang kejadian sembari dipasangkan kabel-kabel dari alatnya.
Hasilnya, hanya ada satu orang yang memiliki rekaman berbeda. Ia mengalami peningkatan proses fisiologis terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait kejahatan. Sedangkan yang lain tidak mengalaminya.
Larson menduga satu orang ini sebagai pelaku. Dan dugaan ini terbukti di pengadilan. Dari sini, purwarupa Larson yang dinamai poligraf diminati dan lambat laun dipakai oleh kepolisian, pemerintahan, dan lembaga partikelir.

Seberapa Akurat Poligraf?
Hasil poligraf tidak mutlak menyebut seseorang bohong atau jujur. Maka itu, sejak ditemukan pertama kali sampai sekarang, pertanyaan mengenai poligraf selalu sama: apakah benar-benar efektif?
Meski perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa rupa poligraf lebih baik dibanding awalnya, tetap saja alat ini menimbulkan kerancuan.
Poligraf mendeteksi kebohongan berdasarkan reaksi fisiologis yang dihasilkan. Masalahnya, menurut American Psychological Association (APA) tidak semua orang memiliki kondisi psikologis serupa.
Ketika diberi pertanyaan yang menjurus pada tindak kejahatan, orang jujur bisa menjadi gugup dan cemas. Hasilnya, berpotensi menandakannya sebagai pembohong.
Lalu, seperti di film-film, ada pula orang yang terlatih menghadapi situasi ini. Misalkan X adalah tersangka pembunuhan. Ketika diinterogasi, X berniat untuk berbohong agar data pemeriksaan dapat berubah. Maka X yang sudah terlatih dapat mengendalikan reaksi fisiologisnya sehingga kebenaran pun tertutupi.
Selain itu, permasalahan lain meliputi kondisi fisik dan mental individu, keobjektifan pemeriksa rekaman data, dan keabsahannya sebagai bukti di pengadilan. Meski demikian, APA juga menyebut keakuratan poligraf mencapai 87 persen.
Terlepas dari itu, menurut psikolog Lara Warmelink di The Conversation, poligraf adalah opsi terbaik yang dapat dimiliki dan masih berguna sebagai media pengungkapan kebenaran.
Editor: Irfan Teguh Pribadi & Muhammad Fakhriansyah
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id