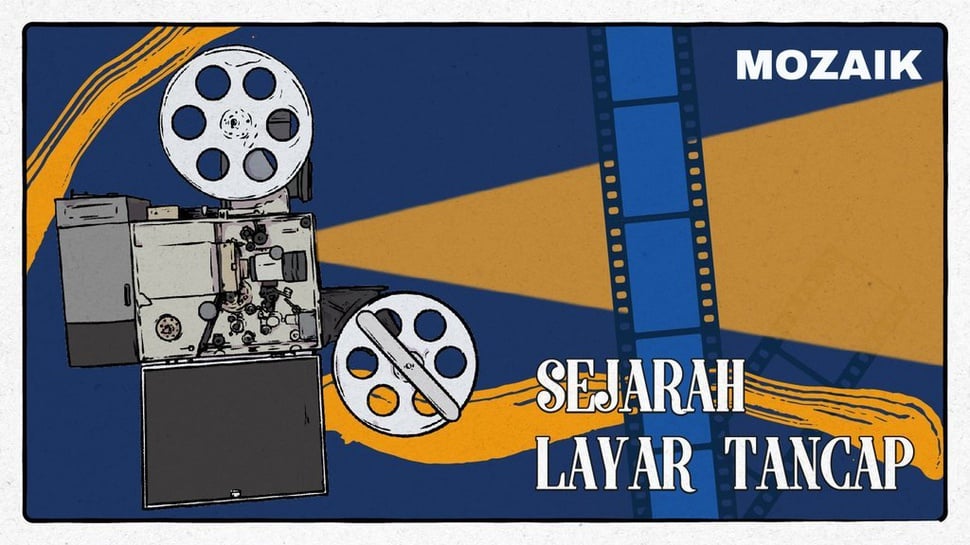tirto.id - Jauh sebelum era Netflix atau Disney Plus, masyarakat Indonesia lebih dulu mengenal layar tancap. Meski di kemudian hari lekat dengan berbagai tudingan negatif, pada suatu masa pertunjukan murah meriah ini menjadi standar gengsi masyarakat yang tengah mengadakan pesta perkawinan atau khitanan.
Propaganda di Ruang Terbuka
Seturut Misbach Yusa Biran dalam Peran Pemuda dalam Kebangkitan Film Indonesia (2009:17), sejarah layar tancap di Indonesia tidak terlepas dari propaganda Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
Enam bulan setelah mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, pemerintah militer Jepang mendirikan Sendenbu, yaitu Badan Propaganda dan Penerangan. Sendenbu dipimpin oleh Machida Kenji, seorang perwira militer Jepang yang punya perhatian pada isu-isu sastra dan kebudayaan.
Jepang paham betul film bisa menjadi alat untuk menarik simpati dan menggiring opini rakyat yang mereka jajah. Itu sebabnya, pada April 1943 mereka mendirikan Jawa Enhai, distributor film yang mengawasi dan mengatur penyebaran film sekaligus penggunaannya sebagai alat propaganda.
Meski film-film propaganda sudah disiapkan, Jepang menghadapi kendala. Pada 1943, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 50 juta jiwa, sementara jumlah bioskop hanya 117 gedung. Jika dirata-rata, satu gedung bioskop diharapkan mampu memutar film untuk 400 ribu penonton, angka yang tidak masuk akal.
Untuk memperluas jangkauan propagandanya, tentara Jepang memutar film di ruang terbuka. Belakangan cara ini dikenal dengan bioskop keliling, misbar (gerimis bubar), atau layar tancap. Meski kemudian digelar di tengah-tengah masyarakat luas, awalnya layar tancap ditujukan untuk kalangan tertentu, seperti murid sekolah, pegawai pabrik, dan romusa.
Seturut Heru Erwantoro dalam “Bioskop Keliling: Peranannya dalam Memasyarakatkan Film Nasional dari Masa ke Masa” (2014:290), menjelang Desember 1943, Jawa Enhai membentuk lima pangkalan operasional layar tancap yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Pada saat yang sama, dibentuk pula 15 tim operator film. Mereka berkeliling dari satu desa ke desa lainnya menggunakan truk bermuatan perlengkapan layar tancap. Masing-masing tim terdiri dari operator dari Jawa Enhai, pegawai Sendebu setempat, penerjemah, dan sopir truk.
Pemerintah militer Jepang berusaha menarik sebanyak-banyaknya penonton di tiap lokasi pertunjukan layar tancap. Saat menyambut Ulang Tahun Perang Asia Timur Raya pada Desember 1943, pertunjukan yang mereka adakan berhasil menjaring penonton dalam jumlah besar.
Di Kotamadya Jakarta sedikitnya 53.000 penonton memadati lokasi, di delapan lokasi di Keresidenan Jakarta 104.000 penonton, dan di delapan lokasi di Keresidenan Bogor 96.000 penonton. Pada 16 sampai 30 Desember 1943, layar tancap yang digelar di 13 titik di Keresidenan Banten berhasil menarik 126.000 penonton dari kalangan romusa.
Film Masuk Desa
Perangkat yang digunakan dalam pertunjukan layar tancap antara lain pita seluloid berukuran 16 mm atau 35 mm, proyektor, layar berukuran 3 kali 7 meter atau 4 kali 8 meter, konstruksi untuk mendirikan layar berupa tiang bambu atau besi knockdown, sound system, player, dan mesin diesel.
Dibanding film yang diputar di bioskop, kualitas gambar layar tancap kurang jernih. Film-film yang ditayangkan pun biasanya second run alias sudah tayang di bioskop empat atau lima bulan sebelumnya. Meski begitu, pada dekade 1990-an layar tancap menjadi primadona bahkan standar gengsi sebagian masyarakat yang mengadakan pesta perkawinan atau khitanan.
Ketika bisnis layar tancap makin menjanjikan, sejumlah pengusaha di bidang itu antara lain Zein Arsyad, Ayong Suteja, Suryo Kencono, Hasan Basri Raja Medan, dan sekira 20-an pebisnis lain mendirikan PERBIKI (Persatuan Bioskop Keliling Indonesia) pada 1978.
Yung Indrajaya ditunjuk sebagai ketua, wakilnya Boih Sumardi, sekretaris jenderal A. Aidizars, bendahara Ayong Suteja dan Munthalibsya. Pada tahun-tahun pertama setelah dibentuk, para pengurus PERBIKI berupaya memperoleh pengakuan hukum bagi organisasi mereka.
Salah satu program PERBIKI yakni Film Masuk Desa disambut hangat pemerintah. Adam Malik, wakil presiden yang mengaku prihatin karena 85 persen penduduk desa belum mendapatkan akses untuk menonton film, mendukung program tersebut.
Ia menyarankan PERBIKI bekerja sama dengan Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga Departemen Pertanian. Dengan kerjasama itu, bisnis layar tancap semakin tumbuh, terutama di wilayah Jawa Barat tempat program tersebut dijadikan pilot project.
Sebelum memutar film utama, operator layar tancap secara sukarela memutar film-film yang bersifat penerangan. Film-film tersebut di antaranya tentang program Keluarga Berencana (KB), transmigrasi, koperasi, penyuluhan pertanian, dan sosialisasi pemilu.
Layar tancap juga kerap memutar film yang berbau propaganda, seperti Janur Kuning (1979), Serangan Fajar (1982), dan Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984), yang ketiganya mengglorifikasi Presiden Soeharto dan menjadikannya tokoh sentral dalam berbagai peristiwa penting.
Layar tancap sangat membantu sosialisasi program pemerintah, juga memoles citra mereka. Sifatnya yang mobile mampu menjangkau penduduk yang tinggal di perdesaan. Lain itu, biaya operasionalnya lebih terjangkau, berbeda dengan bioskop konvensional yang selain mahal juga terkonsentrasi di pusat-pusat kota.
Meski begitu, para pengusaha layar tancap sering mengeluhkan proses izin setiap mereka ingin mengadakan pertunjukan. Biaya izinnya memang murah, tapi “uang rokok” yang diminta oleh pejabat lokal lebih banyak. Tanpa “uang rokok”, jangan harap izin diberikan, bisa-bisa perlengkapan pertunjukan malah disita.
Tersandung Citra Negatif
Tentara Jepang bukanlah pelopor pertunjukan layar tancap. Sebelum kedatangan mereka, seorang pria Belanda yang biasa disapa Tuan Talbot lebih dulu menggelar pertunjukan film atau saat itu disebut gambar idoep, dari lapangan ke lapangan dengan mendirikan bangunan berdinding bambu dan beratap seng.
Seturut Ilmiawati Safitri dalam “Perjalanan Bioskop Keliling dari Media Hiburan hingga Propaganda” (2022:32-33), sebelum Perang Dunia II pertunjukan layar tancap pernah diadakan di Lapangan Gambir. Film yang diputar adalah penerangan tentang penyakit pes, sehingga dikenal dengan “Film Pes”.
Pada 1936, film propaganda pertama diputar di layar tancap. Judulnya Tanah Seberang, yang menceritakan kebijakan transmigrasi Pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan pemerintah Jepang yang memanfaatkan pertunjukan layar tancap dalam skala besar dan luas, pemerintah Hindia Belanda mengadakannya sesekali dan di kawasan tertentu saja.
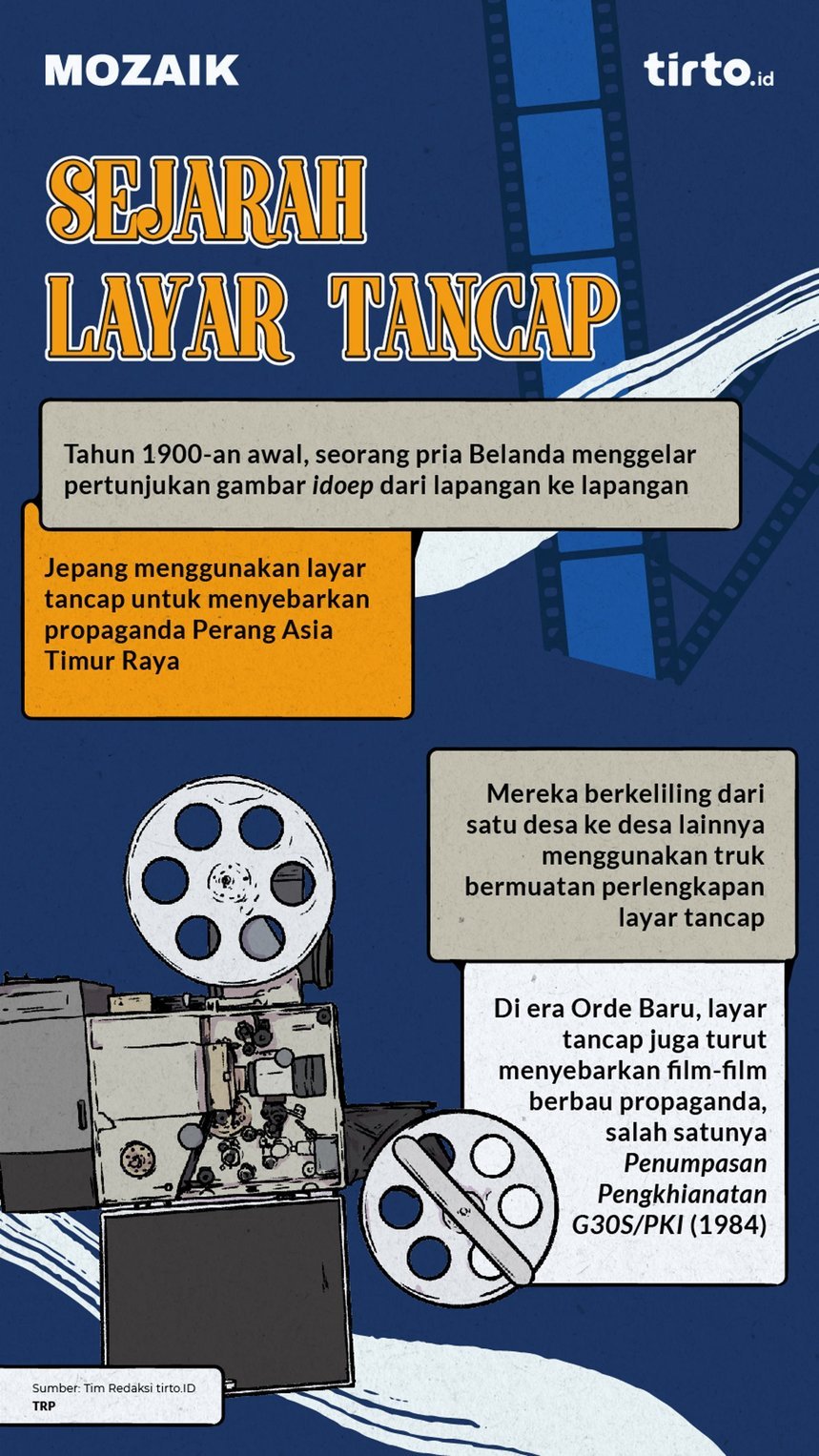
Setelah lebih dari satu dasawarsa, tepatnya pada 1991, PERBIKI mengubah namanya menjadi PERFIKI, akronim dari Persatuan Perusahaan Pertunjukan Film Keliling Indonesia. PERFIKI mempunyai kantor cabang di 16 kota, kebanyakan di Pulau Jawa.
Seturut Quirine van Heeren dalam “Jiwa Reformasi dan Hantu Masa Lalu: Sinema Indonesia Pasca Orde Baru” (2019:50), berdasarkan data PERFIKI pada 1993 terdapat 200 hingga 300 perusahaan layar tancap dengan armada dan perlengkapan mencapai 500 hingga 700 unit.
Ratusan perusahaan itu diperkirakan mengoleksi sekitar 40.000 film dari berbagai genre dan bahasa, mulai India, Mandarin, Inggris, dan tentu saja bahasa Indonesia, terutama film laga dan komedi.
Seiring menjamurnya layar tancap, berbagai persoalan dihadapi para pelaku bisnis tersebut, di antaranya stigma negatif sebagai hiburan yang menghadirkan konten berbau pornografi.
PERFIKI memang melakukan pembinaan terhadap anggotanya agar tidak menayangkan film kategori 17 tahun ke atas, tapi pengusaha yang bukan merupakan anggota sulit ditertibkan.
Selain konten pornografi, film-film yang diputar dalam pertunjukan layar tancap sering disebut “film pelarian”, yaitu film yang masih tayang di bioskop komersial yang belum atau tidak diizinkan diputar di layar tancap. Lain itu, hiburan murah meriah ini kerap menjadi ajang judi dan mabuk-mabukan.
Penulis: Firdaus Agung
Editor: Irfan Teguh Pribadi