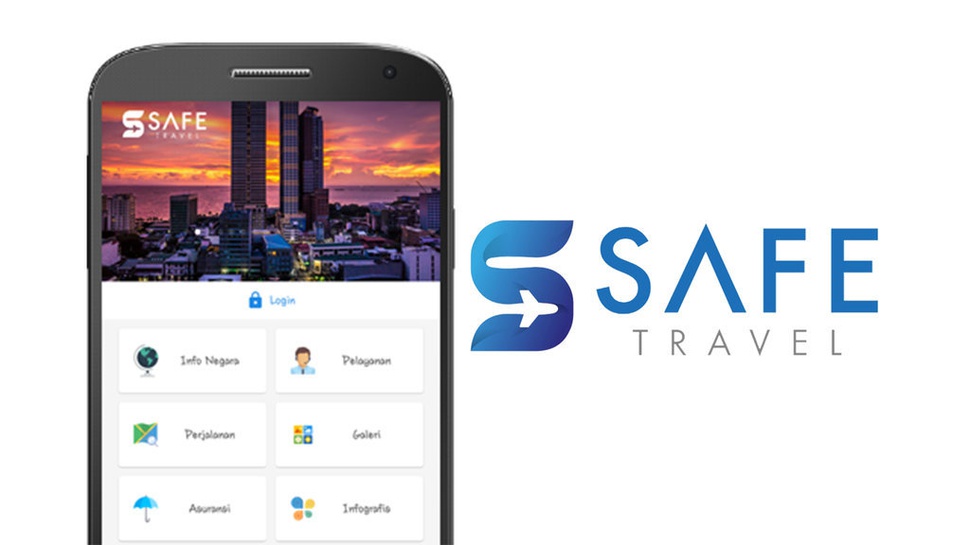tirto.id - Ketika berpergian ke luar negeri dan terjadi bencana, akankah saya berhasil diselamatkan?
Pernahkah pertanyaan semacam itu muncul di benak Anda saat melakukan perjalanan lintas negara? Saya seringkali bertanya, bagaimana negara bisa menemukan warganya saat misalnya mereka terjebak dalam situasi tanpa alat komunikasi, paspor, dan uang di luar wilayah Indonesia.
Kasus semacam ini pernah terjadi secara massal pada April 2015 lalu di Nepal. Ketika itu gempa berkekuatan 7,9 skala richter mengguncang sebagian wilayah negara dan menewaskan hampir sembilan ribu orang. Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) menerima ratusan laporan tentang keberadaan WNI di Nepal. Namun, tak banyak yang memberi lokasi pasti keberadaan objek laporan mereka.
“Mereka semua rata-rata mengatakan saudaranya di Nepal, tapi setelah ditanya Nepal bagian mana, ya tidak tahu. Padahal Nepal, kan, luas,” tutur Hernawan Bagaskoro Abid, Kepala Seksi Kampanye Penyadaran Publik Kemenlu, saat diwawancarai Tirto di kantornya, Selasa (17/9/2019).
Saat itu kira-kira terdapat 270 WNI yang berada di Nepal, namun berdasar data dari kantor perwakilan RI, hanya ada dua orang yang melakukan pelaporan. Kondisi itu sempat membuat pemerintah kesulitan mendeteksi, menolong, dan memberi informasi terkini kepada keluarga di Indonesia.
Saat itu alur pelaporan diri masih sangat konvensional. Mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus datang langsung ke kantor perwakilan RI, melakukan panggilan pada jam kantor, atau mengirim surel. Padahal, tidak semua negara memiliki kantor perwakilan.
Kondisi itu jelas sangat menyusahkan, selain menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga, sangat riskan berpergian ke tempat-tempat asing di negara lain. Apalagi, pelaporan lewat telepon dan surel tidak bisa mendeteksi keberadaan pelapor secara detail. Yang bikin susah, sistem ini kebanyakan tidak terekam kantor pusat.
“Perwakilan punya sistem sendiri, dan lebih banyak yang tidak bersistem, mereka cap (paspor) tapi tidak dilaporkan ke pusat.”
Kondisi ini diperparah dengan aturan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan pelaporan hanya untuk WNI dengan masa tinggal di luar negeri lebih dari satu tahun. Akhirnya, mereka yang sekadar melancong pun berpikiran pelaporan diri tidak terlalu penting dilakukan.
Berdasarkan data Kemenlu (2018), selama empat tahun terakhir, rata-rata jumlah WNI berada di luar negeri mencapai 9,5 juta per tahun. Paling banyak berada di Malaysia (1,3 juta), Arab Saudi (611 ribu), dan Taiwan (213 ribu). Tapi mereka yang melaporkan diri hanya berjumlah sekitar 2,9 juta orang.
“Ini membuat kami melakukan evaluasi. Harus ada yang diperbaiki dari mekanisme pelaporan diri,” kata Hernawan.
Cerita dari Mereka yang Terselamatkan
Sekelumit kisah dari ES, 38 tahun, mungkin bisa mengubah persepsi kita yang menganggap remeh soal pelaporan diri. Sebagai seorang kapten kapal, ES sudah biasa bekerja bersama awak kapal dari negara lain, memberi perintah alur perjalanan kapal, dan bertanggung jawab atas seluruh perjalanan termasuk muatan dalam kapal.
Mungkin ES juga tak pernah menyangka akan menjadi korban eksploitasi kerja seperti berita-berita yang sering ia baca selama ini. Tapi pengalaman di bulan Agustus lalu berbeda, ia terpaksa menggunakan tombol darurat pada aplikasi Safe Travel untuk menyelamatkan diri dari sandera kapal kargo Thailand.
“Saya tidak tahu barang apa yang diangkut. Kapalnya berbobot 1.800-an GT (gross tonnage), terlihat selalu kosong, tapi melakukan bongkar muat di tengah laut,” cerita ES, seperti diceritakan Buruh Migran, situs pemberi layanan pengarusutamaan isu buruh migran.
Sebagai seorang kapten, seharusnya ia punya kuasa penuh terhadap segala aktivitas dalam kapal. Tapi nyatanya, setelah setahun bekerja di sana, ia dan kelima awak kapal berkewarganegaraan Indonesia justru semakin terisolir dari dunia luar.
Ponsel mereka diatur agar tidak bisa mengakses sinyal internet, beragam dokumen disita, dan yang paling parah keluarga mereka ikut diancam apabila ES dan kelima kawannya melakukan hal-hal di luar perintah dari seorang berkewarganegaraan Taiwan yang tidak jelas jabatannya.
“Saya dan teman-teman diminta untuk masuk kamar dan dikunci dari luar ketika bongkar muat barang,” ujar ES.
Akhirnya saat kapal bersandar di Penang, ES berhasil kabur membeli kartu selular Malaysia dan mengunduh aplikasi Safe Travel. Dengan aplikasi buatan Kemenlu itu ia memencet tombol darurat. KJRI Penang langsung menemukan kapal ES karena titik koordinat sudah terlacak dari aplikasi.
Kurang Sosialisasi
Bencana Nepal pada 2015 membuat Kemenlu melakukan evaluasi terhadap sistem pelaporan diri yang selama ini kurang efektif. Mereka mulai menyusun suatu aplikasi yang memudahkan pelaporan dilakukan di manapun, setiap waktu, dan murah biaya. Setahun kemudian, terwujudlah Safe Travel.
Sayangnya aplikasi ini belum tersosialisasikan dengan baik sehingga tak banyak diketahui publik. Hernawan tak menampik fakta tersebut. Kita bisa melihat kenyataan ini ketika, misalnya, Tiga Setia Gara meminta pertolongan kepada warganet pertengahan September lalu. Kala itu Tiga mengaku mendapat kekerasan dari suami dan mengunggah permintaan tolong ke akun Instagramnya.
“Tolong, siapa pun yang nonton, telepon Embassy Indonesia, gue nggak ngerti harus gimana, gue gaptek (gagap teknologi) banget,” ungkap Tiga saat itu, sambil terisak.
Jangankan Tiga yang baru tinggal di Amerika selama setahun. Sofia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah bekerja selama satu dasawarsa di Brunei Darusalam lebih memilih melakukan pelaporan secara konvensional. Biasanya, setiap tiba di Brunei, sebelum mulai bekerja, perempuan setengah baya itu langsung bertandang ke KBRI Bandar Seri Begawan untuk melaporkan diri.
“Wah, enggak pakai (Safe Travel), enggak pernah dikasih tahu, enggak ngerti jadinya,” kata Sofia melalui pesan singkatnya kepada Tirto, Kamis (26/9/2019).
Selain buta soal Safe Travel, Sofia ternyata hanya memanfaatkan KBRI sebagai lembaga formal yang berkaitan dengan kepengurusan dokumen. Tirto pun bertanya padanya, siapa yang akan dihubungi ketika menghadapi situasi kritis atau berbahaya. Sofia memilih cara usang, yakni mengontak keluarga di Indonesia.
Benny Ryplida, 27 tahun, seorang mahasiswa Indonesia di Korea Selatan malah baru tahu ada aplikasi ini setelah saya bertanya padanya. Padahal Benny sudah tinggal di sana sejak tahun 2017 lalu. Mekanisme pelaporan pun ia lakukan hanya sekali, yaitu sewaktu pertama kali datang ke Korea. Setelahnya, meski acap pulang pergi Indonesia, ia tak lagi melakukan pelaporan.
"Sejauh ini aman terkendali sih, ya semoga ke depannya enggak ada apa-apa," katanya menjawab pertanyaan saya soal kondisi kritis atau berbahaya.
Padahal, jika saja aplikasi ini tersampaikan dengan baik dan diunduh oleh semua WNI di luar negeri, tak akan ada kasus seperti Tiga yang kesulitan menghubungi kantor perwakilan RI saat kondisi kritis. Atau TKI macam Sofia yang menjalani alur panjang menghubungi keluarga di Indonesia, baru laporan diteruskan oleh keluarga ke Kemenlu.
Safe Travel dirancang dengan fitur tombol darurat untuk melacak detail lokasi pengguna. Ketika berada dalam kondisi darurat, pengguna cukup menekan tombol tersebut maka akan muncul pilihan untuk menghubungi kantor perwakilan RI terdekat lewat telepon, foto, video, atau langsung mengirim detail lokasi.
“Sosialisasi kami memang tidak langsung ke TKI, tapi ke lembaga yang berurusan dengan TKI, keluarga mereka, dan saat mengisi sesi di BNP2TKI,” jelas Hernawan.

Pilih Dalam atau Luar Jaringan?
Lantaran penasaran dengan aplikasi ini, Tirto mengunduh dan menjajalnya. Di platform Play Store, aplikasi ini sudah mendapat nilai ulasan 4,6. Hanya ada beberapa keluhan dari pengguna seputar penyimpanan data, halaman yang tak bisa diperbaharui, sulit login, pemblokiran peta di negara Cina, dan hal-hal teknis lain. Selebihnya cukup merasa terbantu dengan Safe Travel saat melakukan perjalanan.
Seorang pengguna, Afifatul Humairo, 28 tahun, mengatakan lebih merasa aman jika sudah mengunduh aplikasi Safe Travel saat berpergian. Ia sudah menggunakan aplikasi ini sejak pertama kali muncul dan melakukan pelaporan saat berada di Hong Kong di tahun 2017 dan Arab Saudi di tahun 2018.
“Enaknya aplikasi ini ada peringatan status keamanan negara, jadi kita bisa aware sebelum datang ke tempat wisata,” kata Afifah.
Ada lebih dari 200 negara yang status keamanannya tercantum dalam Safe Travel. Warna merah pada status negara mengindikasikan wilayah tersebut berbahaya, oranye untuk status awas, kuning adalah negara yang perlu diwaspadai, dan hijau masuk ke dalam wilayah wajar atau aman dikunjungi. Pengguna juga bisa melihat status visa dari masing-masing negara di dunia, pun info terbaru tentang negara itu.
Tapi lagi-lagi, fitur Safe Travel kurang maksimal dimanfaatkan penggunanya. Hernawan mengungkap, hingga saat ini tombol darurat lebih banyak digunakan atas laporan kehilangan paspor atau tertahan di imigrasi. Di sisi lain, tidak banyak kantor perwakilan RI menyediakan staf penjaga hotline 24 jam.
Sampai pernah suatu kali Kemenlu mendapat komplain dari pengguna yang sudah memencet tombol darurat, namun tak mendapat respon. Untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan ini, secara reguler Kemenlu melakukan tes random, menghubungi beberapa kantor perwakilan RI guna memastikan pelayanan hotline berjalan baik.
Sementara pelaporan diri secara konvensional masih lebih populer, meski jumlah pertumbuhan pengguna aplikasi jauh lebih tinggi. Sejak diluncurkan tahun 2017, aplikasi ini telah diunduh oleh 48.991 orang dan digunakan melapor oleh total 4.680 pengguna dengan rincian 148 penguna (2016), 4.394 pengguna (2018), 4.138 pengguna (2019).
“Tapi mau pakai aplikasi atau datang langsung (ke KBRI) pelaporan akan tetap kami layani secepatnya,” ujar Hernawan, menjamin pelayanan bagi para WNI.
Editor: Windu Jusuf