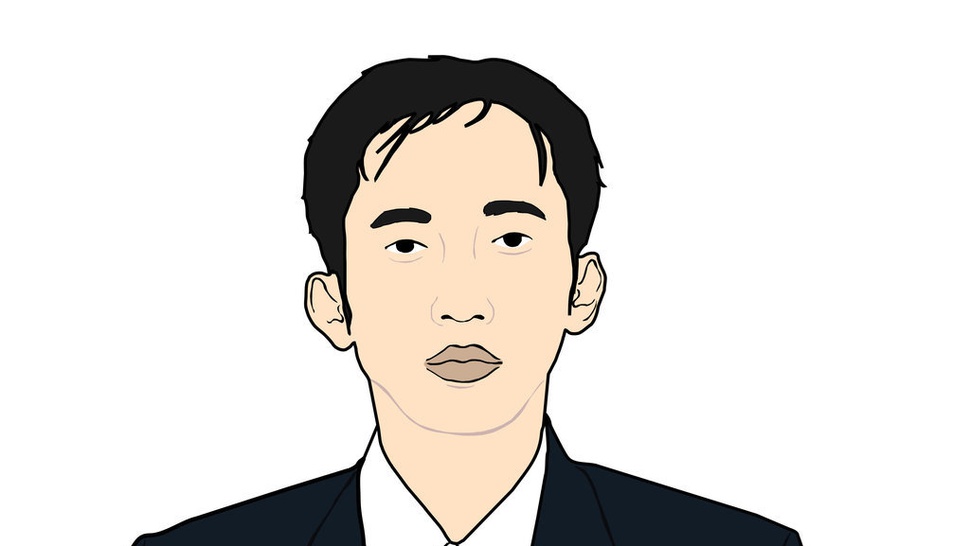tirto.id - Masalah ketimpangan sosial masih bergelayut dan kian merisaukan. Para pengambil kebijakan dibuat pusing dengan problem kronis ini. Pilihan solusi yang tersedia sangat terbatas, sulit, sekaligus dilematis karena melibatkan tak hanya kapasitas teknis tetapi juga landasan ideologis.
Persoalan ketimpangan terjadi pada pelbagai tingkatan: misalnya, antar-individu, antar-gender, antara desa-kota, antar-wilayah, antar-kelompok sosial. Ini sering terjadi di tengah kondisi sosiologis yang terbelah. Tak pelak, kondisi ini turut memperburuk polarisasi politik dengan bangkitnya wacana politik identitas, benturan pandangan antarkelas, dan sentimen anti-globalisasi.
Kepemilikan Aset, Sumber Ketimpangan?
Masalah ini menyeruak di kalangan akademisi setelah Thomas Piketty merilis Capital in the 21st Century (2014). Ekonom asal Perancis ini menyimpulkan persoalan saat ini ekses dari akumulasi aset yang tak terkontrol—sejak era Revolusi Industri—yang terkonsentrasi di kalangan terbatas selama beberapa generasi.
Tulisan Piketty memicu diskursus yang panjang—mungkin melebihi 577 halaman buku Capital—disusul laporan pelbagai lembaga internasional (di antaranya Oxfam, IMF, dan Bank Dunia) yang umumnya sepakat bahwa persoalan ketimpangan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sustainable Development Goals (SDG) juga memasukkan agenda pengurangan ketimpangan. Fenomena ini menunjukkan ada perubahan perspektif yang signifikan.
Sebelumnya, ketimpangan (atau kesenjangan) dianggap alamiah, lumrah, dan merupakan keniscayaan dalam kehidupan. Ketimpangan diyakini menjaga roda perekonomian tetap berputar. Sebagian besar meyakini kekayaan atau kesejahteraan diperoleh sebagai imbalan (reward)hanya melalui kerja keras.
Sementara itu, kemiskinan nyaris lazim diasosiasikan dengan konsekuensi logis atau ‘hukuman’ sebagai akibat kemalasan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dengan argumen ini, ketimpangan selanjutnya dianggap sebagai faktor pendorong masyarakat untuk berinovasi, belajar, dan bekerja lebih keras lagi. Fenomena ini dianggap turut berkontribusi melahirkan para entrepreneur baru dengan kreativitas dan etos kerja yang semakin tinggi.
Klaim ini usang dan tidak adil setelah mengetahui kelompok masyarakat miskin harus bekerja lebih keras dalam kondisi buruk, hanya untuk sekadar mendapatkan upah kecil. Sementara sebagian kelompok yang sudah mapan kesejahteraannya masih berupaya memperkaya diri secara ilegal.
Ketimpangan Global Menurun?
Diskusi mengenai ketimpangan semakin ramai setelah Branko Milanovic dari City University of New York dalam Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization(2016) memaparkan tren penurunan kesenjangan antar-negara (between countries), walaupun kesenjangan di dalam setiap negara (within countries) cenderung memburuk. Salah satu penjelas proses redistribusi dan konvergensi kesejahteraan pada tataran global adalah kebangkitan ekonomi Tiongkok (dan sebagian negara di kawasan Asia) pada dasawarsa terakhir.
Terbaru adalah laporan yang dilansir oleh World Inequality Lab pada Desember 2017 lalu. Digawangi oleh Piketty dan koleganya, laporan tersebut meramalkan penguasaan 24 persen total aset seluruh dunia oleh kelompok "1 persen terkaya" pada 2050. Di sisi lain, kelompok 50 persen terbawah hanya mampu memiliki kurang dari 9 persen aset global.
Laporan ini menyampaikan bahwa tingkat kesenjangan bervariasi pada banyak negara, tetapi Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Rusia meningkat luar biasa sejak 1980. Banyak penyebab yang berpengaruh pada variasi laju ketimpangan, biasanya merujuk pada faktor teknologi, pendidikan, dan kebijakan perpajakan domestik.
Nasib atau Kesempatan?
Kendati fenomena ketimpangan dipercaya menjalankan mekanisme hukuman dan insentif (stick and carrot), itu tak lantas menafikan kenyataan bahwa ketimpangan juga timbul sebagai akibat perbedaan "nasib" atau kesempatan (opportunity).
Jelas bahwa setiap individu tak memiliki kebebasan untuk memilih orang tua, negara tempat lahir, jenis kelamin, suku, dan ras. Anak yang dilahirkan dari keluarga pra-sejahtera atau di kawasan minim fasilitas akan memiliki prospek penghidupan lebih suram dibandingkan temannya yang lebih "beruntung" lahir di tempat yang lebih baik.
Para peneliti saat ini mengalihkan perhatiannya pada faktor yang berpengaruh jangka panjang, seperti mobilitas status sosial yang diyakini dapat menghambat laju peningkatan ketimpangan.
Untuk mengupas persoalan ketimpangan secara lebih obyektif, Francisco Ferreira dari Bank Dunia menjelaskan lewat sudut pandang dunia kesehatan. Bad inequality (ketimpangan buruk) diibaratkan sebagai "kolesterol jahat", yang muncul karena perbedaan nasib antar-individu oleh sebab di luar kuasanya. Sedangkan good inequality (ketimpangan baik), yang diandaikan sebagai "kolesterol baik", adalah manifestasi upaya individu yang murni dihasilkan dari keputusan, kerja keras, bakat, aspirasi, dan mungkin juga keberuntungan.
Gagasan Ferreira untuk melakukan dekomposisi (pemisahan) ukuran ketimpangan sebenarnya dilandasi oleh pemikiran John Roemer—profesor ekonomi dari Universitas Yale—dengan metaforanya: “level of playing field” dan kesamaan kesempatan (equality of opportunity) bagi tiap individu.
Salah satu makalah Ferreira menunjukkan: 1) keterkaitan signifikan antara perbedaan kesempatan dan ukuran ketimpangan konvensional; dan 2) hubungan negatif ketimpangan kesempatan dengan mobilitas antar-generasi (diukur menggunakan variabel lama, yakni sekolah dan pendapatan).
Walter Scheidel, profesor sejarah dari Universitas Stanford, dalam The Great Leveller:Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century(2017) berargumen bahwa tingkat kesenjangan umumnya menurun drastis secara cepat hanya ketika terjadi musibah besar seperti: peperangan, wabah, dan bencana alam.
Dengan menelaah riwayat peradaban kuno Mesir, Romawi, dan kerajaan-kerajaan Eropa lain, Scheidel menemukan bahwa musibah berhasil mengurangi kesenjangan melalui cara yang kurang mengenakkan, khususnya bagi kelompok kaya yang kehilangan sebagian besar hartanya. Mungkin yang terjadi dalam peristiwa tersebut bukanlah redistribusi kekayaan, melainkan dekompresi (penyusutan atau pengurangan aset).
Dalam konteks berbeda, kejadian bencana juga dapat mencetuskan perasaan solidaritas yang kuat dan memunculkan gagasan kebijakan berlatar sosial-demokratiksebagaimana muncul pada banyak negara Eropa pasca-Perang Dunia II.
Ketimpangan di Indonesia
Di Indonesia, isu ketimpangan semakin disorot dan menjadi salah satu indikator dalam pencapaian sasaran pembangunan. Umumnya, tingkat kesenjangan yang diukur lewat indeks rasio Gini. Koefisien Gini menampilkan ketimpangan absolut pada angka satu dan kesetaraan absolut diukur pada angka nol.
Informasi dari arsip zaman kolonial menjelang akhir abad 19 (hasil riset van Zanden, 2003) menunjukkan tingginya tingkat kesenjangan di Hindia Belanda antara lain karena kebijakan pemilahan masyarakat berdasarkan ras—pribumi, pedagang Asia Timur dan Arab, serta Eropa—yang diskriminatif. Struktur masyarakat yang feodalistik dan kuatnya tradisi patron-klien juga turut memperburuk ketimpangan. Dengan kondisi seperti ini, penguasaan modal terkonsentrasi pada kelompok tertentu seperti bangsawan, pengusaha, dan birokrat lokal.

Pada awal abad 20, indeks Gini sempat mengalami penurunan saat pemerintah kolonial mengeluarkan beleid Politik Etis atau Politik Balas Budi (irigasi, imigrasi, dan edukasi) untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Politik Etis melahirkan benih-benih perlawanan rakyat yang dimotori oleh kaum intelektual dan menghasilkan kesadaran untuk bernegara secara merdeka. Namun, ternyata, kondisi ketimpangan semakin memburuk. Pergolakan politik dan konflik berkepanjangan membuat kondisi kesejahteraan semakin timpang hingga mencapai puncaknya pada kisaran 0,5-0,6 menjelang proklamasi kemerdekaan.
Era pasca-revolusi diiringi penurunan ketimpangan meskipun kondisi kesejahteraan secara umum masih memprihatinkan. Walaupun falsafah konstitusi dijiwai semangat sosialisme yang menjunjung tinggi asas pemerataan kesejahteraan, tetapi kenyataannya masyarakat tetap bergumul dengan isu kesenjangan dan permasalahan sosial lainnya.
Masa pemerintahan Orde Baru yang mewarisi persoalan ekonomi relatif berhasil menurunkan tingkat kesenjangan lewat program-program pembangunan kawasan perdesaan dan sektor pertanian. Periode yang terbilang stabil ini semakin diuntungkan dengan windfall profit akhir 1970-an.
Saat itu, naiknya harga minyak dunia dapat mengisi pundi-pundi negara untuk mendanai program pembangunan dan perbaikan kesejahteraan. Namun, cerita sukses disertai represi politik ini berubah tatkala krisis moneter pada 1997. Fondasi perekonomian runtuh dalam waktu singkat dan memunculkan bermacam permasalahan yang sebelumnya terpendam.
Untungnya, proses pemulihan ekonomi dan reformasi politik pada awal abad 21 mampu mengarahkan pembangunan ke jalan yang sesuai. Proses desentralisasi dan demokratisasi secara berangsur menggantikan sistem otoriter yang korup dan terpusat. Namun, tanpa disadari, perbaikan ekonomi juga diiringi tingkat kesenjangan yang merangkak naik, khususnya sejak 2011 ketika kenaikan harga komoditas dunia hanya dinikmati sebagian kecil kalangan.
Hingga kini masih banyak persoalan kesejahteraan yang belum selesai, termasuk tingkat ketimpangan yang masih pada kisaran 0,39, meski pada dua tahun belakangan cenderung menurun. Akan tetapi, tingkat ketimpangan negara terbesar se-ASEAN ini kemungkinan besar masih tetap tinggi apabila diukur indikator pendapatan, bukan dengan pengeluaran rumah tangga seperti selama ini.
Iklim demokratisasi di tingkat lokal dan otonomi daerah memberikan prospek bagi setiap kepala daerah untuk merancang kebijakan sosial yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok rentan. Faktanya, peluang ini belum optimal dimanfaatkan dan masih sering ditemukan praktik money politics serta program-program tak berkesinambungan yang bersifat populis belaka (misalnya: pembagian sembako, pengucuran uang tunai saat kampanye politik, dan gimmick lainnya). Kebijakan seperti ini sering berjalan macet karena semata-mata bertujuan mendongkrak perolehan suara pada musim pilkada.
Untuk mengatasi ketimpangan nasib, harus ada perubahan radikal dalam memandang hak dasar. Misalnya, sarana pendidikan dan kesehatan yang tak cuma tersedia secara luas dan terjangkau tetapi juga seharusnya mempunyai standar kualitas layak yang merata, sehingga dapat memberikan modal kesempatan yang lebih adil bagi setiap warga negara.
Selain itu, perlu gebrakan atas konsep redistribusi, mencakup tak hanya seputar tarif pajak progresif atau reforma agraria tetapi juga mulai meraba kemungkinan instrumen lain, semisal pajak atas harta warisan, rasio ideal gaji tertinggi-terendah, atau universal basic income yang sekarang marak diujicobakan pada banyak negara.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.