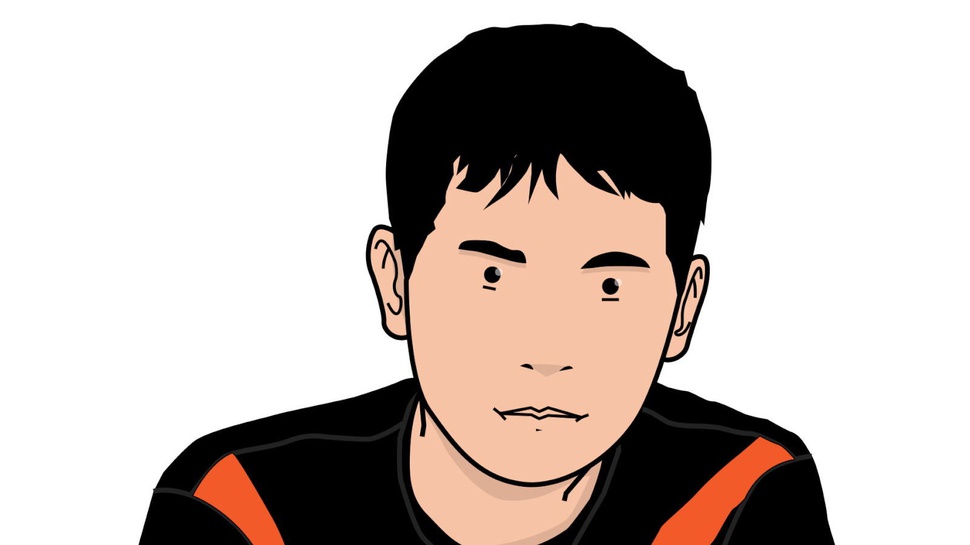tirto.id - —menanggapiartikel Ian Wilson
Dua pekan lalu Ian Wilson menulis artikel di New Mandala, Jakarta: inequality and the poverty of elite pluralism—yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tirto—tentang isu ketimpangan yang tidak menonjol dalam diskursus Pilgub DKI. Isi kritik artikel ini tertuju pada kampanye secara keseluruhan dan kepada kedua kandidat.
Saya setuju dengan maksud utama artikel itu: Melawan narasi dominan yang dibingkai secara biner ("kebinekaan vs populisme sektarian") dalam Pilgub Jakarta; dan menyuarakan krusialnya isu ketimpangan yang seharusnya menjadi salah satu prioritas program politik. Tapi persetujuan saya ini disertai dua koreksi dan satu catatan tambahan.
Ian menulis,“Meski tampak ada pertentangan antara kebhinekaan di satu sisi dan populisme sektarian di sisi lain, kedua kubu punya kesamaan. Keduanya sama-sama mendiamkan satu factor yang secara signifikan membentuk Jakarta, dan agaknya juga pemilu: ketimpangan ekonomi yang semakin parah.”
Saya setuju bahwa isu ketimpangan merupakan “satu faktor yang secara signifikan membentuk Jakarta”. Namun, dan ini koreksi pertama, isu ini muncul dalam kampanye Ahok dan Anies.
Program DP nol persen (terlepas dari apakah ini mungkin terlaksana atau tidak), isu reklamasi, isu penggusuran, dan hal-hal lain yang dibingkai dalam narasi bahwa satu kandidat lebih berpihak kepada si miskin sedang yang lain lebih berpihak kepada si kaya; semuanya berkaitan dengan ketimpangan—meski istilah “ketimpangan” boleh jadi tak dipakai eksplisit. Isu ketimpangan, juga kemiskinan, baik eksplisit maupun implisit, baik benar-benar serius maupun sekadar retorika, telah hadir dalam kampanye.
Kalau mengikuti alur argumentasi Ian, istilah yang lebih tepat agaknya bukan bahwa isu ketimpangan didiamkan, atau tak diperhatikan, melainkan dimanfaatkan atau menjadi instrumen politik belaka.
Koreksi kedua, soal ketimpangan di Jakarta, juga di Indonesia secara umum, yang semakin parah. Dari rujukan dalam hyperlink di artikel, Ian menyatakan level ketimpangan di Indonesia meningkat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2015.
Data Ian perlu diperbarui. Laporan BPS mutakhir (Februari 2017) menunjukkan, ketimpangan di Indonesia secara umum turun: dari rasio gini 0,402 (September 2015), menjadi 0,397 (Maret 2016), lalu 0,394 (September 2016). Ketimpangan di Jakarta juga turun: dari rasio gini 0,421 (September 2015), menjadi 0,411 (Maret 2016), lalu 0,397 (September 2016).
Anda boleh berkata bahwa turunnya angka itu belum cukup signifikan, dan ketimpangan secara umum masih parah: Indonesia menduduki peringkat 4 negara paling timpang sedunia (menurut laporan Credit Suisse yang terkenal itu) dengan 4 orang terkayanya menguasai kekayaan lebih dari yang dimiliki 100 juta orang termiskinnya (berdasarkan laporan Oxfam). Tapi, angka yang ditunjukkan BPS itu jelas turun.
Harian Kompas pernah meliput laporan BPS itu pada 24 Februari lalu, menampilkan grafik bahwa ketimpangan di Jakarta dalam peringkat nasional juga turun: dari peringkat 3 pada September 2015 menjadi peringkat 8 pada September 2016. Di sini kita selaiknya tak lupa bahwa Jakarta adalah kota metropolitan, kota tujuan banyak orang dari mana-mana datang mencari penghidupan. Dengan kalimat lain, tantangan untuk meminimalisasi ketimpangan di ibukota lebih besar, kalau bukan yang paling besar, dibanding banyak provinsi lain. (Catatan sampingan: Provinsi paling timpang dalam laporan mutakhir BPS adalah provinsi tempat saya tinggal, DI Yogyakarta, yang secara nasional peringkatnya naik dari keempat pada 2015 menjadi pertama pada 2016.)
Satu hal lagi: Laporan exit poll Indikator Politik Indonesia pascapilgub DKI putaran II menunjukkan, 58,4 persen menyatakan kondisi ekonomi Jakarta lebih baik dibanding tahun lalu; 23,4 persen menyatakan tidak ada perubahan; sisanya menyatakan lebih buruk atau tidak menjawab. Kalau exit poll ini bisa dianggap cukup merepresentasikan para pemilih Jakarta, data ini bisa relatif melemahkan argumentasi Ian Wilson.
Ketimpangan, juga kemiskinan, boleh jadi adalah “satu faktor yang secara signifikan membentuk” Pilgub Jakarta. Tapi, berdasarkan exit poll, ia bukan yang paling signifikan—jika dengan kata “membentuk” (“shaping”) itu berarti yang paling mempengaruhi jalannya pemilu. Betul, seperti yang telah diliput Tirto, mayoritas warga miskin Jakarta tidak memilih petahana. Tapi ini menunjukkan profil pemilih, bukan motivasi memilih—dengan kata lain, orang miskin tidak niscaya memilih dengan alasan kemiskinannya.
Apa isu yang paling mempengaruhi mayoritas pemilih (atau, meminjam bahasa Ian Wilson, the most significant shaping force in the Jakarta election)? Sebagaimana diliput Tirto, yang berdasarkan laporan lembaga survei, jawabannya adalah agama.
32,5 persen pemilih memilih karena alasan agama. Alasan terbesar kedua, sebanyak 14,5 persen, berkaitan dengan kinerja. 58 persen pemilih kubu penantang memilih karena motivasi agama; dan 31% pemilih kubu petahana memilih karena alasan kinerja. Kesimpulan minimal yang bisa ditarik dari sini: Alasan agama penting dan memang riil berperan dalam pilgub Jakarta. Ketimpangan dan kemiskinan penting; pengaruh esensial agama tak bisa dikesampingkan.
Mengapa agama tetap harus dianggap penting bahkan saat berbicara upaya mengampanyekan isu ketimpangan dalam politik elektoral? Karena, bagaimana mau berbicara isu kemiskinan jika persoalan politik berbasis identitas (semi-)primordial belum selesai?
Kalaupun peran agama dianggap hanya instrumental, dan tidak esensial, pertanyaan selanjutnya: Mengapa agama yang menjadi kanal untuk menyalurkan kegelisahan orang-orang miskin-tertindas itu? Ini pertanyaan yang salah satu isyarat menuju jawabannya ada dalam penelitian dan paper yang pernah ditulis Ian Wilson sendiri, tentang Front Pembela Islam (FPI) dan Front Betawi Rempug (FBR). Dalam paper itu, Ian kurang lebih berkesimpulan bahwa FPI dan FBR kuat di akar rumput dan sanggup memainkan peran “pemerasan atas dasar moralitas” (morality racketeering) ke bawah dan menjalin “patronase politik” (political patronage) ke atas.
Mengarusutamakan isu ketimpangan dan kemiskinan mensyaratkan adanya pendidikan politik, termasuk bagaimana agama semestinya bertempat dalam politik—agar agama tidak menjadi kanal yang dipakai untuk menyalurkan kemarahan. Politiklah yang membawa siapa menduduki apa. Politiklah yang menempatkan siapa yang akan punya kekuasaan untuk meregulasi urusan ekonomi.
Persoalan ini memang kompleks dan tidak bisa disimplifikasi dalam narasi-narasi biner, baik dalam narasi “kebhinekaan vs populisme sektarian” maupun narasi “pro-elite vs pro-kaum miskin”. Dunia politik hari-hari ini, di level lokal maupun global, juga rumit. Kerumitan ini juga terdapat pada hal yang Ian Wilson ingin tawarkan dalam artikelnya: menarik adanya hubungan kausal antara ketimpangan, agama sebagai saluran kegelisahan, dan faktor signifikan pembentuk peta pilgub Jakarta.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.