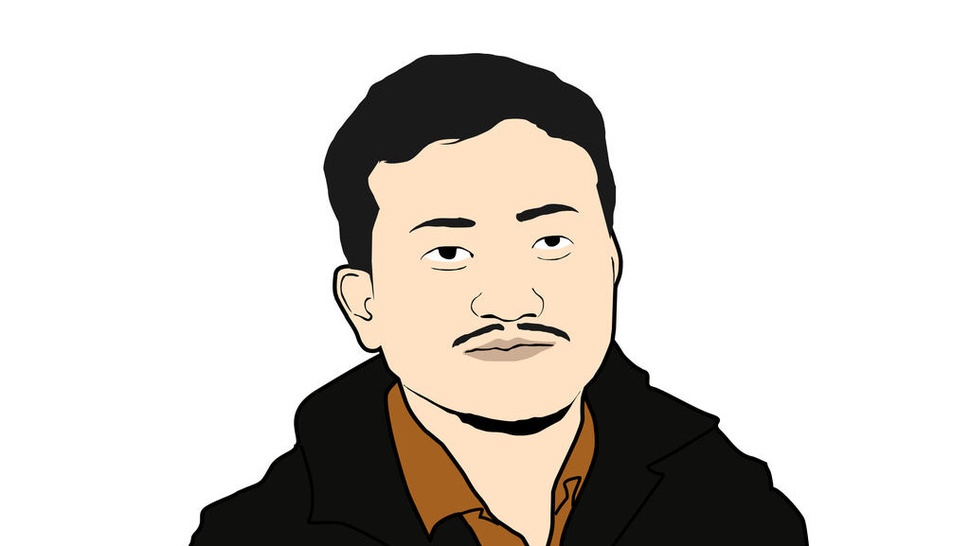tirto.id - Peta politik dunia beberapa tahun terakhir diwarnai kemenangan para politisi ganjil. Amerika Serikat dikejutkan oleh kemenangan Donald Trump, Duterte berhasil menaikkan pengaruhnya dari walikota di sebuah kota kecil hingga jadi orang nomor satu Filipina dalam waktu singkat, dan akhirnya Jair Bolsonaro berhasil mempecundangi calon partai kiri yang dipromosikan oleh Lula, mantan presiden yang masih sangat populer di Brasil.
Apa persamaan ketiga tokoh tersebut? Selain fakta bahwa ketiganya kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial, mereka adalah figur yang melesat lewat mobilisasi politik yang kini dbiasa disebut sebagai populisme kanan. Model politik serupa di Indonesia diusung oleh Prabowo Subianto. Terlepas dari keberhasilan upayanya, pola tersebut masih akan berpengaruh dalam kehidupan demokrasi kita.
Seorang kawan cendekia politik suatu kali mengingatkan, “Kalau Jokowi dan Prabowo sama-sama bisa disebut populis, barangkali konsep ini tidak terlalu berguna.” Pernyataan kawan saya disampaikan karena ia memahami betul bahwa para cendekia pun tidak selalu sepakat soal apa yang mereka maksud sebagai populisme.
Dalam Populism in Southeast Asia, Paul D. Kenny (2019) mencatat dua kelompok besar dalam perdebatan seputar populisme. Kelompok pertama melihat populisme sebagai ideologi yang biasanya ditandai penolakan terhadap kemapanan institusi tradisional. Kelompok kedua melihat populisme sebagai strategi mobilisasi politik. Salah satu karakteristik penting populisme sebagai strategi mobilisasi politik adalah upayanya untuk memangkas jarak antara figur politik dengan pemilih di akar rumput. Pembacaan ini berangkat dari pandangan bahwa populisme terlalu elusif untuk disebut sebagai ideologi. Sebaliknya, jika dibaca sebagai strategi mobilisasi, maka populisme yang digunakan oleh politisi kanan seperti Bolsonaro hingga Chavez yang kiri jadi lebih dapat dipahami. Meski sama-sama populis, cara Bolsonaro dan Chavez mengemas diri sebagai representasi rakyat melawan elite sungguh berbeda.
Di antara varian spektrum tersebut, populisme kanan hari ini lebih dominan di berbagai belahan dunia. Tokoh-tokoh pengusungnya bisa diidentifikasi dari model mobilisasi yang mengawinkan keresahan ekonomi dengan kecemasan soal identitas. Di Amerika Serikat pada 2016, baik Donald Trump maupun Bernie Sanders (ketika itu salah satu kandidat Partai Demokrat) sama-sama menyoroti politisi kebanyakan yang dituduh korup. Namun, ketika Bernie Sanders beranjak lebih jauh mengkritik kapitalisme sebagai akar persoalan, Trump lebih senang menyerang kelompok minoritas seperti Islam ataupun warga negara keturunan Meksiko.
Retorika Trump ternyata disambut oleh sebagian pemilih di Amerika yang juga memiliki sentimen serupa. Pemilih Donald Trump punya keresahan soal ekonomi Amerika yang belum betul-betul pulih sejak krisis 2008, sekaligus kecurigaan besar terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas ini punya kategori yang campur baur mulai dari basis agama seperti Islam, preferensi seksual seperti LGBT, hingga basis ras seperti kelompok kulit hitam. Mereka dicurigai sebagai kelompok yang menggerogoti nilai-nilai tradisional Amerika yang dibayangkan berpijak pada identitas kulit putih dan Protestan.
Di samping pertautan kecemasan ekonomi dan identitas, tokoh populis sayap kanan juga kerap tak malu-malu menunjukkan pandangan otoritarian di ruang publik. Saat berkampanye, Duterte lantang menyebut akan menembak mati para pengedar narkoba langsung di tempat. Pegiat HAM Filipina jelas memprotes pernyataan dan sikap Duterte yang menafikan lembaga peradilan. Meskipun demikian, program Duterte tetap mendapatkan dukungan sejumlah besar pemilih yang muak dengan tingkat kriminalitas di jalan-jalan. Belum sampai dua tahun menjabat, Duterte sudah membunuh ribuan warga Filipina melalui operasi mirip Petrus di indonesia 1980-an. Duterte dengan demikian justru disukai pemilihnya karena ia dianggap mampu menghadirkan rasa aman meskipun harus mengorbankan demokrasi.
Sikap anti-HAM Duterte bukanlah fenomena tunggal. Sikap ini ada dalam kerangka pikir serupa yang umum digunakan oleh para populis kanan. Setidaknya dalam kampanye di muka publik, para figur ini gemar membesarkan kecurigaan terhadap gagasan yang dianggap asing dan berasal dari luar negara bangsa mereka. Kesepakatan soal internasional soal HAM misalnya dipahami sebagai rezim global yang memaksakan kehendaknya pada Filipina. Pandangan senada berada di balik alasan Bolsonaro yang mengundurkan diri dari kesepakatan PBB tentang penerimaan imigran. Ia mendasarkan keputusannya pada motivasi untuk memperkuat kedaulatan negara melalui perancangan aturan yang tidak didikte oleh pihak luar. Bolsonaro juga siap mengeksploitasi hutan Amazon dengan skala yang lebih besar, terlepas dari peringatan banyak badan dunia soal implikasi berbahaya dari tindakan tersebut.
Populisme sayap kanan memang bukan cuma berbahaya karena menguatkan sentimen identitas pada momen kampanye. Potensi masalahnya lebih serius ketika para figur ini memenangkan pemilu dan mulai menjalankan pemerintahan. Kajian Houle dan Kenny (2018) menunjukkan populisme terbukti punya kecenderungan melemahkan demokrasi. Dalam figur-figur yang disebut sebelumnya, kecenderungan itu dapat terlihat dari upaya delegitimasi perangkat hukum dan institusi pemerintahan lain di luar lembaga eksekutif.
Kontradiksi Prabowo
Ekspresi populisme sayap kanan tidak asing bagi wajah politik Indonesia. Salah satu pengusungnya dan masih jadi sosok yang paling mencuat adalah Prabowo Subianto. Sejak 1990-an, ia sudah bicara soal rakyat Indonesia yang tidak menjadi tuan di negaranya sendiri. Pasca Reformasi, dengan berapi-api ia kerap menyampaikan bahwa perkara tersebut disebabkan oleh elit-elit yang korup dan konspirasi bangsa asing. Prabowo sendiri dengan demikian menampilkan diri sebagai penyelamat bangsa yang mampu menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Atau kalau bukan macan, minimal ia mampu menyelamatkan Indonesia dari kepunahan.
Banyak orang mengkritik Prabowo karena model kampanyenya penuh dengan kontradiksi. Ia menampilkan diri sebagai pembela rakyat kecil sementara seluruh hidupnya dihabiskan sebagai bagian dari elite oligarki Indonesia. Prabowo menggembar-gemborkan bakal menolak pengaruh asing, sementara dalam urusan bisnis atau pribadinya ia nampak sangat akrab dengan dunia internasional. Beberapa kritik bahkan mengangkat masalah remeh seperti Prabowo yang mengemas diri sebagai pembela Islam tapi hampir tidak pernah terlihat sholat Jumat.
Di sisi lain, kritik-kritik itu gagal memahami bahwa figur pengusung populisme kanan memang tidak pernah dipilih karena sosoknya bebas kontradiksi. Mereka dipilih karena gagasan yang dikemukakannya bergema dengan imajinasi sejumlah besar pemilih mengenai permasalahan bangsa.
Dalam konteks Indonesia, tema pengaruh asing dalam politik, ekonomi, dan budaya telah lama melekat dalam sejarah. Demikian juga tema kecurigaan terhadap etnis Tionghoa yang mendominasi ekonomi hampir selalu muncul dalam tiap periode pemerintahan. Dalam konteks hari ini, imajinasi-imajinasi tersebut berkelindan dengan aspirasi banyak orang untuk mewujudkan kesalehan di ruang publik. Sebab seperti yang dikemukakan Vedi Hadiz dalam Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (2016) salah satu karakteristik penting populisme di Indonesia adalah diadopsinya konsep “umat” sebagai istilah yang dapat dipertukarkan dengan “rakyat”. Figur populisme kanan di Indonesia dengan demikian akan naik jika mampu merepresentasikan diri sebagai jawaban dari imajinasi umat akan termarjinalkannya mereka baik di ranah ekonomi maupun kebudayaan.
Prabowo dalam hal ini secara aktif berupaya tampil sebagai sosok yang mampu menjawab keresahan itu. Selain terus menuduh pemerintah membiarkan kekayaan Indonesia lari ke tangan asing, Prabowo juga luwes berinteraksi dengan tokoh-tokoh pengusung politik Islam. Ia misalnya bersua dengan Rizieq Shihab yang tengah buron di Arab Saudi. Prabowo juga secara terbuka berterima kasih pada gerakan 212. Populisme kanan yang diusung Prabowo rupanya cukup ampuh. Pilihan Jokowi pada Ma’ruf Amin sebagai kandidat wakilnya pun tidak dapat dipisahkan dari konteks tersebut. Sosok Ma’ruf Amin sebagai Ketua MUI sekaligus Rais Aam NU adalah bagian dari upaya merebut suara umat yang elusif itu.
Pemilu 2019 adalah upaya ketiga Prabowo dalam berkontestasi menjadi pemimpin negara Indonesia. Jika kali ini ia menang, Prabowo akan menjadi bagian dari arus kemenangan populisme kanan di banyak negara demokrasi dunia bersama Duterte dan Bolsonaro. Tapi kalaupun ia gagal, bukan berarti populisme kanan akan hilang dari peta politik Indonesia. Sebab sebagian ekspresi populisme sayap kanan juga ditemukan dalam mobilisasi politik yang dilakukan oleh petahana. Selain itu, seperti yang disampaikan Aspinall (2015), alih-alih soal figur populisme di Indonesia kemungkinan bertahan karena model mobilisasi ini punya akar panjang dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu, ditambah dengan kegelisahan soal ekonomi dan perubahan budaya yang masih akan bertahan, populisme kanan juga masih akan dimainkan dalam waktu yang tidak sejenak.
Kenyataan itu jelas bukan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.