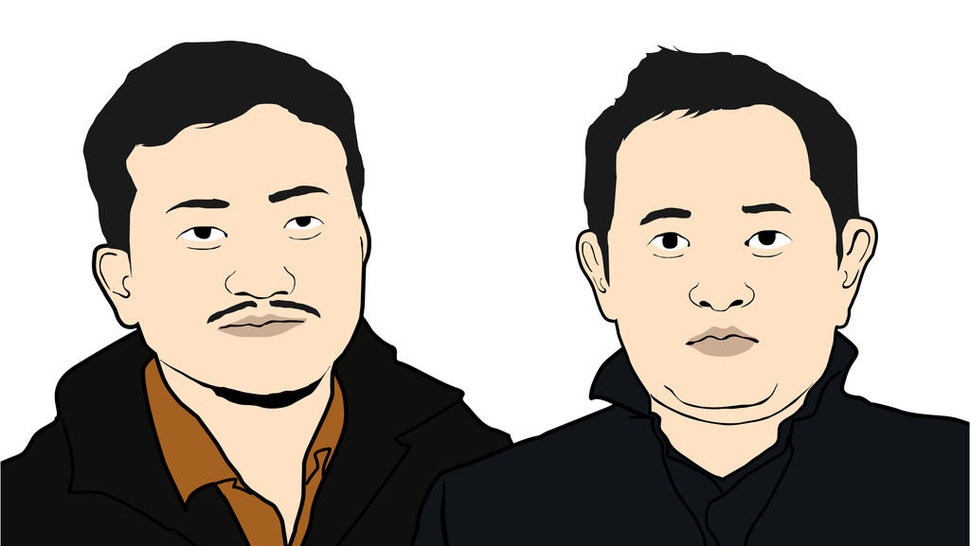tirto.id - Setelah serangkaian demonstrasi 'Aksi 212' yang menyelimuti pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, pembicaraan seputar ketidakpuasan umat Islam dan penguatan peran ulama makin mengemuka di kalangan pengkritik Jokowi dari golongan Islamis.
Ancaman politik ini tak diabaikan Jokowi. Jokowi misalnya menunjukkan komitmen keislaman dengan berkunjung ke pesantren dan merekrut sejumlah tokoh dan politikus Islam ke dalam kubunya. Bahkan, sebelum menggandeng Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden, Jokowi telah mengangkat Ali Mochtar Ngabalin sebagai tenaga ahli di Kantor Staf Presiden pada Mei 2018. Ia juga menunjuk Din Syamsuddin, mantan ketua Muhammadiyah yang konservatif, sebagai “utusan khusus presiden”. Pemilihan Ma’ruf Amin sebagai pasangan cawapres adalah puncak dari strategi akomodatif Jokowi tak lama setelah tragedi Ahok.
Tantangan kelompok Islamis dan respons kubu Jokowi menghadirkan momentum yang tepat untuk mengkaji ulang tesis inklusi-moderasi (inclusion-moderation thesis), sebuah konsep besar yang lazim dipakai untuk memahami pengaruh aktor-aktor Islam dalam politik Indonesia. Menurut tesis ini, pengakomodasian aktor-aktor politik yang berpotensi menggoyang sistem (potentially disruptive actors) ke dalam proses dan lembaga-lembaga politik yang ada, akan mengubah tujuan/perilaku dari yang semula radikal ke arah posisi lebih moderat.
Perspektif ini sering digunakan untuk memahami evolusi partai dan organisasi Islam seperti PKS, yang dari waktu ke waktu melembutkan pandangan keagamannya dengan cara mendukung Pancasila secara resmi, bahkan merevisi AD/ART organisasi sehingga kalangan non-muslim dapat menduduki jabatan eksekutif di tubuh partai. Dari sudut pandang sejarah, Jeremy Menchik berpendapat bahwa selama bertahun-tahun Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah telah menunjukkan kemampuan mereka untuk memoderasi diri dan “menjadi bagian dari sistem, alih-alih menggulingkannya”.
Membesarkan Konservatisme dari Dalam
Jika dibaca lewat teropong tesis inklusi-moderasi, Ma’ruf diprediksi akan mengurangi anasir konservatismenya dan bersikap lebih moderat jika terpilih sebagai wakil presiden pada 2019. Sebagai wakil presiden, mau tak mau, ia akan bekerja sama dengan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pihak-pihak dari kelompok etnis dan agama minoritas di Indonesia. Maka, seperti yang pernah ditulis Greg Fealy di New Mandala, menjadi logis jika Ma’ruf akan lebih toleran jika terpilih sebagai wakil presiden; lebih toleran ketimbang saat duduk di kursi ketua MUI.
Namun, asumsi tersebut terkesan sangat optimis.
Di balik kerangka moderasi yang sama, keterlibatan dalam proses-proses demokratis justru menyuburkan aktor-aktor Islamis. Ketika kaum Islamis berpotensi menjadi lebih moderat ketika masuk ke dalam lembaga kekuasaan, institusi-institusi demokrasi bisa dan akan mengadopsi agenda-agenda Islam politik.
Dalam jangka panjang, fenomena ini akan menciptakan apa yang disebut Jeremy Menchik sebagai “sakralisasi” negara Indonesia—inilah harga yang harus dibayar ketika aktor-aktor Islam tertentu, yang memiliki tendensi anti-demokrasi, diserap ke dalam sistem.
Kami yakin skenario ini lebih bisa digunakan untuk memahami dampak pencalonan Ma’ruf Amin. Jika terpilih, ada kemungkinan Ma’ruf akan memengaruhi periode kedua pemerintahan Jokowi sehingga menjadi lebih konservatif, terutama dalam urusan agama.
Rekam jejak sikap intoleran Ma’ruf sudah bukan rahasia umum. Jika ia mengambil sikap yang sama sebagai wakil presiden, kecil kemungkinan Jokowi bakal mengindahkan tekanan publik untuk mendengar suara kelompok minoritas. Indikasinya sudah terlihat: di tengah kasus Ahok, Jokowi terlihat menjaga jarak dan tidak berusaha membela mantan gubernur Jakarta itu dari dakwaan penodaan agama. Kehadiran Ma’ruf Amin kemungkinan besar menempatkan Jokowi pada posisi yang sama: tak membela kelompok-kelompok minoritas di Indonesia—jika bukan malah secara aktif melegitimasi diskriminasi yang sudah ada.
Di sisi lain, watak ormas-ormas Islam yang berusaha diakomodasi Jokowi juga berubah. Selama satu dekade terakhir, baik NU dan Muhammadiyah, mengalami perubahan internal. Anasir konservatif dalam kedua organisasi makin menonjol. Pengangkatan Ma’ruf Amin—yang mewakili sayap konservatif NU—sebagai Rais Aam NU adalah contohnya.
Kedudukan sosial NU dan Muhammadiyah sebagai otoritas Islam Indonesia juga diperebutkan oleh ormas-ormas keagamaan di luar kedua organisasi. Lagi-lagi, kasus 'Aksi 212' dapat dikutip sebagai contoh. Meskipun beberapa kali NU dan Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan resmi agar anggotanya tidak berpartisipasi dalam 'Aksi 212', tetap saja ada banyak anggotanya yang bergabung dengan ormas semacam Wahdah Islamiyah dan FPI. Semakin luas FPI dan ormas-ormas sejenis menebar di masyarakat, tokoh Islamis dari faksi NU “Garis Lurus” seperti Abdul Somad atau Rizieq Shihab dari FPI boleh jadi akan mengikuti jalan Ma’ruf Amin dan melebarkan otoritas keagamaan mereka ke dalam struktur politik formal.
Tak Sepenuhnya Kalah, Tak Mutlak Menang
Terlepas dari siapa yang akan memenangkan pemilihan presiden 2019, hampir mustahil mengabaikan peran aktor-aktor agama dalam perpolitikan lokal dan nasional di Indonesia hari ini.
Sejak pemilu 2014, banyak orang memilih Jokowi karena takut demokrasi akan terancam jika Prabowo menang. Ketakutan semacam ini sah-sah saja mengingat rekam jejak HAM Prabowo yang bermasalah serta afiliasi sang capres dengan kelompok-kelompok Islam politik. Pada saat bersamaan, penunjukan Ma’ruf Amin sebagai cawapres mengambarkan betapa Islam politik hari ini diakomodasi penuh oleh kedua kubu, baik Jokowi maupun Prabowo.
Pencalonan Ma’ruf Amin menyodorkan pekerjaan rumah besar bagi tesis inklusi-moderasi. Pasalnya, tesis ini berpijak pada asumsi dasar bahwa ancaman terbesar terhadap demokrasi datang dari aktor-aktor yang menolak institusi-institusi demokrasi. Namun, rupanya tantangan itu tidak berasal dari Hizbut Tahrir Indonesia, ormas Islam transnasional yang dipandang oleh pemerintah dan sebagian peneliti sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi di Indonesia.
Aktor-aktor politik Islam yang terjun ke dunia politik seraya mempertahankan konservatisme mungkin akan menjadi ancaman yang lebih besar ketimbang HTI. Tokoh seperti Ma’ruf Amin boleh jadi tidak bercita-cita mengubah sistem demokrasi. Namun, aktor-aktor politik Islam semacam Ma’ruf Amin adalah orang yang sangat percaya pada pentingnya menegakkan norma-norma agama dalam kehidupan publik.
“Sakralisasi negara”, demikian saran Jeremy Menchik, lebih tepat didudukkan sebagai konsekuensi sejarah yang tak terelakkan, alih-alih dipandang sebagai satu-satunya tantangan bagi demokrasi Indonesia. Bagaimanapun juga mengamankan peran agama selalu menjadi bagian penting dalam formasi negara di Indonesia. Untuk memastikan agar demokrasi berfungsi, tegas Menchik, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan situasi tatkala anasir-anasir keagamaan tak sepenuhnya “kalah” atau tak mutlak “menang” dalam lembaga-lembaga demokrasi.
Kami mengakui pentingnya menganalisis demokrasi Indonesia di luar kerangka demokrasi liberal khas Barat. Namun, ada soal mendasar yang tak kunjung terpecahkan: sampai mana demokrasi Indonesia mampu mengakomodasi aktor-aktor politik Islam tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya? Bagi minoritas di Indonesia, sebuah sistem ketika aktor-aktor politik Islam “tidak sepenuhnya kalah maupun menang” hanya menawarkan kekalahan abadi.
Sayangnya lagi, tak ada batasan yang jelas (dan ideal) antara demokrasi dan tuntutan politik Islam di Indonesia. Walhasil, kelak, ketika kita berhasil memahami betapa suksesnya aktor-aktor Islam politik mengubah watak demokrasi Indonesia di masa mendatang, barangkali kita sudah terlambat mengambil sikap.
Pandangan ini mungkin menawarkan prediksi masa depan yang suram. Namun, penting untuk kembali menengok perkembangan 'Aksi 212' yang telah membuat banyak pihak, termasuk peneliti, bingung menentukan sikap. Jika kita masih percaya pada kelebihan tesis inklusi-moderasi, kajian-kajian di masa mendatang perlu membuat garis tegas untuk memastikan pada titik apa kelompok-kelompok Islam politik mulai menjadi ancaman serius bagi demokrasi.
=====
Tulisan ini diterjemahkan oleh Irma Garnesia dari "Ma’ruf Amin and the inclusion–moderation thesis" yang dimuat di New Mandala pada 3 Oktober 2018. Penerjemahan dan penerbitan di Tirto atas seizin penulis.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.