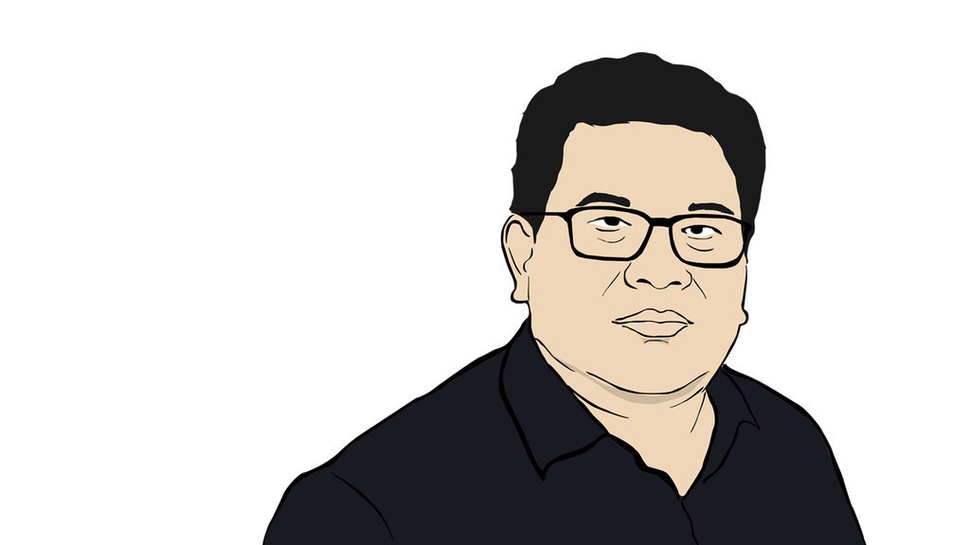tirto.id - Teknologi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) diklaim semakin canggih. Sistem pembakaran yang sempurna bahkan membuat pelaku berani melabelinya sebagai teknologi clean coal. Akan tetapi, sejatinya tidak ada batu bara yang benar-benar bersih. Sebab, penggunaan batu bara sendiri sejak dari hulunya tidaklah bersih.
Di hilir, pemanfaatan batu bara untuk PLTU juga kerap menimbulkan persoalan. Debu halusnya yang diterbangkan angin memicu keluhan kesehatan berupa gangguan pernapasan. Hujan asam – meski belum begitu terasa – merupakan ancaman riil yang mematikan tanaman. Selain itu, pembuangan air panas dari pembangkit menimbulkan kematian biota laut.
Sederet efek kotor tersebut seharusnya membuat pemerintah berpikir seribu kali sebelum membangun PLTU. Namun, dengan pertimbangan batu bara yang melimpah dan harga batu bara yang murah, pemerintah masih memprioritaskan pembangunan PLTU dalam program 35GW. Hingga semester I 2017, dari total kapasitas terpasang pembangkit sebesar 60,1 GW, sekitar 52% masih berasal dari energi batu bara
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Faby Tumiwa menyebut sejumlah faktor yang membuat dominasi pembangkit listrik bertenaga batu bara dalam program 35.000 megawatt (MW) sulit terelakkan. Sikap politisi yang populis berkelindan dengan kepentingan para pemodal menjadi penyebab utama PLTU tumbuh subur di Jawa. Rendahnya kesadarakan publik akan kualitas lingkungan juga turun menghambat perubahan ke pemanfaatan energi terbarukan.
Di samping itu, kendati sumber energi terbarukan, seperti sinar matahari dan angin, tersedia melimpah di tanah air, realisasi pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan pun tidak segampang membalik telapak tangan. Ada banyak kendala, baik teknis maupun non-teknis.
Meski demikian, mengakhiri perbincangan akrab selama 1,5 jam pada 23 September 2017 lalu, Faby memperingatkan bahwa PLTU akan menjadi teknologi yang obsolete alias ketinggalan zaman dalam waktu yang tidak lama lagi. Revolusi teknologi akan membuat ketersediaan pembangkit listrik energi terbarukan lebih mudah. Akhirnya, dalam 10 tahun lagi, PLTU akan menjadi aset yang terbengkalai di tanah Jawa.
Berikut nukilan wawancara Tirto dengan Direktur Eksekutif IESR Faby Tumiwa di kantornya yang beralamat di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.
Bicara proyek 35 GW, menurut Anda, apakah kita memang perlu membutuhkan penambahan sebanyak itu?
Kalau kita melihat sejarah munculnya program 35.000 MW, pada 2013 – 2014, kita mengalami kondisi di mana banyak daerah yang dilayani PLN mengalami kondisi kekurangan pasokan listrik. Yang kedua, ada ancaman serius terhadap kondisi pasokan listrik di Jawa karena, dalam 10 tahun terakhir, permintaan listrik tumbuh gila-gilaan. Pertumbuhan permintaan listrik di Jawa 8% per tahun. Di luar Jawa, bahkan 10%-12%. Jadi berdasarkan kondisi 2013-2014, diproyeksikan akan ada permintaan listrik yang besar, tumbuh 9%-10% per tahun. Jadi dasarnya itu.
Pertimbangan penambahan 35 GW itu bukan out of nowhere. Waktu itu, ada target Nawacita dari Presiden baru. Lalu ada pertimbangan untuk menaikkan rasio elektrifikasi sampai 100%, dari saat itu 85%. Kemudian, ada target untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita dari 700 kwh per kapita per tahun, menjadi 1200 kwh per kapita per tahun. Dihitung-hitung, keluarlah angka 25 GW-35 GW.
Mengapa ditetapkan 35 GW?
Pada saat 2014 itu, Jokowi-JK memang sudah bilang untuk membangun (pembangkit listrik). Waktu itu, keluar angka 25.000 MW. Tapi kemudian, setelah jadi presiden, diusulkan oleh Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla), ditambah sajalah menjadi 35.000 MW. Karena, berdasarkan pengalaman, 25.000 itu bisa saja terlampaui dengan cepat. Karena waktu itu pemerintah sangat optimistis dengan pertumbuhan ekonomi. Dan, kayaknya lebih catchy kalau pakai 35 GW program itu.
Sekarang, ternyata kalau dilihat, dalam dua tahun terakhir, 2015-2016, bahkan kemungkinan sampai tahun ketiga ini, 2017, pertumbuhan eknomi tidak seperti dicanangkan, sebesar 7%. Ini juga memengaruhi pertumbuhan permintaan listrik. Pertumbuhannya tidak sampai 8%-9% per tahun. Kenyataannya, lebih rendah daripada itu. Jadi kalau ditanya, kita sekarang butuh enggak 35.000 MW? Sampai dengan 2020, kita enggak butuh sebesar 35.000 MW.
Estimasinya terbaiknya, kalaupun ekonomi membaik, bisa mencapai 6% di 2018-2019, maka kita butuh listrik sampai dengan 2019-2020, paling pol 20-an GW. Kalau melihat tren tiga tahun terakhir, kalau dibangun 20 GW-22 GW, itu lebih dari cukup.
Mengapa banyak dibangun di Jawa?
Tadinya semua (permintaan listrik) tinggi. Kita pernah lihat Sumatera bisa sampai 10%, Sulawesi 11%. Sebenarnya, tantangan pemerintah, ada dua. Ini memang baru kita lihat setelah 2014, setelah kita menjadi middle income country.
Yang pertama, memenuhi akses listrik bagi rumah tangga atau rakyat yang belum berlistrik. Kalau kita bicara rakyat yang belum berlistrik, di 2014, kira-kira 7 juta-8 juta rumah tangga. Sekarang kira-kira 5 jutaan. Kita bicara desa yang belum berlistrik, data Kementerian ESDM, ada sekitar 2.500 desa. Kalau data PLN, 3.600 desa lebih, ya. Perbedaan ini karena persoalan definisi desa beda-beda. Jadi, tantangan yang pertama, memang harus meningkatkan akses listrik. Itu yang kita bilang sebagai pemerataan.
Yang kedua, sebagai negara yang tengah tumbuh ekonominya, muncul yang namanya kelas menengah baru. Pendapatan bertambah, purchasing power-nya juga bertambah. Kebutuhan akan listriknya juga bertambah. Mulai bisa beli AC. Yang tadinya bisa beli AC satu, jadi beli dua. Mulai bisa beli kulkas. Yang tadinya punya kulkas satu, beli dua atau beli yang lebih besar. Dan, mulai menggunakan barang-barang elektronik yang lain. Nah, kebutuhan listrik kelas menengah yangbertambah ini juga harus dipenuhi. Hanya masalahnya, agak sulit membuat proyeksi untuk pertumbuhan listrik ini. Karena, buying power saya itu sebenarnya tergantung pada kecepatan tingkat kenaikan pendapatan saya. Jadi, akan muncul sekian juta new middle class, yang kita belum tahu persis berapa, diestimasi saja.
Jadi, itu dua challenge yang dihadapi pemerintah; menambah akses energi dan memenuhi kebutuhan energi. Dua-duanya memerlukan suplai. Program 35.000 MW itu karena melihat tren demografi Indonesia bergeser, menjadi lebih kaya.
Sebagian besar pembangkit yang direncanakan masih berbasis batu bara. Mengapa demikian?
Pertama, karena Indonesia punya stok batu bara yang banyak. Dan, yang banyak itu sebenarnya yang kalori rendah atau yang tidak laku atau tidak ada pasarnya di luar negeri. Jadi hanya bisa dipakai di dalam negeri. Kita termasuk salah satu negara dengan cadangan batu bara yang gede. Dari yang gede itu, kira-kira 40% enggak bisa diekspor. Sehingga sejak 10 tahun lalu, jadi sejak zaman Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), strateginya adalah pemanfaatan sumber daya energi domestik untuk menyediakan energi yang murah. Pilihan kepada batu bara karena biaya produksi untuk menghasilkan listrik dari batu bara, itulah yang termurah.
Tapi, dalam perencanaan sistem kelistrikan itu, ada berbagai sistem pembangkit kelistrikan. Enggak bisa hanya batu bara. Harus ada jenis pembangkit lain yang bisa mengikuti perubahan beban. Apa itu? Ya, ada gas, air, dan lain-lain. Tapi batu bara menjadi dominan karena kita masih memiliki banyak resource dan harga listriknya murah. Fokus pemerintah menyediakan listrik dengan harga murah. Itu kenapa alasan dibangun (pembangkit) batu bara dan bukan yang lain.
Bisa saja membangun pembangkit bukan dari batu bara. Tapi membangun sistem pembangkit itu banyak pertimbangannya, tidak asal bangun. Bisa efektif, efisien, dan terjangkau harganya enggak. Renewable energy praktis dapat angin baru 4-5 tahun terakhir, walaupun sudah divisikan dari tahun 1981.
Selain murah, apakah ada hubungannya dengan kondisi internasional, di mana permintaan batu bara berkurang dan harga turun, sehingga ada kebutuhan untuk tetap menghidupkan industri batu bara di dalam negeri?
Ya, sudah jelas permintaan batu bara di seluruh dunia menurun. Pasar terbesar Indonesia, kan, Cina. Baru kemudian, India, Jepang, Korea. Permintaan batu bara di negara-negara tersebut juga menurun. Sejak 2014, permintaan dari Cina berkurang drastis.
Walaupun, kita lihat sekarang ekspor kita masih besar. Dari total produksi sekitar 400 juta ton per tahun, sekitar 75%-78% diekspor. Sisanya dipakai kebutuhan di dalam negeri. Namun, tentunya mereka membaca bahwa industri batu bara ini sulit untuk rebound seperti 2008-2013. Jadi mereka melihat peluang di dalam negeri. Mereka menyadari ini ketika harga masih tinggi pada 2008. Mereka sudah berpikir untuk diversifikasi sekaligus mengoptimalkan resource-nya. Solusi yang keluar waktu itu, kalau begitu kita bikin sendiri saja untuk menyerap batu bara yang kita punya. Karena, kalau mengikuti kebutuhan batu bara PLN, yang volume permintaannya terbesar saat itu, ya pasti lamban penyerapannya.
Jadi benar memang ada dampak dari kondisi global?
Saya kira benar bahwa para pengusaha batu bara itu mencoba untuk memaksimalkan asetnya. Karena saya yakin mereka juga melihat tren di mana 20-30 tahun dari sekarang, batu bara itu tidak lagi jadi pilihan yang mungkin nomor satu seperti sekarang ini.
Apakah karena itu, mereka sekarang menggenjot produksinya karena mungkin di masa depan sudah sunset industry?
Sebenarnya, program 35.000 MW itu memberi kesempatan juga bagi mereka. PLN dikasih 10.000 MW, swasta ngerjain 25.000 MW. Swasta melihat bahwa program ini bisa berdampak pada performance industri mereka.
Kembali soal least cost. Kalau hanya menghitung biaya produksi, batu bara mungkin memang yang paling murah. Tapi, secara jangka panjang, apakah batu bara ini least cost dilihat efeknya pada lingkungan dan kesehatan masyarakat?
Ini juga sebenarnya sudah perdebatan yang lama, sudah 20-30 tahun. Jadi kalau kita bicara cost, apakah kita sudah memasukkan biaya eksternalitas? Untuk pembangkit batu bara, Anda butuh air. Bila ambil air laut, mungkin enggak terlalu efek karena Anda tidak mengurangi fresh water yang di darat. Walaupun, ada persoalan water discharge ke laut yang suhunya tinggi. Kalau temperatur airnya naik 5%, bagaimana ekosistem di situ. Kemudian, ada air pollution. Berapa orang terkena sakit paru-paru, berapa biaya kesehatannya. Sebenarnya eksternalitas ini harus diperhitungkan. Masalahnya, itu tidak embedded dalam biaya ketika kita merancang sistem itu.
Kenapa? Karena tidak ada regulasi sampai hari dari pemerintah untuk mengatur masalah eksternalitas. Dan, sejujurnya, dari sekitar 190 sekian negara yang ada di seluruh dunia, berapa banyak, sih, yang menerapkan eksternalitas? Eropa saja baru-baru, kok. Yang lain malah enggak ada.
Masalahnya, kalau saya investor, yang saya hitung, kan, investasi yang saya keluarkan langsung. Healthcost, environmentaldamage, dan lain-lain itu tidak masuk dalam accounting saya. Itu socialcost yang ditanggung masyarakat, yang indirect. Maksudnya, saya tidak menanggung itu. Oleh karena itu, buat pengusaha, ya ngapain saya ngitungin itu. Nah, di situ sebenarnya peran regulasi. Dan, di sini sebenarnya titik lemah kita.
Bagaimana bentuk regulasi di negara lain?
Sebagai contoh, di Amerika, ketika mereka banyak bangun PLTU, mulai tahun 80-an sudah diterapkan standar emisi SOx (oksidasi sulfur), NOx (oksidasi nitrogen), dipakai teknologi katalitik untuk mengurangi itu. Di banyak negara yang menggunakan PLTU, negara-negara maju khususnya, emisinya diatur dengan ketat.Ada continues monitoring system, sehingga badan regulatornya bisa setiap saat mengecek emisi gas buang dari pembangkit listrik, ataupun yang thermal. Di kita, tidak ada seperti itu.
Kita punya standar kualitas udara dari sumber-sumber stasioner, termasuk pembangkit listrik thermal, itu rendah sekali. Di India tadinya juga, tapi mereka baru mengeluarkan regulasi baru. Dampak-dampak itu bisa dikurangi kalau ada regulasi dan teknologi, walaupun tidak menghilangkan secara keseluruhan. Misalnya, saya punya pembangkit PLTU 1.000 MW dengan teknologi super critical yang konsumsi batu bara untuk per kWh-nya sedikit lebih rendah, konon 20%-25% lebih rendah daripada conventionalcoalpowerplant. Tapi, kan, tetap saya menambang batu bara. Dampak di pertambangan tetap sama. Setuju bahwa ada dampak. Tapi sekarang, yang kita sebut sebagai dampak atau external cost itu, tidak pernah dimasukkan dalam perhitungan.
Kenapa kita tidak belajar dari negara lain yang lebih dulu mengalami dampak buruk PLTU? Ketidakpedulian atau semata pertimbangan bisnis?
Kalau tahun 80-90, itu dianggap tidak terlalu perlu karena konsumsi listriknya masih kecil. Sekarang, sebenarnya bukan tidak ada sama sekali pembicaraan ke arah situ. Tapi saya melihat ada keengganan dari regulator. Pertama, nanti dianggap membuat industrinya tidak kompetitif. Kedua, dari persepsi pelaku atau pengembang atau pemilik pembangkit listriknya, regulasi yang lebih tough berarti additionalcost. Jadi, kepentingan keduanya ketemu. Satu pihak yang khawatir atau malas, dan yang bilang biayanya akan naik.
Kalau saya, IESR, sudah berkali-kali mengusulkan, itu dihitung, dong, berapa external cost-nya. Lalu, itu ditambahin di harga. Tapi, kalau itu dimasukkan, nanti, kan, biaya listriknya jadi lebih mahal. Kita juga bilang, pakai, dong, pajak karbon. Tapi secara regulasi itu juga sulit diterapkan. Kita bilang, eh, ada dong, standar baku emisi yang lebih ketat untuk batu bara. Jadi, nanti dalam pemilihan teknologi tidak sembarangan. Ini juga masih proses. Sebab, selalu dalam pandangan banyak orang, more regulations, more costly. Berarti, listrik mahal. Nah, pimpinan-pimpinan politik kita selalu tidak mau dianggap sebagai penyebab harga energi tinggi, yang kemudian dibilang tidak pro-rakyat.
Yang mau saya katakan adalah, industri batu bara itu punya banyak kepentingan dan banyak interaksi politik. Industrinya sendiri bilang, eh, kita bayar 45% pajak, lo. Ini juga jadi bargainingpower buat mereka. Eh, jangan bikin aturan environment yang ketat-ketat, kita bayarnya 45%, lo. Itu masalahnya.
Tapi, kalau begitu, mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dong?
Masalahnya, yang terdampak, kan, hanya komunitas di mana pembangkit itu ada. Orang Jakarta terdampak, gak? Polusi udara, tergantung arah angin. Hujan asam, terjadi enggak di Indonesia? Tidak atau belum terasa. Tapi, secara langsung, ada enggak orang Jakarta yang diambil tanahnya? Masalahnya, orang itu belum sadar karena belum mengalami environmental disaster.
Orang-orang Eropa sangat kritis terhadap industri barubara karena mereka mengalami hujan asam tahun 70-an sampai 80-an. Itu kenapa mereka beralih ke energi bersih. Tahun 50-60, Jerman udaranya gelap kok. Lebih gelap daripada Jakarta. Bisa tanya sama orang-orang tua di Jerman. Kemudian, environmentaldisaster terjadi, hujan asam terjadi di Eropa tahun 80-an, intensitasnya tinggi. Itu yang membuat, baik masyarakat maupun pemerintahnya, menjadi lebih sadar. Kemudian mereka melakukan pengetatan standar lingkungan maupun mulai memikirkan teknologi-teknologi yang alternatif pada waktu itu.
Poinnya adalah kita tidak merasakan dampak itu. Dampaknya masih sangat terlokalisir di masyarakat lokal. Yang diambil tanahnya, yang kena polusi udara karena penumpukan cadangan batu bara di situ, yang rumahnya kena hujan es, dan seterusnya. Yang mau saya bilang, kalau sudah menjadi persoalan orang banyak dan kemudian ada significant environmental cost, baru kemudian biasanya ribut.
Apakah kita perlu menunggu itu terjadi dulu?
Sebenarnya tidak perlu menunggu itu terjadi kalau masyarakat punya environment quality awareness. Kenyataannya, environment quality awareness masyarakat kita rendah sekali. Jadi, persoalan kita hari ini, tidak ada demand publik untuk mendorong energi bersih.
Kenapa tidak ada demand? Pertama, karena orang masih mau harga energi murah. Sekarang begini, apakah seluruh masyarakat setuju kalau kita keluar dari batu bara? Ada konsekuensinya. Mungkin harga listrik lebih mahal. Mau, enggak? Kemarin harga listrik naik sedikit saja, yang subsidi 900 VA, orang ribut, kok. Padahal, pemakaian listrik kita sembarangan sekali. Tidak ada kebiasaan untuk menghargai listrik. Di negara-negara maju, fase ini sudah terlewati. Kalau saya, lebih baik kita pakai renewable energy, kita naikkan harga listrik, biar orang menghargai listrik.
Di Eropa, Anda bisa memilih, oh, saya mau switch ke 100% renewable. Oke, saya bayarnya 20% lebih mahal, tapi I feel good. Value seperti itu enggak ada di sini. Di sini, naik listrik sedikit, ribut. Begitu (masyarakat) ribut, DPR ribut, Presiden bingung, pengamat komentar.
Kedua, we’ve seen the impacts. Seperti saya bilang tadi, dampaknya sekarang masih sangat lokal di daerah tempat PLTU berada. Kalau Anda tidak pergi ke Cirebon atau Cilacap atau Jepara, apakah Anda akan melihat dampak itu? Kalau tidak melihat dampak itu, bagaimana bisa merasakan? Bagaimana bisa berempati? Contoh gampang saja, Anda lihat di Medan Merdeka (Jakarta), ada indikator polusi udara. Semua merah. Polusinya tinggi. Bahaya. Ada enggak yang ribut? Santai saja, tuh.
Jadi, yang mau saya katakan, memang environmentalqualityawareness kita itu rendah. Rendah sekali. Itu membuat agenda-agenda untuk mendorong perubahan regulasi yang lebih ketat dan lain-lain jadi lambat. Itu kenapa, pemerintahnya juga sangat populis. Oh, kita masih butuh listrik murah. Oh, kalau begitu kita pakai batu bara. Logika politik memang harus begitu. Tapi kalau misalnya voter-nya atau publiknya bilang, eh, iya, kita butuh listrik murah tapi kita juga mau listrik yang bersih. Atau, kami butuh listrik yang lebih bersih dulu, murah urusan lain. Murah, we can think different way. Kalau ada demand yang kayak begitu, baru akan ada perubahan.
Kembali ke soal teknologi PLTU, benarkah yang sekarang memang bersih?
Jadi, ada beberapa macam teknologi pembangkit batu bara, mulai dari pulverized coal, super critical, ultra supercritical, lalu sekarang ada yang namanya advanced supercritical. Sekarang yang mulai dipakai di Indonesia untuk pembangkit-pembangkit listrik baru, yang besar-besar, adalah teknologi ultra supercritital atau supercritical.
Apa yang membuat lebih bagus? Yang pertama, karena pembakarannya di suhu tinggi, maka pembakarannya lebih baik. Karena pembakarannya lebih baik, maka efisiensi thermal-nya itu juga lebih tinggi. Karena efisiensi juga lebih tinggi dan juga pembakaran batu baranya lebih baik, maka konsumsi batu baranya lebih rendah. Jadi untuk menghasilkan 1 kWh listrik, dia konsumsinya lebih rendah. Saya lupa angka persisnya, klaimnya untuk teknologi ultra supercritical, 20%-30% lebih rendah daripada yang konvensional. Jadi, karena batu bara yang dibakar lebih rendah, maka emisi batu bara yang dihasilkan dan juga gas buangnya juga lebih rendah. Kira-kira samalah, 20%-30% lebih rendah. Klaimnya begitu.
Tapi, kebanyakan batu bara kita, kalorinya rendah. Apakah cocok dengan teknologi itu?
Kalau dulu, prinsipnya kalau bangun pembangkit batu bara itu, desainnya disesuaikan dengan feedstock batu baranya. Karena itu, ada desain-desain atau pengaturan-pengaturan tertentu. Boiler disesuaikan dengan feedstock. Ya, bisa saja tidak matched. Itu harus Anda tanyakan. Tapi, saya melihatnya begini, dari sisi bisnis, kalau efisiensi pembangkit saya rendah, saya rugi. Jadi, dari sisi bisnis, mereka akan berusaha untuk menjaga efisiensi pembangkit setinggi mungkin. Itu berarti, mereka harus menjaga feedstock-nya supaya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkitnya. Tekniknya, banyak. Misalnya, bisa dengan blending kalori rendah dengan kalori yang lebih tinggi untuk mendapatkan tingkat kalori yang ideal.
Kalau kita stoknya lebih banyak kalori rendah, ya sebenarnya jangan bangun yang ultra supercritical. Misalnya, bangun CFB (Circulating fluidized bed), teknologi yang lebih cocok untuk batu bara yang kalorinya rendah.
Tapi begini yang menjadi persoalan, mereka mem-branding ini sebagai clean coal. Kata teman-teman yang lebih paham, ya enggak ada yang namanya clean coal. Mungkin cleaner daripada yang sebelumnya. Setahu saya, emisi-emisi itu memang bisa dikendalikan. Misalkan, Anda bisa menggunakan teknologi untuk mengurangi SOx atau NOx. Tapi memasang teknologi itu mahal. Bisa menambah 20%-30% dari investasi awalnya. Itu yang tidak diinginkan oleh investor. Regulasinya juga tidak menuntut itu.
Pemerintah seharusnya memiliki regulasi yang standardized. Jadi semua harus memakai teknologi x untuk mengurangi ini, ini, dan ini. Semua yang minta izin untuk membangun PLTU nanti harus memenuhi ketentuan itu, sehingga ada level playing field. Jadi, saya melihat persoalan kita hari ini dengan segala dampak lingkungan yang memang terjadi, baik direct maupun indirect, di localsite maupun di polusi udara, itu karena the absence of regulation. Ini yang harus dibenahi, khususnya di Jawa dan Sumatra, yang penduduknya tambah padat, yang tingkat polusinya sudah sangat tinggi, yang aktivitas ekonominya tinggi. Pemerintah harus tegas di sana, buat regulasi seketat mungkin. Itu sebenarnya cara lain untuk menginternalisasi biaya ekternalitas, dengan tambahan teknologi. Kalau itu bisa terjadi, maka ada kesempatan yang lebih luas dan keekonomian yang berbeda dan sangat menguntungkan energi terbarukan, yang sekarang belum kompetitif di Indonesia.
Apa yang membuat energi terbarukan di Indonesia belum kompetitif?
Tadi sudah saya sebutkan beberapa. Karena ada persepsi dari policy maker, teknologi ini masih mahal, kemudian coal lebih murah, jadi preferensinya di coal. Kemudian, yang namanya barang baru, enggak mungkin bisa langsung dijual, berlaku yang namanya economic of scale. Kalau saya produksi 50 dengan 500 murah mana, pasti murah yang 500. Nah, karena pasarnya kecil, harganya enggak kompetitif. Makanya, kita butuh instrumen, insentifkah atau pendanaan.
Kita enggak punya insentif seperti itu?
Kalau dibilang gak ada, ada juga, sih, tapi minim dan tidak efektif. Karena energi terbarukan itu different technology, different economics. Dan, different technology requires different treatment. Juga, mengintrodusir teknologi terbarukan itu tidak semudah orang bicara.
Saya kasih contoh begini, katakan saya mau bangun winter bind di Sumba yang potensi anginnya tinggi. Saya hitung-hitung, di atas kertas oke. Tapi begitu saya ke sana, saya ngitung, nih. Ada enggak pelabuhan yang bisa bongkar muat untuk wind power saya. Panjangnya, 60-80 meter dari baja. Ada enggak pelabuhan bongkar muat. Ada juga enggak pelabuhannya untuk sandar kapal yang sekian ratus meter doknya pelabuhannya. Katakan itu ada, ke lokasi saya, jalannya ada enggak? Kan, harus dibawa pakai truk. Ada enggak truk gede yang bisa bawa tower panjangnya 160 meter? Jadi, misalnya saya punya duit, saya mau jadi investor yang baik, saya ingin menyelamatkan lingkungan, saya tahu ada potensi di sana, tapi saya tidak bisa investasi ke sana. Kenapa? Infrastrukturnya enggak ada.
Kalau PLTU, semua orang bikin di pinggir laut. Kalau batu baranya ada di Kalimantan atau Sumatera, enggak masalah. Anda tinggal angkut pakai tongkang ke Jawa, langsung sandar ke pembangkit. Anda bangun terminal pengiriman, Anda bangun terminal bongkar muat. That’s it. Kalau energi terbarukan, Anda harus mengikuti di mana resource-nya berada. Logistic is a must, infrastructure support is a must. Logistik menjadi penting untuk biaya investasi saya. Misalkan, saya mau bangun PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), adanya di gunung-gunung, ke sana lewat hutan. Bagaimana saya mau bawa turbin, bahan bangunan, enggak ada jalan. Pakai orang, katakanlah, berapa orang perlunya, berapa banyak biayanya. Berapa banyak waktu kerjanya. Hal-hal seperti itu sangat berpengaruh pada perkembangan energi terbarukan.
Jadi enggak sekadar kita bicara gampang saja. Kenyataannya di lapangan begitu. Kalau Anda pergi ke pembangkit panas bumi, buat ngebor, mesti bangun jalan bisa 10 km, lo, ke dalam hutan. Buat minta izin bikin jalannya saja bisa tiga tahun baru dikasih. Belum bikin jalannya. Nanti izin ngebornya juga begitu. Jadi saya mau ngembangin energi panas bumi, dari saya mulai minta izin pertama sampai saya mulai ngebor pertama itu bisa lima tahun. Sampai saya bisa berproduksi, mungkin 10 tahun. Coba bayangin, 10 tahun saya harus investasi, upfront. Risiko nanti bisa juga, nanti sudah jadi, diprotes sama masyarakat. Tertunda. Nah hal-hal yang kayak begitu, kan, sebagian banyak orang tidak mau mengerti dan mungkin gak tahu juga. Sebagian besar aktivitis juga enggak tahu. Itu persoalannya. Oh, energi terbarukan, kenapa enggak. Loh, kadang-kadang itu bukan karena enggak mau, tapi tidak bisa, sulit.
Tapi, seharusnya di Jawa bisa mulai dilakukan, dong?
Persoalannya juga, kadang hal-hal teknis. Kalau bangun (kapasitas) kecil-kecil, tidakberpengaruh. Tapi, misalnya, saya mau pasang listrik tenaga surya 1.000 MW di Jawa. Pembangkit surya itu, listrik ada kalau ada mataharinya. Disimpan bisa, tapi Anda butuh baterai. Kalau disimpan di baterai, jadi mahal investasinya. Tapi sekarang kalau engak pakai baterai gimana? Oke, sekarang saya pasang 1.000 MW, kalau ada awan di atas pembangkit listrik itu, menghasilkan listrik engak? Enggak menghasilkan. Berarti, ada kapasitas yang hilang enggak, 1.000 MW. Nah, 1.000 MW itu siapa yang mau pasok?
Jadi akan ada masalah stabilitas pasokan juga, ya?
Itu kan hal teknis yang harus diurus. Itu baru kalau kehilangan 1.000 MW. Kalau dalam waktu serentak ada gerhana matahari, hilang, walaupun hanya satu menit, bagaimana coba? Saya tidak bilang itu impossible dilakukan. Itu possible, karena negera lain juga melakukan. Teknologinya ada, tekniknya ada. Tapi maksud saya hal-hal seperti itu enggak segampang kita ngomong, dan kita menutup mata, terus jadi barangnya ada. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan kalau kita bicara ya namanya revolusi energi.
Jadi, balik lagi ke pertanyaanya, renewable energy di Jawa? Ya banyak concern-nya, dari yang sifatnya non teknis sampai yang teknis. Kenapa lamban di Jawa? Ya, karena ada hal non teknis, yang policymakers enggak percaya, PLN enggak percaya. Tapi ada juga hal-hal teknis yang perlu dipersiapkan, bagaimana grid jaringan listrik bisa menampung itu, bagaimana saya bisa menyiapkan daya cadangan. Daya cadangan itu dari mana? Anda mau coal lagi? Itu sifat teknis, tapi gak mudah dipecahkan. Dan kalau pun bisa diselesaikan secara teknis, ada biaya. Sekarang siapa yang mau menanggung biayanya? Pengusahakah, PLN-kah, pemerintahkah, masyarakatkah? Kalau masyarakat yang tanggung, nanti biaya listrik naik lagi, bagaimana?
Jadi kenapa policy makers memilih coal, karena that’s the simplest thing, enggak perlu mikir. Kamu urusannya sama tanah saja lah, bebasin lahan. Enggak perlu pusing seperti tadi yang saya katakan, kalau itu renewable energy. Jadi renewable development requires a lot of adjusments, di policy framework, regulations, technical standard.
Jadi, apakah jalan masih panjang untuk renewable energy?
Saya enggak setuju juga kalau long way to go, tapi kalau IESR sedang mendorong yang namanya energy system transition, energy system transformation. Jadi kita sekarang sedang mendorong agar di Jawa terjadi energy system transition sebelum 2030. Maksudnya, kita sedang mendorong agar ada kapasitas renewable lebih besar di Jawa dalam waktu tadi, sampai dengan 2030.
Caranya seperti apa?
Nah itu kerjaan kita sekarang. Nanti lain waktu akan saya jelasin bagaimana. Tapi itu yang sedang kami kerjakan.
Dengan pembangunan PLTU yang masif serta cadangan yang akan habis dalam tempo sekitar 20 tahun lagi, apakah investasi di PLTU cukup menguntungkan?
Biasanya, kalau pengusaha bangun pembangkit yang lifetime-nya bisa sampai 40 tahun, dia sudah memikirkan feedstock-nya sampai dengan 40 tahun. Hanya masalah dari mana feedstock itu, biar jadi urusan mereka. Kalau impor enggak masalah. Kita BBM juga impor, enggak ada masalah.
Tapi kalau impor seperti BBM, kita akan sulit mengendalikan harga? Padahal tadi keuntungan membangun PLTU, kan, soal harga feedstock.
Ya itu, kan, persoalan nanti, bukan hari ini. Haha.
Sekarang, saya bicara posisi saya. Kalau saya melihat, bisnis PLTU itu akan menjadi stranded assets di Jawa dalam 10 tahun mendatang. Di Indonesia, bisa jadi. Ini karena ada revolusi teknologi renewable, khususnya solar PV (photovoltaics), dengan penyimpan yang akan mengubah pilihan orang membangkitkan listrik. Itu mungkin sulit dilihat hari ini, tapi saya punya keyakinan bahwa itu akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, saya memang mendorong agar PLN dan pemerintah itu harus mulai membatasi pembangunan PLTU di Jawa. Karena kalau tetap membangun pembangkit listrik batu bara di Jawa, ke depannya itu akan timbul beban finansial, karena nanti orang tidak akan pakai itu.
Penulis: Asih Kirana Wardani
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti