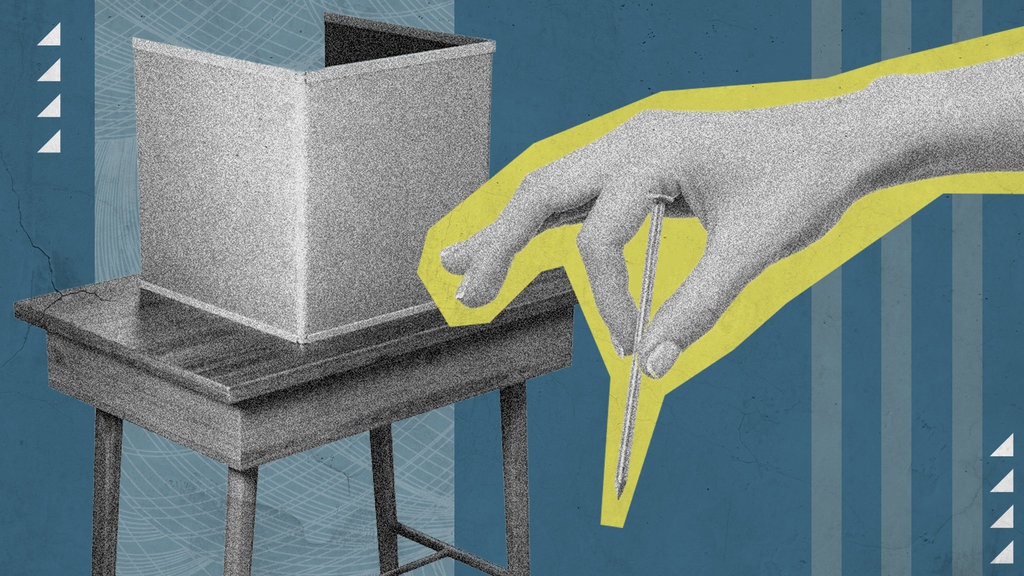tirto.id - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengembalikan pilkada kembali dipilih DPRD sebaiknya tidak direalisasikan serampangan. Wacana yang disusul komentar dukungan dari barisan partai politik pendukung pemerintah itu dinilai berpotensi menggerus daulat rakyat dalam kontestasi politik lokal. Selain itu, tidak ada jaminan biaya politik tinggi proses pilkada yang jadi sebab utama mengapungnya ide ini, dapat serta-merta diselesaikan.
Alih-alih menyelesaikan biaya selangit pelaksanaan pilkada, wacana kepala daerah ditunjuk DPRD berpotensi cuma menggeser persoalan. Politik uang (money politics) yang menyasar pemilih lewat praktik beli suara (vote buying) di pilkada langsung, justru ditransfer ke dalam ruang gelap lobi politik di tingkat legislatif daerah. Inefisiensi biaya penyelenggaraan pilkada justru mencerminkan lemahnya kemampuan jajaran penyelenggara pemilu serta pembentuk undang-undang dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lokal.
Hal itu sebagaimana komentar dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, terkait usulan pilkada dipilih oleh DPRD. Menurut Adi, walaupun pilkada jadi dipilih DPRD, tidak serta-merta mampu mengusir praktik politik uang. Praktik culas tersebut bakal tetap terjadi, namun bergeser hanya kepada sejumlah elite kunci.
“Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal agar dapat rekom partai. Kedua, agar dipilih DPRD, calon pasti mempersiapkan logistik yang juga fantastik,” kata Adi dihubungi reporter Tirto, Senin (16/12/2024).
Jika biaya penyelenggaraan pilkada langsung saat ini mahal, maka Adi menilai bahwa DPR dan pemerintah seharusnya mampu membuat aturan untuk menekan pengeluaran biaya. Sebab, sebagai pembentuk undang-undang, keduanya memiliki kewenangan.
Kalau perlu, kata dia, penyelenggara pemilu cukup berstatus ad hoc untuk pilkada. Hal itu akan menghemat biaya penyelenggaraan pilkada langsung. Pasalnya, kepala daerah yang dipilih DPRD hanya akan menguntungkan parpol yang memenangkan pilpres. Atas jargon soliditas, parpol koalisi pendukung pemerintah bisa dikondisikan agar tak mengajukan calon kepala daerah.
“Buktinya sekarang koalisi KIM Plus terjadi di mana-mana, yang hanya melawan jagoan dari satu partai non-koalisi,” lanjut Adi.
Pilkada yang dipilih oleh DPRD dinilai jelas sekali mengebiri hak politik rakyat. Karena rakyat tidak bisa memilih gubernur, bupati, dan wali kota sesuai selera. Bisa saja yang jadi menjabat kepala daerah hanya figur-figur yang sesuai dengan selera elite. Praktik ini membuat politik oligarki mengental di kancah demokrasi lokal.
Analis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai, latar belakang adanya pilkada langsung, justru diakibatkan pilkada yang dipilih DPRD di era Orde Baru menyimpan segudang masalah. Pilkada yang dipilih DPRD saat itu, justru melanggengkan praktik politik uang yang jumbo di dalam tubuh lembaga legislatif itu sendiri.
“Ada jual beli dukungan, jual beli suara dan kursi dari para anggota DPRD untuk keterpilihan kepala daerah. Ini namanya disebut candidacy buying dan bentuk money politics juga cuma bukan vote buying,” kata Kunto kepada reporter Tirto.
Dalam pilkada langsung saat ini, praktik money politics eksis dalam format membeli suara pemilih atau disebut politik gentong babi. Menurut Kunto, maraknya praktik haram ini dalam pilkada langsung adalah hasil ketidakbecusan partai politik dan juga penyelenggara pemilu dalam proses penyelenggaraan pilkada. Maka meskipun kepala daerah dipilih DPRD, biaya politik pilkada tidak serta-merta turun.
“Ini ketidakmampuan elite politik yang akhirnya membuat money politics subur, lalu kemudian dipindahkanlah ke tempat yang lebih tertutup. Jadi masalahnya mau disembunyikan bukan diselesaikan,” ujar Kunto.
Pilkada dipilih oleh DPRD justru membuat perputaran uang hanya terjadi di elite politik. Vote buying berubah menjadi korupsi politik untuk mendapatkan dukungan dari DPRD. Praktik ini juga berisiko membuat kepala daerah terpilih memiliki segregasi dengan keinginan rakyat.
“Jadi kalau ini dilakukan ya jangan harap ada demokrasi lagi. Ini kan kayak elite berpikiran ya sudah sekalian saja bikin kerajaan, jadi bentuk solusi yang fatalis,” sambung Kunto.
Wacana Presiden Prabowo memang meraup sambutan hangat gerbong parpol pendukung pemerintah. Ide mengembalikan pilkada dipilih DPRD disampaikan Prabowo saat perayaan puncak Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2024). Dalihnya, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD menghemat anggaran triliunan rupiah yang selama ini dikeluarkan untuk pilkada langsung.
Dana pengeluaran dipandang jauh lebih baik digunakan untuk peningkatan fasilitas sekolah dan menyediakan makanan bergizi bagi siswa. Ia juga menyinggung pemenang atau pihak yang kalah dalam pilkada langsung, sama-sama lesu karena telah membakar modal besar.
Parpol di Kabinet Merah Putih seperti PKB, PAN, dan Golkar terlihat menyambut baik wacana tersebut. Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menilai wacana Prabowo pantas untuk dikaji lebih dalam. Politikus Partai Gerindra itu menyatakan ucapan pimpinan parpolnya memang layak dipertimbangkan.
“Pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/12/2024).
Sementara itu, parpol non-koalisi pemerintahan yakni PDIP, menilai wacana Prabowo perlu dikaji masak-masak. Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui pemilihan umum masih relevan hingga kini. Sebab, rakyat terlibat langsung memilih kepala daerah sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, ia memandang ide Prabowo tersebut mencederai kedaulatan rakyat.
“Sistem pemilihan yang kami anggap masih yang terbaik dan untuk menjadikan kepala daerah dipilih oleh DPRD menurut kami itu akan mundur ke belakang dan meninggalkan hakikat-hakikat kedaulatan rakyat,” kata Chico saat dihubungi Tirto, Senin (16/12/2024).
Jika menengok ke belakang, rencana mekanisme pilkada dipilih kembali oleh DPRD pernah mencuat pada 2014 saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, DPR bahkan telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang mengubah mekanisme pilkada langsung yang sudah berlangsung sejak 2005 menjadi dipilih DPRD. Namun, undang-undang itu dibatalkan SBY dengan menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebab desakan besar dari masyarakat sipil.
Perlu Dikaji Mudaratnya
Pengajar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Yance Arizona, menilai wacana Presiden Prabowo yang mengusulkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, sebagai bentuk komitmen yang lemah terhadap demokrasi. Jika sikap ini dibiarkan terus saja menggejala, maka bukan mustahil pemilihan presiden juga mau dikembalikan dipilih oleh MPR, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat.
“Padahal semangat demokratisasi yang diwariskan reformasi adalah gagasan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dengan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung,” kata Yance dihubungi reporter Tirto, Senin.
Dari sisi biaya penyelenggaraan, kata Yance, hadirnya mekanisme pilkada serentak cukup meminimalisasi pengeluaran dibandingkan dengan format pemilihan tidak serentak. Sehingga efisiensi anggaran penyelenggaraan pilkada sebetulnya telah dilakukan.
Namun, jika efisiensi biaya dihitung dari besaran modal yang dikeluarkan parpol dan calon kepala daerah, maka tentu persoalan tersebut merupakan hal yang berbeda. Seharusnya, parpol dan calon kepala daerah membangun kultur politik yang sehat untuk meminimalisasi biaya. Faktanya, walaupun sudah dilarang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, tetap saja praktik politik uang dan mahar politik untuk membeli kursi pencalonan terus saja terjadi.
“Saya menilai kesalahannya justru bukan pada sistemnya, meskipun dalam beberapa hal perlu dibenahi. Kesalahan paling besar terletak dalam kultur demokrasi kita,” ungkap Yance.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, menyatakan bahwa wacana kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD sebagai preseden yang buruk bagi demokrasi Indonesia. Ia memahami masih banyak catatan evaluasi bagi pilkada langsung, namun solusinya bukan menjadikan pilkada menjadi tidak langsung seperti era Orde Baru.
Kalau alasannya terkait efisiensi, kata Annisa, justru hanya elite-elite partai politik atau orang yang punya afiliasi dan koneksi yang akan diuntungkan menjadi cakada. Bahkan, mungkin biaya politik justru menjadi lebih mahal di kalangan elite karena potensi mahar politik. Selain itu, Pilkada yang ditunjuk oleh DPRD berimplikasi pada akuntabilitas kepala daerah terpilih.
“Tidak ada rasa tanggung jawab kepada masyarakat, mereka berpotensi terkungkung oleh partai politik, anggota DPRD yang memilih, dan para pemodal [oligark] yang memberikan dukungan finansial,” ucap Annisa kepada reporter Tirto.
Sementara Peneliti Bidang Politik dari The Indonesian Institute (TII), Felia Primaresti, memandang mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD mungkin dapat mengurangi biaya politik secara langsung dalam konteks biaya kampanye. Namun, format ini tidak serta-merta menjamin bahwa biaya politik secara keseluruhan akan lebih murah.
Selain itu, dengan adanya mekanisme pilkada langsung, masyarakat memiliki kesempatan memilih pemimpin daerah sesuai selera mereka, sehingga memberikan nilai demokratisasi lebih tinggi. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan penunjukan oleh lembaga politik. Felia menegaskan, kepala daerah pilihan DPRD, tidak otomatis merupakan pilihan yang diinginkan rakyat.
“Meskipun mekanisme ini dapat mengurangi biaya politik, dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat perlu dipertimbangkan dengan hati-hati,” ucap Felia kepada reporter Tirto, Senin (16/12/2024).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id