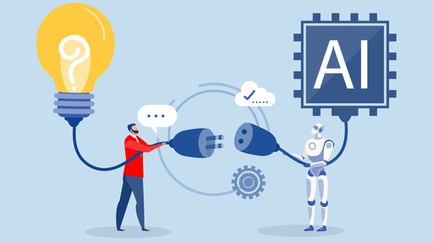tirto.id - Belum genap sebulan selepas Jeff Bezos dan Richard Branson menjelajah luar angkasa dalam beberapa menit, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyebut bumi telah sekarat akibat perubahan iklim. Hal ini ia katakan untuk mengomentari laporan terbaru dari panel ilmuwan di badan bernama Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC berjudul Climate Change 2021: The Physical Science Basis (2021).
"Laporan ini," kata Guterres, "adalah kode merah bagi kemanusiaan."
Dalam laporan yang telah dimulai sejak 1988 dan dirilis setiap tujuh atau delapan tahun tersebut, IPCC menyatakan telah terjadi peningkatan karbon dioksida (CO2) sebesar 410 ppm (parts per million) di atmosfer setiap tahun sejak 2011. Ppm menunjukkan rasio dari satu gas dibanding gas lain.
Misalnya, jika tertulis "1.000 ppm karbon dioksida", berarti terkandung 1.000 karbon dioksida di antara 999 ribu molekul lain di atmosfer. Terjadi pula peningkatan gas metan (CH4) dan dinitrogen monoksida (N2O) masing-masing sebesar 1.866 ppb (part per billion) dan 332 ppb per tahun.
Dengan kian mengepulnya gas rumah kaca di atmosfer, suhu permukaan bumi mengalami peningkatan 1,09 derajat Celsius antara 2011 hingga 2021, dibandingkan dengan peningkatan suhu yang terjadi pada 1850 hingga 1900.
Suhu permukaan laut pun meningkat 0,88 derajat Celsius dalam rentang yang sama, membuat semakin mengikisnya es di Kutub Utara dan Selatan hingga tinggi permukaan lautan (sea level) meningkat rata-rata 3,7 milimeter per tahun. Peningkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan 1901 hingga 1971. Ketika itu permukaan laut hanya meningkat 1,3 milimeter per tahun.
Gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim tersebut terjadi karena, mengutip laporan, "pengaruh manusia."
Kajian mengenai perubahan iklim kerap berbeda dalam hal "siapa pelaku" sesunguhnya. Peneliti Massachusetts Institute of Technology (MIT) bernama Dennis L. Meadows dalam buku The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind (1972) mewakili satu tendensi, yaitu bahwa semua terjadi karena pesatnya (eksponensial super) pertumbuhan penduduk.
Buku tersebut menjelaskan bahwa bumi hanya diisi 0,5 miliar penduduk pada 1650 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,3 persen per tahun. Seiring penemuan obat-obatan untuk menangani berbagai penyakit, semakin berkualitas gizi yang diserap, serta berkurangnya peperangan, kualitas hidup manusia meningkat pula. Demikian pula angka harapan hidup, juga populasi penduduk. Maka, pada 1970 atau 350 tahun kemudian, bumi telah diisi 3,6 miliar penduduk dengan tingkat pertumbuhan 2,1 persen per tahun.
Bersamaan dengan itu tercipta "vicious circle" alias "feedback loop", suatu fenomena yang membuat kenaikan gaji, misalnya, menggiring kenaikan permintaan terhadap barang/jasa, lalu berakibat pada kenaikan harga barang/jasa, kemudian menggiring kenaikan gaji (dan seterusnya dan selamanya). Kenaikan gaji yang menggiring kenaikan permintaan serta harga barang tidak akan memberikan dampak buruk seandainya dapat ditekan di bawah 2 persen. Namun, karena pertumbuhan penduduk naik secara eksponensial super, "vicious circle" yang tercipta pun super.
Pokok/subjek yang digiring pertumbuhan super oleh pertumbuhan penduduk ini adalah industri serta lingkungan, yang sialnya memiliki batas.
Gara-gara pertumbuhan penduduk ini, industri pun harus tumbuh dengan tingkat eksponensial serupa, dari 7 persen pada 1963 menjadi lebih dari 10 persen per tahun setelahnya. Melalui peningkatan industri, meningkat pula material-material bumi yang dimanfaatkan untuk memproduksi berbagai kebutuhan. Hingga, tentu, meningkatkan produksi gas rumah kaca yang berakibat buruk pada lingkungan.
Sementara Jason Hickel dalam studi berjudul "Quantifying National Responsibility for Climate Breakdown: An Equity-based Attribution Approach for carbon Dioxide Emission in Excess of the Planetary Boundry" (The Lancet Planet Health Vol. 4 2020) menyebut bukan manusia secara umum pelaku perubahan iklim, tapi negara-negara berpendapatan tinggi produsen gas rumah kaca. Amerika Serikat menjadi yang paling wahid dengan melepaskan 420 gigaton karbon dioksida dalam rentang 1970 hingga 2015, lalu disusul oleh Uni Eropa sebanyak 377 gigaton.
Hickel menyatakan secara umum Global North atau negara-negara yang terletak di sebelah utara bumi dan umumnya memiliki catatan sejarah sebagai kolonialis menyumbang karbon dioksida jauh lebih banyak dibandingkan Global South. Global North menghasilkan 1,032 teraton atau setara dengan 68 persen total karbon dioksida yang menguap ke angkasa, jauh lebih tinggi dibandingkan Global South yang hanya menyumbang 484 gigaton. Atas dasar itu Hickel mengatakan Global North harus jauh lebih bertanggung jawab atas masalah iklim ini.
Dua negara Global South, Cina dan India, memang menghasilkan karbon dioksida yang besar. Namun Hickel enggan memasukkan mereka ke dalam kantong yang sama karena memiliki banyak sekali penduduk, timpang dengan AS dan Eropa.
Kembali merujuk Guterres, andai persoalan ini tak segera teratasi, maka peningkatan suhu bumi mencapai 1,5 derajat Celsius dalam 20 tahun mendatang. Titik yang dapat menghasilkan petaka bagi umat manusia.
Meskipun mendorong penyelesaian masalah, Steven E. Koonin dalam buku Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn't, and Why It Matters (2021) menyebut PBB dan kawan-kawan di IPCC terlalu naif dengan menyatakan perubahan iklim saat ini sebagai "kode merah". Alasannya, kata mantan penasihat sains pada pemerintahan Barack Obama ini, "tidak ada data yang cukup kuat untuk mengaitkan aktivitas manusia dengan perubahan iklim."
(Catatan: Meskipun buku Koonin terbit lebih dulu dibandingkan laporan IPCC, bersumber pada laporan IPCC terdahulu, Koonin "memprediksi" laporan seperti apa yang keluar pada 2021 ini).
Bukan, Koonin bukan menolak klaim aktivitas manusia melalui industri memengaruhi produksi karbon dioksida. Dengan perbedaan jumlah penduduk antara 1900-an dan 2000-an, menurutnya bukanlah sesuatu yang aneh apabila suhu bumi meningkat gara-gara produksi karbon dioksida yang meningkat. Hanya saja menurutnya dalam kerangka "perubahan iklim" atau, yang semestinya disebut "iklim yang berubah gara-gara manusia", suhu permukaan bumi dan lautan merupakan sesuatu yang sukar diukur. Atau dapat diukur tetapi dengan catatan keras: "perkiraan" semata.
Suatu tempat, misalnya, tak bisa sekadar ditetapkan "memiliki suhu 14,85 Celsius", tetapi wajib menyertakan "sigma" atau "kelenturan". Maka, andai suatu tempat suhu-nya diukur, wajib tertulis 14,85 dan 0,07 Celsius, di mana 0,07 dapat menambahkan atau mengurangi pokok suhu. Artinya, bila hari ini suhu di suatu tempat hanya tertulis 14,85 dan sebulan kemudian tertulis 14,92, tempat tersebut tak bisa disebut mengalami peningkatan suhu. Bagi Koonin, laporan IPCC terlalu berbelit, tak memperlihatkan patokan suhu yang berubah, hanya "peningkatan suhu" semata.
(Catatan: saya sependapat dengan komentar Koonin ini. Silakan cek keruwetan laporan berbentuk PDF berukuran lebih dari 250 megabyte setebal 3.949 halaman dari IPCC ini.)

Kritik dari Koonin mendapat perlawanan dari Michael E. Mann melalui buku berjudul The New Climate War (2021). Dalam buku yang di-endorse Greta Thunberg tersebut, Mann menegaskan kembali bahwa masalah utama perubahan iklim adalah industri yang kian gila mengeksploitasi bumi.
Masalahnya, industri memiliki dana melimpah untuk tetap menjaga produktivitasnya. Dengan kekuatan tersebut, seturut dengan kelakuan perusahaan-perusahaan senjata hingga rokok yang enggan disalahkan atas korban jiwa dan penyakit gara-gara pistol serta tembakau, upaya mengadang perubahan iklim coba dilawan dengan taktik "kill the messenger" alias bunuh kredibilitas individu/lembaga penyebar. Ini dilakukan perusahaan-perusahaan yang sangat mungkin terdampak apabila pengetatan produksi karbon dioksida diterapkan.
Koonin sendiri, sebelum mengabdi pada Obama, merupakan ketua ilmuwan BP alias The British Petroleum Company, salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar saat ini.
Editor: Rio Apinino
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id