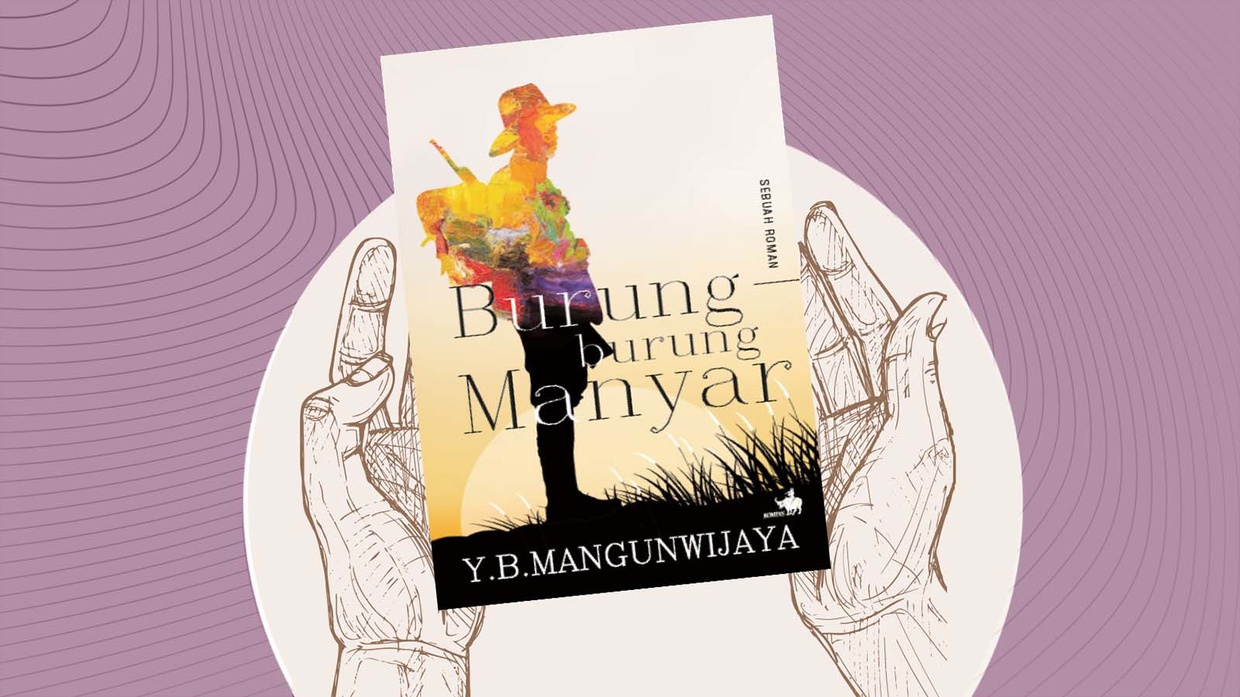tirto.id - Senja mulai menggelayuti Desa Grojogan ketika seorang kurir Staf Umum TNI datang membawa berita bahwa pemerintah Republik Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Itu adalah kabar gembira yang ditunggu-tunggu para gerilyawan Republik yang bersembunyi di desa kecil di lereng Gunung Merapi itu.
Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerbu dan menduduki Yogyakarta. Pucuk pimpinan Republik ditangkap dan di asingkan. Sejak itu, TNI dan laskar-laskar Republikan bergerilya dan membangun kantong-kantong perlawanan di luar Yogyakarta.
Di antara para gerilyawan yang semangatnya sedang membuncah itu, Atik justru galau. Di depan pusara ayahnya—seorang gerilyawan yang tewas tertembak dan dimakamkan di Grojogan, Atik teringat pada teman masa kecilnya Teto.
Teto adalah nama kecil dari Kapten Setadewa yang mengabdikan dirinya pada Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL). Teto dan kesatuannya turut andil dalam operasi pendudukan Yogyakarta yang oleh sejarawan kita disebut Agresi Militer II.
Atik tak habis-habisnya heran, mengapa Teto memilih memihak Belanda. Atik sebenarnya tahu belaka, ada motif dendam yang menggerakkan Teto. Tapi, Teto mungkin lupa bahwa segala yang diperjuangkannya selama ini hanyalah abstrak.
Sementara itu, di suatu tempat, Teto insaf akan kenyataan Belanda kini tersudut. Teto pun telah menghitung dirinya sebagai pihak yang kalah. Tapi, Teto menyadari bahwa sedari awal kekalahannya itu hanyalah satu episode dari serial tragedi hidupnya yang sambung-menyambung.
Teto teringat kata-kata Mayor Verbruggen, komandannya di KNIL, bahwa soal menang dan kalah tidak ada bedanya dari main lotre. Jika kali ini kalah, belilah lotre sekali lagi. Begitulah kehidupan berjalan.
Tapi, setidaknya Teto masih punya pilihan: tetap menjadi pendukung Belanda atau berbalik membela Indonesia. Pada akhirnya, Teto memilih yang kedua, meski dia sendiri ragu apakah dengan begitu Atik akan kembali memandangnya sebagaimana teman kecilnya dulu.
Nasionalisme dan Pencarian Jati Diri
Liku kisah Atik dan Teto itu adalah bagian dari roman sejarah Burung-Burung Manyar (BBM) karya Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau kerap disapa Romo Mangun. Cetakan pertamanya diterbitkan oleh Pustaka Djambatan pada Agustus 1981. Novel ini mengantarkan Romo Mangun meraih kusala SEA Write Award dari Kerajaan Thailand pada 1983.
Selain tinggi mutu sastranya, novel ini juga tergolong laris pada masanya. Pada Desember 1981, ia sudah dicetak untuk kedua kalinya. Hingga 2010, novel ini sudah dicetak ulang sebanyak 16 kali. Kini, BBM bisa digolongkan sebagai novel klasik dalam sejarah sastra Indonesia.
Menurut kritikus Jacob Sumardjo, salah satu keunggulan BBM adalah keberaniannya menengok sejarah dari perspektif seorang Teto yang semula anti-Republik. Ia mengajak pembacanya merenungi lagi nasionalisme dan, dalam taraf lebih pribadi, tentang pencarian jati diri.
Pusat cerita roman ini mengambil latar pada era Revolusi Kemerdekaan dan berpusat pada dua tokoh protagonis yang amat kontras kehidupannya.
Setadewa alias Teto adalah putra semata wayang KaptenBrajabasuki dan Marice—seorang Indo-Belanda—yang tumbuh di lingkungan tangsi KNIL Divisi II Magelang. Brajabasuki masih berkerabat dengan keluarga elite dinasti Mangkunegara. Dia dikisahkan berwatak liberal dan kebarat-baratan.
Sementara itu, Larasati alias Atik adalah putri Antana dan Raden Ayu Marsiwi yang juga masih kerabat Mangkunegara. Atik kecil menjalani hidupnya di Bogor, tempat ayahnya berdinas sebagai pegawai Dinas Kehutanan.
Perjalanan hidup Teto dan Atik dipertautkan oleh Puri Mangkunegaran. Keduanya dikisahkan menjadi teman kecil dan seiring waktu tumbuhlah benih cinta di hati Teto.
Dunia serba indah Teto dan Atik ternyata cuma sebentar. Serangan tentara Jepang pada 1942 menjungkirbalikkan dunia mereka. Usai KNIL dikalahkan, keluarga Teto pun berantakan. Kapten Brajabasuki ditangkap Jepang dan Marice terpaksa menjadi gundik perwira Jepang untuk menyelamatkan hidup suaminya.
Kenyataan itu memporak-porandakan hati Teto yang kini ditampung oleh keluarga Antana. Menjelang kemerdekaan Indonesia, dengan kemarahan meledak-ledak, Teto melarikan diri dari keluarga Antana. Muncullah tekadnya memerangi apa pun yang berbau Jepang.
Teto pun memutuskan ikut KNIL, sesuai wasiat dalam surat terakhir Marice sekaligus untuk membalaskan dendam ayahnya. Teto kemudian menjadi bawahan Mayor Verbruggen, teman sekolah ayahnya di Akademi Militer Breda, Belanda, sekaligus mantan kekasih ibunya.
Sementara itu, keluarga Antana memilih jalan mengikuti Republik Indonesia. Atik sendiri kemudian mengabdi sebagai salah satu juru tik Sutan Sjahrir. Sejak itulah, jurang lebar memisahkan hati Teto dan Atik. Teto patah hati, sementara Atik menutup hatinya.
Teto dan Bumiputra di Kubu Belanda
Menjadikan Teto yang pro-Belanda sebagai protagonis bisa dibilang pilihan yang ganjil. Dalam era Orde Baru, adalah lebih lazim menempatkan tokoh-tokoh veteran TNI atau laskar sebagai pusat cerita. Pun demikian di buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah.
Pilihan Romo Mangun itu tentulah bukan sekadar gaya-gayaan atau memenuhi ego “yang penting melawan arus”. Sekali pun ganjil, kisah Teto tetap punya landasan sejarah yang objektif. Melalui perjalanan hidup Teto, Romo Mangun seakan mengajak pembacanya memahami orang-orang Indonesia yang memilih kubu seberang.
Di era kolonial, banyak orang Indonesia terpelajar yang lebih memilih jadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Sebagian bumiputra juga ikut menjadi bagian militer kolonial dalam KNIL. Alasannya praktis saja: kemapanan hidup. Dengan jadi pegawai kolonial, mereka punya jaminan penghasilan dan keamanan finansial.
Era transisi selalu diikuti dengan ketidakstabilan kondisi sosial-politik. Demikianlah yang terjadi kala Indonesia diduduki Jepang hingga tahun-tahun pertama kemerdekaan. Dalam kondisi macam itu, bukan hal aneh jika ada orang yang berganti haluan.
Ada kisah tentang seorang bernama Yassin yang semula adalah intel Kepolisian Hindia Belanda. Di masa pendudukan Jepang, Yassin beralih jadi Polisi Jepang. Dia sekali lagi berpindah haluan di zaman Revolusi dengan menjadi Polisi NICA.
Dalam konteks inilah, kita dapat memahami keluarga Brajabasuki dan juga Antana. Ketetapan atau perubahan pilihan mereka di kemudian hari pun tidak terlepas dari gerak sejarah Indonesia. Motifnya tentu saja beragam. Dalam diri Teto, kita bisa lihat motif balas dendam yang menggerakkannya. Ada pula motif pragmatis mengamankan sumber pendapatan, seperti halnya Mayor Verbruggen yang siap mendaftarkan diri di Legiun Asing Prancis seandainya didemisionerkan dari KNIL.
Bukan hanya rakyat biasa saja yang seperti itu, tokoh-tokoh elite pun setali tiga uang. Contoh yang paling terkenal adalah Abdulkadir Widjojoatmodjo. Di era Hindia Belanda, Abdulkadir adalah pegawai pemerintah kolonial. Dia ikut mengungsi ke Australia ketika Belanda dikalahkan Jepang pada tahun 1942.
Antara 1944 hingga 1946, kala Belanda mencoba memulihkan kekuasaannya, Abdulkadir ditunjuk menjadi wakil pemerintah NICA di Papua. Abdulkadir juga adalah ketua delegasi Belanda dalam Perundingan Renville.

Sangkan Paran Revolusi
Dalam esai panjang “Pengakuan Seorang Amatir” yang dimuat Pamusuk Eneste dalam bunga rampai Proses Kreatif 3: Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang (2009), Romo Mangun menyebut masalah penokohan dalam BBM tidak ubahnya mengaplikasikan kosmologi wayang ke dalam novel modern. Tentu dengan interpretasi bebas yang tidak terikat pakem.
Misalnya, Teto yang terinspirasi dari sosok Kakrasana (kemudian bergelar Raja Baladewa) yang bersifat seta—putih darah-daging-luar-dalamnya. Dia adalah kakak dari Narayana (kemudian menjadi Raja Kresna) yang bersifat hitam darah-daging-luar-dalamnya. Meski begitu, kontras antara Kakrasana dan Narayana, juga sifat putih dan hitam, itu tidak lantas diejawantahkan sebagai kontras baik dan jahat belaka.
“Nenek moyang kita sangat sadar betapa makna hitam dan putih jangan dicari pada kontras warna fisiknya, baik dan buruk, juga tidak mempersoalkan kedwitunggalan kosmik antara kutub bumi dan angkasa, jantan-betina, kanan-kiri, dan sebagainya, tetapi menunjuk lebih ke dalam, ke pertanyaan hidup yang lebih mendasar, yakni sangkan paran, dari mana mau ke mana,” papar RomoMangun dalam esainya (hlm. 127).
Karena itulah, Romo Mangun mempertanyakan cara orang membaca sejarah yang begitu dikotomis. Gugatan itulah yang disiratkannya melalui tokoh-tokoh utama BBM, Setadewa dan Larasati.
Apakah Teto yang bergabung dengan KNIL lantas jadi sosok jahat? Apakah dia kemudian harus jadi musuh yang disingkirkan Atik si tokoh baik? Bukan premis cerita macam itu yang ingin disampaikan Romo Mangun karena semesta penceritaan mengenai pencarian jati diri bakal tak tercapai jika keduanya dipertentangkan.
“Teto dan Larasati, si dia yang gagal dan dia yang berhasil, dia yang ikut musuh dan dia yang memihak diri kita, Kurawa dan Pandawa, Kama dan Ratih, benarkah mereka saling berlawanan?” gugat Romo Mangun (hlm. 128).
Pada akhirnya, Romo Mangun juga mengajak pembacanya untuk menafsir ulang nasionalisme. Di awal bagian dua, Teto merasa tanah airnya adalah bentuk pengabdian kepada Ratu Belanda yang berdaulat atas Hindia.
“Maaf, Anda keliru alamat menamakan aku budak Belanda. Bagiku NICA hanya sarana seperti Republik bagi mereka sarana juga. Omong-kosong tentang kemerdekaan itu slogan belaka yang menipu. Apa dikira orang desa akan lebih merdeka di bawah Merah Putih Republik daripada di bawah mahkota Belanda?” cecar Teto menjelaskan alasannya masuk KNIL (1981, hlm. 58).
Namun, seiring dengan perkembangan cerita dan karakter, Teto akhirnya memilih menjadi Indonesia. Terlepas dari apakah dia melakukannya untuk mendekat kembali pada Atik atau bukan, itu adalah tengara dari dinamika nasionalisme yang cair.
Demikian pun Larasati dalam permenungannya di depan pusara sang ayah. Sambil membayangkan Teto, Atik bertanya retoris, “Ah, mengapa ada manusia kalah? Bolehkah tanpa berkhayal hampa kita mendambakan dunia sesudah perang kemerdekaan ini, yang menghapus dua kata ‘kalah’ dan ‘menang’ dari kamus hati dan sikap kita?” (1981, hlm. 168).
Revolusi 1945 pun, menurut Romo Mangun, tidak lepas dari pertanyaan sangkan paran ini. Dari mana, untuk siapa, dan hendak ke mana revolusi itu. Burung-Burung Manyar dihadirkan Romo Mangun untuk mencoba membantu kita menjawab pertanyaan sangkan paran itu. Tak hanya dalam soal sejarah lahirnya Indonesia, tapi juga jati diri dan citra menjadi suatu bangsa merdeka.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id