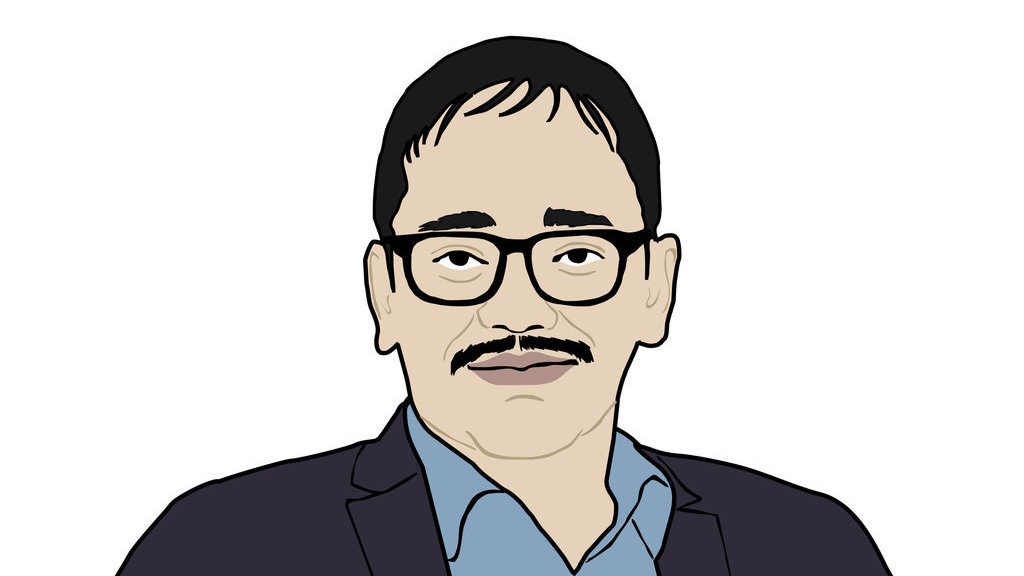tirto.id - Pada akhir Mei 1901, sebagaimana dilaporkan De Locomotief (24/5/1901), sejumlah kuli kontrak di kampung Kebalen dan Krambangan, Surabaya menunjukkan gejala sakit perut dan beberapa di antara mereka meninggal dunia. Seminggu kemudian peristiwa yang sama terjadi di tempat yang sama. Media pun mulai mencium aroma kedatangan wabah kolera di kota itu.
Pemerintah kolonial merahasiakan informasi tersebut. Ini dilakukan untuk mencegah kepanikan juga karena penyebaran kolera senantiasa menjadi tamparan di wajah pejabat dan menjadi bulan-bulanan kritik warga kota. Tapi kerahasiaan macam itu tidak bisa bertahan lama.
Serangan kolera secara sporadis muncul dalam pemberitaan tentang Surabaya di surat kabar yang berlangsung sejak awal Juni sampai akhir Juli 1901. Sekitar 2.600 orang terjangkiti wabah kolera. Wabah ini telah memasuki pusat kota pada Agustus tahun itu. Titik awal perkembangannya bermula di antara narapidana yang menghuni penjara kota kemudian menyebar di perkampungan sekitarnya. Kepanikan pun menjalar ke seluruh penjuru kota.
Lima bulan berselang pemerintah baru secara resmi mengumumkan pembatasan ruang gerak pendatang yang memasuki kota Surabaya. Orang-orang yang keluar-masuk pelabuhan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan mereka tidak membawa atau menyebarkan penyakit itu di tempat lain. Pemerintah juga menyampaikan standar kebersihan tentang apa yang harus mereka makan dan minum, termasuk bagaimana cara memasak yang benar. Di lingkungan kantor pemerintahan dan kompleks militer, pemerintah mengeluarkan aturan agar setiap personel memasak terlebih dahulu air yang akan diminum dan membersihkah buah-buah mentah sebelum dimakan. Sayur-mayur serta buah-buahan dari luar kota sementara waktu dilarang masuk dan tidak boleh dijual di pasar-pasar.
Reaksi Warga Kota
Sejak wabah kolera masuk ke Hindia Belanda pada awal abad ke-19, yang diawali dengan jalur masuk melalui Sumatra, Jawa, lalu pulau-pulau lain, kota Surabaya telah mengalami lima kali wabah kolera.
G.H. von Faber dalam Oud Soerabaja (1931) menyatakan gelombang terbesar kolera terjadi pada 1872 yang merenggut korban sekitar 6.000 jiwa. Sejarah penyebaran wabah di kota itu telah menunjukkan kolera tidak mengenal batas rasial, kelas, dan usia. Warga Eropa kaya, pejabat pemerintah, anak-anak, dan terutama kalangan bumiputra yang hidup di bawah standar kelayakan saat itu menjadi korban.
Dalam Nieuw Soerabaja (1936), G.H. von Faber menyatakan pula bahwa sampai awal abad ke-20 wabah kolera tidak kunjung menghilang. Selama dua dekade awal abad ke-20 Surabaya mengalami empat kali lagi serangan wabah itu yang terjadi pada 1900-1901, 1902, 1908, serta gelombang terakhir pada 1918.
Tidak percaya pemerintah adalah reaksi umum yang muncul di antara warga Surabaya ketika bencana wabah terjadi. Sikap ini sesungguhnya bukan hal baru sepanjang pengalaman sejarah kota tersebut. Warga kota lebih percaya desas-desus—yang mengingatkan kita pada berita hoaks masa kini—tentang perkembangan wabah dan bahaya yang mengancam dibanding seruan pemerintah. Kebiasaan menimbun makanan untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk juga dilakukan di kalangan warga kota yang berada. Langkah lainnya adalah mengungsikan anak-anak mereka ke tempat yang lebih aman di pinggiran kota—upaya yang justru mempersulit penanganan wabah.
Ada dua alasan yang cukup rasional di balik desas-desus yang menimbulkan kepanikan warga kota. Pertama, satu aspek yang menakutkan dari kolera adalah hingga awal abad ke-20 ia tetap menjadi penyakit yang sulit disembuhkan dan sekaligus menegaskan kelemahan ilmu kesehatan saat itu.
Sampai akhir abad ke-19 para dokter masih terus berdebat tentang metode penyembuhan paling efektif bagi pasien yang terkena kolera. Setiap dokter dan ahli medis menyarankan resep sendiri mulai anjuran meminum campuran gula putih dengan sitrun yang dilarutkan dalam air (De Oostpost, 16/6/1864) hingga penggunaan campuran arak putih dengan parutan laos dan bawang putih atau perasan jeruk nipis yang ditambah garam dan kapur sirih dengan 3 sampai 4 tetes minyak kayu putih (Soerabajasch Handelsblad, 23/7/1902). Bahkan metode yang biasa digunakan penduduk pribumi, yaitu akar rumput teki yang ditumbuk dan diperas sampai keluar airnya lalu diberikan kepada pasien pada malam hari sebelum tidur, menjadi salah satu pilihan yang ditawarkan (De Locomotief, 21/12/1868).
Metode yang “lebih ilmiah” mulai dipopulerkan Groneman, yang pernah menjadi dokter pemerintah di Surabaya, melalui penggunaan terapi kreolin. Menurut Groneman dalam Cholera Behandeling met Creoline (1909), “pasien yang terkena kolera sebaiknya diberikan 5 gram kreolin Parson yang dilarutkan dalam segelas air. Untuk anak-anak di bawah usia lima tahun cukup diberikan 2 gram, dan 4 gram untuk usia 5 sampai 12 atau 15 tahun.” Groneman mengklaim metode terapinya telah dibuktikan melalui penelitian laboratorium yang menunjukkan 5,4 gram kreolin bisa mematikan sejumlah baksil Vibrio cholerae di dalam usus pasien.
Tapi tidak semua dokter di Hindia Belanda sependapat dengan Groneman. Seorang dokter rumah sakit militer di Surabaya, G. Fischer, menyampaikan pengalamannya menerapkan terapi kreolin yang tidak menunjukkan hasil. Seperti dilaporkan De Locomotief (3/6/1901), Fischer menekankan bukan berarti metode kreolin sama sekali tidak berguna, "[tapi] dokter di sini lebih melihat efek yang lebih baik dengan penggunaan potassium mangaan yang sekaligus lebih mudah didapat." Seturut kemajuan ilmu kesehatan, kita sekarang bisa menilai semua percobaan itu bukan langkah terbaik untuk menyembuhkan kolera.
Kedua, dan ini juga menjadi faktor yang memengaruhi sikap masyarakat Surabaya saat itu terhadap penanganan wabah oleh pemerintah, adalah buruknya fasilitas kesehatan yang tersedia bagi warga kota. Sampai awal abad ke-20 fasilitas kesehatan yang cukup lengkap hanya terdapat di rumah sakit militer di Simpang. Rumah sakit ini dibangun pada 1808 atas perintah H.W. Daendels untuk melindungi personel militernya dan hingga 1867 memiliki empat ratus tempat tidur pasien. Namun, dibanding sebagai tempat penyembuhan pasien, fungsi utamanya lebih kepada upaya mengisolasi pasien agar tidak menyebarkan penyakit. Untuk pasien dengan kondisi yang tak mungkin lagi ditangani, biasanya mereka akan dikirim ke tempat peristirahatan di Malang atau Tosari sampai kondisi alam "menyembuhkan" mereka.
Selain itu tenaga medis yang tersedia jauh dari memadai dibanding perkembangan penduduk kota Surabaya. Menurut sejarawan Howard Dick dalam Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000 (2003), tenaga medis untuk menjalankan fungsi kesehatan masyarakat pada 1864 terdiri dari dua orang dokter, seorang apoteker, seorang perawat bersalin, dan seorang pengawas rumah sakit. Kondisi rumah sakit umum (stadsverband) di kota itu pun tidak jauh berbeda buruknya. Lokasinya berada di dalam lingkungan penjara kota. Kondisi udara yang pengap, ventilasi dan toilet yang buruk, serta fasilitas air minum yang diambil langsung dari sungai Kalimas memberi gambaran betapa menyedihkan fasilitas yang tersedia di rumah sakit itu (hlm. 166-167).
Kaum Miskin yang Terlunta-Lunta
Di dalam lingkungan kota yang terbagi secara rasial antara golongan Eropa, Tionghoa, dan bumiputra, reaksi yang muncul menyikapi wabah berbanding lurus dengan tingkat ketimpangan ekonomi. Warga yang kaya lebih memiliki peluang untuk bertahan dibanding mayoritas warga bumiputra yang hidup di bawah standar kelayakan dalam ukuran orang-orang Eropa.
H.F. Tillema dalam buku enam jilidnya berjudul Kromoblanda (1916)menyatakan orang-orang bumiputra lebih banyak mati di kota-kota dibanding lingkungan asal desa mereka. Mereka hidup dalam kondisi tanpa sanitasi memadai dan tinggal dalam perumahan padat dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Catatan Tillema menggarisbawahi satu fakta penting: orang-orang miskin pada awal abad ke-20 memang harus mengurus diri sendiri untuk bertahan hidup. Negara hanya hadir ketika memungut berbagai macam pajak yang diambil dari pendapatan mereka yang sangat sedikit.
Warga bumiputra di perkotaan memang tidak lagi dapat melakukan cara lama yang merupakan warisan tradisi prakolonial dalam menghadapi wabah: migrasi massal. John Crawfurd, pembantu Gubernur Jenderal T.S. Raffles ketika Inggris berkuasa di Jawa, menyebut gambaran migrasi massal tersebut dalam analogi “mereka seperti burung yang terbang meninggalkan pohonnya”. Migrasi meninggalkan desa yang terkena wabah terbukti efektif menyelamatkan penduduk.
Sumber-sumber sejarah prakolonial memiliki cukup banyak kisah mengenai desa-desa yang terbengkalai dan kosong ditinggalkan penduduknya akibat peperangan dan wabah. Namun, di bawah kolonialisme Belanda abad ke-19 dan ke-20, praktik lama tersebut sudah tidak lagi dapat dilakukan. Tidak ada lagi lahan-lahan kosong yang dapat menjadi tempat baru untuk warga desa. Semua lahan sudah menjadi milik pemerintah di bawah undang-undang agraria kolonial (Agrarische Wet 1870) yang menjadikan tanah tak tergarap sebagai tanah negara.
Migrasi massal dikabarkan memang kerap terjadi hingga akhir abad ke-19, tapi langkah ini sudah kurang efektif. Kampung-kampung sudah tidak lagi mampu menampung limpahan orang-orang yang melarikan diri menghindari wabah. Jadinya, mereka terpenjara oleh sejumlah keterbatasan yang mengungkung dalam kehidupan kota modern saat itu.
Persoalan lain adalah negara kolonial tetap merupakan entitas asing yang berada di luar kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam kaitan ini kebijakan mengatasi wabah yang dicanangkan pemerintah selalu menghadapi masalah. Saat wabah terjadi pemerintah menyerukan kepada kepala-kepala kampung (desahoofden) untuk membawa warga yang terjangkit kolera ke rumah sakit militer di Simpang. Namun, sampai puncak penyebaran wabah, jumlah pasien dari kalangan bumiputra hanya mencapai 136 orang. Dari jumlah tersebut, 15 orang adalah mereka yang ditemukan sakit di jalanan, 11 orang merupakan kuli yang sedang bekerja, dan sisanya adalah pembantu di kediaman orang-orang Eropa.
Angka-angka itu menunjukkan mayoritas warga bumiputra mengabaikan seruan-seruan pemerintah. Orang-orang yang ada dalam jangkauan pemerintah adalah mereka yang sejak awal memang tidak bisa menghindar dari kebijakan tersebut. Sedangkan mayoritas lainnya lebih memilih merawat sendiri anggota keluarga yang terkena kolera dan merahasiakan keberadaan si sakit. Dalam kaitan ini, peran kaum agamawan, dukun, dan “orang-orang pintar” yang dipercaya mampu memberikan cara bertahan hidup menjadi jauh lebih penting dibanding pemerintah.
Persoalan ini pula yang menjadi ganjalan bagi pemerintah kolonial dalam menjalankan agenda kebijakan kesehatan publik. Kaum agamawan dianggap menjadi kendala dengan kepercayaan terhadap tradisi yang tidak ilmiah ketika menghadapi wabah. Perlu waktu cukup lama bagi pemerintah kolonial untuk menyadari bahwa agama dan pengetahuan medis (baca: pengetahuan rasional Barat) bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Pada dekade-dekade selanjutnya langkah yang efektif adalah bagaimana memanfaatkan kepercayaan tradisional penduduk dan penghormatan terhadap kaum agamawan sebagai sarana mendidik masyarakat tentang pengetahuan kesehatan modern.
Pentingnya Kesehatan Publik
Ada dua persoalan yang perlu mendapat perhatian terkait wabah penyakit dalam sejarah. Pertama, tidak dapat disangkal bahwa bencana, wabah, dan perang adalah serangkaian drama dalam kehidupan masyarakat yang berdampak besar bagi banyak orang. Persoalannya adalah di Indonesia pengetahuan tentang sejarah wabah masih terlalu minim dalam kepustakaan yang ada.
Meski sekarang ini generasi baru sejarawan Indonesia telah mengarahkan perhatian terhadap tema tersebut, tidak dapat disangkal bahwa historiografi Indonesia modern masih bersifat “istana-sentris” yang lebih banyak mengulas persoalan-persoalan tentang negara, orang-orang besar, kaum birokrat, dan penguasa. Penggalian pengetahuan tentang wabah di masa lalu merupakan tantangan bagi generasi sejarawan masa kini.
Kedua, penyelesaian terhadap wabah dan penyakit yang belum diketahui penyembuhannya memang menguras energi dan menciptakan banyak tragedi. Wabah dalam kaitan ini adalah buah peradaban. Ia menyebar dan berkembang semakin luas seiring kemajuan peradaban manusia, yang berbeda ketika manusia masih hidup dalam lingkungan terisolasi satu sama lain. Surabaya memasuki awal abad ke-20 adalah kota komersial yang utama di Hindia Belanda. Kota ini bahkan telah berhasil membangun jaringan perdagangan antarbenua. Namun kedatangan kolera menunjukkan kota ini tetap rentan dalam menghadapi wabah yang mengancam keberlanjutannya.
Gambaran itu pula yang terjadi sekarang. Covid-19 menjadi tamparan yang mengingatkan betapa rentan sebenarnya masyarakat modern dalam menghadapi pandemi. Menanggulangi wabah dalam kaitan ini adalah melihat masa depan kita bersama: bagaimana kita menempatkan kesehatan publik sebagai bagian tak terpisah dalam mengejar kemajuan infrastruktur dan perekonomian.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id