tirto.id - Suatu siang di bulan Juli 2013, Khemal Sundah Prasasti (27) berangkat salat Jumat di gedung Menara Sudirman, Jakarta. Seusai mengambil wudu, Khemal berjalan dari kantornya di Summitmas. Dia membatin, “Jangan sampai bolong salat di bulan puasa.”
Sesampainya di Menara Sudirman, dia langsung mengambil saf yang masih tersedia, lalu duduk tenang untuk mendengarkan khotbah Jumat. “Siapa tahu dapat pencerahan, hati jadi makin tenang kalau bisa menangkap hikmah khotbah,” kata Khemal pada tirto.id, Selasa (1/11/2016).
Namun begitu khatib menyampaikan khotbah, Khemal justru gelisah. “Syiah itu kafir!” suara sang khatib menggelegar.
Mendengar khatib mengkafir-kafirkan syiah dalam khotbah, ia merasa gelisah. “Itu bulan puasa, saya ingin dapat khotbah yang menenangkan, meningkatkan iman, yang terjadi justru mengkafirkan,” tuturnya.
Pada salat Jumat selanjutnya, khotbah di tempat itu tak berubah temanya. Kalau tidak soal syiah kafir, muncul isu SARA, menebar kebencian terhadap pemimpin kafir. Khemal pun tak punya pilihan lain selain mendengar khotbah dengan hati yang makin tak nyaman. Sampai suatu saat Khemal tidak tahan lagi dan memutuskan mencari tempat lain untuk salat Jumat yang jaraknya lebih jauh dari kantornya.
Khotbah Jumat yang didengar Khemal sebenarnya hal yang biasa. Bisa terjadi pada siapa saja dan di masjid mana saja. Sebab, sejatinya, masjid adalah ruang publik yang terbuka bagi muslim siapa pun untuk menggunakannya. Tidak peduli perbedaan warna kulit, bahasa, sosial, pandangan politik, bahkan ideologi, termasuk ideologi yang saling bertentangan.
Ruang bernama masjid pun wajar jika dianggap sebagai tempat strategis bagi berbagai kelompok kepentingan. Masing-masing kelompok mencoba masuk ke masjid dan berupaya menguasai mimbar, khususnya khotbah Jumat. Tujuannya menyebarkan pandangan politik, memengaruhi massa.
Salat Jumat Memang Strategis
Khotbah Jumat menjadi pilihan favorit untuk diperebutkan. Hal itu dikarenakan salat Jumat memang sangat strategis.
Pertama, salat Jumat memiliki daya tarik massa, sebab salat Jumat hanya bisa dilakukan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan sendirian. Ada beragam pendapat para ulama tentang jumlah minimal jamaah salat Jumat, ada yang mengatakan minimal empat puluh orang.
Pendeknya, salat Jumat berpotensi dihadiri oleh lebih banyak orang. Ketika jamaah salat wajib lainnya bisa dilaksanakan sendirian, tidak heran jika salat Jumat menjadi salah satu momen di mana masjid sangat penuh dengan para jamaah.
Kedua, khotbah salat Jumat menjadi bagian tak terpisahkan dari salat. Mendengarkan khotbah Jumat merupakan salah satu rukun yang tidak boleh dilewatkan. Sehingga jamaah mau tak mau harus mendengarkan khotbah. Ini berbeda dengan kuliah tujuh menit atau kultum menjelang atau sesudah salat tarawih atau usai salat Subuh yang bukan menjadi rukun atau syarat sahnya salat.
Ketiga, waktu salat Jumat yang berlangsung tepat tengah hari, pada hari kerja, membuat jamaah tidak punya banyak pilihan memilih masjid. Hal jamak jika jamaah memilih masjid yang lokasinya paling dekat dengan kantor masing-masing. Biar bagaimana pun berlangsung pada hari kerja, dan jam 13.00 banyak di antaranya harus sudah kembali ke meja kerja.
Keempat, aspek terakhir itulah yang membuat salat Jumat menjadi momentum yang memungkinkan bertemunya para jamaah dengan latar belakang yang berbeda-beda bukan hanya secara ras, etnis dan suku tapi juga mazhab, aliran hingga ideologi dan pilihan politik. Salat Jumat menjadi sangat strategis untuk menjangkau orang-orang yang belum terinternalisasi nilai-nilai ideologis atau politik tertentu. Inilah kesempatan untuk mengenalkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ingin disebarkan oleh para pengkhotbah.
Di Indonesia, fenomena menggunakan khotbah masjid untuk penyampaian pandangan politik dan memengaruhi masa ini sebenarnya sudah lama terjadi. Jauh sebelum Gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, dipersoalkan karena insiden surat Al-Maidah 51. Juga sudah terjadi jauh sebelum ramai-ramai urusan Pilkada DKI.
Sekretaris Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Muhammadiyah Amin, mengatakan gejala penggunaan khotbah untuk kepentingan politik dan ideologi tertentu, khususnya kelompok garis keras, mulai marak terjadi pascareformasi 1998.
Menurutnya, di masa pemerintahan Soeharto, kelompok itu tidak memiliki ruang untuk melebarkan sayap. Menyuarakan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau pemerintah jelas sangat berisiko untuk ditumpas. Pasca reformasi, masjid menjadi lebih terbuka untuk membicarakan berbagai hal dengan terang benderang, bahkan verbal.
Kebebasan berpendapat di mimbar-mimbar masjid, sampai batas tertentu, merupakan salah satu buah hasil reformasi 1998. Dari aspek ini, bisa dikatakan, mimbar-mimbar masjid tidak berbeda dengan halaman-halaman surat kabar yang juga bisa lebih leluasa memberitakan apa pun setelah Soeharto lengser.
“Ini dipengaruhi kebebasan berbicara pasca-reformasi. Pada zaman Soeharto itu keras dan tegas,” Kata Amin pada tirto.id, Rabu (2/11/2016).
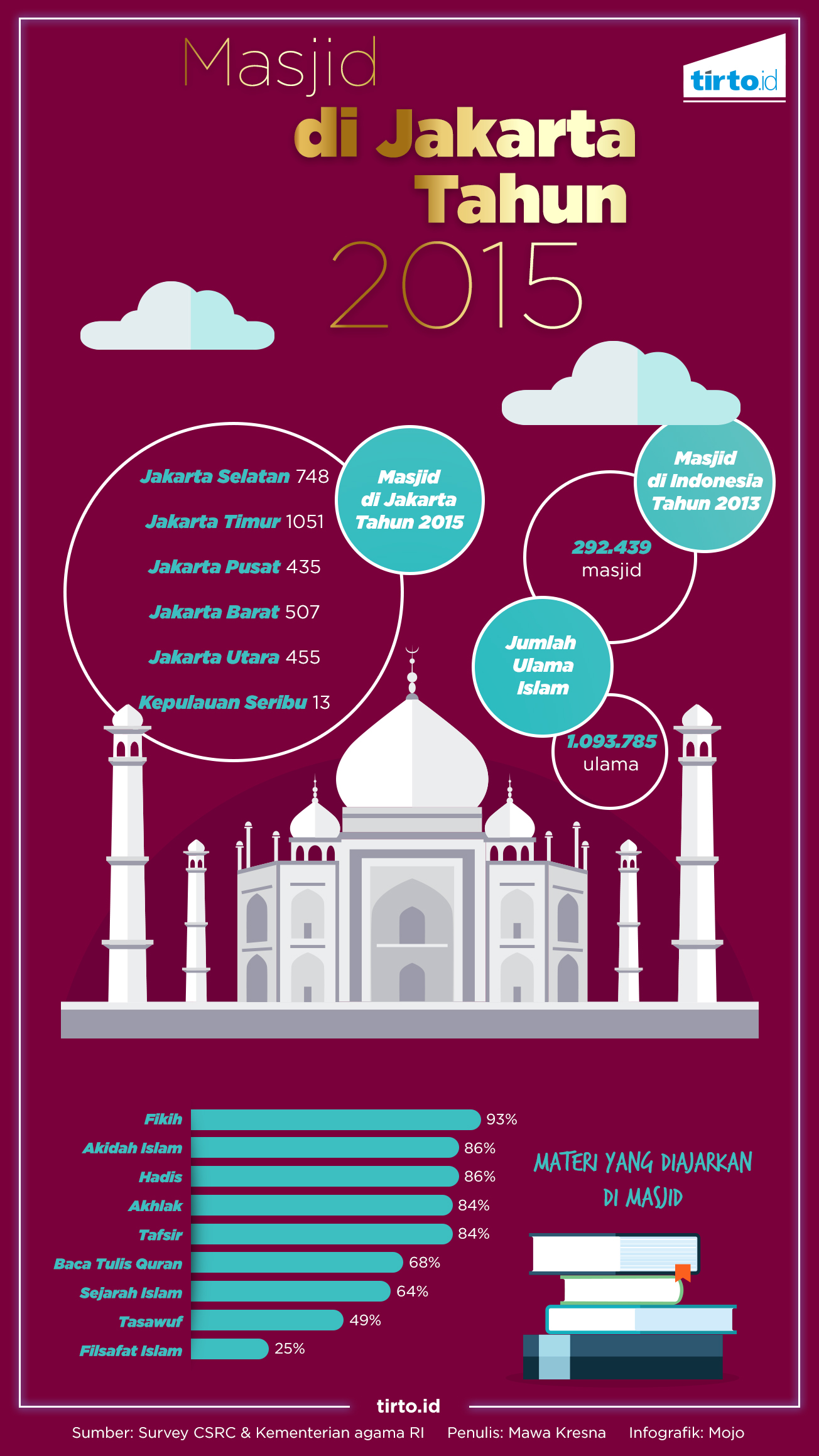
Khotbah Jumat dan Orasi Politik
Salah satu momentum yang meradikalisasi khotbah-khotbah Jumat di Indonesia ketika berlangsung konflik Ambon pada 1999. Seruan jihad berkumandang di banyak masjid, terutama pada khotbah Jumat. Salah seorang eks-kombatan konflik Ambon, dalam sebuah percakapan beberapa tahun lalu di Ambon, mengaku terpanggil untuk melakukan jihad setelah mendengar seruan dari mimbar khotbah Jumat di salah satu masjid di Semarang.
Baru beberapa hari tiba di Ambon, Laskar Jihad langsung menggelar tabligh akbar di Masjid al-Fatah, masjid terbesar di Ambon pada 2 Juni 2000. Menggunakan tajuk “Kumandangkan Jihad untuk Mempertahankan Eksistensi Muslim dari Tipu Daya Muslihat Kaum Kristen”, Laskar Jihad berhasil mengumpulkan ribuan orang pada salat Jumat. Para pengkhotbah dalam tabligh akbar itu, salah satu di antaranya Jafar Umar Thalib, secara heroik mengundang muslim se-Maluku untuk bersatu memerangi kaum Kristen dan menghapus keberadaan mereka dari Maluku.
Penelitian Sumanto al-Qurtuby (Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Christians and Muslims in Mollucas Sumanto al-Qurtuby, 2016) menunjukkan betapa hari Jumat, melalui salat Jumat dan khotbahnya, menjadi momen sangat strategis yang dengan sadar digunakan secara ekstensif untuk menyerukan jihad. Mereka tentu secara berkala menggelar tabligh akbar, tapi khotbah Jumat yang sudah pasti dan rutin waktunya menjadi medium strategis untuk menyerukan jihad.
Ini bukan khas Indonesia. Mohammed Abu-Nimer, dalam buku Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice, mengisahkan betapa penting dan strategisnya salat Jumat di Palestina. Meski sejumlah masjid di Palestina terkait dengan Hamas, peran masjid melebihi organisasi tersebut. Banyak masjid menjadi pusat organisasi dan pengajaran. Meski khatib sangat berhati-hati menjaga bahasanya dalam khotbah Jumat, banyak dari mereka secara tersirat maupun tersurat mendesak para pendengar untuk ikut serta dalam perlawanan. Seringkali, arak-arakan dan unjuk rasa dimulai dari masjid, terutama di hari Jumat setelah salat berjamaah.
Dr. Hilmy Bakar Almascaty M.A., salah seorang bekas petinggi Front Pembela Islam (FPI) yang di masa Orde Baru memilih tinggal di Malaysia bersama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, menyebut khotbah Jumat harus dimaksimalkan untuk menggelar apa yang ia sebut sebagai “jihad lisan”.
Pada 2001 ia menulis buku berjudul Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam (Gema Insani Pers, 2001). Pada salah satu bagian buku itu ia menulis:
“Khotbah Jumat yang dilakukan setiap sepekan sekali ini harus dijadikan salah satu sarana jihad lisan untuk menyadarkan umat, membangkitkan semangat mereka, memobilisasikan kekuatan, menyatukan pendapat, serta menginformasikan strategi baru musuh dan penangkalnya. [...]Para khotib harus dididik agar memiliki wawasan luas dan kesadaran yang tinggi untuk menegakkan Islam dengan tugas mulianya sebagai orang juru pengingat. Khotbah Jumat ini harus senantiasa dijadikan sarana bagi tercapainya tujuan jihad Islam.”
Tegangan Antara Politik Praktis dan Politik Etis
Di Jakarta, menjelang Pilkada 2017, banyak khotbah di masjid menjadi arena pertarungan politik, baik politik etis maupun praktis. Politik etis yang dimaksud adalah politik gagasan yang mengedepankan nilai-nilai etik yang ideal, mengarusutamakan nilai-nilai universal, untuk kepentingan kemanusiaan yang melampaui batas-batas primordial dan identitas. Sedangkan politik praktis berbicara tentang kontestasi politik yang konkret, terkait sirkulasi elit, dan memusatkan perhatian kepada bagaimana caranya merengkuh kekuasaan dan mengalahkan lawan.
Dalam politik praktis, tanpa malu-malu, para khatib menyebut nama calon pemimpin yang harus dipilih atau tidak boleh dipilih. Sedangkan dalam politik etis, para khatib lebih banyak menggaungkan bagaimana mewujudkan politik yang jujur dan adil serta menggaungkan pentingnya pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Kendati demikian, contoh tadi boleh jadi tidak terlalu tepat karena yang etik dan yang praktis seringkali sumir batasannya. Misalkan begini: khatib salat Jumat mengajak jamaah untuk pergi ke kampung yang akan digusur oleh seorang kandidat pemimpin untuk melindungi kepentingan warga miskin agar tidak diperlakukan semena-mena dan tidak manusiawi. Kendati didorong oleh nilai-nilai etik, khotbah macam itu bisa berdampak pada politik praktis, apalagi jika dilakukan menjelang Pilkada. Bedanya, barangkali, pada contoh kedua yang dikedepankan tidak semata politik identitas melainkan memuat juga politik kelas yang mempersoalkan ketimpangan struktural dalam ekonomi-politik.
Memang tidak gampang menarik batasan. Dalam sejarahnya, masjid memang tidak pernah jauh dari kegiatan politik. Sejak masjid pertama didirikan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah ke Madinah, masjid tidak sekadar menjadi tempat ibadah saja. Di masjid, Nabi menyampaikan gagasan politiknya, bagaimana membangun masyarakat, bagaimana membangun pemerintahan, bagaimana membangun peradaban di bawah Islam, dan tentu saja menyerukan jihad pada momen-momen krusial yang menentukan.
Namun, menurut Muhammadiyah Amin, yang dilakukan Muhammad sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Pada masa itu, gagasan politik yang disampaikan di masjid selalu terkait dengan kepentingan publik. Mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial dan politik.
“Kalau dulu zaman nabi, masjid itu sebagai pusat peradaban, ekonomi, sosial, budaya semuanya di masjid, tapi kalau dalam konteks di Indonesia, itu seharusnya tidak dilakukan karena sudah ada ruang dan tempat untuk melakukan pembicaraan soal politik,” beber Amin.
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdathul Ulama, Ahmad Ishomuddin, melihat khotbah politik di masjid sebenarnya tidak masalah. Namun, bukan dalam konteks politik praktis, seperti menjelek-jelekkan calon lain atau menghasut orang untuk tidak memilih calon pemimpin lainnya. Khotbah itu harus yang bersifat universal dan menanamkan nilai perdamaian.
“Itulah barang kali kita jangan terjebak pada penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran yang sebetulnya tidak pada tempatnya untuk menghalangi hak politik orang lain,” kata Ishomuddin pada tirto.id saat ditemui di The Wahid Institut, Selasa (1/11/2016).
Menurutnya, khotbah di masjid seharusnya melihat konteks kebangsaan di Indonesia. Tidak diperbolehkan menyuarakan kebencian di mimbar khotbah atas nama Allah. “Saya kira khotbah itu harus lebih menenangkan masyarakat bukan malah dengan khotbah justru membuat orang membenci makhluk Allah lainnya, itu tidak dibenarkan,” tegas Ishomuddin.
Jika ada khotbah khatib yang menyebarkan kebencian, maka sebenarnya khotbah itu bisa diinterupsi. Tentunya dengan syarat tertentu. Dalam artikel tanya jawab, Hassanudin, warga Jakarta bertanya apakah boleh menginterupsi khotbah khatib salat Jumat di laman nu.or.id. Pada laman yang sama Mahbub Ma’afi Ramdlan, pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU, menjelaskan kemungkinan menginterupsi khatib yang sedang berkhotbah.
Mahbub menjelaskan dalam madzhab Maliki, haram hukumnya berbicara ketika khotbah dan ketika imam duduk di atas mimbar di antara dua khotbah. Semua haram berbicara meskipun berada di teras masjid atau jalan yang terhubung dengan masjid. Meski demikian jika isi khotbah ternyata justru menebar kebencian seperti mencaci orang yang tidak layak dicaci, maka larangan berbicara tersebut menjadi gugur. Mahbub menegaskan interupsi pun harus dilakukan dengan pengetahuan yang benar dan dilakukan dengan cara yang santun.
“Jika pandangan madzhab Maliki ini ditarik ke dalam konteks pertanyaan di atas, maka menginterupsi khatib yang dalam khotbahnya menjelek-jelekkan kelompok lain bisa saja diperbolehkan, sepanjang hal itu adalah masuk dalam kategori laghw,” tulis Mahbub di laman nu.or.id tertanggal 31 Juli 2014.
Risiko Mesjid yang Kosong
Masjid sebagai pusat segala aktivitas sendiri mengalami degradasi fungsi. Perlahan masjid dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Fungsi masjid seolah hanya tunggal : tempat beribadah.
Masjid yang semula begitu dinamis, bisa menjadi tempat belajar, tempat jual beli atau tempat berpolitik menjadi kaku, bahkan terkunci secara harfiah. Pintu masjid tertutup rapat, hanya dibuka pada jam salat atau kegiatan yang sudah diagendakan oleh pengurus masjid. Jika pun ada musafir, atau para pejalan, yang ingin istirahat barang sejenak, biasanya hanya bisa dilakukan di teras.
Tentu saja penyebabnya banyak. Salah satu yang tidak bisa diabaikan adalah faktor keamanan. Apalagi masjid-masjid di wilayah urban juga banyak menyimpan peralatan yang harus dijaga dari kemungkinan pencurian.
Perubahan itu menjadi keprihatinan Bimas Islam Kemenag RI. Mereka merancang program untuk mengembalikan masjid menjadi pusat peradaban seperti pada masa Muhammad. Salah satu yang dilakukan yakni dengan melakukan pembinaan pengurus masjid dan mengaktifkan kegiatan di masjid.
“Jadi nanti tidak ada lagi masjid yang terkunci. Kegiatan harus aktif,” terang Amin.
Problemnya adalah pada saat masjid terpisah dari masyarakat, kelompok-kelompok yang tidak organik dengan lingkungan masjid itu sendiri, pendeknya orang-orang luar wilayah, bisa masuk mengisi kekosongan masjid. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin terjadi ketidakcocokan dengan warga setempat. Apalagi jika orang-orang baru itu menerapkan kebijakan pengelolaan masjid yang eksklusif, seperti hanya menghadirkan khatib-khatib dari kelompoknya sendiri, yang lantas menggunakan mimbar semata untuk mengkampanyekan nilai-nilai sektarian kelompoknya.
Kondisi itu pun dibenarkan oleh Amin. Bimas Islam pun sudah mengetahui ada masjid-masjid yang dikuasai oleh kelompok-kelompok garis keras. “Kita tidak pungkiri bahwa itu ada. Tapi kami tidak punya data, di mana sebarannya,” ujar Amin.
Kekosongan di masjid itu pula yang disesalkan oleh Ishomuddin. Khusus di kalangan NU, memudarnya semangat untuk salat berjamaah kaum Nahdiyin membuka celah kelompok ekstremis menguasai mimbar-mimbar masjid.
“Kenapa kelompok ekstremis bisa menguasai karena mereka semangatnya lebih tinggi, semangat keagamaannya lebih tinggi daripada kemampuan untuk memahami substansi agama. Saya kira ini masalahnya karena ada sebagian orang NU yang malas berjamaah,” tutur Ishomuddin.
Dengan menguasai mimbar-mimbar khotbah di masjid, kelompok garis keras akan dengan mudah menyebarluaskan pandangan politiknya dan memengaruhi massa. Mereka semakin menguat dan membesar. Pada saat yang bersamaan, orang-orang seperti Khemal yang menginginkan khotbah penyejuk hati bisa kian tidak nyaman ke masjid.
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Zen RS
















